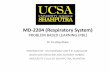LAPORAN PROBLEM BASED LEARNING BLOK RESPIRATORIA PBL KASUS 2 Tutor : dr. Nendyah Roestijawati, MKK Kelompok 7 Heidi Dewi Mutia G1A012061 Maya Alvionita G1A012062 Dwi Bamas Aji G1A012063 Hardina Bawatri G1A012064 Gladys Intan Kirana G1A012065 Tomy Gyanovan G1A012066 Davira Azzahra Firjananti G1A012067 Ummu Nur Fathonah G1A012068 Regina Wahyu Apriani G1A012069 Melati Nuretika G1A012070 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JURUSAN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATAN

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

LAPORAN PROBLEM BASED LEARNING
BLOK RESPIRATORIA
PBL KASUS 2
Tutor :
dr. Nendyah Roestijawati, MKK
Kelompok 7
Heidi Dewi Mutia G1A012061
Maya Alvionita G1A012062
Dwi Bamas Aji G1A012063
Hardina Bawatri G1A012064
Gladys Intan Kirana G1A012065
Tomy Gyanovan G1A012066
Davira Azzahra Firjananti G1A012067
Ummu Nur Fathonah G1A012068
Regina Wahyu Apriani G1A012069
Melati Nuretika G1A012070
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JURUSAN KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2014

BAB I
PENDAHULUAN
A. Skenario
Informasi 1
Gerhana seorang pelajar SMA datang ke klinik, mengeluh batuk berdahak sejak dua bulan terakhir. Batuk dirasakan hampir setiap hari, dahak berwarna kekuningan dan pernah bercampur darah merah segar beberapa kali. Batuk berdahak disertai penurunan berat badan 8 kg dalam waktu 2 bulan, kadang disertai sesak napas terutama apabila beraktivitas.
Informasi 2
Setahun yang lalu Gerhana pernah batuk darah dan diharuskan menjalani pengobatan yang menyebabkan air kencing berwarna merah setelah dilakukan pemeriksaan dahak di puskesmas. Gerhana hanya meminum obat selama 2.5 bulan karena merasa bosan tiap hari minum obat.
Informasi 3
Pemeriksaan fisik :
Keadaan umum : sedang, tampak sesak
Kesadaran : compo mentis
Kesadaran : tekanan darag 130/70 mmHg (Naik), nadi 92x/menit (Normal), pernafasan 28x/menit (Naik), suhu 37.2C (Naik)
Mata : konjungtiva anemis (-) (Normal)
Paru : Inspeksi : simetris kanan dan kiri (Normal)
Palpasi : hantaran paru kanan = kiri (Normal)
Perkusi : sonor di kedua lapangan paru (Normal)
Auskultasi : suara dasar vesikuler, ronki -/-, wheezing -/- (Normal)

Informasi 4
Pemeriksaan penunjang :
Darah rutin : HB 12 gram% (Normal), Leukosit 8600/mm 3 (Normal)
Sputum BTA SPS : (+/ +++ / +)
Foto thoraks : terdapat gambaran infiltrate kecil-kecil yang tersebar merata di kedua lapangan paru
Informasi 5
Diagnosis : TB paru BTA (+) Lesi luas Kasus putus obat
(dengan penyebaran milier)
Penetalaksanaan :
1. Pemberian OAT kategori II yaitu 2RHZES + 1RHZE + 5RH atau 2(4FDC+S) + 1(4DC)
+ 5(2FDC+E)
2. Mukolitik/ekspetorans
3. Vitamin B6 1x1 tab

BAB II
PEMBAHASAN
A. Klarifikasi Istilah
(Tidak ada)
B. Batasan Masalah
1. Identitas Pasien
a. Nama : Gerhana
b. Usia : -
c. Pekerjaan : Pelajar SMA
2. Riwayat Penyakit Sekarang
a. Keluhan utama : Batuk berdahak
b. Onset : 2 hari
c. Durasi : setiap hari
d. Kualitas : dahak berwarna kekuningan dan bercampur darah merah
segar
e. Lokasi : -
f. Faktor pemberat : -
g. Faktor peringan : -
h. Keluhan lain : BB turun, sesak nafas apabila beraktifitas
3. Riwayat Penyakit Dahulu : -
4. Riwayat Penyakit Keluarga: -
5. Riwayat Sosial Ekonomi : -
C. Analisis Masalah
1. Fisiologi batuk dan jenisnya
Reflek batuk terdiri dari 5 komponen utama, yaitu reseptor batuk, serabut saraf
aferen, pusat batuk, susunan saraf eferen, dan efektor (Arimbi, 2012).
a. Reseptor batuk

Batuk bermula dari suatu rangsang pada reseptor batuk. Reseptor ini berupa
serabut saraf non myelin halus yang terletak baik di dalam maupun di luar rongga
toraks. Reseptor yang terletak di dalam rongga toraks antara lain terdapat di laring,
trakea, bronkus, dan di pleura. Jumlah reseptor akan berkurang pada percabangan
bronkus yang kecil dan sejumlah besar reseptor terdapat di laring, trakea, karina
dan daerah percabangan bronkus. Reseptor bahkan juga ditemui di saluran
telinga, lambung, sinus paranasalis, perikardial dan diafragma.
b. Serabut saraf aferen
Serabut aferen terpenting ada pada cabang nervus vagus, yang mengalirkan
rangsang dari laring, trakea, bronkus, pleura, lambung dan juga rangsang dari
telinga melalui cabang arnold dari nervus vagus. Nervus trigeminus menyalurkan
rangsang dari sinus paranasalis. Nervus glosofaringeus menyalurkan rangsang dari
faring. Nervus frenikus menyalurkan rangsang dari perikardium dan diafragma.
Nervus vagus, n. frenikus, n. interkostal, n. trigeminus, n. fasialis, n. hipoglosus
dan lain-lain menuju ke efektor.
c. Pusat batuk
Oleh serabut aferen rangsang ini dibawa ke pusat batuk yang terletak di medula, di
dekat pusat pemapasan dan pusat muntah.
d. Susunan saraf eferen
Kemudian dari pusat batuk serabut-serabut eferen meneruskan rangsangan yang
berupa impuls saraf ke efektor.
e. Efektor
Efektor ini terdiri dari otot-otot laring, trakea, bronkhus, diafragma, otot- otot
interkostal dan lain-lain. Di daerah efektor inilah akan terjadi mekanisme batuk.
Mekanisme batuk terdiri dari 3 fase, yaitu fase inspirasi atau inpulsi, fase
kompresi, dan fase ekspirasi atau ekspulsi (Arimbi, 2012).
Untuk proses pengeluaran mukus, apabila banyak mukus yang terkumpul, reseptor
batuk akan terangsang, sehingga udara beserta mukus akan terlempar keluar dari
saluran napas/ trakhea. Makin ke bawah, epitel dan cillia makin tipis, sehingga bila ada

partikel yang masuk sampai bronkhioli maka partikel akan di tangkap oleh makrofag
alveolar (sel debu/sel dust) atau di batukkan keluar (Arimbi, 2012).
Hemoptisis adalah mendahakkan darah yang berasal dari bronkus atau paru.
Darah yang dikeluarkan dapat berupa dahak bercampur darah atau hanya garis merah
cerah di dahak, atau darah dalam jumlah banyak atau sedikit (Pitoyo, 2006).
Menurut National Lung Health Education Program, 2006, penyebab hemoptisis
tersering, antara lain:
· Bronkitis
· Kanker paru
· Tuberkulosis
· Bronkiektasis
· Pneumonia
· Gagal jantung
· Penggunaan antikoagulan atau fibrinolitik
Arteri-arteri bronkialis adalah sumber darah utama bagi saluran napas, pleura,
jaringan limfoid intra pulmonar, serta persarafan di daerah hilus. Arteri pulmonalis
yang membawa darah dari vena sistemik, memperdarahi jaringan parenkim paru,
termasuk bronkiolus respiratorius. Anastomosis arteri dan vena bronkopulmonar, yang
merupakan hubungan antara kedua sumber perdarahan di atas, terjadi di dekat
persambungan antara bronkiolus respiratorius dan terminalis. Anastomosis ini
memungkinkan kedua sumber darah untuk saling mengimbangi. Apabila aliran dari
salah satu sistem meningkat maka pada sistem yang lain akan menurun. Pada keadaan
kronik, dimana terjadi perdarahan berulang, maka perdarahan seringkali berhubungan
dengan peningkatan vaskularitas di lokasi yang terlibat (Pitoyo, 2006).
Pada tuberkulosis, penyebab perdarahan sangat beragam. Pada lesi parenkim akut,
perdarahan dapat disebabkan oleh nekrosis percabangan arteri/vena. Pada lesi kronik,
lesi fibroulseratif parenkim paru dengan kavitas dapat memiliki tonjolan aneurisma
arteri ke rongga kavitas yang mudah berdarah. Pada tuberkulosis endobronkial,
hemoptisis disebabkan oleh ulserasi granulasi dari mukosa bronkus (Pitoyo, 2006).

2. Perbedaan batuk darah (Hemoptoe) dan muntah darah (hematemesis)
Hemoptoe Hematemesis
Didahului batuk keras tidak tertahankan Tanpa batu, tapi keluar darah saat muntah
Terdengar adanya gelembung udara
bercampur darah du saluran napas
Suara napas tidak ada gangguan
Terasa asin/ darah dan gatal di
tenggorokan
Didahului mual
Warna darah yang dibatukkan merah segar
bercampur buih, lama-lama berwarna
lebih tua dan kehitaman
Warna darah : kehitaman, bergumpal
campur dengan makanan
pH basa pH asam
Beberapa hari, penyebab : kelainan paru Frekuensi muntah tidak sering, penyebab :
sirosis hati, gastritis
3. Hubungan berat badan dengan penyakit pasienPatofisiologi turun berat badan

Gambar 1. Patofisiologi Penurunan Berat Badan pada Pasien TB (Anonim, 2011)
4. Anatomi, fisiologi, dan histologi saluran pernafasan bawaha. Anatomi
Paru atau pulmo merupakan bangunan seperti pons dan sangat elastis. Pada
anak-anak pulmo berwarna merah dan menjadi semakin gelap seiring dengan usia
paru akibat inhalasi debu yang terperangkap dalam fagosit pulmo. Pulmo terletak
sedemikian rupa sehingga masing-masing paru terletak di samping dekstra dan
sinistra dari mediastinum. Masing-masing pulmo dilapisi oleh selaput pelindung
yang disebut pleura visceralis dan pleura parietalis yang diantaranya terdapat
cavum pleura yang berisi cairan pleura. Masing-masing pulmo memiliki apex
pulmonis di atas klavikula, basis pulmonis tempat diafragma, facies costalis yang
menghadap costae, facies mediastinum yang merupakan cetakan mediastinum dan
organ mediastinum lainnya, facies diafragma, dan facies vertebralis. Selain itu,
terdapat pula margo anterior, posterior, dan inferior pada masing-masing pulmo
(Snell, 2006).
Pulmo dekstra terkesan sedikit lebih besar dibandingkan dengan pulmo
sinistra karena memiliki lobus yang lebih banyak. Pulmo dekstra memiliki tiga
lobus, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior yang dipisahkan oleh
fissura horizontal dan fissura oblique. Sedangkan pada pulmo sinistra hanya ada
dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior yang dipisahkan oleh fissura
oblique. Posisi anatomis dari fissura horizontal adalah mengikuti cartilago costalis
IV, costae IV, sampai memotong fissura oblique pada linea axillaris media yang
berjalan dari spina scapulae (baik dekstra maupun sinistra) ke arah anterior,
lateral, dan inferior dan mengikuti costae VI. Perpotongan fissura horizontal dan
fissura oblique ini berada sekitar 6,25 cm di bawah apex pulmonis pulmo sinistra.
Pada facies mediastinalis masing-masing pulmo di tengahnya terdapat hilum
pulmonalis, tempat keluarnya radix pulmonalis yang terdiri dari arteri dan vena
pulmonalis, arteri dan vena bronchiales, pembuluh limfe, dan plexus nervosus dari
nervus cranialis X (Snell, 2006).

Segmenta bronchopulmonalia merupakan unit paru secara anatomi, fungsi,
dan pembedahan. Setiap bronkus lobaris yang masuk ke hilus pulmonalis
bercabang menjadi bronkus segmentalis yang masing-masingnya akan dikelilingi
oleh jaringan ikat dan sebuah cabang arteri pulmonalis. Setelah masuk segmenta
bronchopulmonalia, bronkus segmentalis akan membelah menjadi bronkiolus
dengan struktur tanpa kartilago di dalamnya. Bronkiolus lalu membelah lagi
menjadi bronkiolus terminalis dan membelah lagi menjadi bronkiolus respiratorius
yang merupakan jalan awal dari area pertukaran udara yang terdiri dari bronkiolus
respiratorius, duktus alveolaris, sakus alveolaris, dan alveolus (Snell, 2006).
b. Histologi
1) Hidung
Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi
menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghangatkan udara
pernafasan, juga berperan dalam resonansi suara (Junqueira, 2009).
Rongga hidung (cavum nasi) memiliki sepasang lubang di depan untuk
masuk udara, disebut nares; dan sepasang lubang di belakang untuk
menyalurkan udara yang dihirup masuk ke tenggorokan, disebut choanae.
Rongga hisung sepasang kiri kanan, dibatasi di tengan oleh sekat yang dibina
atas tulang rawan dan tulang (Junqueira, 2009).
Dinding rongga ditunjang oleh tulang rawan dan tulang. Lantai, di
depan terdiri dari tulang langit-langit, di belakang berupa langit-langit lunak.
Atap juga ditunjang oleh tulang rawan sebagian dan sebagian lagi oleh tulang.
Dari tiap dinding ada tiga tonjolan tulang ke rongga hidung, disebut conchae
(Junqueira, 2009).
Rongga hidung dibagi atas 4 daerah (Junqueira : 2009):
1. Vestibula.
2. Atrium.
3. Daerah pembauan.
4. Daerah pernapasan.

Vestibula adalah bagian depan rongga, atrium adalah bagian tengah.
Daerah pembauan berada pada conchae yang atas, sedangkan daerah
pernapasan terletak pada dua conchae yang bawah (Junqueira, 2009).
Rongga hidung dilapisi oleh tunika mukosa. Kecuali di bagian depan
vestibula sampai ke nares. Di sini dilapisi oleh kulit yang strukturnya sama
dengan kulit wajah. Epidermis terdiri atas jaringan epitel squamous kompleks
berkeratin, ada bulu, kelenjar minyak bulu, dan kelenjar peluh. Pada vestibula
itu ada bulu yang keras, disebut vibrissae (Junqueira, 2009).
Tunika mukosa sendiri terdiri atas jaringan epitel columnar
pseudokompleks bersilia. Di daerah pembauan epitel bersilia itu memiliki
struktur dan fungsi khusus, yaitu sabagai indera bau. Diantara sel epitel batang
bersilia tersebar banyak sel goblet. Pada lamina propria banyak terdapat simpul
vena, simpul limfa dan kelenjar lendir. Tak ada bulu, kelenjar minyak bulu
maupun kelenjar peluh. Kelenjar lendir itu di sebut kelenjar Bowman. Tunika
mukosa melekat ketat ke periosteum atau perichondrium di bawahnya
(Junqueira, 2009).
Sekeliling rongga hidung ada empat rongga berisi udara yang
berhubungan dengannya, disebut sinus paranasal. Keempat sinus itu berada
pada tulang-tulang berikut : 1) Frontal; 2) Maxilla; 3) Ethmoid; 4) sphenoid.
Sinus dilapisi oleh tunika mucosa juga, seperti yang melapisi rongga hidung.
Hanya saja lebih tipis dan sel-selnya lebih kecil-kecil serta sedikit mengandung
kelenjar lendir. Lamina propria tidak terliahat dengan jelas (Junqueira, 2009).
2) Faring
Daerah simpangan saluran napas dan saluran makan. Dibedakan atas tiga
daerah :
a) Daerah hidung (naso-pharynx)
Merupakan bagian pertama pharynx kebawah, dilanjutkan dengan bagian
oral organ ini yaitu oro-pharynx.
b) Daerah mulut (oro-pharynx)

c) Daerah jakun (laryngeo-pharynx)
Di daerah mulut lapisan muscularis-mucosa dari tunika mucosa
digantikan oleh serat elastis yang rapat dan tebal. Tunika submucosa hanya ada
di dinding daerah hidung dan dekat ke kerongkongan. Di tempat lain tunika
mukosa melekat langsung ke otot lurik sekitar leher. Lapisan serat elastis yang
ada pada bagian bawah tunika mukosa itu tersusun rapat dan berhubungan
dengan jaringan interstisial otot (Junqueira, 2009).
Lamina propria tunika mukosa terdiri dari jaringan ikat rapat yang
berisi jala serat elastis yang halus. Di daerah mulut dan jakun, tunika mukosa
dilapisi oleh jaringan epitel berlapis banyak dan mengelupas, sedang atapnya
tersusun atas jaringan epitel batang berlapis bersilia, dengan banyak sel goblet.
Pada lamina propria, dibawah lapisan serat elastis, banyak terdapat kelenjar
lendir (Junqueira, 2009).
3) Laring
Gerbang trakea ini disusun oleh beberapa keping tulang rawan hialin dan
elastis, jaringan ikat, serat otot lurik, dan dilapisi sebelah kelumen oleh tunika
mucosa. Tunika mucosa itu memiliki kelenjar lendir (Junqueira, 2009).
Keping tulang rawan yang menunjang jakun ialah (Junqueira : 2009):
(1) Tiroid
(2) Krikoid tunggal
(3) Epiglotis
(4) Aritenoid
(5) Kornikulat sepasang
(6) Kuneiform
Permukaan depan dan sebelah belakang epiglotis dan pita suara
diselaputi epitel squamous kompleks berkeratin. Didaerah lain yaitu dasar
epiglotis, trakea dan bronkhus, epitel itu bersilia (Junqueira, 2009).

Pada tunika mucosa terdapat banyak sel goblet. Kelenjar lendir disini
tergolong jenis tubulo-acinus. Sedikit kuncup rasa terdapat tersebar pada
bagian bawah epiglotis (Junqueira, 2009).
Pita suara berisi ligamen tiro-aritenoid, yang mengandung serat elastis
dan dibagian sisisnya silengkapi serat otot lurik tiro-aritenoid. Ditengah ditutup
dengan tunika mucosa yang tipis dari epitel berlapis mengelupas (Junqueira,
2009).
4) Tenggorok ( Trakea )
Saluran napas ini menghubungkan larynx dengan paru. Histologi
dinding tenggorok dapat dibedakan atas tiga lapis, yaitu tunika mucosa, tunika
muscularis, tunika adventitia (Junqueira, 2009).
Permukaan lumen diselaputi tunika mukosa, dengan epitel batang
berlapis semu dan bersilia, menumpu pada lamina basalis yang tebal. Pada
selaput epitel banyak terdapat sel goblet. Lamina propria berisi banyak serat
elastis dan kelenjar lendir yang kecil-kecil. Kelenjar terletak sebelah atas
lapisan serat elastis. Dibagian posterior tenggorok kelenjar itu menerobos
masuk ke tunika muscularis. Pada lamina propria terdapat pula pembuluh darah
dan pembuluh limfa. Tunika muscularis sendiri sangat tipis dan tidak terlihat
dengan jelas (Junqueira, 2009).
Tunika adventitia juga tidak terlihat secara jelas, dan berintegrasi
dengan jaringan penunjang yang terdiri dari tulang rawan dibawahnya
(Junqueira, 2009).
Tulang rawan di bawah tunika adventitia itu tersusun dalam bentuk
cincin-cincin hialin bentuk huruf C. Cincin inilah yang menunjang tenggorok
pada sebelah samping dan ventral. Sedangkan dibagian dorsal tenggorok,
ditempat itu adalah bagian terbuka cincin, terdapat serat otot polos yang
susunannnya melintang terhadap poros tenggorok. Serat otot itu melekat ke
kedua ujung cincin, dan berfungsi untuk mengecilkan diameter tenggorok. Jika
otot kendur, diameter tenggorok kembali sempurna (Junqueira, 2009).
Diantara cincin bersebelahan terdapat serat fibroelastis. Dengan struktur
cincin yang tak bulat penuh ini maka tenggorok dapat meregang (membesar)

untuk menyalurkan lebih banyak udara ke dalam paru. Di sebelah luar cincin
terdapat jaringan ikat yang berisi banyak serat elastis dan retikulosa (Junqueira,
2009).
5) Cabang Tenggorok (Bronkus)
Merupakan percabangan tenggorok menuju paru kiri-kanan, disebut
bronkus. Tiap bronkus bercabang membentuk cabang kecil, dan tiap cabang
bronkus ini membentuk banyak ranting (Junqueira, 2009).
Histologi dinding bronkus sama dengan trakhea, yaitu terdiri dari :
tunika mucosa, tunika muscularis, tunika adventitia. Cabang yang sudah berada
dalam jaringan paru histologi dindingnya banyak berubah. Cincin tulang rawan
hilang, digantikan oleh keping tulang rawan, yang susunannya tidak teratur dan
mengelilinginy (Junqueira, 2009).
Tunika mucosa pada cabang dan ranting bronkus yang besar, memiliki
epitel bentuk batang bersilia, sedangkan pada ranting yang kecil epitel berubah
jadi kubus dan tak bersilia. Ada lamina basalis tebal, membatasi jaringan epitel
dari lamina propria dan mengandung banyak serat elastis, dan sedikit serat
kolagen serta retikulosa. Di bawah lamina propria erdapat tunika muscularis-
mucosa (Junqueira, 2009).
Kelenjar lendir terkandung dalam tunika mucosa dan tunika submucosa
(Junqueira, 2009).
Tunika adventitia mengandung serat jaringan ikat, sedikit jaringan
lemak, dan dibawahnya terdapat keping tulang rawan yang susunannya tak
teratur. Lapis terluar terdiri dari mesothelium, sebagai penerusan selaput dalam
pleura (Junqueira, 2009).
6) Paru
Cabang bronkus masuk ke dalam paru (pulmo). Paru ada sepasang, kiri-
kanan, terdiri dari lima lobus. Tiap lobus dibatasi oleh septa yang terdiri dari
jaringan ikat terbagi-bagi atas banyak lobulli. Masing-masing lobulus dimasuki

oleh satu bronkhiolus. Di dalamnya bronkiolus bercabang-cabang kecil
membentuk bronkiolus terminalis, dan berakhir pada bronkhiolus pernapasan.
Di dalam lobuli mengandung pembuluh darah, pembuluh limfa, urat saraf, dan
jaringan ikat. Pada banyak tempat sepanjang cabang dan ranting bronkus
terdapat nodus limfa menempel pada dinding (Junqueira, 2009).
Sebelah luar arah ke rongga pleura paru diselaputi oleh selaput lanjutan
dari selaput dalam pluera (Junqueira, 2009).
7) Bronkiolus
Bronkus bercabang berkali-kali sampai jadi ranting kecil. Ranting
bronkus itu bercabang halus berbentuk bronkhiolus . Bronkhiolus bercabang
lagi membentuk ranting, disebut bronkhiolus ujung. Bronkhiolus ujung ini
berakhir pada bronkhiolus pernapasan (Junqueira, 2009).
Tunika mucosa pada bagian ini memiliki epitel kubus yang tak bersilia
(Junqueira, 2009).
Di bawah tunika adventitia tidak ada lagi keping tulang rawan. Lapisan
ini mengandung mesothelium sebagai penerusan selaput dalam pleura
(Junqueira, 2009).
8) Bronkiolus Pernapasan
Merupakan bagian ujung bronkiolus, saluran pendek yang dilapisi sel
epitel bersilia. Sel itu di pangkal bentuk batang, makin ke ujung makin rendah
sehingga menjadi kubus dan siliapun hilang. Di bawah lapisan epitel ada serat
kolagen bercampur serat elastis dan otot polos. Di sini tak ada lagi keping
tulang rawan maupun kelenjar lendir. Lendir di sini dihasilkan oleh sel goblet
yang hanya terdapat dibagian pangkal bronkiolus. Sebagai gantinya ada sel
Clara berbentuk benjolan yang menonjol ke lumen. Sel ini menggetahkan
surfaktan untuk melumasi permukaan dalam saluran (Junqueira, 2009).
Bronkiolus pernapasan bercabang-cabang secara radial membentuk
saluran alveoli (Junqueira, 2009).
9) Saluran alveoli

Merupakan saluran yang tipis dan dindingnya terputus-putus. Saluran ini
bercabang-cabang, tiap cabang berujung pada kantung alveoli. Dinding saluran
alveoli terdiri atas berkas serat elastis, kolagen dan otot polos (Junqueira,
2009).
10) Kantung alveoli dan alveolus
Kantung alveoli berpangkal pada saluran alveoli. Tiap kantung
memiliki dua atau lebih alveoli (Junqueira, 2009).
Alveolus adalah unit terkecil paru-paru, berupa gembungan berbentuk
polihedral, terbuka pada satu sisi, yaitu muara ke kantung alveoli. Dindingnya
terdiri dari selapis sel epitel gepeng yang tipis sekali. Dinding alveolus dililit
pembuluh kapiler yang bercabang-cabang dan yang beranastomosis. Di luar
kapiler ada anyaman serat retikulosa dan elastis (Junqueira, 2009).
Antara alveoli yang bersebelahan terdapat sekat. Sekat itu terdiri dari
dua lapis sel epitel dan pada kedua sisi sel epitel terdapat serat elastis, kolagen,
kapiler, dan fibroblast (Junqueira, 2009).
Epitel alveolus dibatasi dengan endotel kapiler oleh lamina basalis yang
tipis. Ada pula sel epitel yang berbentuk bundar atau kubus, berada pada
dinding alveolus, disebut sel sekat atau sel alveolus besar. Diperkirakan sel ini
mensekresikan lendir. Ia memiliki mikrovilli dan mebentuk kompleks
pertautan dengan sel epitel alveolus yang gepeng dan yang lebih kecil. Sel
alveolus gepeng itulah dengan endotel kapiler yang melilitnya yang membina
membaran pernapasan (Junqueira, 2009).
Membran pernapasan tersusun atas : membran sel epitel alveolus,
sitoplasma sel epitel elveolus, membran sel alveolus, lamina basalis, membarab
sel endotel kapiler, sitoplasma sel endotel kapiler, membran sel endotel kapiler.
Yang tujuh lapis ini sangat tipis. Karena itu kaluar-masuk gas pernapasan
antara lumen alveolus dan lumen kapiler sangat mudah dan cepat (Junqueira,
2009).

Di dinding alveoli sering ditemukan fagosit atau makrofag. Karena
lazimnya sel ini berisi butiran maka disebut dengan sel debu. Sel ini banyan di
temukan pada perokok (Junqueira, 2009).
11) Fisilogi respirasi
Respirasi terdiri dari tiga proses, antara lain (Guyton & Hall, 2008) :
1) Ventilasi pulmonar
Proses pergerakan udara antara atmosfer dengan paru. Pergerakan
udara ini disebabkan oleh perubahan tekanan udara dalam paru. Ventilasi paru
terdiri dari inspirasi/inhalasi dan ekspirasi/ekshalasi.
2) Respirasi eksternal
Proses resapa.n oksigen dalam udara alveoli ke dalam darah di kapiler
alveoli serta proses resapan kabon dioksida dalam arah sebaliknya.
3) Respirasi internal
Merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara kapiler
sistemik dengan sel jaringan. Saat oksigen meresap ke dalam sel, karbon
dioksida akan meresap ke arah yang bertentangan.
D. Pembahasan Masalah
1. Definisi TBC
Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit infeksi kronis jaringan paru tidak termasuk
pleura (selaput paru) yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, atau basil
tuberkel, yang tahan asam. Penularan tuberculosis paru terjadi secara langsung, dan
apabila orang yang belum pernah terpapar TB menghirup cukup banyak tuberkel ke
dalam alveoli, maka terjadilah infeksi tuberculosis yang dapat aktif secara klinis maupun
laten (Depkes, 2002).
2. Patogenesis TBC

Infeksi diawali karena seseorang menghirup basil M.tuberculosis. Bakteri
menyebar melalui jalan napas menuju alveoli lalu berkembang biak dan terlihat
bertumpuk. Perkembangan M.tuberculosis juga dapat menjangkau sampai ke area lain
dari paru-paru (lobus atas). Basil juga menyebar melalui sistem limfe dan aliran darah ke
bagian tubuh lain. Selanjutnya sistem kekebalan tubuh memberikan respon dengan
melakukan reaksi inflamasi. Neutrofil dan makrofag melakukan aksi fagositosis (menelan
bakteri), sementara limfosit spesifik-tuberkulosis menghancurkan atau melisiskan basil
dan jaringan normal. Reaksi jaringan ini mengakibatkan terakumulasinya eksudat dalam
alveoli. Infeksi awal biasanya timbul dalam waktu 2-10 minggu setelah terpapar bakteri
(Somantri, 2007).
Interaksi antara M.tuberculosis dan sistem kekebalan tubuh pada masa awal
infeksi membentuk sebuah massa jaringan baru yang disebut granuloma. Granuloma
terdiri atas gumpalan basil hidup dan mati yang dikelilingi oleh makrofag seperti dinding.
Granuloma selanjutnya berubah bentuk menjadi massa jaringan fibrosa. Bagian tengah
dari massa tersebut disebut ghon tubercle. Materi yang terdiri atas makrofag dan bakteri
menjadi nekrotik yang selanjutnya membentuk materi yang penampakannya seperti keju
(necrotizing caseosa). Hal ini akan menjadi kalsifikasi dan akhirnya membentuk jaringan
kolagen, kemudian bakteri menjadi nonaktif (Somantri, 2007).
Setelah infeksi awal, jika respon sistem imun tidak adekuat maka penyakit akan
lebih parah. Penyakit yang kian parah dapat timbul akibat infeksi ulang atau bakteri yang
sebelumnya tidak aktif kembali menjadi aktif. Pada kasus ini, ghon tubercle mengalami
ulserasi sehingga menghasilkan necrotizing caseosa di dalam bronkus. Tuberkel yang
ulserasi selanjutnya menjadi sembuh dan membentuk jaringan parut. Paru-paru yang
terinfeksi kemudian meradang. Proses ini berjalan terus dan basil terus difagosit atau
berkembang biak di dalam sel. Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih
panjang dan sebagian bersatu membentuk sel tuberkel epiteloid yang dikelilingi oleh
limfosit. Daerah yang mengalami nekrosis dan jaringan granulasi yang dikelilingi sel
epiteloid dan fibroblas akan menimbulkan respon berbeda, kemudian akhirnya akan
membentuk suatu kapsul yang dikelilingi oleh tuberkel (Somantri, 2007).
Paru merupakan port d’entrée lebih dari 98% kasus infeksi TB. Karena ukurannya
yang sangat kecil, kuman TB dalam percik renik (droplet nuclei) yang terhirup, dapat

mencapai alveolus. Masuknya kuman TB ini akan segera diatasi oleh mekanisme
imunologis non spesifik. Makrofag alveolus akan menfagosit kuman TB dan biasanya
sanggup menghancurkan sebagian besar kuman TB. Akan tetapi, pada sebagian kecil
kasus, makrofag tidak mampu menghancurkan kuman TB dan kuman akan bereplikasi
dalam makrofag. Kuman TB dalam makrofag yang terus berkembang biak, akhirnya akan
membentuk koloni di tempat tersebut. Lokasi pertama koloni kuman TB di jaringan paru
disebut Fokus Primer GOHN (Werdhani, 2009)
Dari fokus primer, kuman TB menyebar melalui saluran limfe menuju kelenjar
limfe regional, yaitu kelenjar limfe yang mempunyai saluran limfe ke lokasi fokus
primer. Penyebaran ini menyebabkan terjadinya inflamasi di saluran limfe (limfangitis)
dan di kelenjar limfe (limfadenitis) yang terkena. Jika focus primer terletak di lobus paru
bawah atau tengah, kelenjar limfe yang akan terlibat adalah kelenjar limfe parahilus,
sedangkan jika focus primer terletak di apeks paru, yang akan terlibat adalah kelenjar
paratrakeal. Kompleks primer merupakan gabungan antara fokus primer, kelenjar limfe
regional yang membesar (limfadenitis) dan saluran limfe yang meradang (limfangitis)
(Werdhani, 2009).
Waktu yang diperlukan sejak masuknya kuman TB hingga terbentuknya
kompleks primer secara lengkap disebut sebagai masa inkubasi TB. Hal ini berbeda
dengan pengertian masa inkubasi pada proses infeksi lain, yaitu waktu yang diperlukan
sejak masuknya kuman hingga timbulnya gejala penyakit. Masa inkubasi TB biasanya
berlangsung dalam waktu 4-8 minggu dengan rentang waktu antara 2-12 minggu. Dalam
masa inkubasi tersebut, kuman tumbuh hingga mencapai jumlah 103-104, yaitu jumlah
yang cukup untuk merangsang respons imunitas seluler (Werdhani, 2009).
Selama berminggu-minggu awal proses infeksi, terjadi pertumbuhan logaritmik
kuman TB sehingga jaringan tubuh yang awalnya belum tersensitisasi terhadap
tuberkulin, mengalami perkembangan sensitivitas. Pada saat terbentuknya kompleks
primer inilah, infeksi TB primer dinyatakan telah terjadi. Hal tersebut ditandai oleh
terbentuknya hipersensitivitas terhadap tuberkuloprotein, yaitu timbulnya respons positif
terhadap uji tuberkulin. Selama masa inkubasi, uji tuberculin masih negatif. Setelah
kompleks primer terbentuk, imunitas seluluer tubuh terhadap TB telah terbentuk. Pada
sebagian besar individu dengan system imun yang berfungsi baik, begitu system imun

seluler berkembang, proliferasi kuman TB terhenti. Namun, sejumlah kecil kuman TB
dapat tetap hidup dalam granuloma. Bila imunitas seluler telah terbentuk, kuman TB baru
yang masuk ke dalam alveoli akan segera dimusnahkan (Werdhani, 2009).
Setelah imunitas seluler terbentuk, fokus primer di jaringan paru biasanya
mengalami resolusi secara sempurna membentuk fibrosis atau kalsifikasi setelah
mengalami nekrosis perkijuan dan enkapsulasi. Kelenjar limfe regional juga akan
mengalami fibrosis dan enkapsulasi, tetapi penyembuhannya biasanya tidak sesempurna
focus primer di jaringan paru. Kuman TB dapat tetap hidup dan menetap selamabertahun-
tahun dalam kelenjar ini (Werdhani, 2009).
Kompleks primer dapat juga mengalami komplikasi. Komplikasi yang terjadi
dapat disebabkan oleh fokus paru atau di kelenjar limfe regional. Fokus primer di paru
dapat membesar dan menyebabkan pneumonitis atau pleuritis fokal. Jika terjadi nekrosis
perkijuan yang berat, bagian tengah lesi akan mencair dan keluar melalui bronkus
sehingga meninggalkan rongga di jaringan paru (kavitas). Kelenjar limfe hilus atau
paratrakea yang mulanya berukuran normal saat awal infeksi, akan membesar karena
reaksi inflamasi yang berlanjut. Bronkus dapat terganggu. Obstruksi parsial pada bronkus
akibat tekanan eksternal dapat menyebabkan ateletaksis. Kelenjar yang mengalami
inflamasi dan nekrosis perkijuan dapat merusak dan menimbulkan erosi dinding bronkus,
sehingga menyebabkan TB endobronkial atau membentuk fistula. Massa kiju dapat
menimbulkan obstruksi komplit pada bronkus sehingga menyebabkan gabungan
pneumonitis dan ateletaksis, yang sering disebut sebagai lesi segmentalkolaps-
konsolidasi (Werdhani, 2009).
Selama masa inkubasi, sebelum terbentuknya imunitas seluler, dapat terjadi
penyebaran limfogen dan hematogen. Pada penyebaran limfogen, kuman menyebar ke
kelenjar limfe regional membentuk kompleks primer. Sedangkan pada penyebaran
hematogen, kuman TB masuk ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke seluruh tubuh.
Adanya penyebaran hematogen inilah yang menyebabkan TB disebut sebagai penyakit
sistemik (Werdhani, 2009).
Penyebaran hematogen yang paling sering terjadi adalah dalam bentuk
penyebaran hematogenik tersamar (occult hamatogenic spread). Melalui cara ini, kuman
TB menyebar secara sporadik dan sedikit demi sedikit sehingga tidak menimbulkan

gejala klinis. Kuman TB kemudian akan mencapai berbagai organ di seluruh tubuh.
Organ yang biasanya dituju adalah organ yang mempunyai vaskularisasi baik, misalnya
otak, tulang, ginjal, dan paru sendiri, terutama apeks paru atau lobus atas paru. Di
berbagai lokasi tersebut, kuman TB akan bereplikasi dan membentuk koloni kuman
sebelum terbentuk imunitas seluler yang akan membatasi pertumbuhannya.
Koloni yang sempat terbentuk kemudian dibatasi pertumbuhannya oleh imunitas
seluler, kuman tetap hidup dalam bentuk dormant. Fokus ini umumnya tidak langsung
berlanjut menjadi penyakit, tetapi berpotensi untuk menjadi focus reaktivasi. Fokus
potensial di apkes paru disebut sebagai Fokus SIMON. Bertahun- tahun kemudian, bila
daya tahan tubuh pejamu menurun, focus TB ini dapat mengalami reaktivasi dan menjadi
penyakit TB di organ terkait, misalnya meningitis, TB tulang, dan lain-lain (Werdhani).
Bentuk penyebaran hamatogen yang lain adalah penyebaran hematogenik
generalisata akut (acute generalized hematogenic spread). Pada bentuk ini, sejumlah
besar kuman TB masuk dan beredar dalam darah menuju ke seluruh tubuh. Hal ini dapat
menyebabkan timbulnya manifestasi klinis penyakit TB secara akut, yang disebut TB
diseminata. TB diseminata ini timbul dalam waktu 2-6 bulan setelah terjadi infeksi.
Timbulnya penyakit bergantung pada jumlah dan virulensi kuman TB yang beredar serta
frekuensi berulangnya penyebaran. Tuberkulosis diseminata terjadi karena tidak
adekuatnya system imun pejamu (host) dalam mengatasi infeksi TB, misalnya pada balita
(Werdhani, 2009).
Tuberkulosis milier merupakan hasil dari acute generalized hematogenic
spreaddengan jumlah kuman yang besar. Semua tuberkel yang dihasilkan melalui cara ini
akan mempunyai ukuran yang lebih kurang sama. Istilih milier berasal dari gambaran lesi
diseminata yang menyerupai butur padi-padian/jewawut (millet seed). Secara patologi
anatomik, lesi ini berupa nodul kuning berukuran 1-3 mm, yang secara histologi
merupakan granuloma (Werdhani, 2009).
Bentuk penyebaran hematogen yang jarang terjadi adalah protracted hematogenic
spread. Bentuk penyebaran ini terjadi bila suatu focus perkijuan menyebar ke saluran
vascular di dekatnya, sehingga sejumlah kuman TB akan masuk dan beredar di dalam
darah. Secara klinis, sakit TB akibat penyebaran tipe ini tidak dapat dibedakan

denganacute generalized hematogenic spread. Hal ini dapat terjadi secara berulang
(Werdhani, 2009).
Pada anak, 5 tahun pertama setelah infeksi (terutama 1 tahun pertama), biasanya
sering terjadi komplikasi. Menurut Wallgren, ada 3 bentuk dasar TB paru pada anak,
yaitu penyebaran limfohematogen, TB endobronkial, dan TB paru kronik. Sebanyak0.5-
3% penyebaran limfohematogen akan menjadi TB milier atau meningitis TB, hal ini
biasanya terjadi 3-6 bulan setelah infeksi primer. Tuberkulosis endobronkial (lesi
segmental yang timbul akibat pembesaran kelenjar regional) dapat terjadi dalam waktu
yang lebih lama (3-9 bulan). Terjadinya TB paru kronik sangat bervariasi, bergantung
pada usia terjadinya infeksi primer. TB paru kronik biasanya terjadi akibat reaktivasi
kuman di dalam lesi yang tidak mengalami resolusi sempurna. Reaktivasi ini jarang
terjadi pada anak, tetapi sering pada remaja dan dewasa muda (Werdhani, 2009).
Tuberkulosis ekstrapulmonal dapat terjadi pada 25-30% anak yang terinfeksi TB.
TB tulang dan sendi terjadi pada 5-10% anak yang terinfeksi, dan paling banyak terjadi
dalam 1 tahun tetapi dapat juga 2-3 tahun kemudian. TB ginjal biasanya terjadi 5-25tahun
setelah infeksi primer (Wardhani, 2009).

Gambar 2. Patogenesis Tuberkulosis (Sudoyo, 2009)
3. Perbedaan Microbacterium tuberculosis Primer dan Post Primer
a. Patogenesis Tuberkulosis Primer (Sudoyo, 2009)

b. Patogenesis Tuberkulosis Post-Primer (Sudoyo, 2009)

Tuberkulosis primer adalah infeksi Mycobacterium tuberculosis yang pertama
kali dan menimbulkan gejala. Sedangkan tuberkulosis post-primer atau tuberkulosis
sekunder adalah reinfeksi kuman mikobakterium yang dorman bertahun-tahun dan
muncul sebagai infeksi endogen menjadi tuberkulosis dewasa. Mayoritas reinfeksi
mencapai 90% yang terjadi karena imunitas menurun, seperti malnutrisi, alkohol,
penyakit maligna, diabetes, AIDS, dan gagal ginjal. Tuberkulosis pasca-primer ini
bermula dari sarang primer yang terletak di bagian apikal-posterior lobus superior atau
inferior menginvasi ke daerah parenkim paru dan tidak ke nodus hiler paru (Sudoyo,
2009).
4. Penegakan Diagnosis

Alur penegakan diagnosis
Gambar 2. Alur Penegakan Diagnosis Tb (Depkes RI, 2006)
a. Anamnesis
Keluhan (Alsagaff, 2010) :
1) batuk-batuk lebih dari 3 minggu, batuk darah
2) sesak napas, nyeri dada dan napas berbuyi berlangsung lama
3) demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasanya dirasakan malam hari
disertai dengan keringatmalam. Kadang demam seperti influenza dan bersifat

hilang timbul. Batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu (dapat disertai dengan
darah)
4) Penurunan nafsu makan dan berat badan
5) Perasaan tidak enak (malaise), lemah
b. Pemeriksaan Fisik
Dengan pemeriksaan fisik dapat diketahui (Alsagaf, 2010).:
1) Lokalisasi proses, karena banyak penyakit paru yang mengambil tempat tertentu
di paru, sehingga pemeriksaan fisik yang baik dan teliti akan sangat berguna.
2) Macam-macam proses seperti lambat atau cepatnya suatu proses penyakit
berlangsung sebab tuberkulosis paru jarang yang akut. Umumnya proses
berlangsung menahun. Pada penyembuhannya terbentuk jaringan fibrotik,
kalsifikasi atau disertai dengan kerusakan jaringan parenkim yang meninggalkan
kavitas.
c. Pemeriksaan penunjang (Alsagaf, 2010)
1) Ditemukan basil tahan asam di dalam dahak penderita atau di dalam cairan
lambung, cairan pleura, dll.
2) Radiologis, sesuai dengan gambaran tuberkulosis paru
Pada sebagian besar TB paru, diagnosis terutama ditegakkan dengan
pemeriksaan dahak secara mikroskopis dan tidak memerlukan foto toraks.
Namun pada kondisi tertentu pemeriksaan foto toraks perlu dilakukan sesuai
dengan indikasi sebagai berikut:
a. Hanya 1 dari 3 spesimen dahak SPS hasilnya BTA positif. Pada kasus ini
pemeriksaan foto toraks dada diperlukan untuk mendukung diagnosis TB
paru BTA positif. (lihat bagan alur di lampiran 2)
b. Ketiga spesimen dahak hasilnya tetap negatif setelah 3 spesimen dahak SPS
pada pemeriksaan sebelumnya hasilnya BTA negatif dan tidak ada perbaikan
setelah pemberian antibiotika non OAT(non fluoroquinolon). (lihat bagan alur
lampiran 2)
c. Pasien tersebut diduga mengalami komplikasi sesak nafas berat yang
memerlukan penanganan khusus (seperti: pneumotorak, pleuritis eksudativa,

efusi pericarditis atau efusi pleural) dan pasien yang mengalami hemoptisis
berat (untuk menyingkirkan bronkiektasis atau aspergiloma).
3) Darah rutin, menunjukkan gambaran proses kronis dan disertai LED yang cukup tinggi
Tuberkulosis (Sudoyo,
2009)
Bronkopneumonia
(Ngastiyah, 2005)
Pneumonia
(Gleadle, 2007)
Gejala:
1. Demam; menyerupai
influenza, kadang
dapat mencapai 40oC,
serangan demam
pertama sembuh
sebentar, lalu muncul
lagi. Keadaan ini
dipengaruhi oleh
imun tubuh pasien
dan berat ringannya
infeksi kuman TB
yang masuk.
2. Batuk/batuk darah;
terjadi karena ada
iritasi pada bronkus,
diperlukan untuk
membuang produk-
produk radang keluar.
Sifat batuk dimulai
dari batuk kering
(non-produktif)
kemudian setelah
timbul peradangan
Gejala:
1. Didahului infeksi
respirasi atas
2. Demam dengan
kejang biasanya
3. Nyeri dada seperti
ditusuk
4. Pernapasan cepat
dan dangkal,
pernapasan cuping
hidung sekitar
hidung dan mulut
5. Adanya bunyi
pernapasan
tambahan seperti
ronki dan
wheezing
6. Anoreksia
7. Malaise
8. Batuk kental,
produktif, sputum
kuning kehijauan
kemudian berkarat
atau kemerahan
Gejala:
1. Batuk produktif
menghasilkan
sputum kadang
darah
2. Sesak nafas
3. Kelelahan
4. Anoreksi
5. Mialgia
6. Demam
7. Menggigil

menjadi produktif
(ada sputum). Bisa
selanjutnya batuk
darah karena ada
pembuluh darah yang
pecah.
3. Sesak napas; pada
penyakit yang sudah
lanjut, yang
infiltrasinya sudah
meliputi setengah
bagian paru-paru
4. Nyeri dada; bila
infiltrasi radang
sampai ke pleura,
menyebabkan
pleuritis, terjadi
gesekan saat inspirasi
dan ekspirasi
5. Malaise; penyakit
radang menahun,
sering ditemukan
anoreksia, tidak nafsu
makan, badan makin
kurus, sakit kepala,
nyeri otot, meriang,
keringat malam.
PF:
1. Konjungtiva mata
atau kulit pucat
karena anemia, suhu
PF:
Pemeriksaan penunjang:
1. Ada bercak
infiltrat pada satu
PF:
1. Ada suara
ronki, perkusi
pekak,

demam, berat badan
turun
2. Tempat kelainan TB
paru paling dicurigai
adalah apeks paru:
ada infiltrat yang
agak luas, maka ada
perkusi redup dan
suara napas bronkial.
Bisa juga suara nafas
tambahan berupa
ronki basah, kering,
dan nyaring.
Pemeriksaan penunjang:
1. Pemeriksaan
sputum SPS
2. Pemeriksaan
radiologi
atau beberapa
lobus, ada
komplikasi juga
pada pleuritis,
ateletaksis, abses,
pneumotoraks
pada foto rontgen.
2. Sel
polimorfonuklear
juga terlihat.
3. Tes darah – cek
leukositosis
4. Sputum
5. Kultur darah
pernafasan
bronkial,
demam,
takipneu,
takikardi,
sianosis

Pada anak kecil, TB dapat di diagnosis dan di scorring dengan tabel di bawah ini
5. Penatalaksanaan
d. Medika mentosa
Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip - prinsip sebagai berikut
(Depkes RI, 2006) :
1) OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah
cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan OAT
tunggal (monoterapi) . Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap (OAT – KDT)
lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan.

2) Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung
(DOT = Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas Menelan Obat
(PMO).
3) Pengobatan TB diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan.
a) Tahap awal (intensif)
Pada tahap intensif (awal) pasien mendapat obat setiap hari dan perlu diawasi
secara langsung untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Bila pengobatan
tahap intensif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menular menjadi
tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar pasien TB BTA
positif menjadi BTA negatif (konversi) dalam 2 bulan.
b) Tahap Lanjutan
Pada tahap lanjutan pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam
jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh
kuman persister sehingga mencegah terjadinya kekambuhan.
Obat yang digunakan pada terapi tuberkulosis adalah Obat Anti Tuberkulosis (OAT).
OAT ini terdiri dari dua lini. Lini pertama terdiri dari Isoniazid, Rifampicin, Pirazinamid,
Etambutol, dan Streptomisin. Obat-obatan ini merupakan obat pilihan pertama dalam
terapi tuberkulosis. Lini dua OAT adalah obat-obat pilihan kedua dalam terapi, terdiri dari
Kanamisin, Amikasin, dan Kuinolon. Berikut tabel tentang jenis dan dosis OAT (PDPI, 2006).
Obat Dosis
(Mg/Kg
BB/Hari)
Dosis yg dianjurkan Dosis Maks
(mg)
Dosis (mg) / berat badan
(kg)
Harian
(mg/
kgBB /
hari)
Intermitten
(mg/Kg/BB/kali
)
< 40 40-60 >60
R 8-12 10 10 600 300 450 600
H 4-6 5 10 300 150 300 450
Z 20-30 25 35 750 1000 1500
E 15-20 15 30 750 1000 1500

S 15-18 15 15 1000Sesuai
BB750 1000
Tabel 1. Jenis dan Dosis OAT (PDPI, 2006)
Selain itu, terdapat pula beberapa kategori OAT sesuai dengan masing-masing
kasus OAT. Berikut kategori tersebut (PDPI, 2006).
Kategori Kasus Paduan obat yang diajurkan Keterangan
I- TB paru BTA +,
BTA - , lesi luas
2 RHZE / 4 RH atau
2 RHZE / 6 HE
*2RHZE / 4R3H3
II- Kambuh
- Gagal pengobatan
-RHZES / 1RHZE / sesuai
hasil uji resistensi atau
2RHZES / 1RHZE / 5 RHE
-3-6 kanamisin, ofloksasin,
etionamid, sikloserin / 15-18
ofloksasin, etionamid,
sikloserin atau 2RHZES /
1RHZE / 5RHE
Bila streptomisin
alergi, dapat
diganti
kanamisin
II- TB paru putus
berobat
Sesuai lama pengobatan
sebelumnya, lama berhenti
minum obat dan keadaan
klinis, bakteriologi dan
radiologi saat ini (lihat
uraiannya) atau
*2RHZES / 1RHZE /
5R3H3E3
III -TB paru BTA neg.
lesi minimal
2 RHZE / 4 RH atau

6 RHE atau
*2RHZE /4 R3H3
IV - Kronik
RHZES / sesuai hasil uji
resistensi (minimal OAT yang
sensitif) + obat lini 2
(pengobatan minimal 18
bulan)
IV - MDR TBSesuai uji resistensi + OAT
lini 2 atau H seumur hidup
Tabel 2. Kategori OAT (PDPI, 2006)
Dalam OAT dikenal juga obat kombinasi dosis tepat atau Fixed Dose
Combination (FDC), Kombinasi obat ini terdiri dari tiga atau empat jenis obat dalam
satu tablet. Dalam penggunaan FDC ini, apabila terdapat efek samping serius, harus
segera dirujuk ke rumah sakit atau ke dokter spesialis paru yang mampu
menanganinya (PDPI, 2006).
Fase intensif Fase lanjutan
2 bulan 4 bulan
BB Harian Harian 3x/minggu Harian 3x/minggu
RHZE
150/75/400/275
RHZ
150/75/400
RHZ
150/150/500
RH
150/75
RH
150/150
30-37
38-54
55-70
>71
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
Tabel 3. Dosis obat antituberkulosis dosis tetap (PDPI, 2006)

Jenis OAT Sifat Dosis yang direkomendasikan (mg/kg)
Harian 3x seminggu
Isoniazid (H) Bakterisid 5
(4-6)
10
(8-12)
Rifampicin (R) Bakterisid 10
(8-12)
10
(8-12)
Pyrazinamide (Z) Bakterisid 25
(20-30)
35
(30-40)
Streptomycin (S) Bakterisid 15
(12-18)
15
(12-18)
Ethambutol (E) Bakteriostatik 15
(15-20)
30
(20-35)
Tabel 4. Jenis, sifat dan dosis OAT (Depkes RI, 2006)
OAT memberikan beberapa efek samping,baik yang dapat ditolerir
ataupun harus segera dilaporkan kepada petugas kesehatan. Berikut efek
samping masing-masing OAT yang perlu diketahui (PDPI, 2006).
a. Isoniazid
Sebagian besar pasien TB dapat menyelesaikan pengobatan tanpa efek
samping. Namun sebagian kecil dapat mengalami efek samping, oleh karena itu
pemantauan kemungkinan terjadinya efek samping sangat penting dilakukan
selama pengobatan. Efek samping yang terjadi dapat ringan atau berat, bila efek
samping ringan dan dapat diatasi dengan obat simptomatis maka pemberian
OAT dapat dilanjutkan (PDPI, 2006).
b. Rifampisin
Efek samping ringan yang dapat terjadi dan hanya memerlukan
pengobatan simptomatis adalah: (PDPI, 2006)
1) Sindrom flu berupa demam, menggigil dan nyeri tulang
2) Sindrom perut berupa sakit perut, mual, tidak nafsu makan, muntah kadang-
kadang diare
3) Sindrom kulit seperti gatal-gatal kemerahan

Efek samping yang berat tetapi jarang terjadi adalah: (PDPI, 2006)
1) Hepatitis imbas obat atau ikterik, bila terjadi hal tersebut OAT harus distop
dulu dan penatalaksanaan sesuai pedoman TB pada keadaan khusus
2) Purpura, anemia hemolitik yang akut, syok dan gagal ginjal. Bila salah satu
dari gejala ini terjadi, rifampisin harus segera dihentikan dan jangan diberikan
lagi walaupun gejalanya telah menghilang
3) Sindrom respirasi yang ditandai dengan sesak napas
Rifampisin dapat menyebabkan warna merah pada air seni, keringat, air mata
dan air liur. Warna merah tersebut terjadi karena proses metabolisme obat dan
tidak berbahaya. Hal ini harus diberitahukan kepada pasien agar mereka
mengerti dan tidak perlu khawatir.
c. Pirazinamid
Efek samping utama ialah hepatitis imbas obat (penatalaksanaan sesuai
pedoman TB pada keadaan khusus). Nyeri sendi juga dapat terjadi (beri aspirin)
dan kadang-kadang dapat menyebabkan serangan arthritis Gout, hal ini
kemungkinan disebabkan berkurangnya ekskresi dan penimbunan asam urat.
Kadang-kadang terjadi reaksi demam, mual, kemerahan dan reaksi kulit yang
lain (PDPI, 2006).
d. Etambutol
Etambutol dapat menyebabkan gangguan penglihatan berupa
berkurangnya ketajaman, buta warna untuk warna merah dan hijau. Meskipun
demikian keracunan okuler tersebut tergantung pada dosis yang dipakai, jarang
sekali terjadi bila dosisnya 15-25 mg/kg BB perhari atau 30 mg/kg BB yang
diberikan 3 kali seminggu. Gangguan penglihatan akan kembali normal dalam
beberapa minggu setelah obat dihentikan. Sebaiknya etambutol tidak diberikan
pada anak karena risiko kerusakan okuler sulit untuk dideteksi (PDPI, 2006).
e. Streptomisin
Efek samping utama adalah kerusakan syaraf kedelapan yang berkaitan
dengan keseimbangan dan pendengaran. Risiko efek samping tersebut akan
meningkat seiring dengan peningkatan dosis yang digunakan dan umur pasien.
Risiko tersebut akan meningkat pada pasien dengan gangguan fungsi ekskresi

ginjal. Gejala efek samping yang terlihat ialah telinga mendenging (tinitus),
pusing dan kehilangan keseimbangan. Keadaan ini dapat dipulihkan bila obat
segera dihentikan atau dosisnya dikurangi 0,25gr. Jika pengobatan diteruskan
maka kerusakan alat keseimbangan makin parah dan menetap (kehilangan
keseimbangan dan tuli).
Reaksi hipersensitiviti kadang terjadi berupa demam yang timbul tiba-tiba
disertai sakit kepala, muntah dan eritema pada kulit. Efek samping sementara
dan ringan (jarang terjadi) seperti kesemutan sekitar mulut dan telinga yang
mendenging dapat terjadi segera setelah suntikan. Bila reaksi ini mengganggu
maka dosis dapat dikurangi 0,25gr (PDPI, 2006).
Streptomisin dapat menembus sawar plasenta sehingga tidak boleh
diberikan pada perempuan hamil sebab dapat merusak syaraf pendengaran janin
(PDPI, 2006).
Paduan OAT yang digunakan di Indonesia (Depkes RI, 2006)
1) Kategori-1 (2HRZE/ 4H3R3)
Paduan OAT ini diberikan untuk pasien baru:
Pasien baru TB paru BTA positif.
Pasien TB paru BTA negatif foto toraks positif
Pasien TB ekstra paru
Tabel 5. Dosis untuk paduan OAT KDT untuk Kategori 1 (Depkes RI, 2006)
Berat Badan Tahap Intensif
tiap hari selama 56 hari
RHZE (150/75/400/275)
Tahap Lanjutan
3 x seminggu selama 16 minggu
RH (150/150)
30 – 37 kg 2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT
38 – 54 kg 3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT
55 – 70 kg 4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT
≥71 kg 5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT

2) Kategori -2 (2HRZES/ HRZE/ 5H3R3E3) (Depkes RI, 2006)
Paduan OAT ini diberikan untuk pasien BTA positif yang telah diobati
sebelumnya:
Pasien kambuh
Pasien gagal
Pasien dengan pengobatan setelah default (terputus)
Tabel 6. Dosis untuk paduan OAT KDT Kategori 2 (Depkes RI, 2006)
Berat Badan Tahap Intensif
tiap hari
RHZE (150/75/400/275)+S
Tahap Lanjutan
3 x seminggu
RH (150/150)+E(275)
Selama 56 hari Selama 28 hari Selama 20 minggu
30 – 37 kg 2 tablet 4KDT
+ 500 mg
Streptomisin inj.
2 tablet 4KDT 2 tablet 2KDT
+ 2 tab Etambutol
38 – 54 kg 3 tablet 4KDT
+ 750 mg
Streptomisin inj.
3 tablet 4KDT 3 tablet 2KDT
+ 3 tab Etambutol
55 – 70 kg 4 tablet 4KDT
+ 1000 mg
Streptomisin inj.
4 tablet 4KDT 4 tablet 2KDT
+ 4 tab Etambutol
≥71 kg 5 tablet 4KDT
+ 1000 mg
Streptomisin inj.
5 tablet 4KDT 5 tablet 2KDT
+ 5 tab Etambutol
Catatan (Depkes RI, 2006):
Untuk pasien yang berumur 60 tahun ke atas dosis maksimal untuk
streptomisin adalah 500mg tanpa memperhatikan berat badan.
Untuk perempuan hamil lihat pengobatan TB dalam keadaan khusus.

Cara melarutkan streptomisin vial 1 gram yaitu dengan menambahkan
aquabidest sebanyak 3,7ml sehingga menjadi 4ml. (1ml = 250mg)
3) OAT Sisipan (HRZE) (Depkes RI, 2006)
Paket sisipan KDT adalah sama seperti paduan paket untuk tahap intensif kategori 1
yang diberikan selama sebulan (28 hari).
6. Prognosis
Sejak ditemukannya obat anti tuberkulosis, prognosis penyakit ini baik, kecuali
penderita yang telah mengalami kekambuhan, atau terjadi penyulit pada organ paru dan
organ lain di dalam rongga dada, maka penderita-penderita banyak yang mengalami kor-
pulmonal. Bila terbentuk kaverne yang cukup besar, kemungkinan batuk darah hebat
dapat terjadi dan keadaan ini sering menimbulkan kematian, walaupun secara tidak
langsung. Untuk diabetes melitus sulit dilakukan regulasi sehingga dapat menyebabkan
penyembuhan penderita TBC menjadi lama, walaupun telah memakai regimen yang
adekuat (Alsagaf, 2010).
7. Screening dan pencegahan
Tergantung pada tingkat risiko penularan dari penderita TB, serta faktor
lingkungan dan tingkat interaksi, keluarga atau anggota rumah tangga, teman dekat dan
rekan sekerja sebaiknya menjalani skrining TB secepat mungkin. Apabila menduga sudah
terlalu dekat dengan orang yang menurut diagnosa meng-idap TB, hubungi Unit
Pengendalian TB terdekat (di mana skriningnya dilakukan secara gratis) pada jam kerja,
atau periksakan diri ke dokter, meskipun merasa sehat (Depkes, 2013).
Skrining dan tindak lanjut untuk orang yang berdekatan dengan pengidap TB antara lain:
a. uji kulit tuberkulin (uji Mantoux)
b. Uji Quantiferon TB-Gold (uji darah)
b. rontgen dada
c. vaksinasi BCG
d. pengobatan infeksi TB laten.
Pencegahan infeksi tuberkulosis meliputi (Alsagaf, 2010) :
a. Terhadap infeksi tuberkulosis

1) Pencegahan terhadap sputum yang infeksius
2) Pasteurisasi susu sapi dan membunuh hewan yang terinfeksi oleh
Mikobakterium bovis akan encegah tuberkulosis bovin pada manusia
b. Meningkatkan daya tahan tubuh
1) Memperbaiki standar hidup
a) Makan-makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna
b) Lengkapi perumahan dengan ventilasi yang cukup
c) Usahakan setiap hari tidur cukup dan teratur
d) Lakukanlah olahraga di tempat-tempat yang mempunyai udara segar
2) Usahakan peningkatan kekebalan tubuh dengan vaksinasi BCG
c. Pencegahan dengan mengobati penderita yang sakit dengan obat anti tuberkulsis

DAFTAR PUSTAKA
Alsagaff, H,. dan Mukty, H.A. 2010. Dasar-dasar Ilmu Penyakit Paru. Surabaya : Airlangga
Unevirsity Press
Amin, Zulkifli., dan Bahar, Asril. 2009. Tuberkulosis Paru dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jilid 3. Edisi 5. Jakarta: Interna Publishing.
Anonim. 2011. Tuberkulosis Paru. Available at : repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21492/3/Chapter%20II.pdf (diakses pada tanggal 16 Maret 2014).
Arimbi. 2012. Batuk Berdahak. Surabaya: Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK Universitas Wijaya Kusuma. Downloaded at : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Felib.fk.uwks.ac.id%2Fasset%2Farchieve%2Fmatkul%2FIlmu_Penyakit_Dalam%2FInterna%2Fbatuk-berdahak.pptx&ei=6xQkU526KMf5rAf2i4CABw&usg=AFQjCNHVF0_tMc4NSX45Ys7nDLfvHz3d1g&sig2=Su_Bs3WqI0x-PPvoHXMsKA&bvm=bv.62922401,d.bmk (diakses Rabu, 12 Maret 2014)
Department of Health. 2013. Penyakit Tuberkulosis. Centre for Healthcare Related Infection Surveillance and Prevention & Tuberculosis Control.
Depkes. 2002. Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Djojodibroto, Darmanto. 2009. Respirologi. Jakarta: EGC
Eroschenko, Victor P. 2012. Atlas Histologi diFiore dengan Korelasi Fungsional. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Gleadle, Jonathan. 2007. At A Glance Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik. Jakarta: Erlangga
Werdhani, Retno Asti. 2013. Patofisiologi, Diagnosis dan Klasifikasi Tuberkulosis. Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Okupasi dan Keluarga FKUI.
Guyton, AC., dan Hall, JE. 2008. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 11. Jakarta: EGC.
Junqueira, L.C. dan J. Carneiro. 1995. Basic Histology (Histologi Dasar). Terjemahan Adji Dharma. Edisi ketiga. Jakarta : EGC.
National Lung Health Education Program. Hemoptysis. 2000. Diunduh dari http://www.nlhep.org/books/pul_Pre/hemoptysis.html.
Pitoyo CW. Hemoptisis. Dalam: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, penyunting. Buku ajar ilmu penyakit dalam, jilid II, edisi IV. Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2006. hal.220-1
Ngastiyah. 2005. Perawatan Anak Sakit Edisi 2. Jakarta: EGC
Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI). 2006. Tuberkulosis. Available at: http://www.klikpdpi.com/konsensus/tb/tb.pdf (diakses pada 9 Maret 2014)
Snell. Richard S. 2006. Anatomi Klinik. Jakarta: EGC.
Somantri, Irman. 2007. Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Gangguan Sistem Pernapasan. Jakarta : Salemba Medika.
Sudoyo, Aru W. 2009. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid III Edisi 5. Jakarta: Interna Publishing.
Werdhani, Retno Asti. 2013. Patofisiologi, Diagnosis dan Klasifikasi Tuberkulosis. Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Okupasi dan Keluarga FKUI.
Wibisono, jusuf. 2011. Ilmu Penyakit Paru.Surabaya;DepartemenPenyakit Ilmu Paru FK Unair

Related Documents