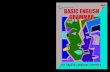ACARA II ENZIM A. Tujuan Praktikum Acara II Enzim ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas kerja enzim Diastase atau Amilase. 2. Mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas kerja enzim Diastase atau Amilase. 3. Mengetahui aktivitas enzim amilase pada kecambah. B. Tinjauan Pustaka Enzim adalah reaksi atau proses kimia yang berlangsung dengan baik dalam tubuh kita ini dimungkinkan karena adanya katalis. Fungsi suatu enzim ialah sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun luar sel. Enzim dapat menurunkan energi aktivitas suatu reaksi kimia (Poedjiadi, 1994). Laju reaksi meningkat dengan kenaikan suhu, dan akhirnya enzim kehilangan semua aktivitas jika protein menjadi rusak akibat panas. Enzim berfungsi pada suhu antara 25-37 C. Laju reaksi berkurang pada

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
ACARA IIENZIM
A. Tujuan Praktikum Acara II Enzim ini bertujuan untuk :1. Mengetahui pengaruh pH terhadap aktivitas kerja enzim Diastase atau Amilase.2. Mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas kerja enzim Diastase atau Amilase.3. Mengetahui aktivitas enzim amilase pada kecambah.B. Tinjauan PustakaEnzim adalah reaksi atau proses kimia yang berlangsung dengan baik dalam tubuh kita ini dimungkinkan karena adanya katalis. Fungsi suatu enzim ialah sebagai katalis untuk proses biokimia yang terjadi dalam sel maupun luar sel. Enzim dapat menurunkan energi aktivitas suatu reaksi kimia (Poedjiadi, 1994).Laju reaksi meningkat dengan kenaikan suhu, dan akhirnya enzim kehilangan semua aktivitas jika protein menjadi rusak akibat panas. Enzim berfungsi pada suhu antara 25-37 C. Laju reaksi berkurang pada di kedua sisi pH optimum untuk setiap kombinasi (Page, 1997).Pengaruh suhu terhadap enzim karena struktur protein menentukan aktivitas enzim. Maka jika struktur ini terganggu aktivitas akan berubah. Proses denaturasi protein untuk protein-protein enzim dan bahan yang mendenaturasi adalah sama. Denaturasi akibat suhu tinggi biasanya irreversibel karena gaya-gaya ikatan lemah yang penting rusak akibat meningkatnya getaran termal komponen atom-atomnya (Ismadi, 1993).Karena reaksi kimia sangat dipengaruhi oleh suhu, maka reaksi yang dikatalis oleh enzim juga peka terhadap suhu. Enzim sebagai protein akan mengalami denaturasi jika suhunya dinaikkan, akibatnya daya kerja enzim menurun. pH juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim, karena sifat ionik gugus karboksil dan gugus amino mudah dipengaruhi oleh pH. Hal ini menyebabkan daerah katalitik dan konformasi enzim menjadi berubah (Girindra, 1990).Amilase adalah enzim yang berfungsi memecah pati atau glikogen. Amilase dibagi menjadi 3 bagian yaitu : Alpha amilase, alpha amilase memecah pati secara acak dari tengah atau dari bagian dalam molekul, karenanya disebut endoamilase. Beta amilase, yaitu menghidrolisis unit-unit gula dari ujung molekul pati, karenanya disebut eksoamilase. Glukoamilase, yaitu yang dapat memisahakan glukosa dari terminal gula non-pereduksi substrat pati (Winarno, 1986).Enzim digunakan dalam industri karena bersifat sangat spesifik dibandingkan dengan katalis anorganik. Selain itu, enzim bekerja sangat efisien, beroperasi pada kondisi lunak, aman dan mudah dikontrol, dapat menggantikan bahan kimia yang berbahaya, dan dapat didegradasi secara biologis. Enzim mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dalam industri pangan, enzim alpha amilase berfungsi menyediakan gula hidrolisis pati sehingga dapat dimanfaatkan untuk produksi sirup glukosa ataupun sirup fruktosa yang mempunyai tingkat kemanisan tinggi, pembuatan roti, dan makanan bayi (Setiasih, 2006).Terjadinya perubahan nilai pH selama proses inkubasi sangat mempengaruhi kerja enzim. Karena perubahan pH menyebabkan terjadinya perubahan pada daerah katalitik dan konformasi dari enzim,dimana sifat ionik dari gugus karboksil dan gugus amino enzim tersebut sangat mudah dipengaruhi oleh pH. Selain itu, perubahan pH dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga dapat menimbulkan hilangnya fungsi katalitik enzim (Hidayat, 2005).Amilase merupakan enzim yang mampu memecah molekul-molekul pati dan glikogen, sehingga banyak digunakan dalam berbagai industri, seperti indusri tekstil, deterjen dan gula cair non tebu. Aktifitas amilase dari enzim kasar ditentukan dengan cara mengukur jumlah gula pereduksi yang dihasilkan oleh aktivitas hidrolisis enzim terhadap substrat pati. Satu unit aktivitas amilase adalah banyaknya enzim yang dapat menghasilkan 1 g glukosa per menit per mL larutan enzim pada kondisi pengujian yang dilakukan (Naiola, 2008).Kecambah kacang hijau mengandung enzim -amilase. Parameter yang diamati adalah air dan kadar protein tunas, pH, aktivitas -amilase, dan dilarutkan protein dalam ekstrak enzim. Potensi enzim yang ditemukan dalam kacang hijau dapat dimanfaatkan dalam pengolahan bahan industri yang memiliki kadar pati tinggi, seperti tepung jagung (Suarni, 2007).Kacang hijau merupakan salah satu tanaman penting dari wilayah Timur Utara India. Fosfatase enzim asam diisolasi dan dimurnikan secara parsial dari kecambah biji kacang hijau lokal. Sekuensial proses pemurnian parsial dilakukan dengan menggunakan metode presipitasi amonium sulfat. Enzim mentah memiliki aktifitas spesifik 0,5 U/mg dimurnikan menggunakan 30-70% amonium sulfat metode presipitasi. Aktifitas enzim diukur pada berbagai waktu inkubasi, pH, suhu, dan konsentrasi substrat (Surchandra, 2012).
C. Metode Penelitian 1. Alata. Pipet tetesb. Pipet volumec. Tabung reaksi dan rak tabung reaksid. Gelas ukure. Lempeng atau cawan porselinf. Gelas bekerg. Penangas airh. Mortar atau blenderi. Stopwatchj. Penjepit k. Kain saringl. Inkubutor2. Bahan a. Larutan buffer 6 ml pH 4.0; pH 6.0; pH 8.0b. Larutan amilum 1%c. Larutan enzim diastase 2 ml d. Larutan Iodin 0,01 M dan 0.01 Ne. Glikogen+Iodf. Amilum+Iodg. Selulosa+Iodh. Biji kacang hijau 50 g dan taoge gi. Aquadesj. Reagen benedict
3. Cara Kerja a. Percobaan 1 Pengaruh pH terhadap Aktivitas Enzim Diastase/Amilase
Uji BenedictDitambah 1 ml reagen BenedictDinkubasi dalam penangas air selama 5 menitDiamati perubahan warnanyaDiambil 1 ml larutan tiap sampel
b. Percobaan 2. Pengaruh Suhu terhadap Aktivitas Enzim Diastase / Amilase
c. Pengujian Amilase dari Biji Kacang Hijau dan Kecambah3 ml amilum 1% + 6 ml buffer pH 6 (atur pH)
Ditambah 1 ml ekstrak kacang hijauDitambah 1 ml ekstrak kecambahDiinkubasi 40CDiambil 1 tetes diletakan pada test plate poselen (menit ke-0 dan ke-20)Ditetesi Iod 0,01 NDicatat perubahan warnanya3 ml amilum 1% + 6 ml buffer pH 6 (atur pH)
3 ml amilum 1% + 6 ml buffer pH 6 (atur pH)
3 ml amilum 1% + 6 ml buffer pH 6 (atur pH)
D. Hasil Pengamatan dan PembahasanTabel 2.1 Hasil Pengamatan Uji Iod terhadap pengaruh pH terhadap Aktivitas Enzim Diastase/Amilase.KelSampel+larBufferPerubahan Warna
5101520
1 dan 26 ml buffer pH 4+3 ml lar amilum1%Bening-keruhKeruh-agak kuningKeruh-kuning keruhKeruh-kuning pucat
3 dan 46 ml buffer pH 6+3 ml lar amilum1%Bening-beningBening-beningBening-kuning ada endapanBening-kuning
5,6 dan 76 ml buffer pH 8+3 ml lar amilum1%Bening-beningBening-agak kuningBening-agak kuningBening-kuning
8 dan 96 ml buffer pH 4+3 ml lar amilum1%Putih-putih (bening)Putih-putih (bening)Putih-putih (bening)Putih-putih (bening)
10 dan 116 ml buffer pH 6+3 ml lar amilum1%Putih-biru mudaPutih-biruPutih-biruBiru tua-biru muda
12,13, dan 146 ml buffer pH 8+3 ml lar amilum1%Putih-beningPutih-beningPutih-beningPutih-bening
Glikogen+IodKuning
Amilum+IodBiru tua
Selulosa+Iodkuning
Sumber : Laporan SementaraPembahasan :Enzim merupakan unit fungsional dari metabolisme sel. Bekerja dengan urutan-urutan yang teratur, enzim mengkatalisis ratusan reaksi bertahap yang menguraikan molekul nutrien, reaksi yang menyimpan dan mengubah energi kimiawi dan yang membuat makro molekul sel dari prekursor sederhana. Di antara sejumlah enzim yang berpartisipasi di dalam metabolisme, terdapat sekelompok khusus yang dikenal sebagai enzim pengatur, yang dapat mengenali berbagai isyarat metabolisme dan mengubah kecepatan katalitiknya sesuai dengan isyarat yang diterima. Melalui aktivitasnya sistem enzim terkoordinasi dengan baik, menghasilkan suatu hubungan yang harmonis diantara sejumlah aktivitas metabolisme yang berbeda, yang diperlukan untuk menunjang kehidupanEnzim diastase merupakan enzim yang dapat memecah bagian dalam atau bagian tengah molekul amilum menjadi senyawa yang lebih sederhana (glukosa). Enzim amilase tergolong dalam enzim hidrolase, sehingga pada umumnya bekerja sebagai katalis pada reaksi hidrolisis. Kerja suatu enzim akan optimal jika ditunjang oleh beberapa hal antara lain pH dan suhu. Namun bila pH terlalu tinggi maka enzim akan mengalami kerusakan yang ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat yang terjadi karena tingkat ionisasi yang terlalu tinggi. Denaturasi protein adalah berubahnya struktur protein dari struktur asalnya atau struktur alaminya.Pada percobaan kali ini dilakukan pengamatan mengenai pengaruh pH terhadap aktifitas enzimdiastase. Untuk mengetahui pengaruh nyata dari pH (tingkat keasaman) ini diperlukan dua tahap pengujian yaitu pengujian Iod dan pengujian Benedict. Pada umumnya setiap enzim memiliki pH optimum, yaitu pH pada saat gugus penerima atau pemberi proton pada sisi katalitik enzim berada pada tingkat ionisasi yang diinginkan. Enzim diastase atau amilase termasuk dalam enzimhidrolase yang berfungsi memecah substrat (pati) dengan bantuan air. Pengujian Iod dilakukan dengan mencampurkan larutan buffer pH 4, pH 6 dan pH 8 dengan substrat 6 ml amilum 1% ke dalam 3 tabung reaksi. Selanjutnya ditambahkan enzimdiastasepada campuran larutan tersebut dan diinkubasi pada suhu 40oC (suhu optimum enzimdiastase) selama 20 menit. Pada tabung I yaitu larutan dengan buffer pH 4 setelah 20 menit dilakukan inkubasi dan diambil setiap 5 menit 1 tetes tidak terjadi perubahan yaitu putih-putih (bening). Pada tabung II yaitu larutan dengan buffer pH 6 setelah 20 menit dilakukan inkubasi dan diambil setiap 5 menit 1 tetes terjadi perubahan warna dari warna putih menjadi biru muda.Sedangkan pada tabung III yaitu larutan buffer pH 8 setelah 20 menit dilakukan inkubasi dan diambil setiap 5 menit 1 tetes warna berubah dari putih menjadi bening. Tapi kelompok lain saat tabung I diinkunbasi perubahan terjadi dari warna bening menjadi kuning keruh, pada tabung II terjadi perubahan terjadi dari warna bening menjadi kuning, sedangkan pada tabung III terjadi perubahan warna dari warna bening menjadi agak kuning.Kemudian warna dari enzim diastase tadi dibandingkan dengan Amilum 1% ditambah Iod (biru tua), glikogen 1% ditambah Iod (kuning), selulosa ditambah Iod (kuning). Perbandingan warna ini digunakan untuk mengetahui bahwa pada rentang pH berapa ia mengubah pati (amilum) menjadi glikogen kemudian mengubah glikogen menjadi glukosa (gula maltosa). Hasil yang diperoleh tidak begitu jauh dari teori. Dari teori dikatakan bila suatu sampel dilakukan uji iod maka warna yang dihasilkan antara kuning kecoklatan biru. Maksudnya jika pH < 7 maka warnanya kuning kecoklatan. Jika pH > 7 warnanya akan biru. Dengan demikian percobaan ini menandakan bahwa pH berpengaruh dalam keoptimalisasian kerja suatu enzim.Tabel 2.2 Hasil Pengamatan Uji Benedict terhadap Pengaruh pH terhadap Aktivitas Enzim Diatase/Amilase.KelSampel+Lar bufferWaktu inkubasiPerubahan warna
1 dan 21 ml buffer pH 4+lar amilum 1 %0 menitBiru-biru
5 menitBiru-biru
3 dan 41 ml buffer pH 6+lar amilum 1 %0 menitBiru-biru
5 menitBiru-biru
5,6 dan 71 ml buffer pH 8+lar amilum 1 %0 menitBiru-biru
5 menitBiru-biru
8 dan 92 ml reagen benedict+1 ml lar sampel Tabung 11 menitTidak ada perubahan warna
10 dan 112 ml reagen benedict+1 ml lar sampel Tabung 21 menitTidak ada perubahan warna
12,13, dan 142 ml reagen benedict+1 ml lar sampel Tabung 31 menitTidak ada perubahan warna
Sumber : Lapaoran SementaraPembahasan :Faktor yang mempengaruhi kerja enzim selain pH adalah suhu. Pada percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzimdiastase. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan semakin tinggi.Energi kinetik akan meningkat pada kompleks enzim dan substrat yang bereaksi. Namun, peningkatan energi kinetik oleh peningkatan suhu mempunyai batas yang optimum. Jika batas tersebut terlewati, maka energi tersebut dapat memutuskan ikatan hidrogen dan hidrofobik yang lemah yang mempertahankan struktur sekunder-tersiernya.Proses pemanasan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan proses inaktivasi enzim meningkat sehingga terjadi denaturasi. Proses denaturasi dapat terjadi karena enzim juga merupakan protein. Aktivitas enzim akan menurun drastis apabila telah mencapai batas suhu maksimumnya. Waktu pemanasan mempunyai pengaruh terhadap aktivitas dan intensitas warna enzim. Semakin lama waktu pemanasan, maka intensitas warnanya akan semakin gelap dan aktivitas enzim akan semakin turun. Enzim akan memecah dan akan membuat aktivitas enzim berhenti yang ditandai dengan warna larutan yang semakin gelap.Pengujian Benedict dilakukan setelah pengujian Iod. Kegunaan uji Iod adalah untuk mengatahui kandungan amilum (polisakarida) pada makanan atau karbohidrat kandungannya. Begitupula dengan kegunaan uji Benedict mengetahui kandungan glukosa (monosakarida) pada karbohidrat yang akan di uji. Selain itu uji benedict juga di gunakan untuk pemeriksaan glukosa dalam urine. Larutan benedict mengandung ion-ion tembaga (II) yang dikompleks dalam sebuah larutan basa. Selain itu mengandung ion-ion tembaga (II) yang kompleks dengan ion-ion sitrat dalam larutan karbonat. Pengompleksan ion-ion tembaga (II) dapat mencegah terbentuknya sebuah endapan (II) karbonat. Pada uji benedict pereaksi ini akan bereaksi dengan gugus aldehid, kecuali dalam gugus aromatik dan alpha hidroksi keton oleh karena itu, meskipun fruktosa bukanlah gula pereduksi, namun karena memiliki gugus alpha hidroksi keton maka fruktosa akan berubah menjadi glukosa dan maltosa dalam suasana basa memberikan hasil positif (+) dengan pereaksi benedict.Pada percobaan kali ini dapat dibahas bahwa praktikum shift 1 pada sampel 1 ml buffer pH 4+larutan amilum 1% setelah 5 menit diinkubasi tidak terjadi perubahan warna. Pada sampel 1ml buffer pH 6+larutan amilum 1% setelah 5 menit diinkubasi tidak terjadi perubahan warna. Pada sampel pH8+larutan amilum 1% setelah diinkubasi juga tidak terjadi perubahan warna. Pada praktikum shift 2 sampel 2 ml reagen benedict+1 ml larutan sampel tabung 1 waktu inkubasi 1 menit tidak terjadi perubahan warna. Pada sampel 2 ml reagen benedict+1 ml larutan sampel tabung 2 waktu inkubasi 1 menit tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan sampel 2 ml reagen benedict+1 ml larutan sampel tabung 3 waktu inkubasi 1 menit juga tidak terjadi perubahan warna. Dari hasil percobaan larutan-larutan tersebut tidak mengalami perubahan warna hal ini membuktikan bahwa larutan tersebut tidak mengandung gula pereduksi. Padahal teori mengatakan bahwa suatu larutan mengandung gula pereduksi jika adanya degredasi amilum menjadi glukosa dengan ditandai adanya endapan merah bata. Warna merah bata yang terbentuk disebabkan oleh maltosa dan glukosa memiliki gugus aldehid yang bebas sehingga dapat mereduksi ion-ion tembaga (Cu) yang terdapat pada larutan benedict menjadi Cu2O yang berwarna merah bata. Hal ini disebabkan mungkin pada saat inkubasi waktu yang diperlukan kurang.
Tabel 2.3 Hasil Pengamatan Pengaruh Suhu terhadap Aktivitas Enzim Diastase/AmilaseKelSampelSuhu InkubasiWaktu InkubasiPerubahan Warna
AwalSesudah inkubasiSetelah ditambah 1 ml 0,01N
1, 22 ml Amilum 1 % + 2 ml diastase40 C30Putih keruhPutih bening ada endapanUngu kehitaman
3, 42 ml Amilum 1 % + 2 ml diastase100 C10Putih keruhPutih bening tanpa endapanBiru kehitaman ada endapan
52 ml Amilum 1 % + 2 ml diastaseSuhu Kamar30Putih keruhBening ada endapanHitam bening
62 ml Amilum 1 % + 2 ml diastaseSuhu Kamar30Putih keruhBening ada endapanUngu pekat
72 ml Amilum 1 % + 2 ml diastase100 C10Putih keruhBening tanpa endapanBiru kehitaman ada endapan
8, 92 ml Amilum 1 % + 2 ml diastase40 C30Putih keruhBeningUngu keruh
10, 11, 142 ml Amilum 1 % + 2 ml diastase100 C10Putih keruhBeningUngu pekat
12, 132 ml Amilum 1 % + 2 ml diastaseSuhu Kamar30Putih keruhBeningHitam bening
Sumber : Laporan Sementara
PembahasanSehubungan pengaruh suhu terhadap aktifitas enzim, semakin meningkat suhu, aktivitas enzim akan semakin meningkat. Pada pemanasan tinggi, enzim yang merupakan suatu protein akan mengalami denaturasi sehingga aktivitas kerjanya menjadi nol. Setiap enzim memiliki suhu optimum tertentu, seperti halnya enzim yang terdapat pada hewan mempunyai suhu optimum antara 400C-500C, pada tumbuhan antara 500C-600C.Pada percobaan ini dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim diastase/amilase. Amilum 1% sebanyak 2 ml dicampur dengan larutan diastase sebanyak 2 ml lalu dipanaskan pada suhu 400C, 1000C, dan pada suhu kamar. Selanjutnya masing-masing larutan ditambah dengan 1ml Iod 0,01 N dan dilakukan pengamatan mengenai perbedaan warna yang terjadi. Hasil yang diperoleh setelah pengujian menunjukkan bahwa setelah dilakukan pemanasan hingga suhu 400C selama 30 menit terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu keruh. Pemanasan setelah suhu 1000C selama 10 menit menyebabkan perubahan warna dari putih menjadi ungu pekat. Sedangkan setelah dipanaskan pada suhu kamar selama 30 menit terjadi perubahan warna dari bening menjadi hitam bening.Pemanasan dengan suhu 400C aktivitas enzim diastase/amilase masih bekerja dengan baik dan pada suhu diatas 400C kerja enzim cenderung tidak meningkat. Hasil tersebut dapat dikatakan sesuai dengan teori dimana suhu optimum enzim yaitu pada suhu 40oC. Enzim sering memperlihatkan kerapuhan akibat suhu jika dipanaskan hingga suhu diatas 50C kebanyakan tidak semua enzim terdenaturasi. Penurunan aktivitas enzim terlihat secara tajam dalam kisaran yang sangat kecil setelah melewati titik muai denaturasi.
Tabel 2.4 Hasil Pengamatan Pengujian Amilase dari KecambahKelSampelPerubahan Warna
Menit ke 0Menit ke 20
1Ekstrak kacang hijauBening- sedikit endapan biru tuaBening- kuning pekat
2Ekstrak kacang hijauBening- beningBening- kuning pekat
3Ekstrak kacang hijauBening- sedikit endapan biru tuaBening- kuning pekat
4Ekstrak kacang hijauBening- sedikit endapan biru tuaBening- kuning pekat
5Ekstrak taogeBening banyak endapan biru tuaBening- putih pekat
6Ekstrak taogeBening banyak endapan biru tuaBening- putih pekat
7Ekstrak taogeBening banyak endapan biru tuaBening- putih pekat
8Ekstrak kacang hijauHijau ungu kehitamanKeruh kuning cerah
9Ekstrak kacang hijauHijau kuning keruhKeruh kuning cerah
10Ekstrak kacang hijauHijau keruh ungu kehitamanKeruh kuning cerah
11Ekstrak kacang hijauHijau keruh ungu kehitamanKeruh kuning cerah
12Ekstrak taogePutih keruh ungu kehitamanPutih keruh- kuning muda
13Ekstrak taogePutih keruh ungu kehitamanPutih keruh- kuning muda
14Ekstrak taogePutih keruh ungu kehitamanPutih keruh- kuning muda
Sumber : Laporan SementaraPembahasanAmilase merupakan enzim pemecah pati dan merupakan enzim hidrolase. Amilase pada percobaan ini didapatkan dari ekstrak biji kacang hijau dan ekstrak taoge yang ditambah larutan amilum yang sudah ditambahkan larutan buffer pH 6 kemudian diinkubasi pada suhu 40oC. Dan pada menit ke-0 dan ke-20 ditetesi larutan Iod 0,01 N serta diamati perubahan warna yang terjadi pada ekstrak kacang hijau maupun ekstrak taoge.Berdasarkan hasil percobaan dari ekstrak kacang hijau sebelum dilakukan inkubasi terjadi perubahan warna dari warna hijau keruh menjadi ungu kehitaman. Setelah di inkubasi pada suhu 40oC selama 20 menit terjadi perubahan warna dari keruh berubah menjadi warna kuning cerah. Enzim amilase bekerja pada suhu kompartemen 40C. Pemanasan yang dilakukan, mengakibatkan enzim amilase menjadi inaktif. Bila dipanaskan secara berlebihan dapat menyebabkan denaturasi protein.Sedangkan percobaan dengan menggunakan ekstrak tauge sebagai bahan uji pada saat sebelum di inkubasi (0oC) terjadi perubahan warna dari putih keruh menjadi warna ungu kehitaman, kemudian setelah dilakukan inkubasi dengan suhu 40oC selama 20 menit juga terjadi perubahan warna dari warna putih keruh menjadi warna kuning muda. Percobaan ini menggunakan bahan uji ekstrak kacang hijau dan ekstrak touge yang bertujuan untuk mempermudah berlangsungnya reaksi enzimatik. Pada percobaan dengan menggunakan bahan larutan ekstrak kacang hijau, terdapat endapan yang lebih banyak dibandingkan pada percobaan dengan bahan larutan ekstrak touge, hal ini menunjukkan bahwa ekstrak touge mempunyai aktivitas amilase lebih besar dibandingkan dengan ekstrak kacang hijau.Enzim amilase bekerja dengan sangat baik pada suhu kamar. Sedangkan, bila suhunya dinaikkan, enzim amilase tidak dapat bekerja dengan baik dalam memecah amilum. Hal ini membuktikan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap cara kerja enzim.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim, yaitu : 1. suhuOleh karena reaksi kimia itu dapat dipengaruhi suhu maka reaksi menggunakan katalis enzim dapat dipengaruhi oleh suhu. Di samping itu, karena enzim adalah suatu protein maka kenaikan suhu dapat menyebabkan denaturasi dan bagian aktif enzim akan terganggu sehingga konsentrasi dan kecepatan enzim berkurang.2. pHUmumnya enzim efektifitas maksimum pada pH optimum, yang lazimnya berkisar antara pH 4,5-8.0. Pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah umumnya enzim menjadi non aktif secara irreversibel karena menjadi denaturasi protein.3. konsentrasi enzimSeperti pada katalis lain, kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim tergantung pada konsentrasi enzim tersebut. Pada suatu konsentrasi substrat tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim.4. konsentrasi substratHasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi substrat akan menaikkan kecepat reaksi. Akan tetapi, pada batas tertentu tidak terjadi kecepatan reaksi, walaupn konsenrasi substrat diperbesar.5. zat-zat penghambat / inhibitorHambatan atau inhibisi suatu reaksi akan berpengaruh terhadap penggabungan substrat pada bagian aktif yang mengalami hambatan.
E. KESIMPULAN1. Pada pengujian pengaruh pH terhadap aktivitas enzim diastase/amilase (Uji Iod) tidak terjadi perubahan warna yang signifikan yang menunjukkan pH optimum untuk kerja enzim amilase. pH optimum untuk kerja enzim yaitu berkisar antara 6-8. 2. Pada pemanasan enzim amilase dengan suhu 400C terjadi perubahan warna dari bening menjadi kunign keruh sedangkan pada pemanasan dengan suhu diatas 400C mengakibatkan warna enzim menjadi ungu pekat (denaturasi). Sehingga dapat dikatakan suhu optimum enzim amilase adalah pada suhu 40oC.3. Pengujian amilase dari kecambah pada percobaan dengan menggunakan bahan uji ekstrak kacang hijau, terdapat endapan yang lebih banyak dibandingkan pada percobaan dengan bahan uji ekstrak touge, hal ini menunjukkan bahwa ekstrak touge mempunyai aktivitas amilase lebih besar dibandingkan dengan ekstrak kacang hijau.
DAFTAR PUSTAKA
Girindra, Aisyah. 1990. Biokima I. Gramedia. Jakarta.Hidayat, Iman. 2005. Pengaruh pH terhadap Aktivitas Endo-1,4--Glucanase Bacillus sp. AR 009. Jurnal Biodiversitas Vol 6, No 4, Hal. 242-244.Ismadi, M. 1983. Biokimia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.Naiola, Elidar. 2008. Mikrobia Amolitik pada Nira dan Laru dari Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Biodiversitas Vol. 9, No 3, Hal. 165-168.Page, David S. 1997. Prinsip-Prinsip Biokimia. Erlangga. Jakarta.Poedjiadi, Anna. 1994. Dasar-Dasar Biokimia. Universitas Indonesia. Jakarta.Setiasih, Siswati, B. Wahyuntari, Trismilah, D. Apriliani. 2006. Karakterisasi Enzim -Amilase Ekstrasel dari IsolatBakteri Termofil SW2. Jurnal Kimia Indonesia Vol 1, No 1, Hal. 22-27.Suarni, R. Patong. 2007. Potensi Kecambah Kacang Hijau sebagai Sumber Enzim -Amilase. Jurnal Kimia Vol. 7, No. 3, Hal. 332-336.Surchandra, Th, S. S. Roy, N. R. Singh, M. R. Sahoo, N. Prakash. 2012. Partial Purification and biochemical characterization of acid phosphatase from germinated mung bean (Vigna radiata) seeds. African Journal of Biotechnology Vol 11, No 103, Hal. 16777-16778.
ACARA IIIISOLASI PATI UBI KAYU DAN FERMENTASI
A. TujuanTujuan dari praktikum acara III Isolasi Pati Ubi Kayu dan Fermentasi adalah1. Mengetahui proses isolasi amilum dari ubi kayu dengan hidrolisisnya2. Mengetahui uji kualitatif terhadap hidrolisis pati3. Mengidentifikasi adanya pati, polisakarida dan gula pereduksi pada pengamatan hidrolisa pati4. Mengetahui uji pikrat, uji barfoed, uji molisch, uji seliwanoff dan uji benedict5. Mengetahui reaksi peragian (fermentasi) dengan uji benedict
B. Tinjauan PustakaKarbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi hampir seluruh penduduk dunia, khususnya penduduk negara yang sedang berkembang. Walaupun jumlah kalori yang dapat dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat hanya 4 Kal (kkal) bila dibandingkan dengan protein dan lemak, karbohidrat merupakan sumber kalori yang murah. Dalam tubuh karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein (Winarno, 2004). Karbohidrat adalah polihidroksi aldehida atau polihidroksi keton yang mempunyai rumus molekul umum (CH2O)n yang pertama lebih dikenal sebagai golongan aldosa dan yang yang kedua adalah ketosa. Dari rumus umum dapat diketahui bahwa krbohidrat adalah suatu polimer. Senyawa yang menyusunnya adalah monomer-monomer. Dari jumlah monomer yang menyusun polimer tersebut, maka karbohidrat dibagi menjadi tiga golongan yaitu, monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida (Martoharsono, 1990). Terdapat tiga kelas besar karbohidrat yaitu, monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Polisakarida dan oligosakarida dapat dihidrolisa secara sempurna untuk menghasilkan monosakarida, dan hidrolisa lebih lanjut tidak menghasilkan molekul apapun yang lebih kecil dari monosakarida. Oligosakarida adalah polimer yang terdiri dari dua hingga enam satuan monosakarida. Polisakarida seperti pati dan selulosa mengandung beribu-ribu satuan monosakarida yang dihubungkan dengan sambungan-sambungan kovalen yang dapat dihidrolisa (Page, 1989).Gula sederhana dan zat-zat yang dengan hidrolisis menghasilkan gula sederhana disebut karbohidat. Nama karbohidrat digunakan karena komposisi kebanyakan gula, pati, dan selulosa berpadanan dengan hidrat hipotesis dari karbon. Pemecahan (hidrolisis) molekul gula, pati, selulosa yang kompleks menjadi molekul monosakarida mudah dilakukan dalam laboratorium dengan mendidihkan larutan atau suspensi karbohidrat itu dengan larutan encer asam (Keenan, 1992). Pati adalah sumber karbohidrat yang penting dalam makanan dan merupakan sumber utama. Pati adalah campuran polisakarida amilosa dan amilopektin. Dapat dipisah satu dari yang lain dengan cara fisik atau kimia. Pati terdiri dari 15% amilosa dan 85% amilopektin. Amilosa adalah polisakarida berantai lurus. Amilosa dapat dianggap baik sebagai polimaltosa maupun sebagai poliglukosa. Pati memberi warna biru tua yang karakteristik bila direaksikan dengan yodium. Reaksi ini digunakan untuk mendeteksi adanya pati, karena reaksinya sangat peka dan spesifik (Tarigan, 1983). Pati tidak larut dalam air dan dalam analisis pati, memberikan warna biru dengan iodium. Hasil hidrolisis pati/ amilum adalah glukosa (Harrow, 1946 dalam Manatar, 2012). Hidrolisis pati akan terjadi pada pemanasan dengan asam encer dimana berturut-turut akan dibentuk amilosa yang memberi warna biru dengan iodium, amilopektin yang memberi warna merah dengan iodium. Pati sagu disebut juga poliglukosa, karena unit monomernya glukosa (Anwar, 1994 dalam Manatar, 2012).Pati atau karbohidrat dapat diperoleh dari berbagai jenis tumbuhan seperti ketela pohon, ketela rambat, padi, pisang dan sebagainya, Di dalam tumbuh tumbuhan, pati disimpan dalam batang, akar, buah atau biji sebagai cadangan makanan (Agra dkk, 1973). Ditinjau dari rumus kimianya pati adalah karbohidrat yang berbentuk polisakharida berupa polimer anhidro monosakarida dengan rumus umum (C6H10O5)n. Penyusun utama pati adalah amilosa dan amilopektin. Amilosa tersusun atas satuan glukosa yang saling berkaitan melalui ikatan 1-4 glukosida, sedangkan amilopektin merupakan polisakharida yang tersusun atas 1-4 glikosida dan mempunyai rantai cabang 1-6 glukosida (Kirk and Othmer, 1954 dalam Yuniwati dkk, 2011).Selama ini penentuan kadar pati oleh para pembeli di lapangan dilakukan berdasarkan perbedaan berat umbi di udara dan berat umbi di dalam air, kemudian dihitung berdasarkan rumus yang dirancang oleh International Starch Institute (1999). Metode ini telah dibuktikan mempunyai korelasi yang tinggi dengan kadar pati yang ditentukan secara kimia seperti hidrolisis asam. Akan tetapi, metode ini kurang praktis dilakukan di lapangan karena beberapa hal yaitu memerlukan jumlah air yang banyak yang biasanya tidak tersedia di perkebunan ubi kayu, memerlukan waktu yang relatif lama dalam pengukurannya, perlu tenaga operator yang terlatih serta harga alat mahal (Nurdjanah dkk, 2007).Hidrolisis pati didapatkan dari dua langkah hidrolisis pati didinginkan, disaring untuk menghilangkan trub dan disterilkan dalam uap autoclave. Etanol fermentasi ragi dalam kondisi anaerob. Fermentasi diulang kembali dengan cara yang sama dengan konsentrasi inokulum dan kondisi laboratorium. Hal ini merupakan produksi etanol yang berasal dari pati singkong (Okon et all, 2009).Hidrolisis pati melibatkan pembelahan yang glukosidik ikatan antara unit monomer (D-glucose) pati. Ini adalah reaksi yang dikatalisis oleh encer asam (hidrolisis asam), enzim (enzim-enzim hidrolisis). Ada juga teknik mikroba mengkonversi pati menjadi produk yang diinginkan (Omemu et all, 2005 dalam Anozie and A.F Aderibigbe, 2011).Mengingat potensi besar untuk assava pati industri produksi sirup di negara-negara tropis. Hidrolisis enzimatik pati merupakan langkah pertama banyak industri konversi produk pertanian menjadi makanan, minuman, dan bahan kimia. Amilase yang mengkatalisasi hidrolisis pati yang baik hadir dalam olahan bahan baku atau diproduksi secara terpisah dengan fermentasi (Aderibigbe et all, 2012).
C. Metode Penelitian1. Alata. Erlenmeyerb. Kertas saringc. Lempeng porselin/ test plated. Gelas bekere. Gelas ukurf. Penangas airg. Penjepith. pH meteri. Pipet ukurj. Propipet k. Rak tabung reaksil. Tabung reaksi2. Bahana. Alkohol 95 %b. Aquadesc. Asam pikrat jenuhd. Larutan fruktosa 1%e. Larutan HCl pekatf. Larutan H2SO4 pekatg. Larutan hidrolisa patih. Larutan iodin 0,01 Mi. Larutan glukosa 1%j. Larutan NaOH 8Nk. Larutan Na2CO3 1Ml. Larutan pati 1%m. Larutan ragi roti 5%n. Larutan sukrosa 10%o. Pereaksi barfoedp. Pereaksi fehlingq. Pereaksi molischr. Pereaksi seliwanoffs. Reagent barfoed dan buffer fosfatt. Reagen benedictu. Suspensi ragi roti 5%v. Ubi kayu
3. Cara Kerja3.1 Isolasi Pati Ubi Kayua. Isolasi Pati Umbi/ Biji-bijianUbi kayu dikupas dan ditimbang sebanyak 100 gramUbi kayu dicuci dan dipotong kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam blenderDitambah 200 ml aquades kemudian diblender selama 30 detik dan lakukan beberapa kaliDitambah lagi 200 ml aquades lalu dikocokHasil diendapkanLarutan keruhdan mengendapLarutan jernihDisaring residu dengan kertas saring dan larutan yang keruh ditampung dalam gelas ukuran 500 mlDitambah 50 ml alkohol 95 %Disaring dengan kertas saring dan dikeringkanDidekantasi
b. Hidrolisis Pati25 ml larutan pati 1%(dibuat dari amilum tahap pertamaDiamati derajat reduksi yang terjadi
Ditambah 2 ml reagen fehlingDimasukkan ke dalam tabung reaksiDitambah 1 tetes larutan iod 0,01 NDiteteskan pada lempeng porselin/ test platePada waktu yang sama diambil 1 ml larutan dan dilakukan uji fehling
Diambil 1 ml larutan dan dilakukan uji iod pada menit ke 5, 10 dan 15
Ditambahkan 10 tetes HCl pekat dan dididihkan
Dimasukkan ke dalam gelas bekerDiamati derajat reduksi yang terjadi
c. Uji Kualitatif terhadap Hidrolisis Pati Diambil sisa hidrolisis pati 1 % lalu dipanaskan dalam penangas air selama 10 menitDitambah 0,5 ml NaOH 8 NDidinginkan dan dinetralkanDiamati perubahan yang terjadiDihitung tingkat keasaman menggunakan kertas pH kemudian selanjutnya untuk diuji kualitatif
1) Uji MolischDiamati perubahan yang terjadiDitambah 5 ml asam sulfat pekat dengan hati-hati dan perlahan-perlahan melalui dinding tabung reaksiDitambah 2 tetes pereaksi molisch Dimasukkan 2 mllarutan hidrolisat pati, larutan pati 1%, larutan fruktosa 1%, dan larutan glukosa 1% ke dalam masing-masing tabung reaksiDisiapkan 4 tabung reaksi
2) Uji PikratDimasukkan 2 ml larutan glukosa 1%, fruktosa 1%, hidrolisa pati dan larutan pati 1% pada masing-masing tabung Ditambahkan 1 ml asam pikrat dan 0,5 ml 1 MDipanaskan dalam penangas air sampai mendidihDiamati dan dicatat perubahan yang terjadiDisiapkan 4 tabung reaksi
3) Uji BarfoedHidrolisa pati, glukosa 1%, fruktosa 1% dan larutan pati 1%Dibandingkan kecepatan reduksi pada setiap sampelDididihkan tabung dalam penangas airDimasukkan ke dalam tabung reaksiDiamati perubahan yang terjadi
4) Uji SeliwanoffDisiapkan 4 tabung reaksiDimasukkan larutan pati 1%, hidrolisat pati, glukosa 1%, fruktosa 1% ke dalam masing-masing tabung reaksiDitambahkan 2 ml larutan pereaksi pada masing-masing tabungDipanaskan selama 10 menitDiamati perubahan warna yang terjadiDicatat hasil percobaan
5) Reaksi Peragian1 ml larutan ragi roti 5% dan 1 ml larutan pati 1%Dimasukkan ke dalam tabung reaksiDiamati perubahan yang terjadiDipanaskan ke dalam penangas air selama 5 menitDitambah 2 ml larutan benedict ke dalam masing-masing tabung
6) Uji BenedictDimasukkan 2 ml reagen benedict dan 1 ml larutan sampel (larutan suspensi ragi roti 5% dan larutan sukrosa 10%) ke dalam tabung reaksiDipanaskan dalam penangas air selama 5 menit
Diamati perubahan yang terjadi
D. Pembahasan1. Isolasi Pati Ubi Kayua. Isolasi Pati Ubi KayuRandemen pati dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Dari percobaan yang telah dilakukan, perhitungan nilai rendemen pati ubi kayu berdasarkan rumus diatas adalah x 100% = 18,8 % dan hasil akhir pada sampel tidak terdapat endapan. Rendemen yang tinggi dapat diperoleh bila pembentukan oligosakarida berbobot molekul rendah (malto-oligosakarida) dan glukosa lebih banyak. Nilai rendemen dipengaruhi oleh jumlah produk yang terbentuk.Cara proses hidrolisa memberikan perbedaan pengaruh terhadap rendemen pati. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah polimer rantai panjang pati yang dipecah oleh enzim untuk masing-masing perlakuan hampir sama. Hidrolisis enzimatis akan memutus rantai polimer pati secara spesifik pada percabangan tertentu. Reaksi Sederhana Pembentukan Pati : nC6H12O6 (C6H12O6)n + n H2OPati tidak larut dalam air dan dalam analisis pati, memberikan warna biru dengan iodium. Hasil hidrolisis pati/ amilum adalah glukosa (Harrow, 1946 dalam Manatar, 2012). Hidrolisis pati akan terjadi pada pemanasan dengan asam encer di mana berturut-turut akan dibentuk amilosa yang memberi warna biru dengan iodium, amilopektin yang memberi warna merah dengan iodium. Pati sagu disebut juga poliglukosa, karena unit monomernya glukosa(Anwar, 1994 dalam Manatar, 2012).Hidrolisis asam dapat memecah hemiselulosa dengan efektif menjadi (arabinose, galaktosa, manosa, dan xilosa) dan laruta oligomer yang dapat meningktkan konversi selulosa (Sun dan Cheng, 2005 dalam Susmiati, 2011). Suhu, waktu, dan konsentrasi asam yang digunakan selama proses terbentuknya komponen-komponen produk samping dan inhibitor fermentasi (Susmiati dkk, 2011).Dari hasil percobaan, didapatkan nilai rendemen pati ubi kayu adalah 18,8 %. Sedangkan randemen ubi kayu dalam jurnal terkini adalah 25 % (Lubis, 2012). Pengolahan ubi kayu menjadi tepung memiliki beberapa keunggulan yaitu lebih tahan lama dalam penyimpanan, mudah didistribusikan karena praktis, permintaan yang cukup tinggi di pasaran, ringan. Tepung pati banyak di manfaatkan sebagai bahan baku ataupun campuran tambahan pada berbagai macam produk, antara lain sebagai bahan baku biji mutiara, sirup cair, alkohol dan lem. Prinsip dasar proses produksi tepung pati adalah ekstraksi ubi kayu menjadi tepung pati. Tahapan proses tepung pati yaitu pengupasan, pencucian, pemarutan, penyaringan, pengendapan pati, pengeringan pati, penggilingan dan penyaringan, dan pengepakan.b. Hidrolisis PatiTabel 3.1 Hidrolisis PatiKelBahanUji Waktu(menit) Perubahan WarnaKeterangan
Awal Akhir
1Larutan pati 1% terhidro-lisisIod 5Bening Biru Terdapat pati
10BeningBiru gelapTerdapat pati
15BeningBiru kehitamanTerdapat pati
85BeningKuning beningTerdapat glikogen
10BeningKuning beningTerdapat glikogen
15BeningKuning pekatTerdapat glikogen
2Fehling 5BeningBiru mudaTidak terdapat gula pereduksi
10BeningBiruTidak terdapat gula pereduksi
15BeningBiru tuaTidak terdapat gula pereduksi
95BeningBiru beningTidak terdapat gula pereduksi
10BeningBiru agak pekatTidak terdapat gula pereduksi
15BeningBiru pekatTidak terdapat gula pereduksi
Sumber : Laporan SementaraPada uji iod, larutan contoh diasamkan dengan HCL. Sementara itu dibuat larutan iod dalam KI. Larutan contoh sebanyak satu tetes ditambahkan ke dalam larutan iodin. Timbulnya warna biru menunjukkan adanya pati dalam larutan contoh, sedangkan warna merah menunjukkan adanya glikogen atau eritrodekstin (Winarno, 2004). Uji iod dilakukan bertujuan untuk menganalisis adanya kandungan pati pada suatu larutan dan untuk mengidentifikasi polisakarida. Hidrolisapati dapat direaksikan sebagai berikut : (C6H10O5)n+n(H2O) n(C6H12O6) Pati GlukosaDari percobaan uji iod yang telah dilakukan didapatkan hasil, dari kelompok 1 yaitu pada menit ke-5 warna berubah dari bening menjadi biru, pada menit ke-10 warna berubah dari bening menjadi biru gelap/ tua dan pada menit ke-15 warna berubah dari bening menjadi biru kehitaman. Sedangkan hasil dari kelompok 8 yaitu pada menit ke-5 warna berubah dari bening menjadi kuning bening, pada menit ke-10 warna berubah dari bening menjadi kuning, pada menit ke-15 warna berubah dari bening menjadi kuning pekat.Dari hasil percobaan tersebut sesuai dengan teori dalam buku Winarno yaitu timbulnya warna biru menunjukkan adanya pati dalam larutan contoh, sedangkan warna merah menunjukkan adanya glikogen atau eritrodekstin. Pada kelompok 1 terjadi perubahan warna menjadi biru yang menunjukkan adanya pati dalam larutan contoh. Hal ini disebabkan oleh struktur molekul pati yang berbentuk spiral, sehingga akan mengikat molekul iodin dan terbentuklah warna biru. Sedangkan hasil percobaan dari kelompok 8 menunjukkan perubahan warna menjadi kuning hal ini karena apabila polimernya kurang dari dua puluh maka akan menghasilkan warna merah, yang memiliki polimer 6,7, dan 8 membentuk warna coklat, sedangkan yang memiliki polimer lebih kecil dari lima sehingga tidak memberikan warna dengan iodin. Dari warna yang kuning (mendekati merah) didapatkan tersebut juga menunjukkan adanya glikogen atau eritrodekstrin.Reaksi ini dilakukan dalam suasana basa lemah. Reaksi kualitatif yang sangat peka terhadap karbohidrat tetapi tidak selektif. Aldehid dan senyawa-senyawa reduktor lain memberi hasil positif. Pembentukan endapan warna merah bata dari tembaga oksida adalah kriteria reaksi positif. Selanjutnya asam yang terbentuk langsung bereaksi dengan natrium hidroksida membentuk garam (Tarigan, 1983). Uji fehling ini bertujuan untuk memperlihatkan ada atau tidaknya gula pereduksi dalam larutan sampel. Dari percobaan yang telah dilakukan, setelah larutan pati 1% dipanaskan dan diberi reagen fehling didapatkan hasil yaitu, dari kelompok 2 yaitu pada menit ke-5 warna berubah dari bening menjadi biru muda, pada menit ke-10 warna berubah dari bening menjadi biru dan pada menit ke-15 warna berubah dari bening menjadi biru tua. Sedangkan hasil dari kelompok 9 yaitu pada menit ke-5 warna berubah dari bening menjadi biru bening, pada menit ke-10 warna berubah dari bening menjadi biru agak pekat, pada menit ke-15 warna berubah dari bening menjadi biru pekat. Pati atau larutan pati merupakan polisakaridaatau karbohidrat kompleks karena polisakarida tidak memiliki gugus gula reduksi sehingga memberikan reaksi yang negatif (warna biru) pada uji Fehling.Dari hasil yang didapatkan tersebut tidak sesuai dengan teori yang diterangkan dalam buku Tarigan yaitu terdapat endapan merah bata dari tembaga oksida yang menunjukkan reaksi positif adanya gula pereduksi pada larutan sampel, karena larutan yng digunakan pada percobaan ini adalah larutan pati. Larutan pati merupakan karbohidrat kompleks karena tidak memiliki gugus gula reduksi sehingga memberikan reaksi negatif (warna biru).
c. Uji Kualitatif terhadap Hidrolisis PatiTabel 3.2 Uji Kualitatif terhadap Hidrolisis PatiKel Sampel Warna Setelah ditambah NaOHKeterangan
Sebelum Sesudah
3Sisa hidrolisis patiBening Bening keruhKuning keruhAda endapan
10BeningBeningMenjadi 2 lapisan:Atas : beningBawah : keruhTidak ada endapan
Sumber : Laporan SementaraUji kualitatif terhadap hidrolisis pati bertujuan untuk menganalisis sakarida dalam bahan makanan berdasarkan sifat-sifat sakarida dan reaksi-reaksi kimia yang spesifik. Cara melakukan uji kualitatif ini yaitu, sisa hidrolisis pati (sampel) dipanaskan selama 10 menit dalam penangas air. Kemudian didinginkan dan dinetralkan dengan ditambah larutan NaOH 8N, lalu dicek dengan kertas pH.Karbohidrat dengan zat tertentu akan menghasilkan warna tertentu yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif. Bila karbohidrat direaksikan dengan larutan naftol dalan alkohol, kemudian ditambahkan H2SO4 pekat secara hati-hati, pada batas cairan akan terbentuk furtural yang berwarna ungu. Reaksi ini disebut reaksi Molisch dan merupakan reaksi umum bagi karbohidrat (Winarno, 2004). Dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa pada kelompok 3 setelah sampel sisa hidrolisis pati dipanaskan selama 10 menit terdapat endapan, kemudian setelah diberi NaOH berubah warna menjadi kuning keruh, sedangkan pada kelompok 10 setelah sisa hidrolisis pati dipanaskan selama 10 menit tidak ada perubahan warna, setelah diberi NaOH terjadi perubahan larutan menjadi dua lapisan, lapisan atas bening dan lapisan bawah keruh.
1) Uji MolischTabel 3.3 Uji MolischKel Sampel Perubahan WarnaKeterangan
AwalAkhir
1Larutan glukosa 1%Bening Ungu kehitamanAda endapan merah bata
8BeningUngu pekatAda endapan ungu gelap kehitaman
2Larutan fruktosa 1%BeningHitamAda endapan merah bata
9BeningUngu pekatAda endapan ungu gelap kehitaman
3Hidrolisat patiBeningHitamAda endapan merah bata
10BeningUngu pekatAda endapan ungu gelap kehitaman
4Larutan pati 1%BeningUngu kehitamanAda endapan merah bata
11BeningUngu pekatAda endapan ungu kehitaman
Sumber : Laporan SementaraUji molisch digunakan untuk menentukan karbohidrat secara umum. Pada uji ini 2 ml larutan sampel ditambah dengan 2 tetes pereaksi molisch kemudian ditambah 5 ml asam sulfat pekat (H2SO4) melalui dinding tabung secara hati-hati sehingga timbul dua lapisan cairan dalam tabung reaksi di mana larutan sampel akan berada di atas. Cincin berwarna merah ungu pada batas kedua cairan menunjukkan adanya karbohidrat dalam larutan sampel (Winarno, 2004).Hasil percobaan yang didapatkan yaitu, pada sampel larutan glukosa 1% terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu pekat/ kehitaman, pada sampel larutan fruktosa 1% terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu pekat dan hitam, pada sampel hidrolisat pati terjad perubahan warna dari bening menjadi ungu pekat dan hitam, dan pada sampel larutan pati 1% terjadi perubahan warna dari bening menjadi ungu pekat/ kehitaman. Dari hasil yang didapat tersebut secara keseluruhan sesuai dengan teori yang ada, bahwa warna violet (ungu) kemerah-merahan pada batas kedua cairan menunjukkan reaksi positif larutan sampel yang diuji mengandung karbohidrat. Reaksi pada uji molisch adalah sebagai berikut :
Larutan H2SO4 berfungsi untuk menghidrolisis karbohidrat dalam uji molisch. Asam sulfat pekat bertindak sebagai agen dehidrasi yang bertindak pada gula untuk membentuk furfural dan turunannya yang kemudian dikombinasikan dengan alfa-naftol untuk membentuk produk berwarna. Reaksi pembentukan furfural ini adalah reaksi dehidrasi atau pelepasan molekul air dari suatu senyawa di mana pereaksi molish membentuk cincin berwarna ungu pada larutan glukosa, laktosa, kanji, madu dan potongan kertas. Cincin ungu pada glukosa lebih banyak karena merupakan monosakarida. Sedangkan kanji adalah polisakarida yang harus dihidrolisis menjadi monosakarida terlebih dahulu sebelum terdehidrasi menjadi furfural. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian dengan molish sangat spesifik untuk menunjukkan adanya golongan monosakarida (glukosa dan fruktosa), disakarida (sukrosa dan laktosa) dan polisakarida (amilum dan dekstrin) pada larutan karbohidrat.
2) Uji PikratTabel 3.4 Uji PikratKel SampelPerubahan WarnaKeterangan
AwalAkhir
1Larutan pati 1%Kuning Kuning kehijauanAda gelembung dan endapan
8Kuning beningKuning pekatTidak ada gelembung dan endapan
5Glukosa 1%KuningOrangeTidak ada gelembung da endapan
12Putih beningMerah bataTidk ada gelembung dan endapan
6Fruktosa 1%Kuning beningMerah kecoklatanAda sedikit gelembung dan tdak ada endapan
13BeningBeningTidak ada gelembung dan endapan
7Hidrolisa patiKuning beningKuning kemerahanAda gelembun dan endapan
14Kuning beningMerah bataTidak ada gelembung dan endapan
Sumber : Laporan SementaraUji pikrat digunakan untuk menguji adanya gugus pereduksi dalam suatu glukosa. Sampel yang digunakan pada uji pikrat sama dengan pada uji molisch. Akan tetapi pada uji pikrat tidak ditambah dengan H2SO4 melainkan ditambah dengan Na2CO3. Fungsi penambahan Na2CO3 adalah untuk mengetahui terjadinya perubahan warna pada masing-masing sampel yang digunakan. Hasil positif pada uji pikrat akan menghasilkan larutan yang berwarna orange (awalnya kuning). Empat sampel pada uji pikrat yaitu glukosa 1%, fruktosa 1%, larutan pati 1% dan hidrolisa pati menunjukkan bahwa pada sampel glukosa 1% dan fruktosa 1% terjadi reaksi positif dengan adanya perubahan warna merah kecoklatan (merah bata) dan hal ini sesuai dengan prosedur kerja tetapi pada sampel larutan pati 1% dan hidrolisa pati reaksinya negatif, hanya sedikit terjadi perubahan warna. Hal ini sesuai dengan pendapat Fessenden (1997) bahwa salah satu sifat karbohidrat dapat beroksidasi kecuali polisakarida. Dalam uji pikrat semua monosakarida dan disakarida membentuk warna merah, kecuali larutan pati 1% dan hidrolisa pati karena tidak dapat beroksidasi. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Harold (2003) yang menyatakan bahwa karbohidrat apabila ditambah dengan asam pikrat akan berubah warna merah kecuali polisakarida. Reaksi uji Pikrat adalah sebagai berikut : CHO | H-C-OH | OH-C-H + | H-C-OH | H-C-OH | CH2O (Glukosa) (Asam pikrat)Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pada sampel glukosa 1% yang dilakukan oleh kelompok 5 dan 12 warna yang dihasilkan orange dan merah bata dari warna semula kuning dan putih bening. Pada sampel fruktosa 1% yang dilakukan oleh kelompok 6 dan 13 warna yang dihasilkan merah kecoklatan coklat dari warna semula kuning. Sedangkan pada sampel larutan pati 1% yang dilakukan oleh kelompok 1 dan 8 warna yang dihasilkan kuning kehijauan dan kuning pekat dari warna semula kuning dan pada sampel hidrolisa pati yang dilakukan oleh kelompok 7 dan 14 warna yang dihasilkan kuning kemerahan dan merah bata dari warna awal kuning. Faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil pada uji pikrat yaitu larutan yang dipergunakan dan lama pemanasan.3) Uji BarfoedTabel 3.5 Uji BarfoedKel Sampel Perubahan WarnaKeterangan
AwalAkhir
2Glukosa 1% + 3ml pereaksi barfoedBiruUngu kehitamanAda endapan merah bata
9Biru terangBiru agak gelapAda endapan merah bata
3Fruktosa 1% + 3ml pereaksi barfoedBiru Biru tuaAda endapan + gelembung
10Biru terangBiru agak gelapAda endapan merah bata
4Hidrolisa pati + 3ml pereaksi barfoedBiruBiruAda gelembung
11Biru terangBiru agak gelapAda endapan
5Larutan pati 1% + 3ml pereaksi barfoedBiruBiruAda gelembung
12BiruBiru Ada gelembung
Sumber : Laporan SementaraUji barfoed digunakan untuk mengidentifikasi antara monoskarida, disakarida, dan polisakarida. Pereaksi barfoed merupakan larutan tembaga asetat dalam air yang ditambahkan asam asetat atau asam laktat. Pereaksi ini digunakan untuk membedakan monosakarida dan disakarida dengan cara mengontrol kondisi percobaan, seperti pH dan waktu pemanasan. Senyawa Cu2+tidak membentuk Cu(OH)2dalam suasana asam. Jadi Cu2O terbentuk lebih cepat oleh monosakarida dari pada oleh disakarida.Pereaksi barfoed digunakan untuk membedakan monosakarida reduktor dan disakarida reduktor. Perbedaan kecepatan reaksi reduksi larutan tembaga asetat dalam asam asetat adalah reaksi ini. Selang tenggang waktu tertentu, biasanya pemanasan selama 10 menit, hanya monosakarida yang akan mereduksi ion tembaga (II), dan terbentuk endapan tembaga (I) oksida yang berwarna merah bata. Jika pemanasan diperpanjang, disakarida terhidrolisis oleh asam, dan monosakarida yang dihasilkan akan memberikan reaksi positif (Tarigan, 1983).Fungsi pemanasan larutan sampel pada uji pikrat yaitu agar ikatan-ikatan yang terdapat pada karbohidrat seperti, glukosa, sukrosa, amilum dan selulosa, akan terurai menjadi satuan monosakarida. Akan tetapi, jika proses pemanasan terlalu lama akan menyebabkan perubahan warna tidak terdeteksi. Reaksi uji Barfoed adalah :C6H12O6 + CuSO4 + CH3COOH Cu2O (endapan merah bata)Endapan berwarna merah bata pada uji barfoed ini menunjukkan adanya monosakarida dalam larutan sampel karena terbentuk hasil Cu2O. Pada sampel yang diujikan yaitu glukosa 1%, fruktosa 1%, hidrolisa pati, menunjukkan adanya endapan merah bata yang menunjukkan adanya gugus monosakarida pada sampel tersebut. Sedangkan pada sampel larutan pati 1% tidak ada endapan setelah dipanaskan. Hal ini berarti bahwa tidak adanya gugus monosakarida pada larutan pati 1%.
4) Uji Seliwanoff Tabel 3.6 Uji SeliwanoffKel SampelPerubahan WarnaKet
AwalAkhir
6Glukosa 1%Kuning beningKuning kecoklatanMengandung gugus ketosa
13Kuning beningMerahMengandung gugus ketosa
7Fruktosa 1%Kuning beningMerah kecoklatanMengandung gugus ketosa
14Kuning beningOrangeMengandung gugus ketosa
1Hidrolisa pati Kuning beningMerah kecoklatanMengandung gugus ketosa
8Kuning beningMerahMengandung gugus ketosa
2Larutan pati 1%Kuning beningCoklat beningMengandung gugus aldosa
9Kuning beningKuning beningMengandung gugus aldosa
Sumber : Laporan SementaraUji Seliwanoff digunakan untuk membedakan monosakarida aldosa dan monosakarida ketosa. Ketosa dibedakan dari aldosa via gugus fungsi keton/ aldehida gula tersebut. Jika gula tersebut mempunyai gugus keton, ia adalah ketosa. Sebaliknya jika ia mengandung gugus aldehida, ia adalah aldosa. Reaksi uji Seliwanoff adalah: Uji ini didasarkan pada fakta bahwa ketika dipanaskan, ketosa lebih cepat terdehidrasi daripada aldosa. Sampel akan bereaksi dengan resorsinol yang terdapat dalam Seliwanoff yang akan menghasilkan warna merah bata pada sampel yang mengandung gugus ketosa. Pada percobaan yang dilakukan ini tidak terdapat gugus ketosa karena tidak ada yang menghasilkan warna merah bata. Sedangkan pada fruktosa, glukosa, larutan pati serta hidrolisat pati pada uji seliwanoff tersebut tidak mengalami perubahan warna menjadi merah bata sehingga termasuk dalam gugus aldosa. Faktor-faktor yang mempengaruhi uji seliwanoff ini adalah lama tidaknya proses inkubasi.Uji seliwanoff dilakukan dengan mencampurkan larutan pereaksi dan larutan contoh atau larutan sampel kemudian ditempatkan dalam air mendidih beberpa menit. Jika terjadi perubahan warna merah cherry menunjukkan adanya fruktosa dalam larutan sampel (Winarno, 2004).Manfaat dari uji seliwanoff adalah untuk mengidentifikasi adanya kandungan fruktosa dalam sampel yang diuji. Kandungan fruktosa dapat diidentifikasi ketika adanya perubahan warna merah setelah sampel uji yang telah dicampurkan dengan larutan pereaksi dipanaskan. Pemanasan dilakukan bertujuan untuk mengetahui perubahan warna pada sampel uji untuk mengidentifikasi adanya kandungan fruktosa yang dapat juga digunakan untuk membedakan sampel uji termasuk monosakarida aldosa dan monosakarida ketosa.Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pada sampel hidrolisa pati, fruktosa 1%, glukosa 1% terjadi perubahan warna yang menunjukkan bahwa larutan sampel tersebut mengandung fruktosa. Perubahan warna yang terjadi yaitu kuning bening menjadi merah, merah kecoklatan dan merah bata. Namun pada larutan pati 1% tidak ada perubahan warna menjadi merah, tetapi masih tetap kuning. Hal ini menunjukkan tidak adanya fruktosa pada kandungan larutan pati. Jadi yang termasuk monosakarida aldosa adalah larutan pati 1%, sedangkan yang termasuk monoosakarida ketosa adalah hidrolisa pati, fruktosa 1%, glukosa 1%.Akan tetapi, secara teori hidrolisa pati bukan termasuk jenis gula. Hanya glukosa dan fruktosalah yang termasuk jenis gula. Perbedaan ini kemungkinan terjadi karena kesalahan saat melakukan prosedur praktikum atau kesalahan kurang telitinya saat pengamatan.5) Reaksi PeragianTabel 3.7 Reaksi PeragianKel Sampel Reaksi yang terjadiKeterangan
4Hidrolisa patiAda gelembung CO2 dan tidak ada endapanReaksi peragian sedikit
5Larutan pati 1%Ada gelembung CO2 dan tidak ada endapanReaksi peragian sedikit
11Larutan ragi 5%Ada gelembung CO2 dan ada endapan putihMenunjukkan adanya reaksi peragian
12Suspensi ragi roti 5%Ada gelembung CO2 dan endapan putihMenunjukkan adanya reaksi peragian
Sumber : Laporan SementaraPercobaan peragian dilakukan untuk menetukan gula (Glukosa C6H12O6 dan Laktosa ) yang dapat difermentasikan. Pada percobaan, setelah ragi ditambahkan dengan larutan glukosa 2 % dan didiamkan kurang lebih selama jam di dalam tabung fermentasi, muncul gelembung-gelembung CO2 pada larutan. Selain terlihat gelembung gas CO2 dapat tercium juga bau alkohol. Selain itu, pada percobaan ragi yang ditambahkan dengan larutan laktosa 2% dan di diamkan 1 selama 1 jam di dalam tabung fermentasi, tidak muncul gelembung-gelembung gas CO2 pada larutan. Untuk membedakan glukosa dan laktosa dilakukan peragian, glukosa bisa diragikan (dapat difermentasikan), menghasilkan gas CO2 dan laktosa dari hasil fermentasi tidak muncul gas CO2. Terjadinya reaksi fermentasi (reaksi peragian) ditandai terbentuknya gelembung- gelembung gas CO2 dan persamaan reaksi berlangsung sebagai berikut:C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP Dari percobaan dengan suspensi ragi roti, yang menghasilkan gelembung dan endapan pada bufer 6 dan 6,6. Hal tersebut menunjukkan gas CO2. Pada buffer 8 tidak timbul gelembung, hal ini menunjukkan tidak ada gas CO2. Uji peragian pada larutan pati, hidrolisa pati, larutan ragi roti, suspensi ragi roti, dan glukosa, yang dilakukan dengan pengujian bahwa glukosa dapat difermentasikan oleh sel-sel ragi, sedangkan pada laktosa tidak dapat difermentasikan oleh sel-sel ragi. Uji fermentasi untuk mengetahui bahwa glukosa dapat difermentasikan oleh sel-sel ragi. Ragi roti yang telah dihaluskan dalam lumpang kemudian ditambahkan dengan larutan sampel masing-masing 5% kecuali larutan pati 1% kemudian dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam tabung peragian dan didiamkan selama I jam, maka akan timbul gelembung-gelembung gas CO2.6) Uji BenedictTabel 3.8 Uji BenedictKel Sampel Perubahan WarnaKeterangan
Awal Akhir
6Suspensi ragi roti 5% + reagen benedictBiru mudaBiru pekatAda endapan, reaksi (-) tidak terjadi perubahan warna
7Larutan sukrosa 10% + reagen benedictBiruBiru pekatTidak terjadi perubahan warna
13Larutan ragi roti 5% + reagen benedictBiru mudaBiru pekatAda gelembung dan endapan
14Larutan sukrosa + reagen benedictBiru Biru pekatTidak terjadi perubahan warna
Sumber : Laporan SementaraUji benedict digunakan untuk menunjukkan adanya gula pereduksi. Hal ini dapat diketahui dengan timbul endapan warna hijau, kuning, atau merah orange setelah sampel uji yang ditambahkan pereaksi kemudian dipanaskan (Winarno, 2004). Uji benedict merupakan uji umum untuk karbohidrat (gula pereduksi) yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas, seperti yang terdapat pada glukosa dan maltosa.Uji benedict berdasarkan reduksi Cu2+ menjadi Cu+ oleh gugus aldehid atau keton bebas dalam suasana alkalis, biasanya ditambahkan zat pengompleks seperti sitrat atau tatrat untuk mencegah terjadinya pengendapan CuCO3. Uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata, kadang disertai dengan larutan yang berwarna hijau, merah, atau orange. Dengan adanya natrium karbonat dan natrium sitrat membuat pereaksi Benedict bersifat basa lemah. Endapan yang terbentuk dapat berwarna biru dan merah bata.Sesuai dengan pendapat Suwandhi (1989) bahwa karbohidrat pereaksi Benedict dipanaskan maka akan terjadi endapan dan perubahan warna biru menjadi merah bata. Sampel apabila ditambah dengan pereaksi Benedict semua larutan karbohidrat berubah warna menjadi warna merah bata dan terjadi endapan. Sesuai pendapat Harold (2003) yang menyatakan bahwa karbohidrat berubah warna menjadi merah bata dan terjadi endapan apabila ditambah pereaksi Benedict. Reaksi uji benedict adalah sebagai berikut :
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa sampel yang positif mengandung gula pereduksi adalah larutan suspensi ragi roti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya gelembung dan endapan setelah sampel ditambah reagen benedict dan dipanaskan selama beberapa menit. Endapan yang dihasikan adalah endapan merah bata. Sedangkan larutan sukrosa negatif mengandung gula pereduksi. Hal ini dikarenakan sukrosa tidak seperti disakarida yang lain, tidak dapat mengadakan murotasi. E. Kesimpulan Dari percobaan isolasi pati ubi kayu dan fermentasi di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :1. Amilum merupakan polisakarida sehingga hidrolisis lengkapnya akan mengubah polisakarida menjadi monosakarida.2. Uji iod digunakan untuk menganalisis adanya kandungan pati pada suatu larutan dan untuk mengidentifikasi polisakarida.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi hidrolisis pati adalah waktu dan larutan yang digunakan.4. Uji kualitatif terhadap hidrolisis pati juga dapat digunakan untuk menganalisis sakarida dalam bahan makanan berdasarkan sifat-sifat sakarida dan reaksi-reaksi kimia yang spesifik.5. Uji molisch menunjukkan reaksi positif jika terbentuk cincin berwarna merah ungu pada batas kedua cairan menunjukkan adanya karbohidrat dalam larutan sampel.6. Reaksi positif pada uji pikrat akan menghasilkan larutan yang berwarna merah.7. Faktor yang mempengaruhi uji pikrat yaitu larutan yang dipergunakan dan lama pemanasan.8. Reaksi positif pada uji barfoed akan menghasilkan endapan merah bata.9. Terjadinya reaksi fermentasi (reaksi peragian) ditandai terbentuknya gelembung- gelembung gas CO2.10. Reaksi positif yang ditunjukkan pada uji benedict adalah terbentuknya endapan merah bata.
DAFTAR PUSTAKAAderibigbe, A. F., A. N. Anoize, L. A. Adejumo, dan R. U. Owolabi. 2012. Optimization of Cassava Starch Hydrolisis by Sorghum Malt. New Clues in Sciences 2: 50-58. Anoize, A. N., A. F. Aderibigbe. 2011. Optimization Studies of Cassava starch hydrolysis using response surface method. New Clues in Sciences 1: 37-43. Keenan, Kleinfelter, dan Wood. 1992. Kimia UntukUniversitas. Jakarta: Erlangga.Manantar, Jardewig E., Julius Pontoh, dan Max R. J. Runtuwene. 2012. Analisis Kandungan Pati dalam Batang Tanaman Aren (Arenga Pinnata). Jurnal Ilmiah Sains, Vol. 12, No. 2, Oktober 2012: 89-92.Martoharsono, Suharsono. 1990. Biokimia. Yogyakarta: UGM-PressNurdjanah, Siti., Susilawati, dan Maya Ratna Sabatini. 2007. Prediksi Kadar Pati Ubi Kayu (Manihot Esculenta) pada Berbagai Umur Panen Menggunakan Penetrometer. Jurnal Teknologi dan Industri Hasil Pertanian, Vol. 12, No. 2, September 2007: 65-73Okon, Anne Anthony, U. Nwabueze, dan Titus. 2009. Simultaneous effect of divalent cation in hydrolyzed cassava starch medium used by immobilized yeast for ethanol production. African Journal of Food Science Vol. 3(8). pp. 217-222, August, 2009. Page, David S. 1989.Prinsip-pronsip Biokimia. Jakarta: Erlangga. Susmiati, Yuana., Dwi Setyaningsih, dan Titi Candra Sunarti. 2011. Rekayasa Proses Hidrolisis Pati dan Serat Ubi Kayu (Manihot Utilissima) Untuk Produksi Bioetanol. Agritech, Vol. 31, No. 4, November 2011: 384-389.Tarigan, DR. Ponis. 1983. Kimia Organik Bahan Makanan. Bandung: Penerbit Alumni. Winarno, F. G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Yuniwati, Murni., Dian Ismiyati, dan Reny Kumiasih. 2011. Kinetika Reaksi Hidrolisis Pati Pisang Tanduk dengan Katalisator Asam Chlorida. Jurnal Teknologi, Vol. 4, No. 2, Desember 2011: 107-112.
1. 6 ml buffer pH 4,0 + 3 ml lrt amilum 1%2. 6 ml buffer pH 6,0 + 3 ml lrt amilum 1%3. 6 ml buffer pH 8,0 + 3 ml lrt amilum 1%
Dimasukkan ke dalam 3 tabung bersih
1 ml larutan enzim diastase
Dicatat waktu saat penambahan
Dicampur baik-baik
Diinkubasi pada penangas air 400C
Diambil 1 tetes masing-masing tabung tiap 5 menit
Diteteskan ke lempeng porselin
Diuji iod
1 tetes lrt 0,01 N Iod
Dicatat perubahan warna yang tejadi
Dibandingkan warnanya dengan Amilum 1%+iod, Selulosa, Glikogen+iod
Diuji dengan reagen Benedict
2 ml amilum 1% dan 2 ml diastase
Disiapkan 6 tabung
Disiapkan penangas air
Diinkubasi pada suhu 40oC selama 30 menit untuk tabung 1 dan 2
Diinkubasi pada suhu 40oC selama 10 menit untuk tabung 3 dan 4
Diinkubasi pada suhu kamar selama 30 menit untuk tabung 5 dan 6
Iod 0,01 N
Ditambahkan larutan ke masing-masing tabung
Diamati perubahan warnanya
Related Documents