BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Blok Farmakologi adalah blok ke-12 dari Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Pada kesempatan ini dilaksanakan tutorial studi kasus sebagai bahan pembelajaran untuk menghadapi kasus yang sebenarnya pada waktu yang akan datang. Kasus yang dipelajari tentangfarmakologi anestesi. B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari laporan tutorial studi kasus ini, yaitu: 1. Sebagai laporan tugas kelompok tutorial yang merupakan bagian dari sistem pembelajaran KBK di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. 2. Dapat menyelesaikan kasus yang diberikan pada skenario dengan metode analisis pembelajaran diskusi kelompok. 3. Tercapainya tujuan dari metode pembelajaran tutorial. C. Data Tutorial 1. Tutor : dr. Reagan, Sp. PD. 2. Moderator : Azora Kartika 1

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Blok Farmakologi adalah blok ke-12 dari Kurikulum Berbasis Kompetensi
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Pada
kesempatan ini dilaksanakan tutorial studi kasus sebagai bahan pembelajaran
untuk menghadapi kasus yang sebenarnya pada waktu yang akan datang. Kasus
yang dipelajari tentangfarmakologi anestesi.
B. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari laporan tutorial studi kasus ini, yaitu:
1. Sebagai laporan tugas kelompok tutorial yang merupakan bagian dari
sistem pembelajaran KBK di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
Palembang.
2. Dapat menyelesaikan kasus yang diberikan pada skenario dengan metode
analisis pembelajaran diskusi kelompok.
3. Tercapainya tujuan dari metode pembelajaran tutorial.
C. Data Tutorial
1. Tutor : dr. Reagan, Sp. PD.
2. Moderator : Azora Kartika
3. Sekertaris : Defina Yunita
4. Waktu : 1. Selasa, 10 November 2015
2. Kamis, 12 November 2015
Pukul 07.30 – 10.00 WIB
Pukul 07.30 – 10.00 WIB
1

BAB II
LAPORAN
A. Skenario
Nona C 21 tahun berobat ke puskesmas dengan benjolan sebesar telur puyuh pada
leher kiri yang terasa membesar sejak 1 bulan terakhir. Berat bada dirasa
menurun, nafsu makan dirasa menurun sejak 1 bulan yang lalu. Dicurigai ada
kontak dengan penderita TB dirumah (bapak). Riwayat keganasan pada keluarga
tidak ada. C datang sambil membawa hasil aspirasi jarum halus dengan kesan
radang kronik spesifik granulomatous kemungkinan infeksi tuberkulosa disertai
catatan untuk control ulang. Aspirasi jarum halus 1 buln setelah terapi.
Pemeriksaan fisik : tampak sakit sedang, sensorium kompos mentis, BB : 43 kg,
TB : 155 cm, sedikit anemis, RR : 24x/menit, nadi : 72x/menit, temperature : 370C
Pemeriksaan spesifik : status lokalis : colli sinistra teraba 2 nodul ukuran 2x2 cm
& 2x1 cm berbatas tegas
Pemeriksaan lab rutin , Hb : 11,4g%, leukosit : 10.200/dl, LED : 43 mm/jam,
Diff.Count : 0/1/4/50/40/5
Bagaimana tindakan anda sebagai dokter umum di puskesmas
B. KlarifikasiIstilah
Benjolan : tanda pertama peradangan; pembesaran abnormal
TB : penyakit infeksi yanga disebabkan Mycobacterium dicirikan dengan
pembentukan tuberkel dengan pembentukan nekrosis kaseosa pada jaringan
Keganasan : kanker nepolasma atau tumor yang tumbuh secara tidak
terkontrol dan dapat menyerang jaringan didekatnya atau menyebar ke area
lain dari tubuh
Aspirasi jarum halus : prosedur biopsy yang menggunakan jarm sangat tipis
yang melekat pada jarum suntik untuk sejumlah kecil jaringan dari lesi
abnormal
Radang kronik spesifik granulomatous : kumpulan histiosit epiteloid sebagai
akibat tidak dapat dihancurkannya substansi tertentu oleh makrofag, yang
disebabkan oleh Mycobacterum tuberculosis
2

Sensorium kompos mentis : kesadaran normal, sadar sepenuhnya
Anemis : penurunan jumlah eritrosit, kuantitas hemoglobin, atau volume
packed red cell darah dibawah normal
Colli sinistra : regio leher kiri
Status lokalis : pemeriksaan setempat
Nodul : sebuah simpul kecil atau benjolan kecil, sebuah perbandingan dari
sedikit kumpulan jaringan
LED : Laju dimana eritrosit mengendap dari specimen darah vena dikur dari
atas tabung hingga ke bawah dimana eritrosit jatuh, peningkatan biasanya
disebabkan oleh meningkatnya protein plasma biasanya pada kasus inflamasi
hipergamaglobulinemia dan anemia
Diff. Count : hitung jenis leukosit untuk mengetahui jumlah berbagai jenis
leukosit yakni eosinophil, basophil, neutrophil batang, neutrophil segmen,
limfosit, monosit
C. Identifikasi Masalah
1. Nona C 21 tahun berobat ke puskesmas dengan benjolan sebesar telur puyuh
pada leher kiri yang terasa membesar sejak 1 bulan terakhir. Berat bada dirasa
menurun, nafsu makan dirasa menurun sejak 1 bulan yang lalu.
2. Dicurigai ada kontak dengan penderita TB dirumah (bapak). Riwayat
keganasan pada keluarga tidak ada.
3. C datang sambil membawa hasil aspirasi jarum halus dengan kesan radang
kronik spesifik granulomatous kemungkinan infeksi tuberkulosa disertai
catatan untuk control ulang. Aspirasi jarum halus 1 bulan setelah terapi.
4. Pemeriksaan umum: tampak sakit sedang, sensorium kompos mentis, BB : 43
kg, TB : 155 cm, sedikit anemis, RR : 24x/menit, nadi : 72x/menit,
temperature : 370C
5. Pemeriksaan spesifik : status lokalis : colli sinistra teraba 2 nodul ukuran 2x2
cm & 2x1 cm berbatas tegas
6. Pemeriksaan lab rutin , Hb : 11,4g%, leukosit : 10.200/dl, LED : 43 mm/jam,
Diff.Count : 0/1/4/50/40/5
3

D. Analisis Masalah
1. Nona C 21 tahun berobat ke puskesmas dengan benjolan sebesar telur puyuh
pada leher kiri yang terasa membesar sejak 1 bulan terakhir. Berat bada dirasa
menurun, nafsu makan dirasa menurun sejak 1 bulan yang lalu.
Apa yang menyebabkan timbulnya benjolan pada leher kiri ?
Jawab :
Benjolan pada leher kiri Nona C disebabkan karena respon dari infeksi
tuberkulosis. Paparan terhadap bakteri akan mengaktifkan germinal center.
Tujuannya untuk meningkatkan proliferasi dan diferensiasi sel limfosit guna
meningkatkan pertahanan tubuh terhadap patogen. Akibatnya, ukuran
germinal center dan lymphoid folikel membesar (mengalami hiperplasia).
Membesarnya lymphoid folikel akan mengakibatkan ukuran kelenjar getah
bening ikut membesar (teraba sebagai benjolan). Keadaan ini dikenal sebagai
folikuler limfoid reaktif hiperplasia.
Mekanisme lain : Bakteri tuberkulosis, terutama yang berhasil berproliferasi
dalam makrofag, masuk ke cairan limfe (menyebar secara limfogenik) dan
terbawa ke kelenjar getah bening terdekat. Pada kelenjar getah bening, kuman
akan mengakibatkan peradangan (limfadenitis kronik spesifik). Limfadenitis
mengakibatkan benjolan pada KGB.
Apa yang menyebabkan berat badan dan nafsu makan menurun?
Jawab :
TNF-alfa memicu metabolisme dengan 5 cara:
o menghambat uptake dari asam lemak bebas dan menyetimulasi
lipogenesis
o menginduksi lipolisis
o menghambat metabolisme lipid yang terikat enzim
o mengatur metabolisme kolesterol
o mengatur turunan adiposit adipokin
4

Gambar 1
Apa saja kemungkinan konsistensi dari benjolan tersebut?
Bagaimana mekanisme timbulnya benjolan tersebut pada kasus?
Jawab :
Bakteri tuberkulosis, terutama yang berhasil berproliferasi dalam makrofag,
masuk ke cairan limfe (menyebar secara limfogenik) dan terbawa ke kelenjar
getah bening terdekat. Pada kelenjar getah bening, kuman akan
mengakibatkan peradangan (limfadenitis kronik spesifik). Limfadenitis
mengakibatkan benjolan pada KGB. Limfadenitis adalah presentasi klinis
paling sering dari TB ekstrapulmoner. Limfadenitis TB juga dapat merupakan
manifestasi lokal dari penyakit sistemik. Pasien biasanya datang dengan
keluhan pembesaran kelenjar getah bening yang lambat. Oleh karena itu,
5

infeksi mikobakterium harus menjadi salah satu diagnosis banding dari
pembengkakan kelenjar getah bening, terutama pada daerah yang endemis.
Limfadenitis TB paling sering melibatkan kelenjar getah bening servikalis,
kemudian diikuti berdasarkan frekuensinya oleh kelenjar mediastinal,
aksilaris, mesentrikus, portal hepatikus, perihepatik dan kelenjar inguinalis
(Mohapatra, 2004).
Pembengkakan kelenjar limfe dapat terjadi secara unilateral atau bilateral,
tunggal maupun multipel, dimana benjolan ini biasanya tidak nyeri dan
berkembang secara lambat dalam hitungan minggu sampai bulan, dan paling
sering berlokasi di regio servikalis. Beberapa pasien dengan limfadenitis TB
dapat menunjukkan gejala sistemik yaitu seperti demam, penurunan berat
badan, fatigue dan keringat malam. Lebih dari 57% pasien tidak
menunjukkan gejala sistemik. Limfadenopati tuberkulosis perifer dapat
diklasifikasikan ke dalam lima stadium yaitu:
1. Stadium 1, pembesaran kelenjar yang berbatas tegas, mobile dan diskret.
2. Stadium 2, pembesaran kelenjar yang kenyal serta terfiksasi ke jaringan
sekitar oleh karena adanya periadenitis.
3. Stadium 3, perlunakan di bagian tengah kelenjar (central softening)
akibat pembentukan abses.
4. Stadium 4, pembentukan collar-stud abscess.
5. Stadium 5, pembentukan traktus sinus.
Gambaran klinis limfadenitis TB bergantung pada stadium penyakit. Kelenjar
limfe yang terkena biasanya tidak nyeri kecuali (i) terjadi infeksi sekunder
bakteri, (ii) pembesaran kelenjar yang cepat atau (iii) koinsidensi dengan
infeksi HIV. Pembengkakan kelenjar getah bening yang berukuran ≥ 2 cm
biasanya disebabkan oleh M.tuberculosis. Pembengkakan yang berukuran < 2
cm biasanya disebabkan oleh mikobakterium atipik, tetapi tidak menutup
kemungkinan pembengkakan tersebut disebabkan oleh M.tuberculosis
(Narang, 2005).
Bagaimana predisposisi umur terhadap munculnya benjolan pada kasus?
6

2. Dicurigai ada kontak dengan penderita TB dirumah (bapak). Riwayat
keganasan pada keluarga tidak ada.
Bagaimana tranmisi penyakit TB?
Apa hubungan keganasan dengan timbulnya benjolan?
bagaimana korelasi keganasan dengan hereditas?
Bagaimana mekanisme pertahanan tubuh dalam menghadapi TB?
3. C datang sambil membawa hasil aspirasi jarum halus dengan kesan radang
kronik spesifik granulomatous kemungkinan infeksi tuberkulosa disertai
catatan untuk control ulang. Aspirasi jarum halus 1 bulan setelah terapi.
Bagaimana prosedur pemeriksaan aspirasa jarum halus?
Bagaimana gambaran mikroskopik dari radang kronik spesifik
granulomatous?
Jawab :
Sediaan dari KGB, dijumpai tuberkel (granuloma) terdiri dari nekrosis
kaseosa di bagian sentral yang dikelilingi oleh sel-sel epithelioid dengan
infiltrasi sel radang limfosit, sel plasma, fibroblast dan sel datia langhans
(giant cell Langhans) serta PMN.
7

Apa saja yang dapat diperiksa dengan aspirasi jarum halus?
Bagaimana mekanisme timbulnya granuloma karena infeksi TB?
Jawab :
Secara umum penyakit tuberkulosis dapat diklasifikasikan menjadi TB
pulmoner dan TB ekstrapulmoner. TB pulmoner dapat diklasifikasikan
menjadi TB pulmoner primer dan TB pulmoner post-primer (sekunder). TB
primer sering terjadi pada anak-anak sehingga sering disebut child-type
tuberculosis, sedangkan TB post-primer (sekunder) disebut juga adult-type
tuberculosis karena sering terjadi pada orang dewasa, walaupun faktanya TB
primer dapat juga terjadi pada orang dewasa (Raviglione, 2010). Basil
8

tuberkulosis juga dapat menginfeksi organ lain selain paru, yang disebut
sebagai TB ekstrapulmoner. Menurut Raviglione (2010), organ
ekstrapulmoner yang sering diinfeksi oleh basil tuberkulosis adalah kelenjar
getah bening, pleura, saluran kemih, tulang, meningens, peritoneum, dan
perikardium.
TB primer terjadi pada saat seseorang pertama kali terpapar terhadap basil
tuberkulosis (Raviglione, 2010). Basil TB ini masuk ke paru dengan cara
inhalasi droplet. Sampai di paru, basil TB ini akan difagosit oleh makrofag
dan akan mengalami dua kemungkinan. Pertama, basil TB akan mati difagosit
oleh makrofag. Kedua, basil TB akan dapat bertahan hidup dan
bermultiplikasi dalam makrofag sehingga basil TB akan dapat menyebar
secara limfogen, perkontinuitatum, bronkogen, bahkan hematogen.
Penyebaran basil TB ini pertama sekali secara limfogen menuju kelenjar limfe
regional di hilus, dimana penyebaran basil TB tersebut akan menimbulkan
reaksi inflamasi di sepanjang saluran limfe (limfangitis) dan kelenjar limfe
regional (limfadenitis). Pada orang yang mempunyai imunitas baik, 3 – 4
minggu setelah infeksi akan terbentuk imunitas seluler. Imunitas seluler ini
akan membatasi penyebaran basil TB dengan cara menginaktivasi basil TB
dalam makrofag membentuk suatu fokus primer yang disebut fokus Ghon.
Jika terjadi reaktivasi atau reinfeksi basil TB pada orang yang sudah memiliki
imunitas seluler, hal ini disebut dengan TB post-primer. Adanya imunitas
seluler akan membatasi penyebaran basil TB lebih cepat daripada TB primer
disertai dengan pembentukan jaringan keju (kaseosa). Sama seperti pada TB
primer, basil TB pada TB post-primer dapat menyebar terutama melalui aliran
limfe menuju kelenjar limfe lalu ke semua organ (Datta, 2004). Basil TB juga
dapat menginfeksi kelenjar limfe tanpa terlebih dahulu menginfeksi paru.
Basil TB ini akan berdiam di mukosa orofaring setelah basil TB masuk
melalui inhalasi droplet. Di mukosa orofaring basil TB akan difagosit oleh
makrofag dan dibawa ke tonsil, selanjutnya akan dibawa ke kelenjar limfe di
leher (Datta, 2004).
Bagaimana proses penyembuhan penyakit pada kasus?
9

Apa saja terapi yang digunakan dalam penyembuhan penyakit pada kasus?
Jawab :
Pengobatan TBC Kriteria I (Tidak pernah terinfeksi, ada riwayat kontak,
tidak menderita TBC) dan II (Terinfeksi TBC/test tuberkulin (+), tetapi tidak
menderita TBC (gejala TBC tidak ada, radiologi tidak mendukung dan
bakteriologi negatif) memerlukan pencegahan dengan pemberian INH 5–10
mg/kgbb/hari.
1. Pencegahan (profilaksis) primer
Anak yang kontak erat dengan penderita TBC BTA (+).
INH minimal 3 bulan walaupun uji tuberkulin (-).
Terapi profilaksis dihentikan bila hasil uji tuberkulin ulang menjadi (-) atau
sumber penularan TB aktif sudah tidak ada.
2. Pencegahan (profilaksis) sekunder
Anak dengan infeksi TBC yaitu uji tuberkulin (+) tetapi tidak ada gejala sakit
TBC. Profilaksis diberikan selama 6-9 bulan.
Obat yang digunakan untuk TBC digolongkan atas dua kelompok yaitu :
o Obat primer : INH (isoniazid), Rifampisin, Etambutol, Streptomisin,
Pirazinamid.
Memperlihatkan efektifitas yang tinggi dengan toksisitas yang masih dapat
ditolerir, sebagian besar penderita dapat disembuhkan dengan obat-obat ini.
o Obat sekunder : Exionamid, Paraaminosalisilat, Sikloserin, Amikasin,
Kapreomisin dan Kanamisin.
Dosis obat antituberkulosis (OAT)
Obat Dosis harian (mg/kgbb/hari)
Dosis 2x/minggu (mg/kgbb/hari)
Dosis 3x/minggu(mg/kgbb/hari)
10

INH 5-15 (maks 300 mg) 15-40 (maks. 900 mg) 15-40 (maks. 900 mg)
Rifampisin 10-20 (maks. 600 mg) 10-20 (maks. 600 mg) 15-20 (maks. 600 mg)
Pirazinamid 15-40 (maks. 2 g) 50-70 (maks. 4 g) 15-30 (maks. 3 g)
Etambutol 15-25 (maks. 2,5 g) 50 (maks. 2,5 g) 15-25 (maks. 2,5 g)
Streptomisin 15-40 (maks. 1 g) 25-40 (maks. 1,5 g) 25-40 (maks. 1,5 g)
4. Pemeriksaan umum: tampak sakit sedang, sensorium kompos mentis, BB : 43
kg, TB : 155 cm, sedikit anemis, RR : 24x/menit, nadi : 72x/menit,
temperature : 370C
Apa interpretasi dari pemeriksaan umum?
Bagaimana hubungannya dengan kasus? (penyebab, mekanisme)
5. Pemeriksaan spesifik : status lokalis : colli sinistra teraba 2 nodul ukuran 2x2
cm & 2x1 cm berbatas tegas
Apa kemungkinan nodul yang teraba?
Mengapa timbul pada regio colli sinistra? Bisakah tumbuh di tempat lain?
Mengapa ukuran kedua nodul dapat berbeda?
Bagaimana karakteristik nodul pada TB?
6. Pemeriksaan lab rutin , Hb : 11,4g%, leukosit : 10.200/dl, LED : 43 mm/jam,
Diff.Count : 0/1/4/50/40/5
Bagaimana interpretasi dari pemeriksaan lab?
Jawab:
1. Hemoglobin :
Anak anak : 11-13 gram/dl.
Lelaki dewasa : 14-18 gram/dl.
Perempuan dewasa : 12-16 gram/dl.
Lelaki tua : 12.4-14.9 gram/dl.
11

Perempuan tua : 11.7-13.8 gram/dl
2. Hematokrit :
Pria berkisar 40,7% - 50,3%.
Wanita berkisar 36,1% - 44,3%.
3. Leukosit (White Blood Cell / WBC) :
Nilai normal leukosit berkisar 4.000 - 10.000 sel/ul darah.
4. Trombosit (platelet) :
Nilai normal trombosit berkisar antara 150.000 - 400.000 sel/ul darah.
5. Eritrosit (Red Blood Cell / RBC) :
Nilai normal eritrosit pada pria berkisar 4,7 juta - 6,1 juta sel/ul darah.
Nilai normal eritrosit pada wanita berkisar 4,2 juta - 5,4 juta sel/ul darah.
6. Laju Endap Darah :
Nilai normal LED pada metode Westergreen :
Laki-laki : 0 – 15 mm/jam
Perempuan : 0 – 20 mm/jam
7. Hitung Jenis Leukosit (Diff Count) :
Nilai normal :
12

Eosinofil 1-3%.
Netrofil 55-70%.
Limfosit 20-40%.
Monosit 2-8%.
Bagaimana hubungannya dengan kasus?
Mengapa tidak digunakan pemeriksan Ziehl Neelsen?
Jawab :
Pemeriksaan mikrobiologi yang meliputi pemeriksaan mikroskopis dan
kultur. Pemeriksaan mikroskopis dilakukan dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen.
Spesimen untuk pewarnaan dapat diperoleh dari sinus atau biopsi aspirasi.
Dengan pemeriksaan ini kita dapat memastikan adanya basil mikobakterium
pada spesimen, diperlukan minimal 10.000 basil TB agar perwarnaan dapat
positif (Mohapatra, 2009; Bayazit, 2004). Diperlukan waktu beberapa minggu
untuk mendapatkan hasil kultur. Pada adenitis tuberkulosa, M.tuberculosis
adalah penyebab tersering, diikuti oleh M.bovis (Bayazit, 2004).
7. Pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan
Foto thoraks
Pemeriksaan sputum BTA
13

E. Keterbatasan Ilmu Pengetahuan
No. Learning Issue What I
know
What I
don’t
know
What I
have to
prove
Media
Pembelajaran
1. Succinylcholine V Internet
Textbook
Jurnal
IT
2. Halothane V
3. Malignant
Hyperthermia
V
4. Appendicitis V
F. Keterikaitan Antar Masalah
14
Tn. Ahmad mengalami Malignant Hyperthermia
Diberikan succinylcholine dan halothane

G. Learning Issue
Radang kronik
Meskipun sulit untuk didefinisikan dengan pasti, peradangan kronik dianggap
sebagai peradangan yang durasinya memanjang (mingguan atau bulanan) berupa
peradangan aktif, kerusakan jaringan, dan upaya perbaikan yang berlangsung
secara bersamaan. Meskipun dapat terjadi setelah peradangan akut, seperti yang
telah dijelaskan, peradangan kronik sering berawal secara samar, sebagai respon
berderajat ringan yang terus-menerus, tetapi asimtomatik. Peradangan kronik tipe
terakhir ini merupakan penyebab kerusakan jaringan pada sebagian dari penyakit
manusia yang tersering dan paling menimbulkan kecacatan, seperti artritis
reumatoid, arterosklerosis, tuberkulosis, dan penyakit paru kronik.
Penyebab Peradangan Kronik
Peradangan kronik timbul pada keadaan-keadaan berikut ini.
o Infeksi persisten oleh mikroorganisme tertentu, seperti basil tuberkel,
Treponema pallidum (penyebab sifilis), dan virus, jamur, dan parasit tertentu.
Organisme-organisme ini memiliki toksisitas rendah dan memicu suatu reaksi
imun yang disebut hipersensitivitas tipe lambat (delayed type
hypersensitivity). Respon peradangan kadang-kadang mengambil pola
spesifik yang disebut reaksi granulomatosa.
o Pajanan berkepanjangan oleh agen yang berpotensi toksik, baik dari luar
maupun dalam sel. Contoh agen eksogen adalah partkel silika, yakni suatu
benda mati tidak teruraikan yang, jika terhirup dalam jangka waktu lama,
dapat menyebabkan penyakit peradangan paru yang disebut silikosis.
Aerosklerosis terjadi akibat proses peradangan kronik di dinding arteri yang
dipicu, palng tidak sebagian, oleh komponen lemak plasma toksik endogen.
o Autoimunitas. Dalam kondisi tertentu, terbentuk reaksi imun terhadap
jaringan tubuh sendiri dan menyebabkan penyakit autoimun. Pada penyakit
ini, autoantigen memicu timbulnya reaksi mun yang terus memperkuat
dirinya dan menimbulkan peradangan dan kerusakan jaringan kronik. Reaksi
imun berperan penting pada beberapa penyakit peradangan kronik, seperti
artritis reumatoid dan lupus eritematosus.
15

Penyembuhan radang kronik (bima, Tania, ican, didik)
Infeksi TBC (azhari, mbak fit, eka)
Pemeriksaan pada radang kronik (Bima, sharoon, Tania, eka, ican, didik,
aufar, ahari, mbak fit, gemi, yeyik)
16

H. Kerangka Konsep
17
Apendiktomi
Pembedahan Intra abdomen
Tn. Ahmad 28 tahun
Pemberian halothane Pemberian succinylcholine
Pengeluaran ion Ca2+ terus menerus dari Retikulum
Sarkoplasma
Eksitasi dan kontraksi otot skeletal terus menerus
Sel otot lisis Hipermetabolic cell
Kekakuan otot
Produksi panas meningkatKebutuhan ATP meningkat
Pelepasan myoglobulin
Hiperkalemia
Kreatine kinase meningkat
Cola-colored urine
O2 turun, CO2 naik di darah
Takikardi Hipertensi
Hipertremia
Aktivasi glikogenolisis
Peningkatan H+ pada darah
pH < 7.25 Base deficit >8

I. Sintesis
Pada kasus, Tn. Ahmad diberikan succinylcholine intravena dan inhalasi halothane.
Pemberian halothane dan succinylcholinemerupakan pemberian yang paling sering
pada operasi karena onset yang cepat dan kerjanya sinergis. Succinylcholine
memiliki waktu paruh yang cepat akan tetapi efek succinylcholine berlangsung
sekitar 4-6 menit.
Succinylcholine disintesis di hati dan ada dalam plasma. BCHE (plasma
cholinesterase and pseudocholinesterase, terletak pada 3q26.1–26.2) menghidrolisis
SCH ke succinylmonocholine, succinic acid, dan kolin. Dalam fungsinya,
suksinilkolin menggantikan asetilkolin dalam membuka kanal-kanal bergerbang
asetilkolin. Mekanisme kerja suksinilkolin teridiri atas dua fase yakni fase
depolarisasi dan fase desensitisasi.
Dalam fase depolarisasi, kerja suksinilkolin mirip dengan asetilkolin, namun bedanya
asetilkolin akan dimetabolisme oleh kolinesterase untuk menghentikan ikatan dengan
reseptor kanal. Namun, karena kolinesterase tidak mampu memetabolisme
suksinilkolin, maka suksinilkolin tetap terus berikatan dengan reseptor kanal dan
mengakibatkan kanal terus terbuka.
Dalam fase desensitisasi, akibat pemaparan dengan suksinilkolin terus menerus,
depolarisasi perlahan-lahan akan menurun dan terjadilah proses repolarisasi. Untuk
memulai suatu depolarisasi baru, dibutuhkan asetilkolin agar kanal terbuka kembali.
Namun karena telah terpapar suksinilkolin, asetilkolin tidak mampu mendepolarisasi
otot kembali.
Pemberian halothane dan succinylcholine akan memberikan dampak yang berbeda
apabila dilakukan pada penderita dengan mutasi kromosom 19q 12.1-13.2.
Mekanisme terjadinya kontraksi pada otot dibantu oleh gen RYR1 (ryanodine
receptor 1). Gen ini menginstruksikan pembuatan suatu protein yang disebut protein
ryanodine reseptor 1. Protein ini akan membentuk chanel yang bertanggung jawab
terhadap transpor kalsium pada sel. Dengan sinyal tertentu, RYR1 chanel akan
membuat kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma menuju sitoplasma.
18

Peningkatan kalsium membuat proses kontraksi otot dimulai. Proses ini disebut
proses E-C coupling.
Pada kondisi terjadinya mutasi gen pada kromosom 19 terjadi peningkatan resiko
malignant hipertermia. Mutasi ini terjadi dan menyebabkan perubahan pada regio di
ryanodine receptor 1 protein. Perubahan ini menyebabkan RYR1 channel membuka
dengan lebih mudah, dan sukar untuk menutup pada anetesi dan obat relaksasi otot
tertentu. Penimbunan kalsium yang berlebihan akibat masalah di RYR1 channel ini
menyebabkan otot hiperkontraksi yang pada akhirnya menyebabkan kekakuan otot
dan gejala-gejala lainnya yang lebih dikenal sebagai malignan hipertermia.
Pemakaian succinylcholine dilakukan bersamaan dengan halothane yang berfungsi
untuk memperpanjang efek dari succinylcholine. Sebelum pemberian
halothane dan succinylcholine, dilakukan pemeriksaan terhadap penyakit jantung dan
paru karena penderita penyakit jantung dan paru merupakan kontraindikasi dalam
penggunaan obat anestesi ini.
Intubasi perlu dilakukan karena efek succinylcholine yang melumpuhkan otot-otot
pernapasan, pasien memerlukan ventilasi mekanis dan pemantauan ketat selama
kelumpuhan.
Saat dilakukan pembedahan, terjadi kekakuan pada otot, suhu tubuh meningkat
sampai 41oC dan tekanan darah menjadi 180/90 mmHg dan denyut jantung 128
kali/menit. Gejala tersebut merupakan Malignant Hyperthermia. Mekanisme secara
molekular yang menyebabkan terjadinya kondisi ini belum ditemukan. Hal ini
disebabkan oleh adanya mutasi pada genetik yang menyebabkan kelainan pada
reseptor ryanodin tipe 1 (RyR1).
Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan datrolene sebelum pemberian
anestesi (secara teori), namun hal ini jarang dilakukan. Pemberian datrolene pra
anestesi dengan dosis 2,5 mg/kgBB. Calcium-channel blockers dapat menyebabkan
hiperkalemia apabila digukanan bersama dantrolene, serta tidak
direkomendasikan. Selain itu, untuk menangani tanda yang terjadi, dapat dilakukan
dengan total body cooling, pendinginan dihentikan jika suhu badan telah mencapai
38,5°C, penghentian pemakaian obat anestesi, pemberian oksigen 100%,
19

memperbaiki asidosis yang terjadi, dan insulin dan glukosa untuk mengatasi
hiperkalemia.
20

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Tn. Ahmad (28 tahun) mengalami Malignant hyperthermia karena pemberian
succinylcholine dan halothane saat operasi.
21

Daftar Pustaka
A. Latief, Said. 2001. Petunjuk Praktis Anestesiologi Edisi Kedua. Jakarta: Bagian
Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alvarellos, Maria L., Ellen M. McDonagh, Sephalie Patel, Howard L. McLeod, Russ B.
Altman, Teri E. Klein. 2015. “Succinylcholine Pathway,
Pharmacokinetics/Pharmacodynamics”,
https://www.pharmgkb.org/pathway/PA166122732#, diunduh pada 10 November
2015
Chapin, James W. 2014. “Malignant Hyperthermia”.
http://emedicine.medscape.com/article/2231150-overview#a6. Diakses pada 11
November 2015. 20:32 WIB.
Drugs.com. 2015. “Succinylcholine”, http://www.drugs.com/cdi/succinylcholine.html,
diunduh pada 10 November 2015
Guyton A.C. and J.E. Hall 2007. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 9. Jakarta: EGC.
Herwana, Elly. 1999. Peranan Kelainan Butirilkolinesterase terhadap Metabolisme
Suksinilkolin. Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Hopkins, P.M. “Malignant hyperthermia: pharmacology of triggering”. British Journal of
Anaesthesia 107 (1): 48–56 (2011)
http://ghr.nlm.nih.gov/gene/RYR1 , diakses pada 12 November 2015
http://www.drugs.com/monograph/succinylcholine-chloride.html (diakses pada tanggal 10
November 2015)
http://www.drugs.com/monograph/halothane.html(diakses pada tanggal 10 November 2015)
http://www.drugs.com/cg/types-of-anesthesia.html , (diakses pada tanggal 10 November
2015)
http://www.drugs.com/uk/pdf/leaflet/509064.pdf(diakses pada tanggal 10 November 2015)
http://www.hop
kinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/surgical_care/types_of_anesthesia_and_you
r_anesthesiologist_85,P01391/ (diakses pada tanggal 10 November 2015)
http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/
8336(diakses pada tanggal 10 November 2015)
http://www.rxlist.com/succinylcholine-chloride.html(diakses pada tanggal 10 November
2015)
http://www.rxlist.com/halothane.html(diakses pada tanggal 10 November 2015)
22

http://www.rxlist.com/malignant_hyperthermia.html(diakses pada tanggal 10 November
2015)
Jurkat-Rott, Karin. “GENETICS AND PATHOGENESIS OF MALIGNANT
HYPERTHERMIA”. John Wiley & Sons, Inc. Muscle Nerve 23: 4–17 (2000)
Katzung, B.G., Masters, S.B., Trevor, A.J. 2009. Basic & Clinical Pharmacology, 11th Ed. New
York:McGraw-Hill.
Mangku, dr, Sp. An. KIC & Senapathi, dr, Sp. An, (2010), Buku Ajar Ilmu Anestesi dan
Reanimasi, PT. Indeks, Jakarta
Tanu, Ian. 2007. Farmakologi dan Terapi. Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik
Falkutas Kedokteran Universitas Indonesia.
Tanto, chris. ed. 2014. Kapita Selekta Kedokteran Edisi 4 Jilid 1 Halaman 213-214. Jakarta:
Media Aesculapius
Tanto, chris. ed. 2014. Kapita Selekta Kedokteran Edisi 4 Jilid 2. Jakarta: Media
Aesculapius.
Wibowo, Andry. 2009. Studi Banding Kejadian Nausea Vomitus antara Penggunaan
Isofluran dan Halothane sebagai Anestesi Inhalasi. Surakarta: Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret
23
Related Documents




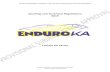
![MANUAL DE INSTALACIÓN MTB-25 y MTB-30 · Componentes de los modelos MTB-25 y MTB-30 FIG. 6-1 ˇ˘ ˆ ˙˝ ˛˚ ˜ ˝ ˜ ˜ ˙˝ ˘ ! "˝ ˜ ˝ ˝ #˜ ˘ ˙˝ ˝ $%&& [680 kg]. Sea](https://static.cupdf.com/doc/110x72/5e7bee99522e1c6814516ea6/manual-de-instalacin-mtb-25-y-mtb-30-componentes-de-los-modelos-mtb-25-y-mtb-30.jpg)






