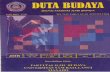Manusia dan Kebudayaan Daerah Maluku dan Minahasa Oleh : Ridho Pratama Satria Kelompok : 13 Jurusan : Sastra Inggris Fakultas : Ilmu Budaya

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Manusia dan Kebudayaan Daerah Maluku dan Minahasa
Oleh : Ridho Pratama SatriaKelompok : 13
Jurusan : Sastra InggrisFakultas : Ilmu Budaya
Universitas AndalasTahun Ajaran 2014/2015
Kata Pengantar
Asalamua’laikum Wr. Wb.
Saya sangat bersyukur kehadirat Allah Swt yang telah memberi saya kesempatan untuk menyelesaikan makalah ini, dan juga Salam tiada henti kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam yang tidak diketahuinya ilmupengetahuan sampai sekarang dimasa yang benar-benar sangat berlimpah akan ilmu pengetahuan ini.
Saya berterimakasih kepada beberapa sumber yang membantusaya untuk menuliskan makalah ini sebagai bagian dari tugasmata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Semoga makalahini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadisumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswaUniversitas Andalas. Saya sadar bahwa makalah ini masih banyakkekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kepada semuapihak saya meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah saya di masa yang akan datang dan mengharapkankritik dan saran dari para pembaca.
Padang, November 2014
2
Penyusun
Kata Pengantar Daftar Isi
I. Kebudayaan Minahasa a. Lokasi .........................................3b. Lingkungan alam ............................... 3c. Demografi ......................................3d. Pola perkampungan ..............................4e. Sistem kemasyarakatan dan kekerabatan ............ 5f. Nilai dan contoh kebudayaan ....................7
II. Kebudayaan Malukua. Lokasi, lingkungan alam, dan demografi ..........8b. Sistem Kemasyarakatan dan kekerabatan...........10c. Nilai dan contoh kebudayaan....................10
3
I. Kebudayaan Minahasa a. Lokasi
Minahasa terletak di bagian timur-laut jazirah Sulawesi
Utara, di antara 0 derajat 51’ dan 1 derajat 51’ 40’ lintang
Utara dan 124 derajat 18’ 40’ dan 125 derajat 21’ 30’ bujur
Timur. Luas Minahasa 5273 Km², sedangkan luas wilayah pulau-
pulau sekitarnya 169 Km². Daerah Minahasa termasuk juga dengan
beberapa pulau kecil di bagian Utara, seperti pulau Manado
Tua, Bunaken, Siladen, dan Naen. Tetangga-tetangga Minahasa
ialah Sangir Talaud di bagian Utara dan Bolaang Mongondow di
bagian selatan.
b. Lingkungan alam
Kawasan Minahasa berupa daerah vulkanik muda. Sifat-sifat
khasnya ialah berbagai tepi gunung yang curam, diselingi oleh
sungai-sungai kecil yang mengering sesudah mengalir cepat dan
singkat ke laut. Di Minahasa terdapat empat gunung tinggi yang
penting, yaitu Kalabat di Utara, Lokon dan Mahawu di tengah,
dan Soputan di Selatan. Selain juga ada beberapa gunung lain,
yakni gunung Dua Saudara, Masarang, Tampusu, Manimporok,
Lolombulan, Lengkoan, dan pegunungan Lembean. Sungai-sungai
yang terdapat di Minahasa, antara lain sungai Tondano,
4
Ranoyapo, Poigar, dan sebagainya. Di tengah Minahasa terdapat
suatu dataran tinggi (700m) dengan danau Tondano di tengahnya.
Di daerah itu dan di wilayah-wilayah datar lainnya ditanami
padi pada wilayah yang beririgasi, jagung di tebing-tebing
gunung beserta sayur-mayur, kelapa di sepanjang pantai dan
pohon cengkeh di wilayah yang lebih tinggi. Iklim Minahasa
tropis dan basah, dengan curah hujan rata-rata 2.000 sampai
4.000 mm. Dalam satu tahun terdapat dua musim, yakni musim
hujan yang berlangsung sejak bulan Oktober sampai Maret dan
musim panas dari bulan April sampai September.
c. Demografi
Orang Minahasa menyebut diri mereka orang Manado atau
Touwenang (orang Wenang), orang Minahasa, dan juga Kawanua.
Masyarakat asli Minahasa terbagi ke dalam 8 sub-etnik atau
suku bangsa, yakni:
1. Tonsea; terdapat di sekitar Timur Laut Minahasa.
2. Tombulu; terdapat di sekitar Barat Laut danau Tondano.
3. Tontemboan/Tompakewa; terdapat di sekitar Barat Daya
Minahasa.
4. Toulour; terdapat di bagian Timur dan pesisir danau
Tondano.
5. Tonsawang; terdapat di bagian tengah dan Selatan
Minahasa.
6. Pasan atau Ratahan; terdapat di bagian Tenggara
Minahasa.
7. Ponosakan; di bagian Tenggara Minahasa.
5
8. Bantik; terdapat di beberapa tempat di pesisir Barat
Laut Utara dan Selatan kota Manado.
d. Pemerintahan tradisonal dan pola perkampungan
Kebanyakan masyarakat Minahasa berdiam di daerah pedesaan.
Pada masa lalu, kesatuan hidup setempat terkecil di Minahasa
disebut banua atau wanua (desa). Pemerintahan banua atau wanua
ini dipimpin oleh hukumtua atau kepala desa, dalam menjalankan
pemerintahannya Hukumtua dibantu oleh sejumlah petugas yang
disebut pamong desa. Petugas atau pamong yang membantu
Hukumtua antara lain juru tulis, mantri air, kepala jaga,
meweteng,kepala jaga polisi, dan palakat idang pemerintahan
juga bertugas pada kegiatan lain seperti pembangunan desa,
gotong royong atau kerja bakti. Dalam kegiatan ini hukumtua
juga dibantu oleh sejumlah orang yang biasa disebut Tua-tua
Kampung. Mereka ini terdiri atas pimpinan agama setempat, para
guru, dan mantan-mantan Hukumtua, pelaksanaan setiap kegiatan
didahului dengan rapat yang dihadiri oleh pamong desa bersama
tua-tua kampung.
Setiap Banua atau wanua yang terdapat di Minahasa terbagi
atas beberapa wilayah kecil yang disebut jaga,dan setiap jaga
juga terbagi menjadi beberapa wilayah kecil yang terdiri atas
sejumlah rumah. Wilayah jaga berada di bawah kekuasan Kepala
jaga yang dibantu oleh meweteng. Selain pembagian tersebut,
setiap desa bila ditinjau dari pembagian secara agama
(protestan) terdiri atas kolom-kolom yang dipimpin oleh
Panatua yang dibantu oleh samasit (wanita) dan atau samas
(laki-laki).
6
Sementara Pendeta tetap bertindak sebagai pemimpin agama.
Pelapisan sosial yang ada di Minahasa terutama di daerah
pedesaan dapat dikelompokkan berdasar pangkat atau jabatan
(Hukumtua,kepala jaga, Meweteng dan sebagainya), agama
(Pendeta, Guru Jumat, Panatua), pendidikan (guru), dan materi
atau kekayaan (tousiga = orang kaya, tou lengei orang =
miskin, dan sebagainya). Hingga kini pelapisan sosial yang
masih ada di tengah masyarakat berdasar pada pendidikan,
pangkat, dan kekayaan.Pola perkampungan desa di Minahasa
bersifat menetap, mengelompok, dan padat. Kelompok rumah-rumah
dalam desa memanjang mengikuti jalan raya. Rumah tradisional
berbentuk panggung dengan tinggi 5-10 meter, dengan maksud
untuk menghindari gangguan binatang buas dan gangguan musuh,
misalnya perampok-perampok yang datang dari luar daerah
seperti dari kepulauan Mindanauw, orang Tidore, dari Maluku,
dan orang Bajo/Wajo. Pada masa lalu, kampung-kampung di Minahasadipagar rapat dan kuat dengan tiang-tiang kayu. Hal ini dimaksudkan
untuk "benteng" pertahanan. Pada masa itu masih sering terjadi
perang antar kelompok. Wale atau rumah-rumah pada masa itu berupa
bangunan tempat tinggal yang berdiri di atas tiang-tiang yang cukup
tinggi. Untuk naik atau masuk ke rumah menggunakan tangga. Tangga
ini diangkat ke atas bila tidak digunakan sehingga musuh tidak mudah
naik atau masuk ke rumah.
Seiring perkembangan zaman, konflik atau perang antar kelompok
berangsur-angsur mulai hilang dan akhirnya hilang. Berkaitan dengan
ini, bentuk rumah pun juga berubah. Tiang¬-tiang rumah tidak
setinggi dulu lagi, bahkan ada yang merapat atau tapas tanah. Rumah
tradisional orang Minahasa umumnya berbentuk rumah panggung yang
berbahan kayu dan beratap rumbia dan ada pula dari seng. Kolong
7
rumah berfungsi sebagai godong (gudang). Di samping rumah atau
tempat tinggal, mereka juga membuat pondok-pondok di areal
perladangan disebut sabuwa atau di areal persawahan disebut terung.
Pondok ini digunakan untuk berteduh/beristirahat dari hujan dan
panas sewaktu bekerja di ladang atau sawah.
Sebuah desa (kampung) biasanya terdiri atas bangunan rumah
tempat tinggal, gereja, pasar atau warung, sekolah dan bangunan
lainnya. Sebagai prasarana penghubung antar penduduk dibangun jalan
desa dan lorong. Rumah penduduk biasanya menghadap ke jalan atau
lorong. Jarak antara rumah masih lega sehingga dapat ditanami pohon
buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, dan bunga-bunga di dalam
areal pekarangan.
e. Sistem Kemasyarakatan dan Kekerabatan
Kelompok kekerabatan di Minahasa dimulai dari bentuk yang
terkecil yakni keluarga batih, yang disebut sanggawu (sangga=
satu; awu= dapur). Sanggawu dapat berupa pasangan suami istri
sendiri, atau beserta anak, baik anak kandung maupun anak
angkat. Terbentuknya sanggawu dimulai dari pernikahan antara
seorang wanita dan pria yang pada umumnya bukan hasil
penjodohan yang tegas dari pihak orang tua. Setiap orang bebas
menentukan jodohnya, asalkan bukan pasangan yang masih
memiliki hubungan darah. Sesudah menikah pun mereka bebas
menentukan tempat tinggal, biasanya secara neolokal (tumampas)
di mana mereka tinggal di suatu tempat yang baru, terpisah
dari kerabat istri maupun suami. Namun sebelum mempunyai rumah
sendiri, adakalanya mereka tinggal di sekitar kerabat suami
atau istri. Dengan tinggal berdampingan dengan keluarga batih
dari kerabat atau orang tua, terbentuk suatu keluarga luas,
8
yang biasanya terdiri dari beberapa keluarga batih, baik dalam
satu rumah maupun satu pekarangan.
Batas-batas dari hubungan kekerabatan yang terdapat pada
orang Minahasa ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan
melalui lelaki dan wanita yang disebut prinsip keturunan
bilateral. Dalam bahasa Minahasa prinsip keturunan seperti ini
disebut taranak (famili), yang dapat dimengerti sebagai sebuah
klen kecil. Setiap taranak memiliki kepala yang disebut tua unta
ranak. Identitas satu taranak dilihat dari nama famili atau
disebut fam. Nama famili ini biasanya diambil dari nama famili
suami tanpa perubahan prinsip bilateral. Hal ini diperkuat
dengan adanya kenyataan penulisan fam suami dan isteri bersama-
sama pada papan nama yang ditempelkan di depan rumah. Hal yang
menonjol dalam hubungan taranak di Minahasa, ialah di bidang
warisan, kematian, perkawinan, dan pemilihan kepala desa.
Dalam beberapa bidang ini sering timbul persaingan antar
taranak dan kerjasama dalam satu taranak. Beberapa istilah yang
digunakan untuk menyapa anggota famili dalam masyarakat
Minahasa, yakni: Opu (kakek dari ayah atau ibu), Omu (nenek
dari ayah atau ibu), Opa/Tek (ayah dari ibu/ayah), Oma/Nek (ibu
dari ayah/ibu), Papa/Papi/Pa’ (ayah), Mama/Mami/Ma’ (ibu), Om/Mom
(paman), Tante (bibi/tanta), dan Bu/Mbu (ipar/kakak lelaki).
Desa (Banua/Wanua) merupakan suatu kesatuan hidup setempat
di Minahasa yang dipimpin oleh seorang kepala desa (hukumtua).
Ia dibantu oleh sejumlah orang yang semuanya disebut pamong
desa. Untuk usaha-usaha gotong royong dan pembangunan desa,
terdapat juga orang-orang yang membantu hukumtua yang biasa
disebut tua-tua kampung. Mereka itu terdiri dari pemimpin-
9
pemimpin agama setempat, guru-guru, mantan hukumtua, pemimpin-
pemimpin kecil/RT dalam desa (kepala jaga), meweteng (pembantu
kepala jaga), juru tulis, dan sejumlah pensiunan yang ada di
desa.
Dalam menghadapi hal-hal kemasyarakatan yang penting
seperti kematian, perkawinan, pengerjaan wilayah pertanian,
kepentingan rumah tangga atau komunitas, masyarakat Minahasa
menampakkan suatu gejala solidaritas berupa bantu-membantu dan
kerjasama yang didasarkan pada prinsip resiprositas. Kegiatan
kerjasama dan gotong royong ini disebut dengan mapalus. Bantuan
yang diberikan bisa dalam berbagai bentuk, baik tenaga maupun
barang-barang atau uang. Bantuan tersebut harus disadari oleh
orang yang menerimanya dan diberikan balasannya, jika tidak ia
akan dianggap sebagai orang yang tidak baik dan tidak akan
menerima bantuan lagi dari siapapun.
Masyarakat Minahasa umumnya memiliki suatu kesadaran akan
kesatuan tempat asal seperti sekampung/sekecamatan/sedistrik
dan juga berdasarkan kekerabatan/famili yang terwujud dalam
kelompok-kelompok sosial seperti perkumpulan-perkumpulan,
persatuan-persatuan, dan kerukunan yang terdapat di kota
Manado maupun di daerah lain di luar Minahasa. Kerukunan
seperti ini biasa disebut pakasa’an, yang dahulu sebenarnya
berarti wilayah kesatuan adat yang sama. Tetapi kini
perkumpulan-perkumpulan pakasa’an ini tidak lagi mendasarkan
kesatuan sosial mereka menurut wilayah-wilayah pakasa’an atau
distrik dahulu.
Perkawinan dalam masyarakat Minahasa bukan berdasarkan
penjodohan oleh orang tua, sehingga pergaulan muda-mudi
10
umumnya bebas tetapi selalu dilihat secara diam-diam oleh
pihak orang tua. Para muda-mudi memiliki waktu tertentu
sebagai kesempatan pertemuan, yakni pada saat pesta-pesta
kawin, malam hiburan, dan mapalus. Bila seorang pemuda sudah
menemukan jodohnya, ia berterus-terang kepada orang tuanya.
Jika disetujui, orang tua kemudian mengambil seorang perantara
(rereoan/pabusean) untuk menyampaikan hasrat pemuda tersebut
dengan mengatasnamakan orang tua pemuda kepada pihak orang tua
perempuan. Bila disetujui, upacara berlanjut pada penentuan
hari pengantaran mas kawin yang dikenal dengan antar harta/mali
pakeang/mehe roko. Upacara itu termasuk juga dengan penentuan
tempat dan tanggal pernikahan, jumlah undangan, surat-surat
yang diperlukan, saksi-saksi, dan sebagainya. Kemudian barulah
dilangsungkan upacara perkawinan yang biasanya diadakan di
gereja dan melalui pemerintah (catatan sipil). Di samping itu,
masih ada juga kawin baku piara yang tidak melalui catatan sipil
atau agama. Hal ini seringkali dipengaruhi oleh persetujuan
orang tua dan keterbatasan ekonomi.
f. Nilai dan contoh kebudayaan
Mapalus adalah suatu sistem atau teknik kerja sama untuk kepentingan bersama dalam budaya Suku Minahasa. Secara fundamental, Mapalus adalah suatu bentuk gotong royong tradisional yang memiliki perbedaan dengan bentuk-bentuk gotong royong modern, misalnya: perkumpulan atau asosiasi usaha. Secarafilosofis, MAPALUS mengandung makna dan arti yang sangat mendasar. MAPALUS sebagai local spirit and local wisdom Masyarakat Minahasa yang terpatri dan berkohesi di dalamnya: 3 (tiga) jenis hakikat dasar pribadi manusia dalam kelompoknya, yaitu: Touching Hearts, Teaching Mind, dan Transforming Life. Mapalus adalah hakikat dasar dan aktivitas kehidupan orang Minahasa (Manado)
11
yang terpanggil dengan ketulusan hati nurani yang mendasar danmendalam (touching hearts) dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab menjadikan manusia dan kelompoknya (teaching mind) untuksaling menghidupkan dan menyejahterakan setiap orang dan kelompok dalam komunitasnya (transforming life). Menurut buku,The Mapalus Way, mapalus sebagai sebuah sistem kerja yang memiliki nilai-nilai etos seperti, etos resiprokal, etos partisipatif, solidaritas, responsibilitas, gotong royong, good leadership, disiplin, transparansi, kesetaraan, dan trust
Seiring dengan berkembangnya fungsi-fungsi organisasi sosial yang menerapkan kegiatan-kegiatan dengan asas Mapalus, saat ini, Mapalus juga sering digunakan sebagai asas dari suatu organisasi kemasyarakatan di Minahasa. Mapalus berasaskan kekeluargaan, keagamaan, dan persatuan dan kesatuan. Bentuk Mapalus, antara lain:
Mapalus tani Mapalus nelayan Mapalus uang Mapalus bantuan duka dan perkawinan; dan, Mapalus kelompok masyarakat.
Dalam penerapannya, Mapalus berfungsi sebagai daya tangkal bagi resesi ekonomi dunia, sarana untuk memotivasi danmemobilisasi manusia bagi pemantapan pembangunan, dan merupakan sarana pembinaan semangat kerja produktif untuk keberhasilan operasi mandiri, misalnya: program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Prinsip solidaritas yang tercermin dalam Mapalus terefleksi dalam perekonomian masyarakat di Minahasa, yaitu dikenalkannya prinsip ekonomi Tamber. Prinsip ekonomi Tamber merujuk pada suatu kegiatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, atau warga sewanua (sekampung) secara sukarela dan cuma-cuma, tanpa menghitung-hitung atau mengharapkan balas jasa.
Prinsip ekonomi Tamber berasaskan kekeluargaan. Dari segimotivasi adat, prinsip ini mengandung suatu makna perekat kultural (cagar budaya) yang mengungkapkan juga kepedulian sosial, bahkan indikator keakraban sosial. Faktor kultural prinsip ekonomi Tamber berdasarkan keadaan alam Minahasa yang
12
subur dan berlimpah, dan tipikal orang Minahasa yang cenderungrajin dan murah hati.
II. Kebudayaan Maluku
a. Lokasi dan lingkungan alam
Terletak disekitaran Indonesia Timur tepatnya di Kepulauan Maluku yaitu sekelompok pulau di Indonesia yang merupakan bagian dari Nusantara dgn koordinat 3°9′LU 129°23′BT. Dengan luas 74.505 km² dgn puncak tertinggi yaitu Binaiya (3.027 m) Kepulauan Maluku terletak di lempeng Australia. Ia berbatasan dengan Pulau Sulawesi di sebelah barat, Nugini di timur, dan Timor Leste di sebelah selatan, Palau di timur laut. Pada zaman dahulu, bangsa Eropa menamakannya "Kepulauan rempah-rempah" — istilah ini juga merujuk kepada Kepulauan Zanzibar.
Sejak 1950 - 1999, Kepulauan Maluku Utara secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Maluku. KabupatenMaluku Utara kemudian ditetapkan sebagai Provinsi Maluku Utara. Ibu kota Maluku adalah Ambon yang bergelar atau memiliki julukan sebagai Ambon Manise, kota Ambon berdiri di bagian selatan dari Pulau Ambon yaitu di jazirah Leitimur. Provinsi Maluku dan Maluku Utara membentuk suatu gugus-gugus kepulauan yang terbesar di Indonesia dikenal dengan Kepulauan Maluku dengan lebih dari 4.000 pulau baik pulau besar maupun kecil.
b. Demografi Maluku
Suku Wemale : Merupakan salah satu etnik maluku dari Pulau Seram yang sekitar berjumlah 9.000 jiwa dan merupakan bagian dari Melayu-Polinesia serta hidup dengan39 desa atau kampung dari pusat Pulau Seram.
Suku bangsa Maluku didominasi oleh ras suku bangsa Melanesia Pasifik yang masih berkerabat dengan Fiji, Tonga, dan beberapa bangsa kepulauan yang tersebar di kepulauan Samudra Pasifik.
Banyak bukti kuat yang merujuk bahwa Maluku memiliki ikatan tradisi dengan bangsa bangsa kepulauan pasifik, seperti bahasa, lagu-lagu daerah, makanan, serta perangkat peralatan rumah tangga
13
dan alat musik khas, contoh: Ukulele (yang terdapat pula dalam tradisi budaya Hawaii).
Mereka umumnya memiliki kulit gelap, rambut ikal, kerangka tulang besar dan kuat, serta profil tubuh yang lebih atletisdibanding dengan suku-sukulain di Indonesia, dikarenakan mereka adalah suku kepulauan yang mana aktivitas laut seperti berlayar dan berenang merupakan kegiatan utama bagi kaum pria.
Sejak zaman dahulu, banyak di antara mereka yang sudah memiliki darah campuran dengan suku lain yaitu dengan bangsaEropa (umumnya Belanda dan Portugal) serta Spanyol, kemudian bangsa Arab sudah sangat lazim mengingat daerah ini telah dikuasai bangsa asing selama 2.300 tahun dan melahirkan keturunan keturunan baru, yang mana sudah bukan rasMelanesia murni lagi namun tetap mewarisi dan hidup dengan beradatkan gaya Melanesia-Alifuru.
Karena adanya percampuran kebudayaan dan ras dengan orang Eropa dan Arab inilah maka Maluku merupakan satu-satunya wilayah Indonesia yang digolongkan sebagai daerah yang memiliki kaum Mestizo terbesar selain Timor Leste (Timor Leste, sekarang menjadi negara sendiri). Bahkan hingga sekarang banyak nama fam/mata ruma di Maluku yang berasal adat bangsa asing seperti Belanda (Van Afflen, Van Room, De Wanna, De Kock, Kniesmeijer, Gaspersz, Ramschie, Payer, Ziljstra, Van der Weden, dan lain-lain) serta Portugal (Da Costa, De Fretes, Que, Carliano, De Souza, De Carvalho, Pareira, Courbois, Frandescolli,dan lain-lain). Ditemukan pula fam/mata ruma keturunan bangsa Spanyol (Oliviera, Diaz, De Jesus, Silvera, Rodriguez, Montefalcon, Mendoza, De Lopez, dan lain-lain) serta fam-fam Arab yang langsung dari Hadramaut (Al-Kaff, Al Chatib, Bachmid, Bakhwereez, Bahasoan, Al-Qadri, Alaydrus, Assegaff, dan lain-lain). Cara penulisan fam orangAmbon/Maluku pun masih mengikuti dan disesuaikan dengan cara pembacaan ejaan asing seperti Rieuwpassa (baca: Riupasa), Nikijuluw (baca: Nikiyulu), Louhenapessy (baca: Lohenapesi), Kallaij (baca: Kalai), dan Akyuwen (baca: Akiwen).
Dewasa ini, masyarakat Maluku tidak hanya terdapat di Indonesia saja melainkan tersebar di berbagai negara di dunia. Kebanyakan dari mereka yang hijrah keluar negeri disebabkan olah berbagai alasan. Salah satu sebab yang paling klasik adalah perpindahan besar-besaran masyarakat Maluku ke Eropa pada tahun 1950-an dan menetap di sana hingga sekarang. Alasan lainnya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, menuntut ilmu, kawin-
14
mengawin dengan bangsa lain, yang di kemudian hari menetap lalu memiliki generasi-generasi Maluku baru di belahan bumi lain. Paraekspatriat Maluku ini dapat ditemukan dalam komunitas yang cukup besar serta terkonsentrasi di beberapa negara sepertiBelanda (yang dianggap sebagai tanah air kedua oleh orang Maluku selain tanah Maluku itu sendiri), Suriname, dan Australia.Komunitas Maluku di wilayah lain di Indonesia dapat ditemui di Medan, Palembang, Bandung, Jabodetabek, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Makassar, Kupang, Manado, Kalimantan Timur, Sorong, dan Jayapura.
c. Sistem Kemasyarakatan dan kekerabatan
Dalam sistem kemasyarakatan masyarakat Ambon mengambil system kekerabatan yang bersifat ke-Ayahan “Patrilineal”. Di dalam kekerabatan yang memegang peranan penting ada dua yaitu
- “Mata rantai”, mata rumah ini biasanya bertugas mengatur perkawinan warganya -
- “Exogami” dan dalam hal mengatur penggunaan tanah-tanah “dati” tanah milik kerabat patrilineal.
- “Family”, family merupakan kesatuan terkecil dalam mata rumah. Family ini berfungsi sebagai pengatur pernikahan klenya.
Perkawinan dalam masyarakat Ambon merupakan urusan mata rumah dan family. Di dalam masyarakat Ambon perkawinan di kenal dengan beberapa macam, diantaranya :
a. Kawin minta ialah perkawinan yang terjadi apabila seorang pemuda telah menemukan seorang gadis yang akan dijadikan istri, maka pemuda in meminta pada mata rumah dan family untuk melamarnya. Sebelum acara pelamaran para mata rumah dan family mengadakan rapat adat satu klen dalam persiapan acara pelamaran.
b. Kawin lari atau lari bini adalah system perkawinan yang paling lazim di lakukan oleh masyarakat Ambon. Hal ini di karenakan oleh masyarakat Ambon lebih suka jalan pendek, untukmenghindari prosedur perundingan dan upacara adat.
c. Kawin masuk atau kawin menua yaitu perkawinan yang pengantin laki-lakinya tinggal di rumah pengantin perempuannya. Perkawinan ini terjadi apabila :
15
· Kaum kerabat si pengantin tidak dapat membayar maskawin secara adat.
· Penganten perempuan merupakan anak tunggal dalam keluarganya.
· Karena ayah dari pengaten laki-laki tidak setuju dengan perkawinan tersebut
d. Nilai dan contoh kebudayaan
Salah satu dari banyaknya budaya Maluku adalah Kalwedo. Kalwedo adalah bukti yang sah atas kepemilikan masyarakat adat di Maluku Barat Daya (MBD). Kepemilikan ini merupakan kepemilikan bersama atas kehidupan bersama orang bersaudara. Kalwedo telah mengakar dalam kehidupan baik budaya maupun bahasa masyarakat adat di kepulauan Babardan MBD. Pewarisan budaya Kalwedo dilakukan dalam bentukpermainan bahasa, lakon sehari-hari, adat istiadat, dan pewacanaan.
Nilai Adat Kalwedo Kalwedo merupakan budaya yang memiliki nilai-
nilai sosial keseharian, dan juga nilai-nilai religius yang sakral yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian, dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya Kalwedo mempersatukan masyarakat di kepulauan Babar maupun di Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat, dimana mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa dan istana adat milik bersama. Nilai Kalwedo diimplementasikan dalam sapaan adat kekeluargaan lintas pulau dan negeri, yaitu: inanara ama yali (saudara perempuan danlaki-laki). Inanara ama yali menggambarkan keutamaan hidup dan pusaka kemanusiaan hidup masyarakat MBD, yang meliputi totalitas hati,jiwa, pikiran dan perilaku.
Nilai-nilai Kalwedo tersebut mengikat tali persaudaraan masyarakat melalui tradisi hidup Niolilieta/hiolilieta/siolilieta (hidup berdampingan dengan baik). Tradisi hidup masyarakat MBD dibentuk untuk saling berbagi dan saling membantu dalam hal potensi alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang diwariskan oleh alam kepulauan MBD.
Budaya Hawear Hawear (Sasi) adalah budaya yang tumbuh dan berlaku dalam kehidupan
masyarakatKepulauan Kei secara turun menurun. Cerita rakyat, lagu
16
rakyat, dan berbagai dokumen tertulis merupakan prasarana untuk melestarikan kekayaan budaya termasuk Hawear. Sejarah Hawear bermuladari seorang gadis yang diberikan daun kelapakuning (janur kuning) oleh ayahnya. Kemudian janur kuning itu disisipkan atau diikat di kain seloi yang dipakainya. Gadis tersebut melakukan perjalanan panjang untuk menemui seorang raja (Raja Ahar Danar). Maksud dari janur kuning tersebut sebagai tanda bahwa ia telah dimiliki oleh seseorang, dimaksudkan agar ia tidak diganggu oleh siapapun selama perjalanan. Janur kuning tersebut diberikan oleh sang ayah, karena sang ayah pernah diganggu oleh orang-orang tak dikenal dalam perjalanannya. Hal ini adalah proses Hawear yang masih dijalankan sesuai dengan maknanya hingga saat ini.
Batu Pamali Batu Pamali adalah simbol material adat masyarakat
Maluku. Selain Baileo, rumah tua, dan teung soa, batu Pamali juga termasuk mikrosmos dalam negeri-negeri yang ditempati masyarakat adat Maluku. Batu Pamali merupakan batu alas atau batu dasar berdirinya sebuah negeri adat yang selalu diletakkan di samping rumah Baileo, sekaligus sebagai representasi kehadiran leluhur (TeteNene Moyang) di dalam kehidupan masyarakat. Batu Pamali sebagai bentuk penyatuan soa-soa dalam negeri adat, dengan demikian batu Pamali adalah milik bersama setiap soal. Di beberapa negeri adat Maluku, batu Pamali dimiliki secara kolektif, termasuk negeri adat yang masyarakatnya memeluk agama yang berbeda. Seiring dengan perkembangan agama di masyarakat, terjadi pergeseran praktik ritus dan keberadaan batu Pamali. Dengan adanya UU No. tahun 1979, adat asli negeri-negeri diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa.
Upacara Fangnea Kidabela Kepulauan Tanimbar yang sekarang menjadi Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, memiliki kebudayaan yang mengatur persaudaraan dan kehidupan sosial masyarakat dalam bentuk Duan Lolat dan Kidabela. Duan Lolat mengatur tentang hubungan sosial masyarakat yang luas, yaitu memperkuat hubungan antardua desa atau lebih, dan hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk Kidabela. Upacara Fangnea Kidabela memperkokoh hubungan sosial masyarakat Tanimbar dalam wadah persaudaraan dan persekutuan agar tidak mudah pecah atau retak.
Makna Upacara Fangnea Kidabela17
Upacara Fangnea Kidabela mengandung makna persatuan dan kesatuan hidup masyarakat Tanimbar baik internal maupun eksternal dalam setiap situasi. Upacara Fangnea Kidabela juga mengandung makna sebagai pemanasan, pengerasan, dan pemantapan (fangnea) terhadap persahabatan, persaudaraan (itawatan) dan keakraban (kidabela) di antara sesama sebagai suatu persekutuan wilayah teritorial Kampung Sulung di pulau Enus yang terletak di Selaru bagian selatan pulau Yamdena. Makna upacara Frangnea Kidabela sama dengan upacara Panas Pela di Ambon, Lease, danMaluku Tengah. Upacara ini menciptakan suasana hidup bermasyarakat yang kokoh dan kuat untuk mencegah fenomena konflik dan perpecahan terhadap hubungan masyarakat.
Hibua Lamo Hibua Lamo adalah rumah besar yang dijadikan simbol masyarakat adat
di Halmahera Utara, sekaligus simbol Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Di Halmahera Utara terdapat tiga etnis masyarakat yang memiliki rumah adat masing-masing, misalnya rumah adat etnis Tobelo disebut Halu. Namun Hibua Lamo yang menjadi pemersatu semua etnis.[8] Hibua Lamo adalah konstruksi dari nilai-nilai hidup dalam masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai komunitas Hibua Lamo. Hibua Lamo merupakan konsep bersama yang disebut Nanga Tau Mahirete (rumah kita bersama). Orang Tobelo, Galela dan Loloda tersegregasi secara geografis, dan terbelenggu dalam tradisi, agama dan kepercayaan yang berbeda. Perbedaan tersebut dipahami dan dihayati dengan kesucian hati dan kemurnian pikiran, kemudian diterapkan dalam sebuah ungkapan filosofis Ngone O'Ria Dodoto yang bermakna satu ibu satu kandung. Konsekuensi dari falsafahNanga Tau Mahurete dan Ngone O'Ria Dodoto adalah lahirnya sebuah komunitas asli Halmahera Utara daratanmaupun kepulauan dalam satu kesatuan yang teridentifikasi sebagai komunitas Hibua Lamo dan kemudian disimbolkan dalam rumah adat HimuaLamo.
Dalam konteks ini komunitas Tobelo, Galela, dan Loloda mengalami proses penyatuan dalam satu sosiokultural baru yang dinamis. Sosiokultural ini berlandaskan pada nilai-nilai O'dora (saling kasih), O'hanyangi (saling sayang), O'baliara (saling peduli), O'adili (perikeadilan) dan O'diai (kebenaran) dalam bingkai Nanga Tau Mahurete dan Ngone O'Ria Dodoto.
18
Budaya Arumbae Arumbae adalah bentukan karakter masyarakat Maluku, baik yang
tinggal di pesisir maupun di pegunungan. Arumbae adalah kebudayaan berlayar dalam masyarakat Maluku. Perjuangan melintasi lautan merupakan bagian dari terbentuknya suatu masyarakat. Sebagai contoh,masyarakat Tanimbar - dalam mitos Barsaidi meyakini bahwa leluhur mereka tiba di pulau Yamdena setelah melewati perjuangan yang sulit di lautan. Perjuangan melintasi lautan merupakan sejarah keluhuran. Kedatangan para leluhur dari pulauSeram, pulau Jawa (seperti Tuban dan Gresik) dan pulau Bali menjadi bagian dari cerita keluhuran masyarakat di Maluku Tengah, Buru,Ambon, Lease, dan Maluku Tenggara. Ragam cerita inilah yang membentuk terjadinya persekutuan Pela Gandong antar negeri. Dalam pataka daerah Maluku, Arumbae menjadi simbol daerah yang di dalamnya terdapat lima orang sedang mendayung menghadapi tantangan lautan. Secara filosofis, maknanya ialah masyarakat Malukuadalah masyarakat yang dinamis, dan penuh daya juang dalam menghadapi tantangan untuk menyongsong masa depan yang gemilang.
Laut adalah medan penuh bahaya dan Arumbae menstrukturkan cara pandang bahwa laut adalah medan kehidupan yang harus dihadapi. Itulah sebabnya, masyarakat Maluku melihat laut sebagai jembatan persaudaraan yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Berlayar ke suatu pulau, seperti dalam Pela Gandong bertujuan untuk mengeratkan jalinan hidup orang bersaudara sebagai pandangan dunia orang Maluku. Kebiasaan papalele, babalu, maano, dan konsekuensi berlayar ke pulau lain, membuat laut dan arumbae sebagaisimbol perjuangan ekonomi.
Arumabe tampak dalam beragam karya seni. Misalnya dalam syair kata tujuh ya nona, ditambah tujuh, sapuluh ampa ya nona dalang parao Banyak gapura negeri adat Maluku berbentuk Arumbae. Lagu daerah banyak mengumpamakan keharmonisan dengan simbol perahu atau Arumbae. Di bidang olahraga, Arumbae Manggurebe menjadi programpariwisata dan olah raga tahunan yang diselenggarakan di Teluk Ambon.
Sasahil dan Nekora Sasahil dan Nekora merupakan tradisi masyarakat adat di Negeri Siri
Sori Islam dan Negeri Siri Sori Kristen di pulau Saparua. Bagi masyarakat desa Telalora, Nekora memiliki basis nilai tolong-menolong antarwarga. Nilai tradisi Sasahil dan Nekora terletak pada cara dan proses pelaksanaan. Nilai tolong-menolong yang terdapat
19
dalam tradisi Sasahil maupun Nekora memiliki basis solidaritas yang kuat, dan menciptakan relasi saling memberi dan menerima antarwarga agar suatu pekerjaan berat untuk mendirikan rumah bisa lebih ringan. [10] Dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berubah, tradisi Sasahil dan Nekora selalu dipertahankan dan dipelihara dengan baik. Hal ini dimaksudkan sebagai modal sosial kelangsungan hidup bermasyarakat di masa mendatang.
Daftar Pustaka
1. http://planologynote.blogspot.com/2012/11/minahasa-mari-
jo-jaga-torang-pe-budaya.html
2. http://randyefferputra.blogspot.com/2012/08/mengenal-
suku-bangsa-minahasa.html
3. Koentjaraningrat. 2007. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta:
Djambatan
4. http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2010/10/budaya-
mapalus-sistem-gotong-royong.html
5. http://nilakatrin.blogspot.com/2013/04/kebudayaan-maluku.html
20
Related Documents