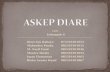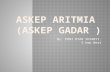MAKALAH SISTEM PENCERNAAN I “GASTROSCISIS“ DISUSUN OLEH : RO’UUFUN NISA HAQU RAHAYU TRI NURITASARI ARIS SEPTIANA AJI PRAMUSTYO ANDRIANUS ASA BELE ROY SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN i

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MAKALAHSISTEM PENCERNAAN IGASTROSCISIS
DISUSUN OLEH :ROUUFUN NISA HAQURAHAYU TRI NURITASARIARIS SEPTIANAAJI PRAMUSTYOANDRIANUS ASA BELE ROY
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATANPATRIA HUSADA BLITAR2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul Asuhan Keperawatan Gastroskisis. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pencernaan I. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memenuhi kriteria penilaian dan bermanfaat bagi pembaca.
Blitar, November 2013
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARiiDAFTAR ISIiiiBAB I PENDAHULUAN 11.1 Latar Belakang11.2 Rumusan Masalah21.3 Tujuan31.4 Manfaat3BAB II KONSEP DASAR4 2.1 Dfinisi4 2.2 Etiologi52.3 Patofisiologi72.4 Pemeriksaan Penunjang82.5 Penatalaksanaan92.6 Komplikasi132.7 Prognosis13BAB III ASUHAN KEPERAWATAN15 3.1 Pengkajian15 3.2 Dianogsa Keperawatan15 3.3 Interverensi16BAB IV PENUTUP20 4.1 Kesimpulan20 4.2 Saran20DAFTAR PUSTAKA21
i
BAB IPENDAHULUAN1.2 Latar BelakangDinding perut mengandung struktur muskulo aponeuresis yang kompleks. Pada bagian belakang, struktur ini melekat pada tulang belakang dan sebelah atas melekat pada iga, sedangkan di bagian bawah melekat pada tulang panggul. Dinding perut sendiri terdiri dari berbagai lapis, yaitu lapisan kulit yang terdiri dari kutis dan sub-kutis, lemak sub-kutan dan fasia superfisialis. Struktur otot dinding perut terdiri dari muskulus oblikus abdominis externus, muskulus oblikus abdominis internus, muskulus tranfersus abdominis, dan lapisan preperitoneum. Selanjutnya adalah lapisan peritoneum yang terdiri dari fasia tranversalis, lemak peritoneal dan peritoneum (Hunter dan Soothill, 2002).Perkembangan dinding perut dipengaruhi terutama pada masa perkembangan embriologi, yaitu pada minggu kelima hingga minggu kesepuluh. Pada minggu keenam akan terjadi pertumbuhan yang cepat dari midgut yang akan menyebabkan hernia fisiologis dari usus kemudian pada minggu kesepuluh bagian usus tersebut akan kembali ke kavum abdomen. Pada bayi yang lahir dengan gastroshisis proses ini tidak terjadi. Cacat kongenital dinding abdomen ini memberi ancaman yang mematikan bagi neonatus sebagai akibat terpaparnya visera dan kemungkinan kontaminasi bakteri(Hunter dan Soothill, 2002). Gastroschisis adalah kelainan paraumbilikal kongenital dari dinding anterior abdomen yang menyebabkan herniasi dari visera abdominal ke luar cavum abdomen. Kelainan ini biasanya kecil, memiliki pembukaan yang memiliki pinggir yang lembut yang selalu berada di sebelah lateral umbilikus dan tidak memiliki pembungkus. Merupakan kecacatan yang muncul kira-kira 0,5-1 dalam 10.000 kelahiran hidup. Gastroshisis bukan merupakan penyakit genetik, namun lebih pada kelainan kongenital yang jarang terjadi, di mana penelitian epidemiologi menyatakan bahwa penyakit ini kemungkinan besar berhubungan dengan ibu yang mengandung pada usia muda dengan status sosial-ekonomi menengah ke bawah dan kondisi malnutrisi (Kumar dan Burton, 2008). Gastroshisis merupakan kasus dengan tingkat kegawat-daruratan dan resiko kematian yang tinggi, oleh karena itu penanganan yg tepat dapat membantu meningkatkan prognosa hidupannya. Penanganan pembedahan dilakukan segera setelah kondisi bayi stabil pasca-persalinan, hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi dan kerusakan jaringan yang berherniasi. Penanganan cepat dapat dilakukan apabila diagnosis dapat ditegakkan selama kehamilan atau sebelum kelahiran. Diagnosis pre-natal dapat mendeteksi kira-kira 83% dari kelainan dinding abdomen.Oleh karena itu dibutuhkan screening pada ibu hamil trimester pertama untuk bisa menentukan diagnosa pre-natal sehingga kita bisa merencanakan persalinannya.Di negara barat tingkat kematian pada gastroshisis terus berkurang karena diagnosa dini yang bagus. Gastroshisis dapat dideteksi dini pada kehamilan melalui ultrasound dan kenaikan level serum alpha-fetoprotein ibu. Setelah diagnosis pre-natal dapat ditegakkan, persalinan dilakukan lebih awal untuk membatasi kerusakan dari jaringan usus. Dari keakuratan diagnosis pre-natal inilah dapat dilakukan persiapan penanganan secara tepat dan cepat. Kombinasi dari diagnosis dan penatalaksaan ini dapat meningkatkan prognosis gastroshisis menjadi lebih baik.Dari data di atas, penulis akan mengangkat studi pustaka mengenai gastroshisis, terutama mengenai diagnosis pre-natal karena memegang peranan penting untuk menekan tingkat kematiannya dan meningkatkan prognosa kehidupannya.1.2 Rumusan Masalah1. Apakah yang dimaksud dengan Gastroscisis?2. Apa penyebab darigastroscisis?3. Bagaimana manifestasi klinis dari Gastroscisis?4. Bagaimana patofisiologi dari Gastroscisis?5. Apa pemeriksaan penunjang untuk Gastroscisis?6. Bagaimana komplikasi Gastroscisis?7. Bagaimana penatalaksanaan Gastroscisis?8. Bagaimana asuhan keperawatan pada klien dengan Gastroscisis? 1.3 Tujuan1.3.1 Tujuan UmumMenjelaskan tentang Gastroscisisdan Asuhan Keperawatan pada klien dengan kasus Gastroscisis.1.3.2 Tujuan Khusus1. Menjelaskan tentang Gastroscisis.2. Menjelaskan tentang penyebab dari Gastroscisis.3. Menjelaskan tentang manifestasi klinis dari Gastroscisis.4. Menjelaskan tentang patofisiologi dari Gastroscisis.5. Menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang untuk Gastroscisis.6. Menjelaskan tentang komplikasi Gastroscisis.7. Menjelaskan tentang penatalaksanaan Gastroscisis.8. Menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan Gastroscisis.
1.4 Manfaat 1. Untuk mengetahui tentang Gastroscisis.2. Untuk mengetahui tentang penyebab dari Gastroscisis.3. Untuk mengetahui tentang manifestasi klinis dari Gastroscisis.4. Untuk mengetahui tentang patofisiologi dari Gastroscisis.5. Untuk mengetahui tentang pemeriksaan penunjang untuk Gastroscisis.6. Untuk mengetahui tentang komplikasi Gastroscisis.7. Untuk mengetahui tentang penatalaksanaan Gastroscisis.8. Untuk mengetahui tentang asuhan keperawatan pada klien dengan Gastroscisis.
BAB IIKONSEP DASAR2.1 DefinisiGastroschisis adalah kelainan paraumbilikal kongenital dari dinding anterior abdomen yang menyebabkan herniasi dari visera abdominal ke luar cavum abdomen. Kelainan ini biasanya kecil, memiliki pembukaan yang memiliki pinggir yang lembut yang selalu berada di sebelah lateral umbilikus dan tidak memiliki pembungkus. Merupakan kecacatan yang muncul kira-kira 0,5-1 dalam 10.000 kelahiran hidup. Gastroshisis bukan merupakan penyakit genetik, namun lebih pada kelainan kongenital yang jarang terjadi, di mana penelitian epidemiologi menyatakan bahwa penyakit ini kemungkinan besar berhubungan dengan ibu yang mengandung pada usia muda dengan status sosial-ekonomi menengah ke bawah dan kondisi malnutrisi (Kumar dan Burton, 2008). Gastroshisis merupakan kasus dengan tingkat kegawat-daruratan dan resiko kematian yang tinggi, oleh karena itu penanganan yg tepat dapat membantu meningkatkan prognosa hidupannya.
Gambar: Bayi dengan Gastroshisis
Gambar: Bayi dengan Gastroshisis
2.2 EtiologiEtiologi secara embriologi pada defek kongenital abdomen tidak sepenuhnya diketahui dan masih merupakan subyek yang kontroversial. Meskipun beberapa bukti mengatakan bahwa etiologi gastroschizis terletak desebelah lateral dan hampir sama. Banyak kontroversi berhubungan dengan penyebab gastroschizis. Defek abdominal pada gastroschizis terletak disebelah lateral dan hampir selalu pada sebelah kanan dari umbilicus. Defek tersebut sebagai hasil dari rupturnya basis tali pusat dimana merupakan area yang lemah dari tempat involusi vena umbilicus kanan. Pada awalnya terdapat sepasang vena umbilikalis, yaitu vena umbilikalis kanan dan kiri. Ruptur tersebut terjadi in-utero pada daerah lemah yang sebelumya terjadi herniasi fisiologis akibat involusi dari vena umbilikalis kanan. Keadaan ini menerangkan mengapa gastroschizis hampir selalu terjadi lateral kanan dari umbilicus. Teori ini didukung oleh pemeriksaan USG secara serial, dimana pada usia 27 minggu terjadi hernia umbilikalis dan menjadi nyata gastroschizis pada usia 34,5 minggu. Setelah dilahirkan pada usia 35 minggu, memang tampak gastroschizis yang nyata.Penulis lain berpendapat bahwa gastroschizis diakibatkan pecahnya suatu eksomphalos. Rupturnya omphalokel kecil dan transformasi menjadi gastroschizis dapat terjadi didalam uterus. Tetapi banyak kejadian anomaly yang berhubungan dengan omphalokel tidak mendukung teori ini. Pada gastroschizis jarang terjadi anomaly, tetapi sering lahir premature (22%).Factor resiko tinggi yang berhubungan dengan omphalocel atau gastroschizis adalah resiko tinggi kehamilan seperti:1. Infeksi dan penyakit pada ibu2. Penggunaan obat obatan berbahaya, merokok3. Kelainan genetik4. Defisiensi gizi seperti asam folat, protein dan vitamin B. Complex5. Hipoksia6. Salisilat dapat menyebabkan defek pada dinding abdomen7. Unsur polutan logam berat dan radioaktif yang masuk kedalam tubuh ibu hamil.
Gambar USG GastroschisisDengan penggunaan USG (ultrasonografi) yang makin luas, maka diagnosis dapat diketahui saat janian masih dalam kandungan atau saat prenatal. Pada usia kehamilan 10 minggu, dinding dan kavitas abdomen dari fetus sudah dapat terlihat. Pada usia 13 minggu, secara normal terjadi kembalinya usus ke cavitas abdomen. Pada saat ini, baik gastroschizis dan omfalokel dapat terdeteksi.
2.1 PatofisiologiMenurut Suriadi & Yuliani.R patofisiologi dari gastroschizis atau omphalocele yaitu selama perkembangan embrio ada suatu kelemahan yang terjadi didalam dinding abdomen semasa embrio yang mana menyebabkan herniasi pada isi usus pada salah satu samping umbilicus (yang biasanya pada samping kanan), ini menyebabkan organ visera abdomen keluar dari kapasitas abdomen dan tidak tertutup oleh kantong. Terjadi malrotasi dan menurunnya kapasitas abdomen yang dianggap sebagai anomaly. Gastroschizis terbentuk akibat kegagalan fusi somite dalam pembentukan dinding abdomen sehingga dinding abdomen sebagian terbuka. Letak defek umumnya disebelah kanan umbilicus yang berbentuk normal. Usus sebagian besar berkembang diluar rongga abdomen janin, akibatnya usus menjadi tebal dan kaku karena pengendapan dan iritasi cairan amnion dalam kehidupan intra uterin, usus juga tampak pendek, rongga abdomen janin sempit. Usus usus, visera, dan seluruh rongga abdomen berhubungan dengan dunia luar menyebabkan penguapan dan pancaran panas dari tubuh cepat berlangsung, sehingga terjadi dehidrasi dan hipotermi, kontaminasi usus dengan kuman juga dapat terjadi dan menyebabkan sepsis, aerologi menyebabkan usus usus distensi sehingga mempersulit koreksi pemasukan kerongga abdomen sewaktu pembedahan. Embryogenesis, pada janin usia 5-6 minggu isi abdomen terletak diluar embrio dirongga selom. Pada usia 10 minggu terjadi pengembangan lumen abdomen sehingga usus dari ekstra peritonium akan masuk kerongga perut. Bila proses ini terhambat maka akan terjadi kantong dipangkal umbilicus yang berisi usus, lambung kadang hati. Dindingnya tipis terdiri dari lapisan peritonium dan lapisan amnion yang keduanya bening sehingga isi kantong tengah tampak dari luar, keadaan ini disebut omfhalocele, bila usus keluar dari titik terlemah dikanan umbilicus usus akan berada diluar rongga perut tanpa dibungkus peritonium dan amnion keadaan ini disebut gastroschizis (Retno Setiowati, 2008).
Gambar 2.2: Embriologi Midgut
2.4 Pemeriksaan PenunjangPemeriksaan diagnostiknya adalah:1. Pemeriksaan fisik, pada gastroschizis usus berada diluar rongga perut tanpa adanya kantong.2. Pemeriksaan laboratorium3. Prenatal ultrasound4. Pemeriksaan radiologi, fetal sonography dapat menggambarkan kelainan genetik dengan memperlihatkan marker struktural dari kelainan kariotipik. Echocardiography fetal membantu mengidentifikasi kelainan jantung (Retno Setiowati, 2008).
Gambar: USG Gastroschisis
2.5 PenatalaksanaanMasalah-masalah setelah kelahiran yaitu usus-usus, visera dan seluruh permukaan rongga abdomen berhubungan dengan dunia luar menyebabkan:1. Penguapan dan pancaran panas dari tubuh cepat berlangsung, sehingga terjadi dehidrasi dan hipotermi 2. kontaminasi usus dengan kuman juga cepat berlangsung sehingga terjadi sepsis.3. Aerofagi menyebabkan usus-usus distensi sehingga mempersulit koreksi pemasukan intestin ke rongga abdomen pada waktu pembedahan.
Pertolongan pertama untuk penyulit yang timbul dengan: 1. Pemasangan sonde lambung dan pengisapan yang kontinue untuk mencegah distensi usus-usus yang mempersulit pembedahan.2. Pemberian cairan dan elektrolit atau kalori intravena 3. Antibiotika dengan spektrum luas secara intrabvena dan pada prabedah 4. Suhu tubuh dipertahankan dengan baik 5. Pencegahan kontaminasi dengan menutup menggunakan kasa steril lembab dengan cairan NacL steril.6. Pembedahan segera dilakukan sebelum penyulit sseperti distensi usus dan hipotermi terjadi. Pembedahan segera dengan persiapan yang baik maka gastroskisis memiliki prognosis yang baik. Operasi koreksi untuk menempatkan usus kedalam rongga perut dan menutup lubang harus dikerjakan secepat mungkin kerena tidak ada perlindungan infeksi. Tambahan lagi makin ditunda opersi makin sukar karena usus akan edem. Operasi Pada gastroskisis, tujuan utama adalah untuk mereduksi visera yang mengalami hernia masuk kembali ke dalam abdomen dan untuk menutup fasia dan kulit untuk menciptakan dinding abdomen yang solid dengan umbilikus yang relatif normal untuk meminimalkan resiko bayi. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak teknik yang dapat digunakan. Pengobatan sangat bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis defek, ukuran bayi dan masalah yang berhubungan. Karena terdapat sedikit bukti untuk mengganggap suatu metode lebih bagus dari yang lain, terdapat variasi dalam pendekatan operasi.Pada gastroskisis, hilangnya panas dan cairan yang terus menerus dan perubahan metabolik membuat penutupan menjadi prioritas tinggi. Selama resusitasi awal pada saat lahir atau sesegera mungkin setelahnya, a prefabricated, spring-loaded Silastic silo ditempatkan pada defek untuk menutupi usus yang terpapar tadi. Praktek ini, akan meminimalisasikan kehilangan melalui penguapan, mencegah trauma tambahan dan juga dapat menilai perfusi usus secara terus menerus. Alat ini dapat ditempatkan dalam ruang bersalin atau disamping tempat tidur tanpa anestesi. Jika defek dinding abdomen terlalu kecil untuk mengakomodasi alat, defek dapat dbesarkan dengan anestesi lokal dan sedasi. Jika alat tidak dapat ditempatkan di samping tempat tidur, sesegera mungkin setelah resusitasi awal dan stabilisasi, bayi dilakukan operasi untuk penutupan primer atau pemasangan silo. Penutupan di kamar bersalin merupakan konsep yang menarik yang meminimalisasi waktu dan trauma perioperatif tetapi hanya mungkin dengan kelahiran yang terencana dari defek yang diketahui sebelumnya dan membutuhkan komitmen berbagai pihak. Perbaikan primer segera tanpa anestesi pernah dilaporkan untuk kasus tertentu dan mungkin menjadi contoh dramatik operasi dengan trauma dan invasif minimal.Setelah pemasangan spring-loaded silo, bayi dievaluasi lebih lanjut dan dirawat di ICU. Dengan diuresis spontan, dekompresi traktus gastrointestinal dari atas dan bawah dan resolusi edema dinding usus, maka volume usus yang terpapar yang berada di dalam bag menjadi turun dalam periode waktu yang singkat. Ketika bayi berada dalam kondisi stabil dan reduksi spontan usus ke dalam abdomen telah mencapai keadaan puncak, bayi dibawa ke kamar operasi untuk dilakukan percobaan penutupan primer tunda. Reduksi serial alat pada tempat tidur pernah disarankan, tetapi resiko salah pemasangan alat membuat rencana ini kurang menarik. Di kamar operasi, jika usus dapat direduksi ke dalam abdomen dan defek menutup primer (atau melalui perbaikan primer tunda), maka operasi dilakukan. Keputusan apakah bayi dapat mentoleransi reduksi dan perbaikan dapat menjadi susah dan dapat ditambahkan dengan mengukur tekanan intragastik selama penutupan berlangsung. Tekanan < 20 mm Hg dapat memprediksikan kesuksesan penutupan tanpa komplikasi tekanan intra-abdomen yang berlebihan. Metode lain dilaporkan untuk membantu dalam keputusan untuk menutup atau tidak adalah mengukur perubahan tekana vena sentral, tekanan ventilator dan karbondioaksida. Jika bayi dalam keadaan stabil ketika fascia ditutup, umbilicus dapat direkontruksi pada tingkat krista iliaka posterior selama penutupan kulit. Pembuatan umbilicus dapat selalu ditunda untuk waktu berikutnya. Jika perbaikan tidak mungkin, formal silastic silo dijahitkan ke fasia dan reduksi serial dilakukan post-operasi. Bayi dengan gastroskisis dan atresia intestinal memiliki tantangan yang cukup serius, jika usus berada dalam kondidi bagus dan abdomen dapat ditutup dengan mudah, perbaikan primer kombinasi dari kedua defek menjadi mungkin dilakukan. Oleh karena itu, jika atresia terjadi, prioritas pertama adalah menutup abdomen dengan primer atau primer tunda atau perbaikan silo bertahap. Bayi dijaga dengan dekompresi gaster dan nutrisi parenteral selama beberapa minggu hingga laparotomy dan perbaikan atresia intestinal. Tahap perbaikan ini akan menyebabkan inflamasi menghilang dan isi hernia kembali ke abdomen sebelum pembukaan usus dan pembuatan anastomosis.Pada omfalokel, strategi yang digunakan berbeda. Pertama, menutup kantong yang intak, kemudian tidak perlu terburu-buru untuk melakukan operasi penutupan. Sepanjang visera tertutupi membrane, evaluasi yang lengkap untuk defek yang berhubungan dapat dilakukan dan masalah lain teratasi. Ketika bayi stabil dan jika defek relative kecil, perbaikan primer dapat dilakukan dengan insisi membrane omfalokel, mengurangi hernia visera dan menutup fasia dan kulit. Membrane yang melapisi liver mungkin terluka saat insisi, karena itu dapat dibiarkan saja. Ketika penutupan primer tidak mungkin dilakukan, ada banyak pilihan, namun yang dapat dilakukan adalah mengobati kantong omfalokel dengan sulfadiazine silver topical dan membiarkan agar terjadi epitelisasi hingga beberapa minggu atau bulan. Makanan enteral biasanya dapat ditolerasi setelah bayi sembuh dari berbagai masalah sistemtik. Setelah masalah lain yang berhubungan sudah diatasi, keluarga dapat diajarkan untuk untuk melakukan perawatan luka dan bayi diijikan untuk rawat jalan. Ketika epitelisasi kantong sudah terjadi atau sudah cukup kuat untuk mendapatlan tekanan luar, kompresi dilakukan dengan plester elastic dan secara serial dilakukan hingga isi abdomen mereduksi. Ketika isi abdomen tereduksi, membran mengalami epitelisasi dan bayi berada dalam keadaan baik, perbaikan hernia ventral dilakukan. Proses ini dapat dicapai dalam waktu 6-12 bulan, namun terdapat sedikit resiko dalam menunggu dalam menunggu selama masa tadi. Defek fasia menyisakan ukuran yang sama ketika bayi tumbuh. Hal ini membuat penutupan relative sedikit terlambat dari omfalokel yang berukuran besar. Strategi ini awalnya diadopsi hanya untuk pasien yang memiliki omfalokel berukuran besar atau berhubungan dengan masalah yang serius tetapi berjalan dengan baik pada kasus sulit yang sebelumnya tidak dapat ditutup. Teknik ini juga dapat mencegah kompromis paru, pecahnya luka, infeksi dan tertundanya pemberian makanan enteral yang terganggu dengan sejumlah operasi besar pada bayi yang baru lahir. Hal ini juga berguna khususnya untuk memperoleh penutupan fasia pada regio epigastrium omfalokel besar. Banyak strategi alternative untuk penutupan omfalokel, termasuk hanya penutupan kulit, reduksi silastic silo dan perbaikan, reduksi di dalam membrane omfalokel, inverse amnion dan penambalan fasia.
2.6 Komplikasi Komplikasinya adalah:1. Komplikasi dini adalah infeksi pada kantong yang mudah terjadi pada permukaan yang telanjang2. Kekurangan nutrisi dapat terjadi sehingga perlu balance cairan dan nutrisi yang adekuat misalnya: dengan nutrisi parenteral3. Dapat terjadi sepsis terutama jika nutrisi kurang dan pemasangan ventilator yang lama4. NekrosisKelainan congenital dinding perut ini mungkin disertai kelainan bawaan lain yang memperburuk prognosis (Retno Setiowati, 2008).
2.7 PrognosisMeskipun pada awalnya managemen dari gastroschisis sulit, namun efek jangka panjang memiliki problem yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan omfalokel. Mortalitas gastroschisis pada masa lampau cukup tinggi, yaitu sekitar 30%, namun akhir-akhir ini dapat ditekan hingga sekitar 5%. Mortalitas berhubungan dengan sepsis dan vitalitas dan kelainan dari traktus gastrointestinal pada saat pembedahan.Pada pasien gastroshisis dapat timbul short bowel syndrome, yang dapat disebabkan karena reseksi usus yang mengalami gangren, atau yang memang secara anatomik sudah memendek maupun adanya dismotilitas. Insidens dari obstruksi usus dan hernia abdominal juga meningkat pada pasien dengan gastroschisis maupun omfalokel. Gangguan fungsional baik nyeri abdominal dan konstipasi juga meningkat.Kurang lebih 30% pasien dengan defek kongenital dinding abdomen terjadi gangguan pertumbuhan dan gangguan intelektual. Namun hal ini perlu dipikirkan pula keadaan yang dapat menyertai pada defek dinding abdomen seperti premauritas, komplikasi-komplikasi yang terjadi dan anomali lainnya (Imam Sudrajat& Haryo Sutoto).
BAB IIIASUHAN KEPERAWATAN
3.1 PengkajianData fokus pengkajian menurut Doengoes,MF 1991:1. Mengkaji kondisi abdomena. Kaji area sekitar dinding abdomen yang terbukab. Kaji letak defek, umumnya berada disebelah kanan umbilicusc. Perhatikan adanya tanda tanda infeksi atau iritasid. Nyeri abdomen, mungkin terlokalisasi atau menyebar, akut atau kronis sering disebabkan oleh inflamasi, obstruksie. Distensi abdomen, kontur menonjol dari abdomen yang mungkin disebabkan oleh perlambatan pengosongan lambung, inflamasi, obstruksi.2. Mengukur temperatur tubuha. Demam, manifestasi umum dari penyakit pada anak anak dengan gangguan GI biasanya berhubungan dengan dehidrasi, infeksi atau inflamasib. Lakukan pengukuran suhu secara continue setiap 24 jamc. Perhatikan apabila terjadi peningkatan suhu secara mendadak3. Kaji sirkulasi, kaji adanya sianosis perifer4. Kaji distress pernafasana. Lakukan pengkajian fisik pada dada dan parub. Kaji adanya suara nafas tambahanc. Perhatikan bila tampak pucat, sianosisd. Perhatikan irama nafas, frekuensi
3.2 Diagnosa KeperawatanPre Operasi1. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penekanan rongga abdomen (paru-paru) 2. Resiko kurang volume cairan berhubungan dengan dehidrasi3. Resiko infeksi berhubungan dengan isi abdomen yang keluar4. Cemas pada orang tua b.d kurang pengetahuan penyakit yang diderita anaknya.
Post Operasi1. Nyeri Akut berhubungan dengan prosedur pembedahan menutup abdomen.2. Resiko Infeksi berhubungan dengan trauma jaringan luka post operasi3.2 IntervensiPre OperasiDx 1: Pola nafas tidak efektif b.d penekanan rongga abdomen (paru paru)NOC: respiratory status: AirwayTujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan manajemen jalan nafas selama 3 x 24 jam, diharapkan pola napas pasien kembali normal dan efektif dengan status respirasi skala 4Kriteria Hasil:a. Pola nafas efektif, tidak ada sianosis dan dypsneu, mampu bernapas dengan mudah.b. Bunyi nafas normal atau bersihc. TTV dalam batas normald. Ekspansi paru normalNIC: Airway Management1. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi2. Identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan napas buatan3. Atur intake untuk cairan mengoptimalkan keseimbangan.4. Monitor respirasi dan status oksigen
Dx 2 : Resiko kurang volume cairan b.d. dehidrasiNOC: Keseimbangan cairanTujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan manajemen cairan selama 3 x 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan pada pasien adekuat dengan status cairan skala 4.Kriteria hasil:1. Keseimbangan intake & output dalam batas normal2. Elektrolit serum dalam batas normal3. Tidak ada mata cekung4. Tidak ada hipertensi ortostatik5. Tekanan darah dalam batas normalNIC: Manajemen Cairan1. Pertahankan intake & output yang adekuat2. Monitor status hidrasi (membran mukosa yang adekuat)3. Monitor status hemodinamik4. Monitor intake & output yang akurat5. Monitor berat badan
DX 3 : Resiko infeksi berhubungan dengan isi abdomen yang keluarNOC: Knowledge: infection controlTujuan: Setelah dilakukan tindakan keperawatan kontrol infeksi selama 3 x 24 jam, diharapakan infeksi tidak terjadi (terkontrol) dengan status kontrol infeksi skala 4.Kriteria hasil:1. Klien bebas dari tanda dan gejala infeksi2. Menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi3. Jumlah leukosit dalam batas normal4. Menunjukkan perilaku hidup sehat
NIC: Infection control1. Pertahankan teknik isolasi2. Batasi pengunjung bila perlu3. Cuci tangan setiap sebelum dan sesudah tindakan keperawatan4. Bersihkan lingkungan setelah dipakai pasien lain5. Tingkatkan intake nutrisiPost OperasiDx 1: Nyeri Akut berhubungan dengan agen pencedera biologis, prosedur pembedahan menutup abdomen.NOC I: Tingkat NyeriTujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan manajemen nyeri selama 3 x 24 jam diharapkan pasien tidak mengalami nyeri, antara lain penurunan nyeri pada tingkat yang dapat diterima anak dengan status penerimaan nyeri skala 2Kriteria hasil :1. Anak tidak menunjukkan tanda-tanda nyeri (rewel)2. Nyeri menurun sampai tingkat yang dapat diterima anakNOC II: Level NyeriKriteria hasil :1. Memberikan isyarat rasa nyaman (tidak rewel)2. Nyeri menurunNIC : Menejemen Nyeri1. Kaji nyeri secara komprehensif (lokasi, durasi, frekuensi, intensitas)2. Observasi isyarat isyarat non verbal dari ketidaknyamanan.3. Berikan pereda nyeri dengan manipulasi lingkungan (misal ruangan tenang, batasi pengunjung).4. Berikan analgesia sesuai ketentuan5. Kontrol faktor faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan (lingkungan yang berisik).
Dx 2 : Resiko Infeksi berhubungan dengan trauma jaringan luka post operasiNOC : Pengenalian ResikoTujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan pengendalian infeksi selama 3 x 24 jam diharapkan pasien tidak mengalami infeksi dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi pada pasien dengan status pengendalian skala 4Kriteria hasil :1. Anak tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi2. Temperatur badan3. ImunisasiNIC : Pengendalian Infeksi1. Pantau tanda atau gejala infeksi2. Informaiskan kepada orang tua tentang jadwal imunisasi3. Rawat luka operasi dengan teknik steril4. Memelihara teknik isolasi (batasi jumlah pengunjung)5. Ganti peralatan perawatan pasien sesuai dengan protaps(Imam Sudrajat& Haryo Sutoto).
BAB IVPENUTUP
4.1 KesimpulanGastroschisis adalah kelainan paraumbilikal kongenital dari dinding anterior abdomen yang menyebabkan herniasi dari visera abdominal ke luar cavum abdomen. Kelainan ini biasanya kecil, memiliki pembukaan yang memiliki pinggir yang lembut yang selalu berada di sebelah lateral umbilikus dan tidak memiliki pembungkus.Kondisis gastroshisis berkaitan erat dengan kegagalan perkembangan pada masa embriologi, terutama pada minggu kelima hingga minggu kesepeluh.Etiologi masih belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, faktor resikonya terutama berhubungan dengan kondisi ibu saat mengandung. Diagnosis dari gastroshisis merupakan elemen yang penting dalam penanangan kasus ini. Diagnosis harus dapat ditegakkan sebelum kelahiran bayi. Prognosis meningkat karena pemeriksaan dan diagnosis pre-natal.
4.2 SaranSebagai seorang perawat, sedah menjadi kewajiban untuk memberikan tindakan perawatan dalam asuhan keperawatan yang diarahkan kepada pembentukan tingkat kenyamanan pasien, manajemen rasa sakit dan keamanan. Perawat harus mampu mamahami faktor psikologis dan emosional yang berhubungan dengan diagnosa penyakit, dan perawat juga harus terus mendukung pasien dan keluarga dalam menjalani proses penyakitnya.
DAFTAR PUSTAKA
Corwin, Elizabeth J. 2000. Buku Saku Patofisiologi. Jakarta : EGC.Doenges, E, Marilyn. 1999. Rencana Asuhan Keperawatan pedoman untuk perencanaan keperawatan pasien. Edisi 3 . Jakarta : EGC.Price, Sylvia & Loiraine M. Wilson. 1998. Patofisiologi Konsep Klinis Proses Penyakit. Edisi 4. Jakarta : EGC.Reksoprodjo S. Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah. 2002. Staf Pengajar Bagian Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Binarupa Aksara. Jakarta.Sadler TW. 2000. Embriologi Kedokteran Langman edisi 7. EGC. JakartaSmeltzer & Brenda G. bare. 2002. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah.Vol III. Edisi 8. Jakarta : EGC.
Related Documents