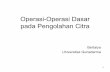1. PERENCANAAN OPERASI SISTEM TUJUAN PELAJARAN : Setelah mengikuti pelajaran ini peserta memahami penerapan konsep perencanaan operasi sistem DURASI : 4 JP PENYUSUN : 1. Rangga Jatnika

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. PERENCANAAN OPERASI SISTEM
TUJUAN PELAJARAN:Setelah mengikuti pelajaran ini peserta memahami penerapan konsep perencanaan operasi sistem
DURASI:4 JP
PENYUSUN:1. Rangga Jatnika
i
DAFTAR ISI
TUJUAN PELAJARANi
DAFTAR ISIii
1.PRAKIRAAN BEBAN1
1.1 Karakteristik Kurva Beban2
1.2Pembentukan Model Beban4
1.3Proses Updating dan Rencana Baru7
1.4Akurasi Prakiraan Beban9
2.PERENCANAAN HIDRO10
2.1Pola Operasi Waduk Citarum10
2.2Metode Perhitungan10
3.RENCANA OPERASI SISTEM13
3.1Rencana Operasi Sistem Jangka Panjang dan Menengah14
3.2Rencana Operasi Sistem Tahunan14
3.3Rencana Operasi Sistem Bulanan15
3.4Rencana Operasi Sistem Mingguan16
3.5Rencana Operasi Sistem Harian17
4.NERACA DAYA DAN ENERGI18
5.SPESIFIKASI BAHAN BAKAR21
DAFTAR PUSTAKA 22
SOAL LATIHAN23
Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal ii
PERENCANAAN OPERASI SISTEMPerencanaan Operasi Sistem adalah perencanaan pengoperasian sistem tenaga listrik yang meliputi perencanaan pembangkitan dan penyaluran untuk mencapai sasaran operasi sistem tenaga listrik yang ekonomis, andal dan berkualitas. Rencana Operasi disusun sebelum suatu sistem dioperasikan, yang selanjutnya dipakai sebagai pedoman untuk pengoperasian sistem tenaga listrik.Dalam penyusunan rencana operasi, dilakukan hal-hal sebagai berikut:1. Prakiraan Beban (Rencana Energi)2. Perencanaan Hidro3. Penjadwalan Pembangkit4. Penjadwalan Penyaluran 5. Penyusunan Neraca Daya6. Optimasi Hidrothermal7. Simulasi Produksi1. PRAKIRAAN BEBANDalam sistem Jawa Bali proses pembuatan prakiraan beban dimulai dengan pengolahan statistik terhadap data historis dari realisasi operasi. Pada tulisan ini akan dibahas proses pembuatan prakiraan beban dengan metode koefisien untuk aplikasi pada rencana operasi tahunan, bulanan, mingguan, dan harian.Pada kenyataannya, setiap realisasi beban tidak selalu sama untuk setiap saat, namun demikian terdapat karakteristik yang masih mempunyai pola-pola spesifik. Bila dibuat pendekatan, karakteristiknya tetap disamping memperhatikan pola pergeseran akibat adanya hari libur yang tidak selalu tetap. Pola-pola inilah yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menentukan prakiraan beban.Dalam dekade terakhir berkembang metode statistik dalam proses pembuatan prakiraan beban yaitu kombinasi dengan algoritme artificial intelligence seperti neural networks, fuzzy logic dan expert system. Dalam tulisan ini akan dipaparkan metode yang selama ini dipakai di Sistem Jawa Bali yaitu metode koefisien dengan menggunakan realisasi data operasi sebagai acuan dalam menentukan pola prakiraan beban puncak.
1.1.Karakteristik kurva bebana. Beban Puncak Sistem Mingguan dalam SetahunLangkah prakiraan beban untuk keperluan operasi dimulai dari pembuatan kurva beban puncak selama satu tahun yang terdiri dari 52 beban puncak mingguan. Pada kurva ini, hal yang paling spesifik adalah pergeseran hari libur pada hari raya Lebaran yang berbasiskan tahun Hijriah dimana hari raya akan bergeser dua minggu ke depan setiap tahunnya dengan beban puncak yang sangat rendah bila dibanding minggu-minggu lainnya. Hal lain yang sangat spesifik dari kurva ini adalah saat hari Natal dan Tahun Baru yang pada saat itu beban puncak juga rendah walaupun tidak serendah saat hari Lebaran seperti terlihat pada Gambar-1.4.
Gambar-1.1. Kurva Beban Puncak Mingguan dalam Setahunb. Beban Puncak Sistem Harian dalam SemingguPada Sistem Jawa Bali, periode mingguan dimulai dari hari Jumat sampai hari Kamis. Kurva beban puncak ini merupakan rangkaian dari kurva beban harian selama satu minggu yang bentuk kurvanya sangat dipengaruhi oleh jenis hari; secara garis besar dibedakan atas: hari Kerja, Sabtu, dan Minggu.
Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu KamisGambar-1.2. Kurva Beban Puncak Harian dalam Semingguc. Beban Puncak HarianKarakteristik beban puncak harian pada dasarnya tidak selalu sama untuk masing-masing hari. Berdasarkan realisasi, beban puncak harian dapat dibedakan dari sifat-sifat harinya menjadi 35 jenis beban harian yaitu:
Gambar-1.3. Tipe Beban Puncak Harian
PT. PLN (PERSERO) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHANPERENCANAAN OPERASI SISTEM
Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal 21.Hari Minggu2.Hari Senin3.Hari Selasa4.Hari Rabu5.Hari Kamis6.Hari Jumat7.Hari Sabtu8.Hari Senin Libur9.Hari Selasa Libur10.Hari Rabu Libur11.Hari Kamis Libur12.Hari Jumat Libur13.Hari Senin Kerja, Selasa Libur14.Hari Selasa Kerja, Rabu Libur15.Hari Rabu Kerja, Kamis Libur16.Hari Kamis Kerja, Jumat Libur17.Hari Selasa Kerja, Senin Libur18.Hari Rabu Kerja, Selasa Libur19.Hari Kamis Kerja, Rabu Libur20.Hari Jumat Kerja, Kamis Libur21.Hari Selasa Kerja, Senin-Rabu Libur22.Hari Rabu Kerja, Selasa-Kamis Libur23.Hari Kamis Kerja, Rabu-Jumat Libur24.Hari Jumat Kerja, Kamis-Sabtu Libur25.Hari Raya Lebaran26.Satu Hari Sebelum Hari Raya Lebaran27.Dua Hari Sebelum Hari Raya Lebaran28.Tiga Hari Sebelum Hari Raya Lebaran29.Tiga Hari Sesudah Hari Raya Lebaran30.Dua Hari Sesudah Hari Raya Lebaran31.Satu Hari Sesudah Hari Raya Lebaran32.Hari Raya Idhul Adha33.Hari Natal34.Hari Tahun Baru35.Hari 17 Agustus
Simple, Inspiring, Performing, Phenomenal 4
1.2. Pembentukan model bebana. Kurva TahunanKurva tahunan merupakan suatu kurva yang dibentuk oleh beban puncak mingguan selama satu tahun yang terdiri dari 52 beban puncak mingguan. Kurva ini dibentuk dengan mengetahui dahulu besarnya target pembelian energi dan load factor untuk menghitung prakiraan beban puncak tahunan disamping data beban puncak mingguan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pergeseran hari raya lebaran setiap tahunnya maka perlu adanya koreksi kurva beban puncak tahunan tersebut.Proses pembentukan prakiraan energi tahunan dilakukan secara bottom up, yaitu dibuat oleh PLN Distribusi yang mengacu pada target penjualan energi ke konsumennya. Target penjualan kemudian teruskan menjadi Energi Netto. Energi Netto adalah target penjualan distribusi ditambah losses distribusi, susut transmisi (losses) dan pemakaian sendiri gardu induk. Energi netto ini nantinya akan dipakai sebagai acuan dalam pembentukan beban sistem per setengah jam-an untuk periode tahunan untuk keperluan simulasi produksi dalam rangka memperoleh alokasi energi setiap pembangkit.Beban Puncak (MW) = Target pembelian energi (MWh) 8760 jam x Load FactorPembentukan koefisien beban puncak mingguan selama satu tahun dengan data operasional sbb :P11 P12 P13 .. P1r1 P152 ; d1r1P21 P22 P23 .. P2r2 P252 ; d2r2Pn1 Pn2 Pn3 .. Pnrk Pn52 ; dnrkdimana :Pn1 = beban puncak mingguan pada minggu ke-1 untuk data ke-nPnrk = beban puncak mingguan pada hari raya yang jatuh pada minggu yang ke dnrk (minggu ke-k untuk data yang ke-n)Apabila diketahui prakiraan hari raya yang akan datang terjadi pada minggu ke-q, maka data di atas dapat digeser sbb :P11 P12 P13 .. P1rq = P1r1 P152P21 P22 P23 .. P2rq = P2r2 P252Pn1 Pn2 Pnrq = Pnrk Pn51 Pn52sehingga koefisien beban puncak mingguan dapat dibentuk menjadi :t11 t12 t13 .... t152t21 t22 t23 .... t252tn1 tn2 tn3 .. tn52dimana :tn1 = Pn1 Pnmadalah koefisien beban puncak mingguan dengan Pnm merupakan beban puncak tertinggi selama setahun dari data yang ke-nDengan menjumlahkan n data setiap minggu yang sama, maka akan diperoleh koefisien rata-rata beban puncak mingguan selama 52 minggu (satu tahun), yaitu:tn1 tn2 tn3 .. tn52Apabila koefisien terrtinggi dalam 52 minggu tersebut adalah 1, maka diperoleh koefisien baru, yaitu: t1 t2 t3 ... t52Dengan mengalikan masing-masing koefisien beban puncak mingguan selama setahun dengan prakiraan beban puncak tertinggi dalam periode tahun tersebut, maka akan diperoleh prakiraan beban puncak mingguan untuk periode satu tahun (52 minggu) sbb:P1 P2 P3 ... P52b. Kurva MingguanKurva mingguan merupakan rangkaian kurva beban harian selama 7 hari dimulai dari hari Jumat sampai dengan hari Kamis sesuai dengan periode mingguan Sistem Jawa Bali.Dengan melihat kenyataan bahwa hari Minggu selalu ada dalam setiap minggunya dan karakteristik hari Minggu ternyata relatif selalu sama sehingga pembentukan kurva mingguan ini mengacu pada hari minggu.Koefisien beban puncak harian selama satu minggu merupakan perbandingan antara beban puncak yang terjadi setiap harinya selama satu minggu terhadap beban puncak hari Minggu untuk periode yang sama.Beban puncak: Ph1Ph2Ph3Ph4Ph5Ph6Ph7Koefisien: m1m2m3m4m5m6m7dimana,Ph1 = beban pada hari ke-1 (hari minggu)Phi = beban pada hari ke-i (sesuai dengan 35 sifat beban harian)mi = Phi Ph1adalah koefisien beban harian selama satu minggu dengan i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau disebut koefisien mingguan.Untuk koefisien beban setiap setengah jam dalam satu hari yang merupakan perbandingan beban setiap setengah jamnya terhadap beban puncak tertinggi pada hari itu, maka:Beban setengah jam: Pj1Pjh2Pj3Pj4 Pj48Koefisien: h1h2h3h4 .. h48dimana, Pj1= beban pada jam ke-1
hi= Pji PpAdalah koefisien beban setiap setengah jam selama satu hari dengan i = 1, 2, 3, 4, , 48. atau disebut koefisien harian.
Tabel-1.1. Koefisien Beban Puncak HarianUntuk membentuk kurva mingguan ini diperlukan prakiraan sifat-sifat hari yang akan terjadi dalam satu minggu. Dengan mengetahui beban puncak mingguan yang diperoleh dari kurva tahunan, koefisien mingguan dan koefisien harian maka diperoleh bentuk kurva mingguan yang dibentuk dari beban setiap setengah jam selama 168 jam.1.3. Proses updating dan rencana baruProses updating data merupakan cara untuk memperbaharui koefisien beban yang ada dengan melihat kondisi realisasi beban periode berjalan sehingga didapatkan data terbaru yang akan digunakan untuk memperbaharui prakiraan beban yang akan datang.a. Update koefisien dan rencana baruUpdating koefisien harian dibatasi jika terjadi penyimpangan berkisar 5%. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pencatatan data atau adanya gangguan sistem. Proses updating ini bisa dilakukan setiap hari.Updating koefisien tahunan dan rencana baru adalah proses memperbaharui prakiraan beban puncak mingguan yang belum berjalan selama periode satu tahun dengan perubahan yang mengacu pada data realisasi sebagian beban puncak mingguan dalam periode tersebut.Proses updating tersebut, misalnya :Prakiraan beban puncak awal rencana adalah (mingguan dalam setahun):P1 P2 P3 .................. P51 P52Setelah 1 minggu berjalan, prakiraan beban puncak mingguan yang baru dengan menggunakan koefisien rata-rata akan diperoleh :Pr1 (P2/ P1) x Pr1 (P3/ P1) x Pr1 . (P52/ P1) x Pr1Atau,Pr1 P2b P3b . P52bApabila realisasi telah berjalan sampai minggu ke-2, maka beban puncak mingguan yang baru adalah :Pr1 Pr2 (P3/P1) x Pr1 + (P3/P2) x Pr2 .dst 2dimana,Pr1 merupakan beban puncak realisasi minggu ke-1.Dengan demikian akan terbentuk kurva mingguan dan harian baru yang direvisi berdasarkan mingguan realisasi yang telah berjalan.
b. Updating Energi TahunanProses updating energi tahunan pada prinsipnya sama dengan cara membuat updating koefisien tahunan, misalnya prakiraan energi tahunan awal rencana adalah:E1 E2 E3 E11 E12Setelah 1 bulan berjalan, prakiraan energi tahunan yang baru dengan menggunakan koefisien rata-rata akan diperoleh :Er1 (E2/ E1) x Er1 (E3/ E1) x Er1 . (E12/ E1) x Er1Atau Er1 E2b E3b . E12bApabila realisasi telah berjalan sampai bulan ke-2, maka energi tahunan yang baru adalah :Er1 Er2 (E3/E1) x Er1 + (E3/E2) x Er2 .dst 2dimana,Er1 merupakan energi realisasi bulan ke1.Er2 merupakan energi realisasi bulan ke2Dengan demikian akan terbentuk energi bulanan dalam satu tahun yang baru dan direvisi berdasarkan realisasi yang telah berjalan.c. Updating Pembuatan Data Beban Setengah Jam-anProses updating pembuatan data beban per setengah jam-an sama dengan proses pembuatan data energi tahunan. Yang perlu diperhatikan adalah realisasi beban per setengah jam yang sudah berjalan. 1.4. Akurasi Prakiraan BebanKurva beban sistem Jawa Bali ternyata mempunyai karakteristik yang berbeda dalam setiap harinya, namun untuk hari yang sama pada periode tertentu masih mempunyai kemiripan bentuk sehingga proses prakiraan beban dengan metode koefisien sangat relevan.Ada beberapa faktor yang mengakibatkan data realisasi beban menjadi rancu untuk digunakan sebagai acuan dalam proses membuat prakiraan beban, misalnya: adanya gangguan sistem dan perubahan cuaca ekstrim. Oleh karena itu, diperlukan jam terbang khusus dari pembuat prakiraan beban agar tingkat akurasinya tinggi dengan penyimpangan tidak terlalu besar.Bila dibandingkan antara angka rencana prakiraan beban dengan realisasi di sistem Jawa Bali, deviasi berkisar antara 2% 3%.Metoda pembentukan model beban ini akan berhasil mendekati realisasi bilamana :1. Prakiraan produksi dari Distribusi dan load factor tidak terlampau banyak menyimpang.2. Tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal pemilihan atau prakiraan tipe beban puncak maupun tipe kurva beban.3. Tidak ada perubahan pola konsumsi yang tiba-tiba dari konsumen PLN.4. Tidak adanya perubahan musim. Hal ini didasarkan dari kenyataan bahwa pertambahan atau pemakaian energi listrik di musim hujan lebih rendah bila dibandingkan di musim kemarau.5. Kesalahan pencatatan atau pemasukan data akan memperbesar penyimpangan rencana terhadap realisasi bahkan mungkin akan menyebabkan metoda ini sudah tidak dapat dipakai lagi.
2. PERENCANAAN HIDRO2.1. Pola Operasi Waduk CitarumAir Sungai Citarum mempunyai peranan yang sangat strategis pada kehidupan di sepanjang aliran sungai. Agar pengelolaaan air sungai Citarum menjadi optimal, terencana, dan teratur dalam berbagai fungsinya, maka perlu ada pola pengaturan pemanfaatan aliran sungai Citarum.Sesuai karakteristik air masuk sungai Citarum, maka diharapkan Tinggi Muka Air (TMA) ketiga waduk dapat mencapai maksimal pada awal bulan Mei atau Juni. Pola Operasi Tahunan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan air di hilir Ir. H. Djuanda dengan urutan prioritas sebagai berikut :I. Kebutuhan air minum & rumah tangga (municipal water supply).II. Penggelontoran kota (flushing).III. Kebutuhan pertanian & perkebunan (irrigation requirement).IV. Kebutuhan pembangkitan tenaga listrik (power generation)V. Kebutuhan industri (water requirement far industry).2.2. Metode PerhitunganPengelolaan waduk seri Citarum memperhatikan kondisi air masuk (AM / inflow), air keluar (AK / outflow), perubahan kapasitas tampung dari masing-masing waduk (S), rugi-rugi / penguapan (E), sehingga waduk tetap dapat dioperasikan secara berkesinambungan.Metode perhitungan yang digunakan adalah prinsip keseimbangan air yang dapat diformulasikan sebagai berikut : S = AM ( AK + E ) atau AK = AM - S - E
Gambar-1.4. Prinsip keseimbangan airDalam menyusun Pola Operasi Tahunan, data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :a. Data air masuk yang digunakan merupakan hasil kajian Balai Hidrologi, Puslitbang Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum dengan menggunakan metode Analisis Frekuensi LN-3 Probability.b. Kebutuhan pengairan ditentukan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta II yang dikeluarkan setiap tahun.c. TMA minimum operasi untuk ketiga Waduk ditetapkan sebagai berikut : Saguling 625 m.dpl, Cirata 206 m.dpl dan Ir. H. Djuanda 87.5 m.dpl.d. TMA maksimum operasi untuk ketiga Waduk ditetapkan sebagai berikut : Saguling 643 m.dpl, Cirata 220 m.dpl dan Ir. H. Djuanda 107 m.dpl.e. TMA awal operasi untuk ketiga waduk ditetapkan sesuai pola hidro tahunan yang diprakirakan (normal, kering, atau basah).f. Pola keseimbangan dalam pengoperasian waduk Seri Citarum didasarkan pada prosentasi kapasitas tampung efektif dari masing-masing waduk terhadap kapasitas tampung efektif total ketiga waduk yaitu : Waduk Saguling 20,98%; Cirata 29,39%; dan Ir. H. Djuanda 49,63%.g. Simulasi debit air keluar dilakukan dengan Program (Software) yang dibuat oleh Konsultan NEDECO (Direktorat PPSDA, Ditjen Pengairan, Departemen PU). Dari hasil perhitungan diperoleh pola pengusahaan waduk Citarum seperti terlihat pada Gambar-1.5 (contoh).
Gambar-1.5. Pola operasi tahunan Cascade Waduk Citarum
3. RENCANA OPERASI SISTEMRencana Operasi adalah suatu rencana mengenai bagaimana suatu sistem tenaga listrik akan dioperasikan untuk periode waktu tertentu secara bertahap dari perencanaan tahunan (ROT), bulanan (ROB), mingguan (ROM) dan harian (ROH). Tujuan dari perencanaan operasi tersebut, meski memiliki perbedaan horizon waktu, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia (pembangkitan, penyaluran) untuk memenuhi kebutuhan beban secara efisien, dengan mempertimbangkan sekuriti dan mutu sistem tenaga listrik.Perbedaan di antara jenis perencanaan adalah pada fokus dan tingkat akurasi. Pada perencanaan alokasi pembangkit tahunan lebih fokus kepada kondisi umum pengoperasian, prakiraan alokasi energi, dan prakiraan jadwal pemeliharaan dengan tingkat akurasi masih moderat dan tidak terlalu detil, sedang pada perencanaan harian sudah fokus pada jadwal pembebanan per pembangkit per jam dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan sangat detil. Perencanaan tahunan memberi gambaran umum dan belum mengikat secara transaksional, sedang perencanaan mingguan dan harian sudah mengikat secara transaksional.Dalam setiap perencanaan operasi, terdapat dua unsur pokok dalam hal penjadwalan, yakni pekerjaan pembangkit dan pekerjaan penyaluran.a. Penjadwalan Pekerjaan PembangkitPembangkit sebagai mesin listrik yang berputar tentunya memerlukan pemeliharaan secara berkala untuk mempertahankan kinerjanya agar selalu dapat bekerja optimal sesuai dengan kapasitasnya. Pemeliharaannya ada yang memerlukan unit tidak beroperasi atau keluar dari jaringan (outage) dan ada pula yang tetap beroperasi tapi dengan pengurangan mampu pasok (derating). Jenis pekerjaannya dapat berupa inspection, maintenance, maupun perbaikan.Penjadwalan pemeliharaan terhadap sebuah pembangkit harus memperhatikan kecukupan daya sepanjang periode perencanaan sehingga sistem masih mampu melayani permintaan beban. Penjadwalan juga harus memperhitungkan probabilitas sistem tidak mampu memenuhi permintaan beban yang sifatnya di luar perencanaan, misal karena gangguan.b. Penjadwalan Pekerjaan PenyaluranPekerjaan instalasi penyaluran sistem 500 kV meliputi pemeliharaan, perbaikan, rekomisioning dan pekerjaan lain yang dianggap perlu dilakukan dalam mempertahankan keandalan instalasi penyaluran dan kelangsungan pasokan pada sistem tenaga listrik Jawa-Bali.Dalam rangkaian perencanaan pekerjaan penyaluran, terdapat mekanisme pengajuan pekerjaan, studi kontingensi, dan persetujuan dari pihak manajemen. Diharapkan keandalan sistem senantiasa terjaga di saat dilaksanakannya pekerjaan penyaluran. Selain itu, perencanaan penyaluran juga memiliki kode terkait sifat pekerjaan, yaitu:Tabel-1.2. Kode Pekerjaan PenyaluranKODEKETERANGAN (SIFAT)
01Pemadaman beban selama pekerjaan
02Pemadaman beban selama manuver
03Peralatan bebas tegangan selama pekerjaan
04Peralatan bebas tegangan selama manuver
05Peralatan bertegangan
ABKAkan diberi tahu kemudian
3.1. Rencana Operasi Sistem Jangka Panjang dan MenengahPerencanaan jangka panjang yaitu perencanaan untuk perioda jangka waktu di atas 10 tahun. Rencana operasi ini meliputi kebutuhan pembangkit baik yang sudah menyatakan siap operasi maupun yang direncanakan beroperasi berdasarkan jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTG, PLTN maupun PLTA) sesuai dengan kebutuhan Sistem. Tujuannya untuk mendapatkan biaya produksi yang paling ekonomis dan keandalan sistem yang terjamin. Setelah dilakukan simulasi produksi dapat dihitung alokasi energi per pembangkit maupun kebutuhan bahan bakarnya. Sedangkan rencana jangka menengah yaitu periode 5 tahun ke depan biasanya adalah penajaman dari rencana operasi jangka panjang. Kedua perencanaan tersebut disimulasikan dengan aplikasi jROS (joint Resource Optimization and Scheduler) tipe RO (Resource Optimization).3.2. Rencana Operasi Sistem TahunanPerencanaan operasi dengan jangka waktu 1 tahunan meliputi rencana pemeliharaan unit-unit pembangkit yang memerlukan persiapan sejak tahun sebelumnya karena pengadaan suku cadangnya memerlukan waktu lama. Bisa berupa pemeliharaan rekomendasi pabrikan, inspeksi, ataupun overhaul. Rencana operasi tahunan juga meliputi perencanaan alokasi energi yang akan diproduksi oleh setiap unit pembangkit, rencana pemeliharaan unit pembangkit, prakiraan beban tahunan, beroperasinya unit-unit pembangkit baru serta perencanaan pembangkit hidro (produksi PLTA). Rencana Operasi Tahunan merupakan bahan utama bagi penyusunan Rencana Anggaran Biaya Tahunan suatu Perusahaan Listrik (RKAP: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).Perencanaan operasi tahunan terkait penjadwalan pemeliharaan pembangkit dimulai dari rapat koordinasi pada bulan September dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan rencana operasi tahunan. Laporan tersebut harus sudah diterima oleh seluruh Pemakai Jaringan paling lambat tanggal 15 Desember dan revisi final tengah tahun paling lambat tanggal 15 Juni tahun berikutnya (yang berjalan).Rencana pekerjaan tahunan instalasi penyaluran 500 kV diajukan selambat-lambatnya minggu pertama bulan Agustus untuk bahan rapat tahunan pembahasan Jadwal Pemeliharaan Penyaluran 500 kV pada bulan Nopember sebelum tahun pelaksanaan dan agar mendapat persetujuan pihak manajemen (Perencanaan Operasi Sistem).3.3. Rencana Operasi Sistem BulananRencana Operasi Bulanan merupakan koreksi terhadap Rencana Tahunan dan sebagai proyeksi perencanaan satu bulan ke depan yang menyangkut hal-hal operasional dan manajerial dalam sistem. Di antaranya, peninjauan atas jam kerja unit-unit pembangkit terutama dalam kaitannya dengan rencana pemeliharaan. Hal ini diperlukan untuk membuat jadwal operasi unit-unit pembangkit yang bersangkutan dan alokasi produksi tiap jenis pembangkit dalam kaitannya dengan pemesanan kebutuhan bahan bakar.Rencana pembangkitan harus dapat memenuhi prakiraan kebutuhan beban bulanan sistem dengan biaya variabel yang minimal dengan tetap memperhatikan kriteria keandalan dan kualitas Sistem tenaga listrik (grid).Rencana pekerjaan tahunan instalasi penyaluran 500 kV diajukan paling lambat tanggal 2 pada bulan sebelumnya untuk mendapat persetujuan pihak manajemen (oleh Perencanaan Operasi Sistem) dan selanjutnya dilakukan rapat bulanan pembahasan Jadwal Pemeliharaan Penyaluran 500 kV yang diadakan dua bulan sekali.Pada perencanaan bulanan dan tahunan, berlaku status PO (Planned Outage) dan PD (Planned Derating) baik untuk pekerjaan pambangkitan maupun penyaluran.a. Pemeliharaan dengan keluarnya pembangkit atau penurunan daya mampu pembangkit untuk pekerjaan pemeliharaan periodik pembangkit seperti inspeksi, overhaul atau pekerjaan lainnya yang sudah dijadwalkan sebelumnya dalam rencana tahunan pemeliharaan pembangkit atau sesuai rekomendasi pabrikan.b. Pemeliharaan dengan keluarnya instalasi penyaluran atau penurunan kemampuan instalasi penyaluran untuk pemeliharaan rutin, rekomisioning, SCADATEL, pekerjaan komisioning yang terkait kontrak dan pekerjaan lainnya yang dianggap perlu yang sudah dijadwalkan sebelumnya dalam rencana tahunan.
Gambar-1.6. Alur perencanaan pembangkitan bulanan
2Pengajuan dari APP4Approval APB14 15Approval BOPSPelaksanaan OperasionalRapat Bulanan31Tanggal Studi kontingensiGambar-1.7. Alur perencanaan penyaluran bulanan1.4. Rencana Operasi Sistem MingguanDalam Rencana Operasi Mingguan (ROM) disusun langkah-langkah operasional yang akan dilakukan dengan memperhatikan rencana bulanan dan mempertimbangkan prakiraan atas hal-hal yang bersifat tidak menentu, misalnya: jumlah air masuk PLTA serta prakiraan beban jangka pendek (satu minggu). Periode rencana mingguan adalah mulai Jumat hingga Kamis minggu berikutnya.Rencana pembangkitan mingguan berisi jadwal operasi serta pembebanan unit-unit pembangkit per-setengah jam selama 1 minggu atas dasar pertimbangan ekonomis (pembebanan yang optimum) dengan memperhatikan berbagai kendala operasionil seperti beban minimum dan maksimum dari unit pembangkit serta masalah aliran daya dan tegangan dalam jaringan.Pada perencanaan mingguan, berlaku status MO (Maintenance Outage: keluarnya pembangkit atau instalasi penyaluran) dan MD (Maintenance Derating: penurunan kemampuan pembangkit atau instalasi penyaluran) untuk keperluan pengujian, pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, perbaikan atau penggantian suku cadang atau pekerjaan lainnya yang dianggap perlu dilakukan, yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya hingga jadwal PO berikutnya dan telah dijadwalkan dalam ROM berikutnya.
Kesiapan unit & jadwal pemeliharaan dari PembangkitSelasapkl. 10:00 WIBRevisi kesiapan & jadwal pemeliharaan dari PembangkitRabupkl. 15:00 WIBP3B menerbitkan Rencana Operasi MingguanKamispkl. 15:00 WIBPelaksanaan OperasionalJumatpkl. 00:00 WIB Kamispkl. 24:00 WIBP3B menerbitkan persetujuanSelasapkl. 16:00 WIB
Senin14.00Pengajuan APP Selasa14.00Approval APB & Disampaikan ke BOPSKamis10.00Studi Kontingensi & Approval BOPSPelaksanaan OperasionalJumatHari :Pukul :KamisGambar-1.8. Alur perencanaan pembangkitan mingguan
Gambar-1.9. Alur perencanaan penyaluran mingguan3.5. Rencana Operasi Sistem HarianRencana Operasi Harian merupakan koreksi dari Rencana Operasi Mingguan untuk disesuaikan dengan kondisi yang mutakhir dalam sistem tenaga listrik. Rencana Operasi Harian merupakan pedoman pelaksanaan Operasi Real Time.Rencana pembangkitan harian harus memperlihatkan pembebanan setiap unit pembangkit dalam basis waktu setengah jam. Tingkat pembangkitan harus memenuhi prakiraan kebutuhan beban harian sistem, biaya variabel minimum, serta mempertimbangkan semua kendala jaringan dan kondisi lain yang berpengaruh seperti peristiwa khusus kenegaraan atau hari libur dan sebagainya.Pada perencanaan harian, berlaku status FO (Forced Outage: keluarnya pembangkit atau instalasi penyaluran) dan FD (Forced Derating: penurunan kemampuan pembangkit atau instalasi penyaluran) akibat adanya perbaikan, kondisi emergensi, atau karena adanya gangguan yang tidak diantisipasi sebelumnya serta yang tidak digolongkan ke dalam PO ataupun MO.
Kesiapan unit & jadwal pemeliharaan dari PembangkitH-1pkl. 10:00 WIBP3B menerbitkan Rencana Operasi HarianH-1pkl. 15:00 WIBPelaksanaan OperasionalHari-Hpkl. 00:00 WIB Hari-Hpkl. 24:00 WIB
Gambar-1.10. Alur perencanaan pembangkitan harian
09.00Pengajuan APP 13.00Approval APB & Disampaikan ke BOPS15.00Studi Kontingensi & Approval BOPSPelaksanaan Operasional00:00Pukul :23:30Gambar-1.11. Alur perencanaan penyaluran harian
4. Neraca Daya dan EnergiNeraca daya adalah gambaran kondisi sistem terkait dengan besarnya beban sistem pada saat beban puncak dan besarnya pasokan daya untuk memenuhi permintaan konsumen.Memuat informasi: Outage, Derating, Probability, (Variasi Musim) Hidro, Reserve shutdown, Unit test, Mampu pasok, Beban puncak netto, Cadangan operasi.Hal yang diutamakan adalah ketersediaan pasokan daya pada tiap periode beban puncak. Jadwal pekerjaan pembangkitan dan penyaluran akan senantiasa disesuaikan dengan kondisi cadangan sistem hasil perhitungan di neraca daya.
Gambar-1.12. Alur penyusunan neraca dayaContoh neraca daya mingguan:Tabel-1.3. Neraca daya mingguan
Gambar-1.13. Grafik neraca daya bulananDalam periode tahunan, setelah Energi Bruto tahunan diketahui dan LF sudah ditetapkan besarnya, maka Beban Puncak Sistem bisa dihitung. Dari kapasitas pembangkit yang terpasang (Installed Capacity) dan Beban puncak maka bisa dihitung besar Reserved Marginnya (RM). RM = Install Capacity Beban Puncak X 100 %Beban PuncakNeraca Daya biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui keandalan sistem, dengan mempertahankan LOLP (Lost of Load Probability) 1 day/year dari hasil perhitungan WASP diperoleh RM sistem.Apabila terjadi kekurangan daya, maka perencanaan sistem dibuat dari sisi hulu ke hilir, dimulai dari kapasitas pembangkit yang terpasang, dihitung LOLP, RM dan cadangan putarnya, sehingga bisa dihitung Beban Puncak tertinggi sistem yang diijinkan.
5. Spesifikasi Bahan BakarDalam membuat proyeksi kebutuhan bahan bakar, beberapa istilah dan satuan yang perlu diketahui: SFC (Spesific Fuel Consumption) : rasio antara jumlah pemakaian bahan bakar terhadap jumlah produksi (kWh). Misalnya SFC pembangkit dengan BBM adalah 0.03 liter/kWhHeat. Heat Content : jumlah kalori yang terkandung dalam bahan bakar, misalnya nilai kalori dari batu bara adalah 5100 kCal/kg, namun hal ini tergantung dari jenis batubaranya. Nilai kalori dari HSD : 9095 kCal/liter, MFO 9598 kCal/liter dan untuk gas 252000 kCal/MMBTU. Beberapa nilai satuan bahan bakar adalah sebagai berikut : BTU (British Thermal Unit) : satuan energi panas dalam sistem British yang biasanya digunakan dalam satuan gas. BSCF (Billion Standard Cubic Feet) : satuan energi panas yang digunakan dalam satuan gas. MMSCFD (Million Meter Standard Cubic Feet per Day) : satuan energi dalam satuan gas. m3 : Meter Cubic MMBTU : Million Metric British Thermal Unit BBTUD : Billion British Thermal Unit per Day BTU/SCF : British Thermal Unit per Square Cubic Feet Kkal/m3 : Kilo Kalori per Meter Kubik MMSCFD : Million Metric Square Cubic Feet per Day Konversi satuan:1 Barel = 159 liter1 BTU = 251.995760485 Cal1 Cal = 4.1868 J1 SCF = 1000 BTU1 bcf = 1012 BTU1 J = 2.7777 x 10-7 kWh1 MSCF = 103 SCF1 MMSCF = 106 SCF1 BSCF =109 SCF1 MMSCF = 1 GBTU = 1000 MMBtu1 MMBtu = 25 Sm31 MMSCFD = 1 GBTU/D = 1000 MMBtu/D = 1000 Sm3/h1 Juta Ton LNG = 50 bcf = 50 x 107 mmbtu
DAFTAR PUSTAKA[1]PT. PLN (Persero). Protap Deklarasi Kondisi Pembangkit dan Indeks Kinerja Pembangkit. Maret 2012.[2]PT. PLN (Persero) P3B JB. Prosedur Tetap Penjadwalan Pekerjaan Instalasi Penyaluran 500 KV Sistem Jawa Bali, Mei 2014.
Nama hariKoefisien
Jumat0,9913
Sabtu0,9445
Minggu0,9009
Senin0,9978
Selasa0,9978
Rabu0,9978
Kamis1,0000
Related Documents