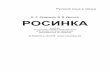SARANA RETORIKA PADA ALUR UTAMA DAN ALUR BAWAHAN DALAM NOVEL GAJAH MADA: TAKHTA DAN ANGKARA KARYA LANGIT KRESNA HARIADI DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS XII Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) Oleh: Dessy Husnul Qotimah 1110013000028 JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

SARANA RETORIKA PADA ALUR UTAMA DAN ALUR
BAWAHAN DALAM NOVEL GAJAH MADA: TAKHTA
DAN ANGKARA KARYA LANGIT KRESNA HARIADI
DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS XII
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Oleh:
Dessy Husnul Qotimah
1110013000028
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015

LEMBAR PENGESA}IAN SKRIPSI
SARANA RETORIKA PADA ALUR UTAMA DAN ALUR BAWAHAN
DALAM NOVEL GAJAH MADA: TAKHTA DAN ANGKAR,4 KARYA
LANGIT KRESNA HARIADI DAN IMPLIKASINYA DALAM
PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA KELAS XII
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Saiah Satu SyaratMencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Oleh
Dessy Husnul Qotimah
I 1 10013000028
JURUSAN PBNDIDIKAN BAIIASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKTILTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGBRI SYARIF HIDAYATULLAII
JAKARTA
z0t5
Bimbingan
ati, M.Hum.
NIP. 19771030 200801 2 009

LEMBAR PENGESAIIA}I
Skripsi berjudul "Sarana Retorika pada Alur Utama dan Alur Bawahandalam Novel Gajah Mada: Takhta danAngltaral{arya Langit Kresna Hariadidan Implikasinya dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia KelasXU,, disusun oleh DESSY HUSN{.IL QOTIMAH, NIM 1110013000028,
diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam NegeriSyarif Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan LULUS dalam ujian munaqasahpada tanggal 06 Maret 2015 di hadapan dewan penguji. Oleh karena itu, penulis
berhak memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam bidang PendidikanBahasa dan Sastra Indonesia.
JakartA06
Panitia Uj ian Munaqasah
Ketua Panitia (Ketua Jurusan/Prodi)
Dra.Ilindun. \t[. Pd.IYIP, 19701215 200912 2 00t
Sekretaris furusan
D_ona Aii Karunia Putra. M.A.N[IP. 19840409 201101 I 015
Penguji I
Prlis Nurmuiininssih. M. Hum.IYIP, 19630731 198803 2 002
Penguji 2
Dqa.. Hindun.l\{. Pd.niIP. 1970121s 2009t2 2 001
Tanggal
14n:!
Tanda
?a\h
las
2Apn\
, /p.i\ ?otl""1""'-"'

KEMENTERIAN AGAMA
@, UIN JAKARTAtffiffiYmi FlrK-'-"---** Jl. lr. H. Juanda No 95 Ciputat 15412lndonesia
FORM (FR)
No. Dokumen : FITK-FR-AKD-089
Tgl. Terbit : 1 Maret 2010
No. Revisi: 01
Hal 111
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama
Tempat/Tgl.Lahir
NIM
Jurusan / Prodi
Judul Skripsi
Dessy Husnul Qotimah
Wonogri, 19 Desember 1992
1 I 10013000028
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Sarana Retorika pada Alur 'Utama dan
Dosen Pembimbing
Alur Bawahan dalam Novel Gajah Mada:
Takhta dan Angkara Karya Langit Kresna
Hariadi dan Implikasinya dalam Pembelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas XII: 1. Rosida Erowati, M.Hum.
dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya
sendiri dan saya bertanggung jawab secara akademis atas apa yang saya tulis.
l3 Februari 2015Jakarta,
tYDesslz Husnul Qotimah
1 1 10013000028

i
ABSTRAK
Dessy Husnul Qotimah, NIM 1110013000028, “Sarana Retorika pada Alur Utama
dan Alur Bawahan dalam Novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara Karya Langit
Kresna Hariadi dan Implikasinya dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia Kelas XII”.
Penelitian ini dilakukan dengan dasar bahwa retorika tidak hanya diterapkan
pada keterampilan berbicara saja, tetapi juga pada keterampilan menulis. Sarana-
sarana yang digunakan dalam retorika tekstual adalah penyiasatan struktur, dan
pemajasan. Keduanya terdapat pada unsur intrinsik gaya bahasa dalam sebuah
prosa. Berbicara mengenai prosa, ada beberapa novel yang memiliki lebih dari
satu alur. Tentunya, tiap alur tersebut memiliki cara penyampaiannya tersendiri.
Perbedaan gaya penceritaan itu tergantung dari seberapa pentingkah alur tersebut
untuk disampaikan. Perbedaan gaya penceritaan tersebut bisa dilihat salah satunya
dari retorika tekstual yang digunakan oleh pengarang dalam menceritakan alur-
alur tersebut karena setiap sarana retorika tekstual memiliki efek tersendiri dalam
membangun suasana.
Penelitian yang menggunakan teori gaya bahasa milik Gorys Keraf ini
menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan penyajian deskriptif. Dalam
penelitian ini, peneliti menentukan alur apa saja yang ada dalam novel Gajah
Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi. Setelah itu, peneliti
mendata sarana retorika apa saja yang digunakan pengarang dalam menyampaikan
alur-alur tersebut. Dari pendataan tersebut, dapat diketahui berapa banyak sarana
retorika beserta efeknya yang digunakan pada tiap alur.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pada tahapan alur
manakah yang paling sering menggunakan sarana retorika dan apa efeknya. Dari
hasil penelitian ini ditemukan bahwa tahapan alur yang paling banyak
menggunakan sarana retorika adalah tahapan klimaks pada semua alur dalam
novel ini, kecuali pada alur bawahan pertama yang justru terletak pada tahap
pengenalan.
Penggunaan sarana retorika dalam novel ini menimbulkan beberapa efek yang
dirasakan oleh pembaca. Efek-efek tersebut adalah 53 kali penekanan emosi, 33
kali penguatan imaji, 79 kali ketegangan, 45 kali penegasan makna, 85 kali
pemberian informasi, 3 kali penciptaan nama baik tokoh, 7 kali pemulihan
kebosanan, 19 kali pengenduran urat saraf, dan 9 kali penggiringan opini
pembaca.
Kata kunci: Retorika tekstual, Majas, Penyiasatan Struktur, Efek, Alur.

ii
ABSTRACT
Dessy Husnul Qotimah, NIM 1110013000028, “The Means of Textual Rethoric
of Main Plot and Subordinate Plot in The Novel Gajah Mada: Takhta dan
Angkara Written by Langit Kresna Hariadi and The Implication Towards
Indonesian Language and Literature Learning in Students of 12th
Grade.”
This study was carried out to be based on the rhetoric that is not only
applied in speaking skill but also in writing. The means used in textual rhetoric
are figures of thought and figures of speech. Both are on the intrinsic elements of
language style in a prose. Talking about prose, there are some novels that have
more than one plot. Of course, each plot has its own way of delivery. Different
style of narrating depends on how important the plot is to be told. The different
style of narrating can be seen from textual rhetoric used by the author in telling
the plots because each mean of textual rhetoric has its own effect in creating the
atmosphere.
This study that used Gorys Keraf’s theory of language style used qualitative
research methodology with descriptive presentation. In this study, the researcher
determined what plots were there in the novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara
written by Langit Kresna Hariadi. Furthermore, the researcher collected the data
of the means of rhetoric used by the author in conveying the plots. From those
data, it could be seen how much means of rhetoric and their effects were used in
each plot.
The purpose of this study was to determine at what stage of plot was means
of rhetoric frequently used and what effects it has. The result of this study showed
that stage of plot that frequently used means of rhetoric was the climax stage on
all plots of this novel, except the first subordinate plot on the introduction stage.
The use of means of rhetoric in this novel caused some effects on readers.
Those effects are 53 times of the suppression of emotion, 33 times of the
strengthening of images, 79 times of tension, 45 times of the affirmation of
meaning, 85 times of the provision of information, 3 times of the creation of good
character’s name, 7 times of boredom recovery, 19 times of the relaxation of
nerves, and 9 times of convey of the reader’s opinion
Key words: Textual Rhetoric, Figures of Speech, Figures of Thought, Effect, Plot.

iii
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah wa syukurillah atas kemudahan dan nikmat Allah SWT yang
sangat melimpah sehingga penelitian yang menguras waktu, tenaga, pikiran,
emosi, dan tentu saja dana ini bisa selesai pada waktu yang tepat.
Seiring dengan selesainya penelitian ini, penulis ingin mengucapkan
terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dra. Hindun, M.Pd., selaku ketua jurusan PBSI yang telah memudahkan
segala urusan penulis selama menjadi mahasiswa tingkat akhir.
3. Dra. Mahmudah Fitriyah ZA, M.Pd., karena telah membuat perjalanan
skripsi ini mulus tanpa hambatan yang berarti.
4. Rosida Erowati, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang tak pernah
sungkan mengeksplor pengetahuan demi mahasiswa bimbingannya yang
satu ini.
5. Kedua orangtua, Bapak Suwarno dan Ibu Suti Astuti, yang tak pernah
kehabisan kasih, sayang, dan cinta untuk selalu mendoakan anaknya agar
selalu seperti nama yang mereka sematkan, husnul khotimah, dalam setiap
langkah yang diambil.
6. Seluruh jajaran dosen PBSI yang telah menambah wawasan penulis
selama menjadi mahasiswa Strata 1.
7. Sahabat DDD−Nur Amalina, Sri Wahyuningsih, Amalia Utami Syahadah,
Ratna Agustina Pangestuti, Liza Amalia, Ayu Rizki Pramulyaningrum,
Nur Rafiqah, dan Astuti Nurasani−yang mampu membalikkan tiap duka
menjadi canda.
8. DM, seseorang yang telah berhasil membuat peneliti sedikit berguna di
akhir masa studi strata satu ini. DM, kita tak pernah sanggup mendikte
waktu, tapi terima kasih kuhambakan atas kesediaanmu kujelmakan dalam
kekataan, angan, dan kenangan.

iv
9. Rekan sidang paling greget, Ade Fauziah, Fitri Khoiriani, dan Rifki Alim
Annur.
10. Sahabat PBSI A 2010 yang selalu membuat warna dalam tiap patahan
jalan. Sehitam apapun, itu tetap warna.
11. Sahabat PBSI B dan PBSI C 2010. Bangga rasanya ada di tengah kalian
sebagai saudara.
12. Keluarga besar HMJ PBSI, terutama divisi Bahasa dan Sastra Indonesia
periode 2013/2014, yang telah memberikan pengalaman berharga tentang
cita, cerita, dan tentu saja cinta.
13. Nayaga-nayaga Degung Sunda POSTAR yang sudah mengajariku menjadi
setengah Sunda.
14. Mbak Ziah yang selalu menyokong riset sejarah, my partner Kunia Dewi
Nurfadillah, Holida Hoirunnisa, Hanan, Anis, Uchi, Maya, Syifa, Ida, dan
Iroh yang saling setia mendukung untuk terus maju. Tak peduli
semenyakitkan apa jalan yang wajib kita taklukan nanti, kita akan sukses.
Catat itu!!!
15. Bang Dimas, Ka Unet, Dimas Albiyan, Miss Maret, Miss Nadia, Ozhi, dan
Hafiz yang selalu sabar dengan penodongan-penodongan pertanyaan
seputar agama Hindu, sastra, penerjemahan, hingga pengeditan skripsi ini
yang kerap kali diminta secara dadakan dan meminta hasilnya selekas
mungkin.
16. Kepala Sekolah SMK Farmasi Minasa Mulia dan Akademik Bimbel Gama
Jogja yang tak pernah kehabisan pemakluman untuk mengizinkan tenaga
pengajarnya ini “rehat” dari tugasnya sejenak.
17. Murid-murid SMK Farmasi Minasa Mulia dan Bimbel Gama Jogja Depok
karena selalu rajin bertanya kapan Ibu Gurunya ini wisuda. Pertanyaan
kalian doa bagi saya.
18. Pihak Pengelola Perpustakaan Riset UI yang telah menyediakan tempat
yang sangat kondusif bagi penulis selama pengerjaan skripsi ini.
19. Beberapa pihak informal, namun memegang salah satu posisi kunci dari
skripsi ini, pekerja fotokopian. Di mana pun kalian membuka gerai

v
fotokopian, kalianlah pahlawan super berkepala dingin menghadapi
puluhan ilmu di depan kalian.
Semoga Allah berkenan melimpahkan balasan yang tiada terkira bagi
semua pihak yang telah memudahkan penulis menyelesaikan tugasnya ini.
Aamiin.
Penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih banyak
terdapat kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati,
penulis menanti sumbangan kritik dan saran yang membangun guna bahan
pelajaran penulis ke depannya.
Khatam kalam, semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan
dan tentu saja pembaca pada umumnya.
Depok, Februari 2015
Dessy Husnul Qotimah

vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI
ABSTRAK ..................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................. vi
BAB I : PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Identifikasi Masalah .......................................................................... 5
C. Pembatasan Masalah ......................................................................... 6
D. Perumusan Masalah .......................................................................... 6
E. Tujuan Penelitian .............................................................................. 7
F. Manfaat Penelitian ............................................................................ 7
G. Metodologi Penelitian ....................................................................... 8
BAB II : KAJIAN TEORI ....................................................................... 13
A. Retorika ............................................................................................... 13
1. Sarana-Sarana Retorika .............................................................. 17
a. Gaya Bahasa ........................................................................... 17
b. Penyiasatan Struktur Kalimat ................................................. 23
B. Novel ................................................................................................... 30
1. Hakikat Novel ............................................................................ 30
2. Sastra Sejarah ............................................. ............................... 32
3. Unsur Intrinsik ............................................................. ............. 35
C. Implikasi Pembelajaran Sastra ........................................................... 39
D. Penelitian Relevan ............................................................................... 42
BAB III : PEMBAHASAN .......................................................................... 44
A. Biografi Pengarang .............................................................................. 44

vii
B. Analisis Unsur Intrinsik .............................................. ........................ 49
1. Tema………………………………………………………………. 49
2. Sudut Pandang …………………………………………………….. 50
3. Latar ……………………………………………………………… 52
4. Tokoh …………………………………………………………….. 57
5. Gaya Bahasa …………………………………………………….. .. 74
6. Alur ………………………………………………………………. 76
7. Amanat …………………………………………………………… 88
C. Analisis Penggunaan Sarana Retorika Dalam Alur ............................ 90
1. Analisis Penggunaan Sastra Retorika Alur Utama .................... 90
2. Analisis Penggunaan Sastra Retorika Tekstual Alur
Tambahan Pertama ......................................................................... 114
3. Analisis Penggunaan Sarana Retorika pada Alur
Tambahan kedua .............................................................................. 137
4. Analisis Penggunaan Sarana Retorika pada Alur
Tambahan Ketiga ............................................................................ 157
D. Ethos, Pathos, Logos ………………………………………... .......... 180
E. Implikasi Pembelajaran……………………………………… .......... 190
BAB IV : PENUTUP ..................................................................................... 192
A. Simpulan ............................................................................................. 192
B. Saran ………………………………………………………………. 197
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………….. 199
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENELITI

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan utama dari sebuah komunikasi, baik verbal maupun non-
verbal, adalah tersampainya informasi dari seorang komunikator kepada seorang
atau lebih komunikan dengan baik tanpa ada satu pun yang tercecer dari pesan
tersebut. Namun, pada kenyataannya, untuk menyampaikan isi pesan dengan
utuh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tanggung jawab seorang
komunikator tidak hanya sebatas menyampaikan pesan yang dibebankan di
pundaknya saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk mempertahankan perhatian
si komunikan agar pesan yang hendak disampaikan terserap secara utuh oleh
komunikan. Di sinilah seorang komunikator unjuk kebolehan dalam kemampuan
olahbahasanya. Sebenarnya, unjuk kebolehan olahbahasa ini adalah sebuah
pertaruhan yang cukup prestisius bagi seorang komunikator. Jika ia berhasil
mengolah bahasanya sedemikian rupa, maka mendapatkan perhatian penuh para
komunikan adalah sebuah jaminan mutlak. Hal sebaliknya akan terjadi bila
komunikatornya adalah seseorang yang miskin dalam hal olahbahasa.
Kemampuan olahbahasa ini telah ada sejak zaman Yunani kuno yang lebih
dikenal dengan retorika. Keterampilan berbicara merupakan titik tolak retorika.
Secara umum, retorika dapat dikatakan sebagai seni berbicara untuk menarik
minat pendengar dengan menggunakan bahasa yang indah, menggugah, baik, dan
terstruktur. Dalam retorika, efek estetiklah yang diutamakan dalam proses
penyampaian pesan. Pengolahan bahasa yang tidak mudah ini dapat
menggunakan teknik pemilihan diksi, penguasaan kaidah-kaidah ketatabahasaan,
dan kaya akan gaya bahasa. Tak ayal seorang pembicara yang kreatif dan penuh
terisi dengan ide-ide cemerlang tentang bagaimana caranya membidani lahirnya

2
sebuah tata bahasa yang komunikatif dan menghentak para pendengarnya akan
mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pendengarnya.
Selama ini retorika dalam bahasa tulisan belum banyak diakui oleh
mayoritas pengguna bahasa. Kebanyakan orang menganggap bahwa retorika
hanya mutlak milik bahasa lisan saja. Namun kenyataannya tidak. Pada awalnya
retorika sampai beberapa abad lamanya berada dalam ranah bahasa lisan. Baru
pada saat retorika mengalami zaman kemunduran, lahirlah sebuah konsep
retorika modern yang mengubah haluan titik tekannya pada bahasa tulisan tanpa
harus membelakangi bahasa lisan.
Ada banyak hal yang bisa membuktikan bahwa keterampilan menulis,
retorika juga digunakan. Semua penikmat sastra−khususnya prosa−pastinya
pernah terperangah tatkala membaca sebuah prosa dan mengalami perasaan yang
begitu menegangkan saat membaca puncak masalah dari cerita tersebut dan
hendak segera menyelesaikan bacaannya karena ingin mengetahui akhir dari
cerita yang tengah dibacanya. Namun, tak jarang juga seorang pembaca begitu
membaca satu atau dua halaman sudah bosan dan tidak berminat lagi
menghabiskan bacaan tersebut. Pembaca, pengarang, hingga ide cerita bisa
menjad kambing hitam kalau hal tersebut terjadi.
Betapapun briliannya sebuah ide yang digarap oleh pengarang, jika
eksekusinya tidak menghentak pembacanya, tetap saja, kisah itu seperti kisah-
kisah yang dinafasi oleh ide yang biasa-biasa saja. Ada banyak cara untuk
menghadirkan eksekusi tersebut. Cara-cara tersebut sangat berguna membantu
pembaca mencapai sebuah perasaan katarsis.
Eksekusi yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara pengarang
mengalihtransformasikan ide yang sederhana ke dalam sebuah tulisan dan
mampu merebut hati pembaca dengan tulisan tersebut dan bagaimana cara
pengarang membuat pembaca beranggapan bahwa apa yang ditulisnya adalah
sebuah kejadian nyata. Pada akhirnya semua usaha ini berujung pada bagaimana
cara pengarang membahasakan ide-ide sederhana yang bercokol di benaknya

3
menjadi sebuah kisah luar biasa untuk dibaca. Tidak cukup hanya nyaman dibaca
saja, tetapi juga membawa pembaca ke dunia yang ia ciptakan dan secara tidak
langsung melibatkannya dalam kisahan tersebut.
Pengeksplorasian penggunaan bahasa semaksimal mungkin dapat
digunakan untuk mencapai eksekusi tersebut. Pengarang dituntut untuk
menggunakan pengolahan bahasa yang sama sekali baru dalam penulisan. Lagi-
lagi tidak hanya berhenti pada tatanan sintaksis dan morfologi saja, tetapi juga
memainkan peran semantik dan pragmatik dalam kalimat-kalimat yang menjadi
pembawa ceritanya. Ditambah dengan pemilihan diksi dan pemainan gaya
bahasa, niscaya, ide yang sederhana dapat disulap menjadi sebuah kisahan yang
luar biasa untuk dibaca.
Biasanya, dalam sebuah cerita yang disuguhkan dalam sebuah novel yang
memiliki jumlah halaman yang cukup tebal, pengarang tidak hanya
menyuguhkan pembaca dengan satu alur saja walaupun tidak semua novel
dengan volume halaman tebal akan seperti itu. Di dalam novel yang berhalaman
tebal itu akan memuat beberapa alur bawahan, di samping alur utama. Alur
utama, alur yang menjadi tema utama dalam novel itu, akan berjalan seiring
dengan alur-alur lainnya yang biasanya mengisahkan kehidupan atau pergolakan
batin tokoh lain yang bukan tokoh utama dalam novel tersebut.
Kehadiran alur bawahan bisa menunjang jalan cerita di alur utama, tapi
adakalanya kehadiran alur bawahan itu sama sekali tidak mempengaruhi jalan
cerita alur utama sama sekali. Jadi alur bawahan yang sifatnya seperti itu bisa
saja dihilangkan. Hadirnya alur bawahan, baik yang mendukung atau tidak jalan
cerita tersebut, dimanfaatkan oleh pengarang agar pembaca memiliki variasi
cerita agar tidak jenuh dengan alur utama. Alur-alur bawahan inilah juga yang
akan membantu pembaca memahami karakter atau situasi macam apa yang
tergambar dari novel ini secara keseluruhan.
Di sinilah peran retorika bermain. Terlepas dari sifat kehadiran alur
bawahan yang bisa mendukung atau tidak jalannya sebuah cerita utama di novel

4
tersebut, mau tidak mau, harus diakui bahwa yang dapat mengaduk emosi
pembaca tidak hanya ide dan jalan cerita saja, tetapi juga bahasa yang digunakan
untuk menggambarkan peristiwa tersebut. Ide cerita yang sederhana tentunya
akan terlihat cemerlang dituangkan penggunaan bahasa yang memadai. Maksud
dari ‘memadai’ dalam hal ini adalah bahasa yang digunakan oleh pengarang
sudah dapat membawa pembaca ke dalam jalan cerita tersebut dan seolah-seolah
pembaca ada di dalam kisah tersebut.
Dalam sebuah kisahan, tentu ada bagian yang dipentingkan oleh
pengarang. Bagian yang dipentingkan tersebut tentunya dibedakan dari bagian
lainnya agar pembaca mudah mengenali bagian itu. Hal-hal fundamental ini yang
mengilhami peneliti untuk menganalisis keberadaan sekaligus kadar pemakaian
sebuah retorika tekstual yang ada dalam tiap klimaks di alur-alur yang digunakan
pengarang.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan novel Gajah Mada: Takhta dan
Angkara karya Langit Kresna Hariadi yang mengambil latar sejarah sebagai latar
waktu, tempat, alur, dan tokohnya. Novel sejarah menjadi alternatif lain dalam
memahami, atau sedikitnya untuk mengetahui sejarah, walaupun memang tidak
bisa dijadikan acuan dalam pembelajaran sejarah. Dalam novel ini,
pengarangnya, Langit Kresna Hariadi, berhasil menguasai kata-kata yang
memang digunakannya untuk memukau dan menjaga pembaca agar terus berada
di alur sejarah yang ia suguhkan. Di sinilah letak retorika modern bermain. Hal
ini memang diperlukan mengingat novel yang berlatarbelakangkan sejarah
mempunyai beban tersendiri yang tentunya lebih berat daripada novel fiksi.
Pengarang novel sejarah harus menjaga agar alur yang dikembangkannya tidak
melenceng jauh dari fakta sejarah. Juga, pengarang bertanggung jawab pada
bagaimana caranya pembaca bisa memasuki sisi sejarah yang utama dalam novel
itu.
Lebih dari itu, pengarang novel sejarah harus membuat pembacanya tidak
seperti didongengi tentang sejarah, seperti buku-buku sejarah yang melulu

5
berkutat dengan tanggal, tempat, dan tahun. Pengarang novel sejarah haruslah
mampu menjadikan pembacanya salah satu dari tokoh tersebut atau minimal
pembaca merasakan bahwa ia sedang berada di tahun bersejarah itu dan ikut
menyaksikan apa yang terjadi di tempat tersebut. Dengan bantuan sarana retorika
inilah, pembaca akan merasakan efek tersebut.
Dengan berbagai pertimbangan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis
memutuskan untuk menggunakan novel sejarah dalam analisis ini. Sebenarnya
novel fiksi bisa diangkat untuk dianalisis. Namun, novel sejarahlah yang paling
pas untuk mengetahui apakah retorika dalam bahasa tulisan sudah diterapkan
atau bahkan apakah retorika ini dapat mempengaruhi bahasa sejarah yang
terkesan monoton menjadi bahasa yang sangat nyaman untuk dibaca. Jika novel
fiksi terlebih novel teenlit sepenuhnya dapat mengandalkan imajinasi
pengarangnya yang akhirnya bebas menggunakan diksi apa saja dan gaya bahasa
apa saja serta tema-tema yang memang sudah mendarah daging pada remaja saat
ini, seperti percintaan dan persahabatan. Lain halnya dengan novel sejarah yang
tidak bisa menggunakan sembarang gaya bahasa karena salah menggambarkan
suasana dengan gaya bahasa, maka tafsiran pembaca akan tidak sesuai dengan
fakta sejarahnya. Selain itu, dengan mengangkat novel sejarah sebagai objek
penelitian ini, maka akan dengan mudah penulis berupaya membuktikan bahwa
retorika dalam bahasa tulisan perlu dikaji, khususnya dalam novel Gajah Mada:
Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi.
B. Identifikasi Masalah
1. Pengetahuan bahwa retorika hanya ada di bahasa lisan saja.
2. Kurangnya pengetahuan bahwa retorika juga hadir dalam bahasa tulisan.
3. Penggunaan bahasa sebagai salah satu sarana untuk mengantarkan pembaca
ke jalan cerita.
4. Anggapan novel sejarah yang sama membosankannya dengan buku
pelajaran sejarah.

6
5. Hadirnya lebih dari satu alur dalam sebuah novel menimbulkan masalah
penyajian alur.
6. Kurangnya perhatian kritikus pada pilihan-pilihan retorika.
C. Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat di atas, maka peneliti
menitikberatkan penelitian ini pada penggunaan sarana retorika tekstual pada alur
utama dan alur bawahan novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara. Novel ini
memiliki satu alur utama dan tiga alur bawahan. Penggunaan sarana retorika
yang digunakan untuk menganalisis alur-alur tersebut juga dibatasi hanya pada
penggunaan gaya bahasa dan penyiasatan struktur kalimat. Pembatasan tersebut
dikarenakan kedua subbahasan itu lebih banyak berperan untuk menyajikan
cerita daripada kedua sarana retorika lainnya, yaitu diksi dan pencitraan. Subjek
yang digunakan untuk penelitian ini adalah novel Gajah Mada: Takhta dan
Angkara karya Langit Kresna Hariadi yang terbit pada tahun 2012.
D. Perumusan Masalah
1. Pada tahap alur manakah yang paling sering menggunakan sarana retorika di
alur utama dan tiap alur bawahan?
2. Bagaimana efek yang dihasilkan dari penggunaan sarana retorika tersebut?
3. Bagaimana implikasi pembahasan sarana retorika tektual pada tiap alur
dalam novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi
pada pembelajaran sastra di SMA?

7
E. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui unsur alur mana yang paling sering menggunakan sarana
retorika tekstual di semua alur yang ada di novel Gajah Mada: Takhta dan
Angkara karya Langit Kresna Hariadi.
2. Untuk mengetahui efek yang dihasilkan dari penggunaan sarana retorika
dalam novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna
Hariadi.
3. Untuk mengetahui implikasi penelitian ini pada pembelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia di kelas XII SMA.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
a. Mahasiswa: Mengembangkan wawasan mahasiswa bahwa retorika tidak
hanya muncul dalam bahasa lisan saja, tetapi juga dalam bahasa tulisan.
Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat menginspirasi
mahasiswa untuk membuat karya sastra dengan menggunakan retorika
yang baik.
b. Guru: Guru mendapatkan ilmu baru tentang penggunaan retorika dalam
penulisan prosa dan dapat mengenalkannya pada siswa-siswanya.
2. Manfaat Praktis
a. Guru: Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi
guru-guru mata pelajaranBahasa Indonesia sebagai bahanajar dalam
pembahasan unsur intrinsik dalam prosa.
b. Siswa: Siswa dapat mempraktikkannya ke dalam tugas-tugas harian
ataupun ujian praktik mata pelajaran Bahasa Indonesia.
c. Para penggiat sastra: Peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat
bagi para penggiat sastra, khususnya bagi para pemula (pemula dalam
hal menulis karya sastra dalam bentuk prosa). Retorika dalam bahasa

8
tulisan ini bisa menjadi teknik dalam mengembangkan ide-ide yang
tersemat dalam pikiran para penulis.
G. Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu
sebuah metode penelitian yang menitikberatkan pada data deskriptif dalam
bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.1 Metode ini
yang cocok untuk melakukan penelitian ini karena penulis akan melakukan
pengkajian terhadap kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyajikan alur
utama dan alur-alur bawahan yang ada dalam novel Gajah Mada: Takhta dan
Angkara karya Langit Kresna Hariadi. Penggunaan metodologi penelitian
kualitatif memungkinkan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menganalisa
teks.2
Berdasarkan metodologi penelitian ini, peneliti berupaya menjawab
pertanyaan rumusan masalah penelitian dengan beberapa cara. Pertama, peneliti
membaca novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi
untuk menemukan alur utama dan alur bawahan. Kedua, setelah tahap membaca,
peneliti mendata sarana retorika apa saja yang digunakan pengarang untuk
mengisahkan cerita tersebut pada semua alur. Ketiga, peneliti menganalisis saana
retorika yang terdapat dalam semua alur yang digunakan. Terakhir, peneliti
menghitung penggunaan sarana retorika yang digunakan dalam setiap alur dan
menarik kesimpulan.
1S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 36.
2Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2011). h. 30.

9
1. Fokus Penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah novel Gajah Mada: Takhta dan
Angkara karya Langit Kresna Hariadi cetakan pertama yang terbit pada
tahun 2012 sebanyak 508 halaman. Objek penelitian ini adalah alur utama
dan ketiga alur bawahan yang ada dalam novel tersebut.
Alasan digunakannnya novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara karya
Langit Kresna Hariadi ini adalah karena ini adlaah judul pertama yang
dibaca peneliti pada seri Gajah Mada. Alasan lain, adanya lebih dari satu
alur. Dengan hadirnya banyak alur dalam novel ini akan memudahkan
peneliti membuktikan bahwa penggunaan sarana retorika sangat berpengaruh
pada gaya penceritaan tiap alurnya, meskipun berada dalam satu novel.
Alasan lain adalah banyaknya amanat yang dapat diambil dari tiap alur
sehingga nilai lebih dari novel ini tidak hanya karena mengangkat kisah
sejarah, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan saat ini.
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah sebagai
berikut:
a. Peneliti membaca dengan cermat keseluruhan isi novel tersebut untuk
menentukan unsur intrinsiknya. Lewat unsur alurlah, penulis dapat
menemukan alur utama dan alur bawahan yang dihadirkan oleh
pengarang.
b. Peneliti mengklasifikasikan adegan apa masuk ke alur mana.
c. Peneliti membuat kartu data untuk mengklasifikasikan kalimat-kalimat
dari tiap alur yang terindikasi disajikan dengan sarana retorika.
d. Memasukkan data yang telah diperoleh tadi ke dalam kolom-kolom
unsur sarana retorika, yakni pegaya bahasaan dan penyiasatan struktur
kalimat.

10
3. Teknik Analisis Data
a. Peneliti menganalisis unsur intrinsik novel Gajah Mada: Takhta dan
Angkara karya Langit Kresna Hariadi. Analisis ini sangat diperlukan
untuk penentuan alur utama dan alur bawahan dalam novel ini.
b. Setelah menganalisis alur, peneliti menemukan satu alur utama dan tiga
alur tambahan. Alur-alur tersebut adalah sebagai berikut:
1. Alur Utama : Kisah usaha perebutan kekuasaan Majapahit
oleh Rangsang Kumuda
2. Alur Bawahan 1 : Kisah cinta segitiga antara Raden Kudamerta
dengan kedua istrinya
3. Alur Bawahan 2 : Kisah perseteruan antara mantan Bhayangkara
Pradhabasu denganBhayangkara Gagak
Bongol
4. Alur Bawahan 3 : Kisah prajurit Ra Kembar yang sombong.
c. Dari keempat alur yang telah ditemukan, peneliti menentukan wacana
mana yang menceritakan alur-alur tersebut.
d. Peneliti mendata kalimat yang digunakan untuk menceritakan alur-alur
tersebut dengan menggunakan sarana retorika.
e. Kalimat-kalimat yang telah didata itu kemudian dimasukkan ke dalam
kolom gaya bahasa dan penyiasatan struktur.
f. Peneliti menganalisis kalimat-kalimat dalam kolom data tersebut
dengan teori gaya bahasa dan penyiasatan struktur.
g. Setelah menganalisis kalimat-kalimat tersebut dengan teori sarana
retorika tekstual, peneliti menganalisis efek apa yang dihasilkan oleh
penggunaan sarana retorika yang digunakan dalam kalimat tersebut.
h. Setelah selesai mendata dan menganalisis penggunaan sarana retorika
dan efek yang dihasilkannya pada satu alur, peneliti mendata berapa kali

11
sarana retorika tersebut digunakan dan pada unsur alur manakah yang
paling sering menggunakan sarana retorika.
i. Setelah itu, peneliti membandingkan perolehan data penggunaan sarana
retorika yang terdapat dalam alur utama dengan ketiga alur bawahan.
j. Mengimplikasikan penelitian ini pada pembelajaran sastra di kelas XII
SMA semester ganjil dengan cara mencocokkan materi pelajaran sastra
di sekolah dengan teori yang digunakan dalam analisis ini.
4. Triangulasi Data
Secara garis besar, triangulasi data merupakan cara bagaimana seorang
peneliti mengecek ulang kebenaran data yang telah disajikan dalam
penelitian yang dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah
keabsahan yang dapat dipertangggungjawabkan keilmiahannya. Triangulasi
data dapat digunakan, terutama pada penelitian yang menggunakan
metodologi kualitatif agar terhindar dari hal-hal yang bersifat subjektif.
Ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan pengecekan
ulang data yang telah digunakan. Salah satu cara tersebut adalah dengan
membandingkan data yang telah ditemukan dengan teori yang digunakan
dalam kajian teori pada penelitian tersebut. Teori tersebut nantinya yang
akan dipakai untuk menganalisis hasil temuan tersebut.
Seperti yang telah dijelaskan pada teknik pengumpulan data, awalnya
peneliti mendata kalimat apa saja yang disinyalir mengandung gaya bahasa
dan atau struktur kalimat. Sebelum langsung menentukan kalimat yang
terindikasi mengandung gaya bahasa atau struktur kalimat, peneliti telah
membaca teori tentang gaya bahasa dan struktur kalimat. Untuk
memasukkannya ke dalam tabel gaya bahasa atau struktur kalimat, peneliti

12
melakukan sebuah pengecekan ulang dengan teori gaya bahasa atau struktur
kalimat yang digunakan.
Cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengecekkan
tersebut adalah dengan menyamakan sebuah kalimat yang diduga
mengandung gaya bahasa atau struktur kalimat dengan pengertian dan
contoh kedua materi tersebut yang ada di dalam buku teori. Dari cara
pengecekkan ulang seperti ini, hampir seluruh kalimat yang awalnya diduga
oleh peneliti mengandung gaya bahasa dan atau struktur kalimat benar
adanya. Hanya ada beberapa kalimat yang sebenarnya mengandung sebuah
gaya bahasa, namun dalam buku teori yang digunakan gaya bahasa tersebut
tidak ada. Sebagai jalan keluar dari masalah ini, peneliti memutuskan untuk
tidak memasukkan kalimat tersebut ke dalam tabel gaya bahasa.
Peneliti juga melakukan penghitungan ulang penggunaan sarana
retorika pada tiap tahapan alurnya, baik pada alur utama maupun alur
bawahan. Hal ini sangat perlu dilakukan agar rumusan masalah yang
pertama bisa dijawab dengan benar.

13
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Retorika
Dalam berbahasa, baik dalam bentuk berbicara maupun menulis,
komunikator dituntut mampu menyampaikan pesan yang dimilikinya dengan
utuh kepada komunikan. Sebuah pesan akan diterima dan dipahami dengan baik
oleh komunikan bila komunikator mampu menyampaikan pesan tersebut dengan
bahasa yang efektif. Tidak hanya itu, komunikator juga harus tahu betul
bagaimana menyusun kalimat dengan baik dan menarik minat agar lawan
bicaranya merasa yakin dengan apa yang dibicarakan. Strategi yang digunakan
komunikator itulah yang diharapkan akan mampu menarik minat komunikan
tanpa mengurangi pesan yang dimaksud. Hal-hal inilah yang diperhatikan oleh
retorika.
Menurut KBBI edisi keempat, retorika adalah “1. keterampilan berbahasa
secara efektif: 2. studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam karang
mengarang: 3. seni berpidato yang muluk-muluk dan bombastis”.1 Dari
pengertian retorika tersebut, sedikit banyak dapat diketahui bahwa retorika
berada dalam ranah kemampuan berbicara, maka tidak berlebihan jika peneliti
menyebut bahwa titik tolak dari retorika adalah berbicara. Sumber lain juga
mengatakan bahwa retorika adalah “kesenian untuk berbicara baik (Kunzt, gut zu
redden atau Arts bene dicendi), yang dicapai berdasarkan bakat alam (talenta)
dan keterampilan teknis (ars, techne)”.2 Selain itu, dalam referensi lain retorika
juga diartikan sebagai “seni dan ilmu pemakaian bahasa untuk meyakinkan
1DEPDIKNAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), h. 1171. 2Dori Wuwur Hendrikus, Retorika, (Yogyakarta: Kanisisus, 1991), h. 14.

14
khalayak atas kebenaran gagasan yang dikemukakan”.3 Edward P.J Corbett
mengartikan retorika seperti yang ia tulis dalam bukunya, “What is rhetoric?
One definition is that rhetoric is the art of effective communication.”4 Retorika
adalah seni komuniksi yang efektif. Dalam bahasa Arab, “ilmu yang mempelajari
tentang penggunaan bahasa yang indah, estetis, memberikan makna yang sesuai
dengan keadaan, dan menghasilkan sebuah efek mendalam bagi pendengar atau
pembacanya disebut dengan ilmu balaghah”.5
Dari berbagai pengertian retorika yang dipaparkan tersebut, agaknya
retorika memang berawal dari keterampilan berbicara. Namun, zaman renaisans
turut menyumbang perkembangan retorika yang semula berada dalam ranah
berbicara menjadi turut digunakan dalam keterampilan tulis-menulis. Hal ini
diawali ketika ditemukannya mesin pencetak. Sejalan dengan hal ini, Gorys
mengatakan bahwa retorika adalah “suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni,
baik lisan maupun tertulis, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang
tersusun baik”.6
Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengambil
kesimpulan bahwa retorika adalah sebuah seni menggayakan kalimat semaksimal
mungkin untuk mempengaruhi orang lain. Selain mempengaruhi, pemaksimalan
penggunaan kalimat ini juga bertujuan untuk menyampaikan pesan agar pesan
tersebut bisa dirasakan benar oleh komunikannya dengan mempertimbangkan
aspek keindahannya.
Disiplin ilmu yang bertolak pada keterampilan berbicara ini bertumpu pada
bagaimana cara seorang komunikator meyakinkan para komunikannya dengan
berbagai cara. Aristoteles mengemukakan ada tiga cara yang dapat dijadikan cara
atau acuan dalam mempengaruhi para komunikan. Komunikator kaitannya dalam
3Abdul Rozak Zaidan, dkk.,Kamus Istilah Sastra, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 171.
4Edward P.J Corbett, The Little Rhetoric, (Canada: John Wiley & Sons, Inc, 1977), h. 1.
5Emsoe Abdurrahman dan Apriyanto Ranoedarsono, The Amazing Stories of Al-Qur’an;
Sejarah yang Harus Dibaca, (Bandung: Salamadani, 2009), h. 106. 6Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa; Komposisi Lanjutan I, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2010), Cet. 20, h. 3.

15
karya sastra adalah pengarang dan komunikannya adalah para pembaca karya
tersebut.
Ketiga cara tersebut yang dapat dilakukan oleh para pengarang untuk
mempengaruhi pembacanya adalah ethos, pathos, dan logos. Aspek ethos
berhubungan dengan komunikator atau pengarang. Dalam aspek ini dijelaskan
bahwa komunikator atau pengarang harus memiliki “pengetahuan yang luas,
kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat”.7 Ethos menuntut
pengarang untuk memiliki kredibilitas. Dengan memiliki hal itu, komunikan atau
pembaca akan mudah mempercayai apa yang akan disampaikan oleh
komunikator atau pengarang. Lebih jauh lagi, pengarang atau komunikator
dituntut menguasai bidang yang akan ia sampaikan.
Aspek pathos berkaitan dengan efek yang dihasilkan dari apa yang
disampaikan oleh pengarang atau komunikator. Efek tersebut akan dirasakan
oleh pembaca atau komunikan. Pengarang harus mampu menyentuh hati
pembacanya, seperti perasaan kasih sayang, benci, emosi, dan harapan”.8
Pembaca akan merasa dan berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh pengarang
lewat karya sastranya itu memang sungguh terjadi. Dengan merasakan efek
tertentu, pembaca akan sampai pada tahap katarsis.
Aspek terakhir untuk mempengaruhi pembaca atau komunikan disebut
dengan logos. Logos adalah “bukti-bukti yang dapat diajukan oleh pengarang”.9
Dengan mengajukan bukti, pembaca akan benar-benar sepenuhnya dapat
mempercayai bahwa apa yang disampaikan oleh pengarang memang benar.
Ketiga aspek retorika yang berfungsi untuk mempengaruhi lawan bicara tersebut
dapat diaplikasikan dalam retorika tekstual.
7 Jalaluddin Rakhmat, Retorika Modern; Pendekatan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2008), h. 7. 8 Ibid.
9 Ibid.

16
Retorika tekstual memiliki beberapa sarana yang bisa digunakan oleh
pengarang untuk menyampaikan gagasannya. Sarana-sarana inilah yang
kemudian akan menghasilkan efek yang bisa dirasakan oleh pembaca. Efek yang
dihasilkan dari sarana-sarana itu berupa efek “mempengaruhi atau meyakinkan
pembaca kalau apa yang disampaikan pengarang itu benar adanya”.10
Selain itu,
sarana retorika yang digunakan juga dimanfaatkan pengarang untuk
menghadirkan nilai estetis dari tulisan tersebut agar pembaca percaya dan tertarik
dengan gagasan yang disuguhkan.
Sarana retorika yang dimaksud adalah “figures of thought atau tropes dan
figures of speech, rethorical figures atau schemes”.11
Figures of thought adalah
penggunaan kalimat yang dimanfaatkan untuk menghasilkan penyimpangan
makna. Dengan kata lain, sarana retorika yang pertama ini lazim disebut dengan
gaya bahasa. Figures of speech adalah adalah penggunaan kalimat yang telah
disusun dengan konstruksi-konstruksi yang tidak biasa. Kalimat dalam sarana ini
dibuat sedemikian mungkin dengan memperhatikan fungsi-fungsi sintaksis.
Sarana ini lazim disebut dengan “penyiasatan struktur”.12
Pembagian prinsip-prinsip yang secara umum menyangkut ke arah ilmu
stilistika ini juga sejalan dengan empat elemen yang ada dalam sebuah sumber
berbahasa asing. Keempat elemen retorika itu salah satunya adalah “style or
expression of thoughts in the best possible language”.13
Penyiasatan struktur yang telah dijelaskan oleh Burhan Nurgiyantoro
dalam bukunya yang berjudul Teori Pengkajian Fiksi mengarah kepada teori
gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat milik Gorys Keraf dalam bukunya
yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa. Penyimpangan makna yang dijelaskan
10
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Gaya Bahasa, (Bandung: Angkasa, 1985), h. 5. 11
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press,
2005), Cet. 5, h. 296. 12
Ibid. 13
Francis Connoly dan Gerald Levin, A Rethoric Case Book, (New York: Harcourt, Brace, &
World, Inc, 1969), Cet. 3, h. 4.

17
dalam buku yang sama mengarah pada teori gaya bahasa berdasarkan langsung
tidaknya makna.
1. Sarana-Sarana Retorika
a. Gaya Bahasa Berdasarkan langsung Tidaknya Makna
Gaya bahasa yang didasarkan pada langsung tidaknya makna dapat
diketahui dari “apakah acuan yang dipakai masih mempertahankan makna
denotasi atau sudah menggunakan makna konotasi”.14
Makna yang ada dalam
kalimat itu sudah melewati batas lazim atau belum. Melewati batas lazim yang
dimaksud di sini adalah sebuah kata atau kalimat digunakan untuk
menggambarkan sesuatu yang terkadang tidak sejalan atau sesuai dengan arti
kata itu sendiri secara harfiah. Terdapat unsur penyimpangan makna dari kata
sebenarnya yang dilakukan oleh pengarang untuk membantu tercapainya
pengertian yang diinginkan. Seringkali pengertian antara gaya bahasa dengan
majas disamakan. “Majas bertugas membantu gaya bahasa”.15
Dengan begitu,
dapat diketahui bahwa cakupan gaya bahasa lebih luas dari majas. Selain itu,
dengan menggunakan majas, pengarang mampu membantu pembaca lebih dapat
memahami makna yang sebenarnya ingin dicapai lewat majas yang digunakan.
Hal ini dikarenakan “majas lebih konkret menjelaskan sesuatu daripada
penggambaran tanpa menggunakan majas”.16
Sejalan dengan sarana retorika yang dikemukakan oleh Burhan, gaya
bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna menurut Gorys terbagi atas dua
kelompok besar, yakni retoris dan kiasan.17
14
Keraf, op., cit, h. 129. 15
Nyoman Kutha Ratna, Stilistika; Kajian Puitika, Bahasa, Sastra, dan Budaya, (Jogjakarta:
Pustaka Pelajar, 2009), h. 165. 16
Anton M. Moeliono, Kembara Bahasa, Kumpulan Karangan Tersebar, C. Ruddyanto (ed.).
(Jakarta: PT. Gramedia. 1980), h. 175 17
Keraf, op., cit, h. 129.

18
1. Gaya Bahasa Retoris
Gaya bahasa retoris adalah gaya bahasa yang dibuat dengan memanfaatkan
penyimpangan konstruksi yang lazimnya digunakan agar dapat mencapai efek
yang diinginkan pengarang.18
Jenis gaya bahasa ini terdiri atas dua puluh satu
jenis yang masing-masing menghasilkan efek tersendiri. Kedua puluh satu gaya
bahasa itu adalah ”aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis, apostrof, asindenton,
polisindeton, kiasmus, ellipsis, eufimisme, litotes, histeron preteron, pleonasme
dan tautologi, perifrasis, prolepsis, erotesis atau pertanyaan retoris, silepsis dan
zeugma, koreksio, hiperbol, paradoks, dan oksimoron”.19
Namun, peneliti hanya
menjabarkan beberapa gaya bahasa yang ditemukan dalam penelitian ini saja.
Gaya bahasa yang terdapat dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut.
a. Eufimisme
Gaya bahasa eufimisme atau eufemismus berarti “mempergunakan kata-kata
dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik”.20
Gaya bahasa ini
merupakan cara yang biasa digunakan oleh pengarang untuk menggantikan
kata-kata yang awalnya memiliki makna yang buruk dengan kata-kata lain
yang maknanya sedikit lebih halus maknanya. Tujuan penggunaan gaya bahasa
ini adalah untuk “menghindari kesan merugikan atau tidak menyenangkan dari
hal yang disebutkan”.21
b. Pleonasme dan Tautologi
Sebuah kata dapat dikatakan sebagai gaya bahasa pleonasme jika “kata yang
berlebihan dapat dihilangkan tanpa mengubah makna awal”.22
Gaya bahasa ini
digunakan pengarang untuk menimbulkan efek penegasan terhadap makna
18
Ibid. 19
Ibid. 20
Ibid, h. 132. 21
D. Damayanti, Buku Pintar Sastra Indonesia, (Yogyakarta: Araska, 2013), h. 57. 22
Keraf, op. cit., h. 133.

19
yang akan disampaikan. Kata yang dapat dinamai tautologi adalah apabila
“kata yang berlebihan tersebut mengandung perulangan dari sebuah kata yang
lain”.23
Sama seperti pleonasme, tautologi membutuhkan dua kata yang
berfungsi untuk saling menegaskan. Namun, pada majas tautologi ini, kata
yang digunakan hanya bersifat mengulang saja dan jika memungkinkan, tidak
ada yang perlu dihilangkan dari penggunaan kata-kata tersebut.
c. Perifrasis
Perifrasis adalah “gaya bahasa yang menggunakan kata yang lebih banyak dari
yang diperlukan”.24
Hal yang perlu diperhatikan pada pleonasme, tautologi,
dan perifrasis perbedaan ketiga gaya tersebut terletak pada kata-kata yang
digunakan. Apabila dalam pleonasme, kata-kata yang digunakan cukup
dihilangkan salah satu dari kedua kata tersebut, lalu tautologi terletak pada kata
yang saling menjelaskan sehingga bila dimungkinkan tidak perlu ada yang
dihilangkan, maka pada perifrasis ini, kata-kata yang banyak itu bisa diganti
hanya dengan satu kata saja yang lebih konkret.
d. Erotesis atau pertanyaan retoris
Gaya bahasa yang satu ini berupa “pertanyaan yang dipergunakan dalam
pidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam
dan penekanan yang wajar, dan tidak membutuhkan jawaban sama sekali”.25
Karena bentuk kalimat pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban, maka yang
ingin dicapai dari penggunaan majas ini adalah sebuah bentuk penegasan untuk
lawan bicara.
23
Ibid, h. 134. 24
Ibid. 25
Ibid.

20
e. Hiperbola
Hiperbola ini merupakan gaya bahasa yang “menggambarkan sesuatu dengan
cara yang berlebih-lebihan”.26
Efek yang ingin ditonjolkan dari penggunaan
gaya ini adalah untuk “meningkatkan kesan dan pengaruh kalimat tersebut
kepada pembaca”.27
f. Paradoks
Sebuah gaya yang mengandung “pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta
yang ada”.28
Paradoks digunakan pengarang dengan tujuan untuk
menimbulkan efek dramatis terhadap pembaca. Gaya bahasa ini juga berfungsi
untuk mengasah imajinasi pembaca terhadap dua hal atau situasi yang berbeda.
2. Gaya Bahasa Kiasan
Pokok dasar dalam membuat sebuah bahasa kiasan adalah perbandingan
atau persamaan.29
Gaya bahasa kiasan ini terdiri atas sembilan belas gaya.
Kesembilan belas gaya bahasa tersebut adalah simile, metafora, alegori, parabel,
fabel, personifikasi, alusi, eponim, epitet, sinekdoke, metonimia, antonomasia,
hipalase, ironi, sinisme, sarkasme, innuendo, antifrasis, dan paronomasia.
Namun, di bawah ini peneliti hanya akan menjelaskan beberapa gaya bahasa saja
yang ditemukan dalam penelitian ini.
a. Simile atau Perbandingan
Gaya bahasa simile adalah “gaya bahasa perbandingan yang bersifat
eksplisit”.30
Maksud dari eksplisit adalah perbandingan yang langsung
26
Ibid, h. 135. 27
Tarigan, op. cit., h. 55. 28
Keraf, op. cit., h. 136. 29
Ibid. 30
Ibid, h. 138.

21
menyatakan sesuatu sama dengan hal lain. Perbandingan ini mengunakan
“kata bandingan berupa seperti, sama, sebagai, layaknya, laksana, serupa,
ibarat, umpama, bak, dan bagai”.31
b. Metafora
Gaya bahasa ini merupakan “perbandingan semacam analogi yang
membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang
singkat”.32
Metafora ini sama halnya dengan simile, termasuk ke dalam majas
persamaan atau perbandingan. Bedanya, metafora tidak memerlukan kata
perumpamaan seperti halnya simile. Dalam membandingkan, metafora
langsung membandingkan benda yang ingin disamakan dengan benda lain
yang memiliki sifat yang sama. “Salah satu cara untuk membuat metafora
adalah dengan menggunakan gaya sinestesia”.33
Perbandingan sesuatu dengan
yang biasa dirasakan oleh indera manusia ini banyak digunakan untuk
menghasilkan sebuah makna yang mudah dimengerti oleh pembaca.
c. Personifikasi
Personifikasi adalah “gaya bahasa perbandingan yang mengggambarkan
benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah
memiliki sifat kemanusiaan”.34
Dalam gaya bahasa ini, benda mati diceritakan
mampu melakukan apa yang lazimnya dilakukan oleh makhluk hidup, baik itu
manusia maupun hewan. Dengan menggunakan personifikasi, “pembaca akan
mendapatkan efek berupa kejelasan pembeberan suatu kondisi dan imajinasi
yang jelas”.35
31
Damayanti, op. cit., h, 48. 32
Keraf, op. cit., h. 139. 33
Ibid, h. 99. 34
Keraf, op. cit., h. 140. 35
Damayanti, op. cit., h. 27.

22
d. Sinekdoke
Gaya bahasa sinekdoke ini “berasal dari bahasa Yunani yang berarti menerima
bersama-sama”.36
Dalam pengertian lain, sinekdoke adalah “majas yang
menyebutkan nama sebagian sebagai nama pengganti barang sendiri”.37
Sinekdoke ini terbagi menjadi dua jenis, yakni totem pro parte dan pars
prototo. Totem pro parte adalah gaya bahasa yang menggambarkan
keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebagian. Pars prototo adalah
kebalikan dari totem proparte, yakni menyatakan sebagian tapi maknanya
adalah seluruhnya.
e. Metonimia
Gaya bahasa yang “menggunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal
lain karena memiliki pertalian yang sangat dekat”.38
Hal yang disebutkan itu
merujuk kepada manusia, benda, atau hal lain yang memiliki makna tertentu
yang ingin disampaikan secara khusus.
f. Antonomasia
“Sebuah bentuk khusus dari sinekdoke yang berwujud penggunaan sebuah
epitet untuk menggunakan nama diri, atau gelar resmi, atau jabatan untuk
menggantikan nama diri”.39
Gaya bahasa ini digunakan untuk menyebutkan
seseorang dengan panggilan lain. Tujuannya adalah untuk memberikan
pengetahuan lain kepada pembaca bahwa tokoh tersebut memiliki panggilan
lain yang kemungkinan besar berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan
yang ia miliki. Gaya bahasa ini sangat sering digunakan dalam novel-novel
yang berlatarbelakangkan kerajaan karena biasanya seorang raja memiliki
banyak gelar atau juga nama sapaan.
36
Keraf, op. cit., h. 142. 37
Ratna Susanti, Ejaan Yang Disempurnakan Terbaru, (Klaten: CV. Sahabat, 2012), h. 100. 38
Keraf, loc. cit. 39
Ibid.

23
g. Ironi, Sinisme, Sarkasme
Ketiga gaya bahasa ini merupakan saya bahasa yang digunakan untuk
menyindir seseorang. Perbedaan dari ketiganya terletak pada seberapa
tajamkah atau parahkah sindiran yang dilontarkan. Gaya bahasa sindiran yang
paling ringan adalah ironi. Lalu meningkat ke sinisme dan sindiran yang
paling menyakitkan adalah sarkasme.
Ironi adalah “suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau
maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya”.40
Biasanya, bila seseorang akan mengatakan sesuatu yang buruk, maka ia akan
mengatakan hal yang baik untuk mengungkapkannya tentunya dengan
intonasi yang jauh berbeda dengan cara memuji.
Sinisme adalah suatu “sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung
ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati”.41
Sinisme memiliki tingkat
ketajaman satu tingkat lebih tinggi dari ironi.
Sarkasme adalah “suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang
getir”. Dibandingkan kedua sindiran yang sebelumnya, gaya bahasa ini
memang ditujukan untuk menyakiti lawan bicaranya. Tanpa sungkan lagi,
seseorang akan menggunakan gaya bahasa ini untuk memaki.
b. Penyiasatan Struktur
Kalimat yang baik karena mengikuti tata bahasa belum tentu merupakan
sebuah tulisan yang menarik perhatian. Kaidah kebahasaan memang dibuat
untuk mengatur penelitian agar sedap dan nyaman untuk dibaca. Namun,
adakalanya terlalu mengikuti kaidah yang ada hanya akan membuat pembaca
40
Ibid, h 143. 41
Ibid.

24
bosan, apalagi bila semua kalimat yang disajikan menggunakan pola yang
sama, kalimat tersebut terkesan kaku. Untuk itu, ada tiga jenis struktur kalimat
yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni kalimat periodik, kalimat
kendur, dan kalimat berimbang.42
Ketiga jenis struktur kalimat ini memiliki
tujuan penggunaannya masing-masing.
1. Kalimat Periodik
Kalimat periodik adalah “sebuah teknik penyajian kalimat yang
menempatkan inti atau gagasan utama kalimat tersebut di akhir kalimat”.43
Kalimat tersebut disusun berdasarkan konstruksi anak kalimat yang umumnya
tidak mengandung informasi penting kemudian diikuti oleh hadirnya induk
kalimat. Dalam penyusunan kalimat ini, sangat diperlukan pengetahuan
tentang fungsi kalimat dengan baik. Kalimat jenis ini juga sering disebut
dengan “kalimat berklimaks”.44
Susunan kalimat yang demikian disengaja
“untuk membentuk sebuah ketegangan saat pembaca membaca kalimat
tersebut”.45
Contoh:
Sebelum Anca pergi ke tanah rantau, ia masih sempat tersenyum
padaku, meski hanya seulas saja.
Pada kalimat tersebut, kalimat ini diawali oleh fungsi keterangan
waktu yang ditandai oleh konjungtor sebelum. Info penting yang ingin
disampaikan oleh kalimat ini adalah Anca sempat tersenyum kepada tokoh
aku.
42
Ibid, h. 124. 43
Keraf, loc., cit. 44
Zaenal Arifin dan Amran Tasai, Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi,
(Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1988), Cet. 3, h. 108. 45
Ibid.

25
2. Kalimat Kendur
Kalimat kendur adalah “sebuah susunan kalimat yang dibangun
dengan menempatkan bagian terpenting dari sebuah kalimat di awal dan
diikuti oleh bagian yang kurang penting”.46
Pada kalimat ini, induk kalimat
yang mengandung gagasan terpenting diletakkan di awal kalimat dan anak
kalimatnya diletakkan di belakangnya. Kalimat ini juga disebut dengan
struktur kalimat melepas.47
Makna yang dikandungi oleh struktur kalimat jenis
ini sudah bisa diketahui tanpa harus membaca lanjutannya. Kalimat yang
disajikan dengan jenis penyusunan ini biasanya mengandung makna yang
sangat penting dan untuk menjaga konsentrasi pembaca, pengarang
menempatkannya di awal terlebih dahulu. Ditakutkan, bila info penting
tersebut diletakkan di akhir kalimat, sebagaimana dengan konstruksi kalimat
periodik, pembaca tidak akan langsung menangkap makna kalimat tersebut.
Sama halnya dengan konstruksi kalimat periodik, untuk membuat kalimat ini
diperlukan kecermatan dalam menggunakan fungsi kalimat.
Misal:
Saya akan tidur saat rasa kantuk datang.
3. Kalimat Berimbang
Struktur kalimat jenis ini adalah “kalimat yang mengandung dua
bagian kalimat yang kedudukannya sama tinggi”.48
Biasanya kalimat ini
disusun dengan menggunakan dua klausa atau lebih. Dengan begitu, kalimat
ini dibangun oleh konstruksi kalimat majemuk.49
Kalimat majemuk dalam
bahasa Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat
46
Keraf, loc., cit. 47
Arifin,loc., cit. 48
Keraf.loc. cit. 49
Arifin dan Amran Tasai.loc. cit.

26
majemuk berimbang, dan kalimat majemuk bertingkat. Ketiga kalimat
tersebut dibangun dengan cara yang berbeda.50
4. Kalimat Majemuk Setara
Kalimat majemuk setara adalah “konstruksi sebuah kalimat yang
dibangun dari gabungan beberapa kalimat tunggal yang unsur-unsurnya tidak
ada yang dihilangkan”.51
Maksud dari unsur-unsur yang tak dapat dihilangkan
adalah kalimat-kalimat tunggal yang kemudian digabungkan menjadi satu
kalimat tidak ada yang dihilangkan. Baik makna atau strukturnya, “kedua
klausa yang digunakan ini tidak saling bergantung sama lain”.52
Dengan kata
lain, bila salah satu di atara kedua klausa ini ada yang dihilangkan, makna
yang dikandungi tidak akan berubah. Kalimat majemuk setara ini memiliki
tiga jenis kalimat yang tergantung dari jenis hubungan antarkalimat yang
digabungkan tersebut. Ketiga kalimat tersebut yakni, kalimat majemuk setara
sejalan, kalimat majemuk setara berlawanan, dan kalimat majemuk setara
penunjukkan.
5. Kalimat Majemuk Setara Sejalan
Jenis kalimat majemuk ini memiliki arti yang sejalan dengan klausa
lainnya. Pada kalimat ini, semua klausa yang digunakan bisa digabungkan
tidak hanya dengan menggunakan konjungtor, tetapi juga dengan tanda baca
koma (,). Kalimat majemuk setara sejalan ini juga terbagi lagi menjadi tiga
jenis, yaitu KMS Sejalan Biasa, KMS Sejalan Mengatur, dan KMS Sejalan
Menguatkan.
50
Ida Bagus Putrayasa, AnalisisKalimat; Fungsi, Kategori, dan Peran, (Bandung: PT. Refika
Utama, 2007), h. 55-61. 51
Ibid, h. 55. 52
Dendy Sugono, Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2009), h. 158.

27
6. Kalimat Majemuk Setara Berlawanan
Kalimat majemuk setara jenis ini memiliki makna yang bertentangan
dengan makna pada klausa lainnya. Biasanya, kedua klausa yang saling
bertentangan maknanya itu digabungkan dengan konjungtor pertentangan
seperti tetapi atau namun. Konjungtor inilah yang berfungsi untuk
mempertentangkan makna kedua klausa yang digunakan.
Jenis kalimat ini juga dibagi lagi menjadi tiga kalimat, yaitu KMS
Berlawanan Biasa, KMS Berlawanan Mengganti, dan KMS Berlawanan
Mewatasi. Semua jenis KMS berlawanan ini menggunakan konjungtor yang
berbeda fungsinya, sesuai dengan nama kalimat ini.
7. Kalimat Majemuk Setara Penunjukkan
Jenis kalimat ini mengarahkan pembaca untuk memperhatikan klausa
kedua yang ada dalam kalimat tersebut. Klausa pertama dalam kalimat jenis
ini menjadi penunjuk untuk klausa kedua. Biasanya, jenis kalimat ini juga
menggunakan konjungtor yang sesuai dengan makna penunjukkan yang
dimaksud. Kalimat penunjukkan ini juga terbagi ke dalam lima jenis, yaitu
KMS Penunjukkan Sebab-Akibat, KMS Penunjukkan Perlawanan, KMS
Penunjukkan Waktu, KMS Penunjukkan Tempat, dan KMS Penunjukkan
Syarat.
8. Kalimat Majemuk Rapatan
Kalimat majemuk rapatan adalah kalimat yang dibangun dari beberapa
klausa yang memiliki unsur yang sama kemudian unsur yang sama itu
dihilangkan atau dijadikan satu. Jenis kalimat majemuk rapatan ini tergantung
dari jenis unsur yang dihilangkan atau dirapatkan.Jenis-jenisnya adalah KMR
Subjek, KMR Predikat, KMR Objek, dan KMR Keterangan.

28
9. Kalimat Majemuk Bertingkat
Kalimat majemuk ini dibangun oleh sisa dari klausa utama yang bisa
dibentuk sebuah kalimat baru. “Kalimat yang baru dibuat tersebut kemudian
digabungkan dengan klausa utama dengan menggunakan konjungtor ketika,
supaya, meskipun, jika, atau sehingga”.53
Dapat diperhatikan, bahwa dalam penyusunan sebuah kalimat
majemuk, apapun itu jenisnya, harus menggunakan konjungtor sesuai dengan
makna yang ingin dicapai. Hal ini dikarenakan “lewat konjungtorlah dua atau
lebih klausa dihubungkan dan pembaca bisa langsung mengetahui
maknanya”.54
Berdasarkan ketiga struktur kalimat yang kerap digunakan tersebut,
hadirlah bentuk-bentuk gaya bahasa yang bertolakbelakang dari teknis
penelitiannya. Gaya bahasa berdasarkan struktur yang dimaksud di sini adalah
“bagaimana tempat sebuah unsur kalimat yang penting ditempatkan karena
tempat sebuah unsur memengaruhi kepentingan informasi yang
disampaikan”.55
Beberapa gaya bahasa tersebut adalah sebagai berikut:
a. Klimaks
Gaya bahasa klimaks merupakan turunan dari kalimat yang bersifat periodik
atau kalimat berklimaks. Dengan begitu, pembaca diajak untuk merasakan
ketegangan dan bertanya-tanya tentang gagasan apa yang sebenarnya ingin
disampaikan oleh peneliti.
53
Sugono, op., cit, h. 173. 54
Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), (Jakarta: Rineka Cipta,
2009), h. 81. 55
Keraf, loc., cit.

29
b. Antiklimaks
Gaya bahasa yang satu ini dihasilkan dari struktur kalimat melepas atau
kendur. Bagian terpenting dari kalimat yang mengandung gagasan inti justru
ditempatkan di awal kalimat.
c. Paralelisme
Gaya bahasa ini dihasilkan dari struktur kalimat berimbang. Kedua bagian
kalimat dari susunan ini dibangun oleh dua konstruksi yang memiliki
kesejajaran bentuk gramatikal. Paralelisme ini mengandung konsep
pengulangan, yakni “pengulangan struktur gramatikal atau pengulangan
struktur bentuk”.56
Kehadiran gaya paralelisme mudah kenali karena
digunakannya struktur gramatikal yang sama di awal kalimat. Jadi,
paralelisme ini adalah sebuah gaya bahasa yang mengulang bentuk gramatikal
kalimat dan terlihat sejajar karenanya.
d. Antitesis
Sama dengan gaya bahasa paralelisme, antitesis ini juga dihasilkan dari
struktur kalimat berimbang. Namun, gagasan yang dikandunginya
mengandung sebuah gagasan yang bertentangan dengan menggunakan
kelompok kata yang berlawanan.
e. Repetisi
Gaya bahasa ini mengulang bunyi, suku kata, kata bahkan bagian kalimat
apapun yang dianggap penting sebagai bentuk penekanan pada konteks
tertentu. Repetisi juga dihasilkan dari struktur kalimat berimbang. Selain itu,
dalam sumber lain dikatakan bahwa segala macam gaya bahasa yang
menggunakan bentuk pengulangan termasuk ke dalam gaya bahasa repetisi
56
Nurgiyantoro, op., cit, h. 252.

30
karena gaya bahasa ini juga “mengulang frasa, klausa, kalimat, larik, bait,
alinea, dan tanda baca”.57
Gaya bahasa yang termasuk ke dalam repetisi adalah sebagai berikut:
1. Epizeuksis: Kalimat yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-
turut. Struktur kalimat ini bersifat repetisi langsung.
2. Tautotes: Repetisi atas sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi.
3. Anafora: Repetisi yang berwujud pengulangan kata pertama pada tiap baris
atau kalimat berikutnya.
4. Epistrofa: Kebalikan dari anafora. Bentuk yang diulang terletak di akhir
kalimat atau baris.
5. Simploke: Unsur yang diulang berada di awal dan akhir kalimat atau baris.
6. Mesodiplosis: Unsur yang diulang terletak di tengah kalimat atau baris.
7. Epanalepsis: Unsur yang akan diulang di awal kalimat atau baris terletak
pada akhir kalimat atau baris sebelumnya.
8. Anadiplosis: Kata atau frasa terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi
kata atau frasa pertama dari klausa atau kalimat berikutnya.58
B. Novel
1. Hakikat Novel
Sebagai genre sastra, novel ternyata telah banyak menarik minat banyak
kalangan. Pertanyaan seputar apa yang dimaksud dengan novel mengundang
berbagai pandangan karena ia tidak hanya sulit dijawab, tetapi juga
problematik untuk didekati. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh banyak
kalangan adalah dalam hal pemberian definisi kepada unsur-unsur yang
membentuk istilah sekaligus menjadi pembeda novel dengan karya lainnya.
57
Ibid., h. 247-248. 58
Keraf, op., cit, h. 124-129.

31
a. Novel dipandang sebagai salah satu “bentuk sastra yang menawarkan
sebuah gambaran kehidupan yang diidealkan, imajinatif, dan dibangun
oleh unsur-unsur yang disebut intrinsik seperti peristiwa, plot, tokoh,
latar, sudut pandang, yang sifatnya imajinatif”.59
b. “Jenis prosa yang dibangun berdasarkan unsur-unsur intrinsik dan
mengandung nilai-nilai kehidupan”.60
Dari berbagai pengertian yang telah diberikan, maka dapatlah diambil
kesimpulan bahwa novel adalah sebuah bentuk prosa rekaan yang kisahannya
tidak akan lepas dari kehidupan nyata meskipun terdapat unsur imajinasi di
dalamnya dengan menggunakan beberapa unsur intrinsik sebagai tubuh dan
unsur ekstrinsik sebagai jiwa yang akan menghidupi prosa rekaan tersebut.
Dalam berbagai sumber, “novel juga disebut dengan fiksi karena keidentikan
yang dimiliki oleh kedua kata tersebut”.61
Karakterisasi novel ini dilakukan sebagai upaya mempermudah para
peneliti dalam mengembangkan analisis mereka. Seringkali, sebuah novel
memiliki corak beragam dalam kisahannya sehingga cukup menyulitkan para
peneliti untuk mengkajinya menggunakan pendekatan apa.
Jenis novel yang telah berkembang saat ini dilihat dari isi cerita novel
tersebut. Jenis novel tersebut adalah “Picaresque, Epislatori, Sejarah,
Regional, Satir, Bildungrongsman, Tesis, Gotik, Roman-Fleuve, Roman
Feuileton, Fiksi Ilmiah, Novel Baru, Metafiksi”.62
Jenis-jenis novel tersebut
sudah ada sejak berabad-abad lalu.
59
Nurgiyantoro, op., cit, h. 4. 60
Zaidan, op.,cit, h. 136. 61
Nurgiyantoro, op.,cit, h. 9. 62
Furqonul Aziez dan Abdul Hasim, Menganalisis Fiksi; Sebuah Pengantar, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), h. 22-31.

32
2. Sastra Sejarah
Berbicara tentang sastra memang tidak akan bisa terlepas dari disiplin
ilmu lainnya. Sastra tidak bisa lahir begitu saja tanpa ada campur tangan dari
ilmu lain atau setidaknya kehidupan yang mendukungnya. Sastra yang sudah
terlahir dapat dikatakan sebagai cerminan dari kehidupan-kehidupan yang
secara tidak sengaja telah lahir dan hidup subur dan sengaja diamati oleh
penciptanya, yaitu pengarang.
Dewasa ini dunia kesusastraan dibanjiri oleh beragam disiplin ilmu yang
mentranformasikan wujudnya ke dalam karya sastra. Katakanlah sebuah novel
yang banyak menampung berbagai ide dan terbuka bagi semua disiplin ilmu.
Di dalamnya banyak dijumpai unsur-unsur ilmu alam yang mendominasi dan
menjadi alur, latar bahkan tokohnya pun terarah kepada keilmuan alam
tersebut. Tidak hanya ilmu alam saja yang kian menyerbu dunia kesusastraan,
ilmu sosiologi dan antropologi pun ikut menjamur dan ambil bagian dalam
pembuatan sebuah novel. Namun, ada satu disiplin ilmu yang menarik untuk
ditelaah lebih lanjut dalam dunia sastra, yakni sejarah.
Sejarah, pada hakikatnya adalah sebuah disiplin ilmu yang bertanggung
jawab penuh terhadap pewartaan tiap kejadian di masa lalu untuk dikaji di
masa kini dan diambil pelajaran yang terdapat dalam tiap kisahnya.
Seringkali, sejarah hanya dianggap sebuah bentuk penceritaan yang tidak bisa
diganggu gugat, seperti membaca sebuah kabar dari surat kabar hari ini.
Sebagai disiplin ilmu, sejarah berfungsi mengubah pengetahuan menjadi ilmu
pengetahuan yang posisinya layak disejajarkan dengan ilmu alam dan sosial
lainnya seperti geografi. Seperti disiplin ilmu lainnya, seorang sejarawan tidak
bertanggung jawab terhadap permasalahan bahasa, meskipun untuk
memberitakannya kepada khalayak luas, bahasa adalah satu-satunya media
yang tepat untuk itu. Mereka, para ilmuwan, sejarawan dan filsuf termasuk di
dalamnya, hanya memiliki tanggung jawab terhadap esensi isi dari sejarah
yang ia paparkan. Itulah yang menyebabkan seringnya teks sejarah menjadi

33
sebuah teks yang membosankan dan merumitkan pembacanya karena belum
tentu seorang sejarawan atau arkeolog yang lihai menggali fakta-fakta sejarah
di masa lampau juga lihai dalam mengolah kata.
Pada posisi inilah sastrawan mendapat peran ganda yang tak semua
ilmuwan mendapatkannya. Seorang sastrawan, selain ia bertanggung jawab
terhadap penampilan sebuah cerminan masyarakat, juga terhadap
pengeksploitasian bahasa yang tepat untuk tujuan yang pertama tadi.
Keterkaitan antara sastra dengan sejarah bukanlah barang baru dalam
sejarah kesastraan. Tercatat bahwa Aristoteles pun pernah memperdebatkan
masalah sastra dengan sejarah. Pokok permasalahanya adalah bahasa sejarah
bermain dalam ranah lampau dan sastra berada di wilayah penceritaan yang
mungkin saja terjadi. Selain itu, “sejarah hanya menceritakan masa lalu tanpa
pernah bisa menceritakan masa yang akan datang, seperti halnya sastra yang
terkadang juga bisa menceritakan hal yang belum terjadi”.63
Sastra dan sejarah juga saling berkaitan jika ditinjau dari segi
etimologisnya. “Padanan kata sejarah dalam bahasa Inggris adalah history dan
sastra yang diwakili oleh kata cerita memiliki berpadanan dengan story dalam
bahasa yang sama”.64
Historia berarti cerita, sejarah, penelusuran fakta atau
peristiwa. Kira-kira sekitar tahun AD 1700, ilmu sejarah berkembang sebagai
ilmu pengetahuan tersendiri, khususnya berkembang dengan kritik dan data.
Akibatnya di dunia barat nampaknya sejarah dan sastra makin terlihat jelas
bedanya, yang satu menjelaskan fakta-fakta yang sungguh terjadi dan yang
satu lagi bermain dalam imajinasi walaupun juga terkadang digunakan fakta
sebagai bahan untuk menciptakan karya.65
Misalnya saja, kisah sejarah Gajah
Mada sendiri tentunya berbeda dengan Pentalogi Gajah Mada karangan Langit
Kresna Hariadi meskipun Langit sendiri untuk membuatnya memerlukan
63
Ibid, h. 331. 64
A. Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra; Pengantar Teori Sastra, (Jakarta: PT Dunia Pustaka
Jaya, 1984), h. 244. 65
Ibid.

34
waktu yang tak sebentar dalam melakukan riset atas validitas data yang
hendak diolahnya. Dalam karya sejarah yang paling ilmiah pun masih terdapat
unsur subjektivitas pengarang yang tidak terhindar karena untuk kasus ini,
posisi sejarah sama dengan sastra yang multitafsir, meskipun sifatnya masih
tetap lebih besar kemultitafsiran sastra.
Sebagai hasil dari keterkaitan antara sejarah dengan sastra adalah
“hadirnya tiga aspek terpenting dalam sastra, yaitu sejarah sastra, sastra
sejarah dan novel sejarah”.66
Sejarah sastra berfungsi untuk mencatat
rangkaian peristiwa sastra sejak lahir hingga sekarang yang dengan sendirinya
tersusun secara kronologis. Sastra sejarah adalah karya sastra (hikayat) yang
mengandung unsur-unsur sejarah, seperti babad (Babad Buleleng, Babad
Tanah Jawi), hikayat (Sejarah Melayu, Hikayat Raja-raja Pasai, Hikayat Raja
Malaka). Sastra sejarah juga sering disebut teks historis atau teks genealogis.
Ia tumbuh subur pada masyarakat yang belum dapat membedakan secara jelas
antara rekaan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Teks historis ini ada
hampir di seluruh tanah nusantara.
Konsep yang dihadirkan dalam sastra sejarah dengan novel sejarah
berbeda. Sebagai peninggalan kebudayaan masyarakat lampau, sastra sejarah
merupakan refleksi sekaligus sebagai dokumen yang memandang bahwa seni
dan ilmu memiliki tugas yang sama, menghibur sekaligus mendorong
perkembangan masyarakat. Dilihat dari bagaimana keduanya lahir juga
berbeda. Sastra sejarah lahir sebagai akibat dari adanya kearifan budaya
masyarakat setempat sedangkan novel sejarah lahir sebagai genre tradisi sastra
modern. Selain itu, sastra sejarah lebih bersifat dokumen atau prasasti yang
dianggap memiliki nilai magis dan bernilai sejarah yang tinggi sedangkan
novel sejarah tidak lebih dari bersifat fiksional.
66
Ratna, op., cit, h. 340.

35
Lebih ringkas dijelaskan bahwa novel sejarah adalah “novel yang
memaparkan kejadian atau tokohnya dalam konteks sejarah yang jelas, dan ia
bisa pula memasukkan tokoh-tokoh rekaan dan nyata dalam rangkaian
ceritanya”.67
Dalam sumber lain, novel sejarah lebih mengutamakan
penceritaannya pada peristiwa atau tokoh sejarah tertentu. Sebagai karya fiksi,
semata-mata unsur itulah yang bersifat sebagai fakta sejarah, sedangkan
bagaimana unsur-unsur tersebut kemudian disusun menjadi sebuah cerita,
sepenuhnya merupakan imajinasi. Karya sastra berperan sebagai refleksi dari
sebuah kejadian yang di dalamnya terdapat periode sejarah tertentu, sesuai
dengan sejarah apa yang hendak diketengahkan oleh pengarangnya. Ciri-ciri
novel sejarah bukan semata-mata pada tokoh sejarah, tema, dan latar sebagai
penunjuk waktu tertentu, tetapi lebih kepada unsur-unsur psikologi dan sikap
sehingga peristiwa dan tokoh-tokoh merupakan representasi dari masa
tertentu. “Dialektika antara ciri-ciri dengan sikap pengarang inilah yang
menimbulkan kualitas estetis”.68
3. Unsur Intrinsik
a. Tema
Tema adalah “dasar cerita atau gagasan umum cerita dalam
sebuah karya”.69
Disebut gagasan umum dalam sebuah cerita karena
unsur inilah yang akan menggerakkan semua unsur intrinsik lainnya
untuk mendukung tema tersebut. Juga, dalam sumber berbahasa asing,
tema dikatakan sebagai “whatever general idea or insight the entire
story reveals”.70
Dari kedua pengertian tersebut, dapat diambil
67
Aziez, op., cit h. 22-31. 68
Ibid, h. 344. 69
Nurgiyantoro, op., cit, h. 70. 70
X.J. Kennedy, An Introduction to Fiction, (Canada: Little, Brown, and Company Limited,
1983), h. 103.

36
kesimpulan bahwa tema adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar dari
sebuah cerita yang disampaikan dari awal hingga akhir pengisahan.
b. Sudut Pandang
Unsur intrinsik yang kerap disebut dengan point of view ini
adalah “strategi, teknik, siasat, yang sengaja dipilih pengarang untuk
mengemukakan gagasan dan ceritanya”.71
Sudut pandang ini terbagi atas
dua macam, yakni “persona pertama dan persona ketiga”.72
Sudut pandang persona pertama biasanya juga disebut dengan
sudut pandang akuan. Penyebutan itu dikarenakan “dalam teknik
penceritaannya, digunakan kata ganti orang pertama aku atau saya”.73
Sudut pandang persona juga kerap disebut sebagai sudut
pandang diaan. “Jika pada sudut pandang akuan pencerita bertindak
sebagai salah seorang pelaku dalam cerita atau narrator acting,
pencerita dalam sudut pandang ini menjadi pengamat”.74
Pencerita yang
menjadi pengamat ini menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia,
ia, atau mereka.
c. Alur
Alur disebut juga dengan plot. Alur merupakan “konstruksi yang
dibuat pembaca mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logik
dan kronologik saling berkaitan dan yang diakibatkan atau yang dialami
oleh para pelaku”.75
Alur memiliki beberapa tahapan setiap tahapannya
memiliki pengaruh tersendiri bagi tahap selanjutnya. Tahapan tersebut
71
Nurgiyantoro, op., cit, h. 248. 72
Ibid., h. 249. 73
Endah Tri Priyatni, Membaca Sastra dengan Ancangan Literasi Kritis, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2010), h. 115. 74
Ibid., h. 115. 75
Jan Van Luxemburg, dkk., Pengantar Ilmu Sastra,Terj. dariInleiding in de
Literatuurwetenschap oleh Dick Hartono, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), Cet. 3, h. 149.

37
adalah “eksposisi atau pengenalan, komplikasi atau konflik, klimaks,
resolusi atau leraian, dan penyelesaian”.76
Hal yang perlu diperhatikan dalam alur tak melulu soal jenis alur
(maju, mundur, campuran), tetapi juga peristiwa-peristiwa apa saja yang
ada dalam cerita tersebut. Dalam setiap penceritaan, terutama novel
dengan jumlah halaman yang banyak, pasti memiliki peristiwa yang
dipentingkan. Peristiwa yang dipentingkan itu biasa disebut dengan
peristiwa utama atau lazimnya disebut dengen kernel. Sebaliknya, ada
peristiwa yang kurang dipentingkan dan sifatnya hanya sebagai
penambah keindahan saja disebut dengan satelit. “Satelit dihadirkan
pengarang untuk mengisi, mengelaborasi, melengkapi, dan
menghubungkan antarkernel”.77
d. Latar
Unsur yang satu ini “berkaitan erat dengan elemen-elemen yang
memberikan kesan abstrak tentang lingkungan, baik tempat maupun
waktu, di mana para pelaku menjalankan perannya”.78
Latar dalam
karya prosa tidak hanya terbatas pada penggunaan tempat atau sesuatu
yang sifatnya fisik saja, tetapi juga “menyangkut adat istiadat,
kepercayaan dan nilai-nilai yang ada dalam kisah tersebut”.79
Dengan
adanya pengetahuan tentang tempat dan waktu serta adat istiadat yang
diceritakan dalam novel tersebut, bisa diketahui suasana macam apa
yang timbul dalam adegan tersebut. Hadirnya unsur ini juga bertujuan
untuk mendukung tema yang diangkat oleh pengarangnya.
76
Priyatni, op., cit, h. 113. 77
Nurgiyantoro, op., cit, h. 120-121. 78
Aziez,op., cit, h. 74. 79
Nurgiyantoro, op.cit., h. 219.

38
e. Penokohan
Tema dan amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang
dibawakan lewat perantara hadirnya para tokoh yang masing-masing
memiliki karakter yang berbeda. Lewat karakter yang berbeda itulah,
tema dapat berjalan dan amanat tersampaikan.
Tokoh-tokoh terbagi ke dalam tiga bagian, yakni dilihat dari segi
peranannya, fungsi tokoh, dan perwatakannya. Berdasarkan peranannya,
tokoh terdiri atas tokoh utama dan tokoh sampingan. Bila dilihat dari
segi fungsinya, tokoh terbagi menjadi tokoh protagonis dan tokoh
antagonis. Terakhir, tokoh dibagi menjadi tokoh dengan watak yang
datar dan tokoh berwatar bulat.
f. Gaya Bahasa
Hadirnya sebuah gaya bahasa sangat penting dalam posisi karya
sastra. Sekalipun cerita tersebut dibuat dengan menggunakan alur atau
tema yang sangat baik, namun dibungkus dengan bahasa yang tidak
dapat mewakili keindahan dan makna yang dinginkan oleh pengarang,
cerita tersebut tidak akan mampu menggugah perasaan pembaca.
“Tiap pengarang memiliki ciri khasnya masing-masing”.80
Contohnya, bila pengarang itu adalah seorang Jawa, maka karya
sastranya akan menggunakan sedikitnya kosa kata dalam bahasa Jawa
sebagai identitas. Tentu penggunaan kosakata daerah itu juga
disesuaikan dengan unsur intrinsik lainnya.
80
Nani Tuloli, Teori Fiksi, (Gorontalo: BMT “Nurul Jannah”, 2000), h. 60.

39
g. Amanat
Amanat atau pesan adalah “suatu ajaran moral atau pesan yang
ingin disampaikan pengarang kepada pembaca”.81
Amanat akan sejalan
dengan tema yang diangkat oleh pengarang. Dengan begitu, amanat
merupakan “gagasan yang menjadi dasar bagi tulisan itu sendiri”.82
Pesan atau amanat bisa disampaikan lewat dua cara, yakni
langsung dan tak langsung.
a. Penyampaian langsung
Dalam teknik ini, pengarang menggurui pembaca secara
langsung memberikan nasihat dan petuahnya.
b. Penyampaian tak langsung
Teknik ini menggunakan bantuan unsur intrinsik lainnya
dalam menyampaikan amanat. Lewat permainan semua unsur
itulah, pembaca dituntut untuk mencari dan atau menafsirkan
sendiri amanat yang disampaikan pengarang. Jadi, “teknik ini tidak
bersifat menggurui pembaca sebagaimana yang terjadi pada teknik
penyampaian langsung”.83
4. Implikasi Pembelajaran
Bukan hal yang baru bila di dunia pendidikan, matapelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia seolah menjadi pelajaran yang kerap dianggap tidak sepenting
pelajaran eksakta. Di berbagai sekolah, banyak guru yang latar belakang
pendidikannya bukan berasal dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
mengampu matapelajaran ini. Tidak hanya itu, tak sedikit peserta didik yang
lebih memilih untuk mendalami matapelajaran lain, seperti bidang studi eksakta
dan sosial.
81
Panuti Sudjiman, Memahami Cerita Rekaan, (Jakarta: Pustaka jaya, 1988), h. 57. 82
Nurgiyantoro, op. cit., h. 321. 83
Nurgiyantoro, op., cit,h. 339.

40
Berbagai perlakuan yang sering “menganaktirikan” matapelajaran Bahasa
dan Sastra Indonesia ini bisa sampai terjadi karena, baik bagi pengajar yang
berasal bukan dari bidang ini atau pun peserta didik, menganggap pelajaran ini
hanya formalitas saja yang bisa dipelajari sendiri. Anggapan seperti inilah yang
mengakibatkan bidang Bahasa dan Sastra Indonesia bukanlah pilihan yang
menarik bagi para calon mahasiswa. Mereka lebih tertarik untuk mengambil
jurusan eksakta atau sosial.
Sayangnya, tindakan sebelah mata ini tidak diiringi oleh kemampuan
mereka dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sampai hari ini,
kesalahan berbahasa Indonesia sering terjadi. Ironisnya, kesalahan-kesalahan
dalam berbahasa Indonesia terjadi atau dilakukan di ruang publik, seperti brosur,
pamflet, hingga media massa. Inilah bukti bahwa bidang Bahasa dan Sastra
Indonesia sangat penting dan segera diberi penanganan khusus dalam rangka
mengubah stigma peserta didik maupun pengampu matapelajaran ini.
Pelajaran Sastra Indonesia dalam pembelajaran juga tidak kalah penting
dari pelajaran Bahasa Indonesia itu sendiri. Jika dalam materi Bahasa Indonesia,
peserta didik akan mendapatkan pengetahuan tentang seluk beluk bahasa
Indonesia, seperti struktur satuan bahasa, struktur kalimat, jenis dan kelas kata,
hingga berbagai macam bentuk paragraf, dalam pembelajaran Sastra Indonesia,
peserta didik akan diajak untuk mempelajari kehidupan dalam bentuk teks.
Selama ini, masih banyak peserta didik yang menganggap pelajaran sastra
hanya berkisar pada pembacaan berbagai macam karya prosa, menentukan unsur
intrinsik, menunjukkan bukti kutipan, dan berakhir pada pembuatan salah satu
bentuk prosa. Padahal, pembelajaran yang bisa diambil dari materi sastra tidak
hanya pada permasalahan apakah peserta didik mengerti unsur-unsur yang
terdapat pada sebuah karya sastra dan bisa membuatnya sendiri, tetapi hal-hal
menarik yang tidak bisa didapatkan pada pelajaran lain yang terkandung di dalam

41
karya tersebut. Hal-hal tersebut sangat bermanfaat bagi pengetahuan dan
kehidupan peserta didik.
Hal-hal menarik yang tak mungkin didapatkan pada matapelajaran lainnya
berupa pengetahuan tentang budaya, sejarah, agama, sosial, pendidikan,
psikologi, dan berbagai nilai yang biasanya terdapat pada unsur ekstrinsik sebuah
karya. Sejauh ini, materi tentang unsur ekstrinsik diajarkan oleh guru hanya
dengan cara menentukan mana kutipan yang mendukung unsur ekstrinsik
tersebut dan apa nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut.
Tentunya metode ini, tidak akan membuat peserta didik meresapi apa
maksud dan bagaimana menyikapi unsur ekstrinsik yang telah didapatkannya
tersebut. Hal ini akan membuat karya sastra hanya sebuah bacaan yang
membosankan dan peserta didik tidak akan mendapatkan manfaatnya. Tentunya,
keadaan ini tidak sejalan dengan fungsi sifat sastra menurut Horatius, dulce et
utile, sastra itu menghibur sekaligus bermanfaat.
Karya sastra, bukanlah hanya sebuah teks yang berisikan tentang sebuah
kisah yang dapat mengaduk emosi pembaca, tetapi juga “sebuah teks yang di
dalamnya menyimpan sesuatu dan tak jarang menyuguhkan banyak hal yang bila
dipahami dengan sungguh-sungguh dapat menambah pengetahuan
pembacanya”.84
Dengan metode yang tepat, karya sastra akan menjadi seperti
sebuah ensiklopedia yang menyimpan banyaksekali pengetahuan. Sebagai
contoh, ketika peserta didik ditugaskan untuk membaca novel Para Priyayi karya
Umar Kayam, mereka akan mengetahui bagaimana kehidupan sosial pada suku
Jawa, mulai dari pemberian nama tua bagi seseorang yang sudah dikatakan
dewasa, pengertian luas dari kehidupan priyayi, sampai latar waktu yang
tercermin dari novel tersebut. Pengetahuan ini akan sangat membantu menambah
pengetahuan siswa tentang salah satu budaya di Indonesia, terutama bagi peserta
84
B. Rahmanto, Metode Pengajaran Sastra, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 17.

42
didik yang bukan berasal dari suku Jawa. Tentunya, pengetahuan tambahan yang
tidak ada pada matapelajaran lainnya ini akan terlaksana bila metode yang
digunakan tidak hanya mencari, mendata, dan membuktikan kutipannya.
5. Penelitian Relevan
Pentalogi novel Gajah Mada karya Langit Kresna Hariadi banyak diambil
untuk dijadikan penelitian. Sehubungan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,
ada dua penelitian relevan yang juga menggunakan novel Gajah Mada: Takhta
dan Angkara.
Penelitian yang pertama berjudul Analisis Struktural Novel Gajah Mada:
Bergelut dalam Kemelut Takhta dan Angkara dan Perang Bubat Karya Langit
Kresna Hariadi. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Handoyo, mahasiswa
FKIP Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Sebelas Maret pada tahun
2009 ini meneliti tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada dalam novel
Gajah Mada: Bergelut dalam Kemelut Takhta dan Angkara dan Perang Bubat
Karya Langit Kresna Hariadi. Dalam penelitian perbandingan dua novel ini, hasil
yang didapatkan adalah kedua novel ini memiliki kesamaan tokoh utama, setting
alur, penggunaan sudut pandang, alur yang dipakai, dan juga sosail pengrang
budaya pengarangnya. Juga, letak perbedaan di antara kedua novel ini adalah
pada penokohan secara umum, setting suasana, tempat, dan waktu, amanat, tema,
dan gaya bahasa.
Penelitian tentang novel ini juga pernah dilakukan oleh Atik Fauziah,
mahasiswa di universitas yang sama jurusan Sastra Indonesia pada tahun 2007.
Judul penelitiannya adalah Kajian Intertekstualitas Novel Gajah Mada Karya
Langit Kresna Hariadi terhadap Kakawin Gajah Mada Gubahan Ida Cokorda
Ngurah. Hasil yang ditemukan oleh penelitian ini adalah terdapat perbedaan
antara asal usul Gajah Mada yang diceritakan dalam novel dengan Kakawin

43
Gajah Mada gubahan Cokorda Ida Ngurah. Dalam novel diceritakan bahwa
Gajah Mada berasal dari rakyat biasa. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil menjadi
patih di Majapahit. Dalam Kakawin, Gajah Mada adalah keturunan agung.
Berkat asal usulnya yang besar itulah, ia memiliki kewibawaan yang
membawanya menjadi seorang patih. Perbedaan ini dapat terjadi karena Langit
Kresna Hariadi, pengarang pentalogi novel ini, melakukan mitos pembebasan.
Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan kedua penelitian yang
dilakukan oleh dua mahasiswa Universitas Sebelas Maret ini adalah sama-sama
menjadikan novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna
Hariadi sebagai objek penelitian. Namun, penelitian yang dilakukan peneliti
dengan dua penelitian lainnya ini juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut
adalah pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret
ini berpusat pada kajian instrinsik dan penokohan, sedangkan titik tolak analisis
peneliti adalah bahasa yang digunakan untuk menyajikan alur-alur yang ada
dalam novel ini.
Dari penjabaran singkat hasil dua penelitian tentang novel Gajah Mada:
Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi ini, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa peneltian ini melengkapi dua penelitian yang telah ada
sebelumnya. Hal ini dikarenakan penelitian ini menitikberatkan kajian pada
unsur intrinsik pada aspek gaya bahasa. Dari sarana retorika yang digunakan
dalam penceritaan, dapat diketahui bahwa gaya bahasa dapat digunakan untuk
menunjukkan bagian mana yang lebih dipentingkan dalam sebuah cerita.

44
BAB III
PEMBAHASAN
A. Biografi Pengarang
Nama Langit Kresna Hariadi menjadi buah bibir penikmat sastra ketika
novel Gajah Mada yang mengambil sejarah sebagai latar belakangnya muncul ke
jagad sastra Indonesia. Awalnya, pria kelahiran 24 Februari 55 tahun yang lalu
ini tidak menyangka bahwa “novel yang sebelumnya ditujukan untuk sebuah
naskah drama radio ini akan membawa namanya naik melambung”.1 Semula,
setelah ia memutuskan mengubah haluan naskah drama radio ini menjadi sebuah
naskah novel, ia menawarkan ke berbagai penerbit namun usahanya untuk
menerbitkan novel ini tak kunjung membuahkan hasil. Penolakan demi
penolakan dialaminya. Hingga akhirnya Penerbit Tiga Serangkai yang berkantor
di daerah Solo setuju menerbitkannya dan ia memutuskan menjual naskah
tersebut seharga lima juta rupiah. Namun, ia sempat pesimis kalau novelnya itu
akan menarik minat pembaca di pasaran lantaran oleh pihak Tiga Serangkai
judulnya diganti. “Semula novel itu berjudul Duaja Bhayangkara kemudian
diubah menjadi Gajah Mada”.2 Namun, nasib baik berpihak pada karyanya
tersebut. Di luar prediksinya, novel tersebut laku keras di pasaran. Belajar dari
pengalaman tersebut, ia tak lagi menjual naskah kepada penerbit setelah ia
diminta oleh Tiga Serangkai menyiapkan seri selanjutnya.
Dari Novel Gajah Mada ini, lahirlah novel-novel yang sengaja mengambil
latar belakang sejarah Indonesia yang selama ini hanya dikenal lewat buku-buku
1Bayu Putra, Lebih Dekat dengan Langit Kresna Hariadi Penulis Novel Sastra Sejarah
Nusantara, http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/70960-lebih-dekat-dengan-langit-
kresna-hariadi-penulis-novel-sastra-sejarah-nusantara. Diunduh pada Jumat, 22 Agustus 2014 pukul
14.35 WIB. 2Ibid.

45
pelajaran sejarah dan dari perspektif yang bagi sebagian siswa membosankan.
Berikut daftar novel-novel LKH yang diterbitkan oleh berbagai penerbit:
a. Diterbitkan oleh Balai Pustaka
1. Balada Gimpul
b. Diterbitkan oleh Era Intermedia
1. Kiamat Para Dukun
c. Diterbitkan oleh Qalam Press
1. Libby 1
d. Diterbitkan oleh Tinta Yogyakarta
1. De Castaz
2. Alivia
3. Serong
4. Melibas Sekat Pembatas
5. Antologi Manusia Laminating
e. Diterbitkan oleh Gama Media
1. Kiamat Dukun Santet
f. Diterbitkan oleh Diva Press
1. Siapa yang Nyuri Bibirku? (nama samaran: Amurwa Pradnya Sang
Indraswari)
2. Jaka Tarup (nama samaran: Amurwa Pradnya Sang Indraswari)
g. Serial bersambung
1. Beliung dari Timur (Harian Umum ABRI)
2. Sang Ardhaneswari (harian Solopos)
3. Pentalogi Gajah Mada
1. Gajah Mada
2. Gajah Mada: Takhta dan Angkara
3. Gajah Mada: Hamukti Palapa
4. Gajah Mada: Perang Bubat

46
5. Gajah Mada: Madakaripura Hamukti Moksa
4. Mengarang? Ah Gampang
5. Menak Jinggo, Sekar Kedaton
6. Amurwa Bhumi, episode Cleret Tahun, (penerbitan ulang berasal dari
judul Candi Murca terbitan Diterbitkan oleh Tiga Serangkai)
h. Diterbitkan oleh Langit Kresna Hariadi Production
1. Candi Murca
1. Candi Murca: Ken Arok Hantu Padang Karautan
2. Candi Murca: Air Terjung Seribu Angsa
3. Candi Murca: Murka Sri Kertajaya
4. Candi Murca: Ken Dedes Sang Ardhanareswari
2. Perang Paregrek
1. Perang Paregrek 1
2. Perang Paregrek 2
3. Cinta Bergeming
i. Penerbit Narasi
1. Narasi 1 Teror
2. Narasi 2 Balada Gimpul (Penerbitan Ulang dengan judul sama, semula
diterbitkan oleh Balai Pustaka)
3. Narasi 3. Selingkuh (Penerbitan ulang berasal dari judul Serong,
diterbitkan oleh Penerbit Tinta)3
Karya-karya tersebut memang tidak diterbitkan oleh hanya satu penerbit
saja. Mengenai penerbitan buku, LKH pernah berseteru dengan penerbit Tiga
Serangkai. Ketika ia tahu bahwa ia sudah memiliki tempat di pasaran, ia
memutuskan mendirikan sendiri penerbitan yang bernama LKH Productions.
3Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Langit_Kresna_Hariadi. Diunduh pada
Jumat, 22 Agustus 2014 pukul 14. 52 WIB.

47
Namun, seiring dengan meledaknya novel Gajah Mada, banyak novelis-novelis
sejenis bermunculan. Hal inilah yang kemudian membuatnya harus mengalami
getirnya merugi sekitar 60 juta rupiah. Akhirnya, ia memutuskan kembali
bekerjasama dengan Tiga Serangkai untuk menerbitkan karya-karya selanjutnya.
LKH mengakui bahwa karyanya ini menginspirasi banyak penulis fiksi
lainnya. Namun, di balik kesuksesan ini, ia sadar untuk menulis novel yang
mengambil sejarah sebagai bahan bakunya tidak boleh sembarang.
Kesembronoan dalam mengolah fakta sejarah yang ada akan menimbulkan
masalah yang cukup berarti. Hal ini terjadi pada seri pertama Gajah Mada.
Dalam novel ini, terdapat banyak hal yang berbenturan dengan fakta sejarah. Tak
urung, hal ini mengundang kecaman dan kritik dari para sejarawan yang
dialamatkan padanya.
Kesalahan-kesalahan tersebut ialah penulisan lokasi penyelamatan
Jayanegara oleh Bhayangkara yang seharusnya di daerah Bedander, ia tulis
Kudadu. Tak hanya itu, rentang waktu antara pemberontakan Ra Kuti dengan
kematian Jayanegara juga tak lepas dari kritikan pembaca. Fakta sejarah
mengatakan bahwa ada rentang waktu sebanyak sembilan tahun antara kematian
Jayanegara dengan pemberontakan Ra Kuti, tapi dalam novel LKH justru
menuliskan bahwa Jayanegara meninggal bertepatan dengan meletusnya
pemberontakan tersebut. Juga, dalam novel tersebut, LKH menyebutkan bahwa
Lembu Anabrang masih hidup saat pemberontakan Ra Kuti padahal fakta sejarah
menyatakan bahwa Lembu Anabrang telah mati saat meredam pemberontakan
Ranggalawe di Tuban.4 Kekeliruan-kekeliruan itulah yang membuatnya semakin
serius lagi menggarap novelnya dengan cara melakukan riset lebih detil lagi. Tak
tanggung-tanggung, ia pernah menetap di Trowulan Mojokerto selama dua
4Langit Kresna Hariadi, Gajah Mada: Takhta dan Angkara, (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h.
vii-viii.

48
minggu untuk melakukan riset dan membaca beberapa buku akademik guna
memperbaiki kesalahannya.5
Diakuinya, penulis yang pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana
dari Presiden Megawati lantaran tercatat sebanyak 150 kali melakukan donor
darah ini, terinspirasi oleh M.H. Mintardja dan Herman Pratikno. Sejak kecil ia
telah akrab dengan cerita silat kedua penulis tersebut. Setelah selesai
membacanya, ia akan membacakan ulang untuk teman-teman sekolahnya.6
Namun, ia sadar bahwa sampai sekarang ia belum bisa menandingi sang pionir
sastra, M.H. Mintardja.7
5The Jakarta Post, Langit Kresna Hariadi Between Fact Fiction,
http://www.thejakartapost.com/news/2013/08/15/langit-kresna-hariadi-between-fact-
fiction.html. Diunduh pada 22 Agustus 2014 pukul 14.55 WIB.
6Ibid.
7Bayu Putra, Lebih Dekat dengan Langit Kresna Hariadi Penulis Novel Sastra Sejarah
Nusantara, http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/70960-lebih-dekat-dengan-langit-
kresna-hariadi-penulis-novel-sastra-sejarah-nusantara. Diunduh pada Jumat, 22 Agustus 2014 pukul
14.35 WIB.

49
B. Analisis Unsur Intrinsik
1. Tema
Setiap tulisan, baik itu karya sastra ataupun sebuah karya ilmiah pasti
memiliki sebuah tema atau gagasan yang melandasi seluruh tulisannya.
Mustahil ada sebuah tulisan, apapun itu genrenya, ditulis tidak dilandasi
sebuah tema, sesederhana apa pun tema tersebut. Pun demikian halnya
dengan novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara ini. Kali ini LKH
menyuguhkan sebuah tema yang sebenarnya tidak jauh dari kehidupan pada
zaman kerajaan, yakni perebutan kekuasaan. Hal ini dibuktikan oleh
kutipan di bawah ini:
Sebagaimana layaknya sesuatu yang amat berharga dan
diperebutkan, untuk memperolehnya bahkan bila perlu dengan
menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara membunuh
sekalipun. Sesuatu yang sungguh menggiurkan itu bernama
singgahsana, sebuah puncak kedudukan tanpa ada lagi yang
mengungguli.8
Novel yang mengambil latar belakang sejarah ini tak ubah laiknya
novel detektif yang menempatkan sang tokoh utama, yakni Gajah Mada
membongkar semua kasus pembunuhan yang terjadi di sekitar istana dan
melibatkan dua orang menantu Ratu Gayatri. Pembunuhan demi
pembunuhan yang terjadi di wilayah istana Majapahit memang ditujukan
untuk merebut kekuasaan Majapahit setelah Jayanegara wafat di tangan Ra
Tanca hanya dengan meninggalkan dua orang adik tirinya, yaitu Sri Gitarja
dan Dyah Wiyat. Melihat kondisi yang seperti itu, orang-orang di balik
suami masing-masing Sekar Kedaton mampu melihat peluang emas untuk
menjadikan tuannya sebagai orang nomor satu di tanah Wilwatikta. Untuk
mencapai hal tersebut, apapun tentu akan dilakukan. Tak peduli berapa
8Langit Kresna Hariadi, Gajah Mada: Tahkta dan Angkara, (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h.
347.

50
banyak darah yang harus tumpah demi mencapai singgahsana dan betapa
licik strategi untuk menyingkirkan lawan politiknya.
Intrik pembunuhan yang dilakukan inilah yang melatari hampir
semua bab yang ada dalam novel ini. Tercatat ada enam pembunuhan
dengan satu percobaan pembunuhan terhadap Raden Kudamerta yang di
balik semua pembunuhan tersebut adalah seseorang bernama Rangsang
Kumuda. Semua pembunuhan ini bermuara pada satu tujuan, yakni
menjadikan menantu kedua Gayatri sebagai raja Majapahit. Semua
pembunuhan maupun usaha pembunuhan yang gagal pasti melibatkan ular
sebagai alat membunuh, entah itu bisa ular yang dilumurkan pada keris
maupun ular hidup yang sengaja diletakkan oleh pembunuh ke objek yang ia
bunuh.
Menariknya, dari sekian banyak usaha perebutan kekuasaan yang
digencarkan oleh pendukungnya masing-masing, baik Raden Kudamerta
ataupun Raden Cakradara tidak berminat menjadi raja Majapahit. Memang
benar jika pernah terbersit di benak mereka bayangan akan seorang raja, tapi
itu pun karena mereka selalu mendapat tekanan dari pendukungnya. Pada
akhirnya apa yang selama ini dilakukan oleh Panji Wiradapa dan Pakering
Suramurda sia-sia karena tidak mendapat dukungan penuh dari orang yang
mereka jagokan.
2. Sudut Pandang
Untuk menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam novel ini,
LKH mengambil sudut pandang orang ketiga maha tahu dan diambil dari
sudut pandang seorang pujangga kenamaan di zaman Majapahit yang sampai
sekarang masih kita rasakan hasilnya, yakni kitab Negarakertagama karya
Mpu Prapanca. Di dalam novel, Mpu Prapanca disebut Pancaksara.

51
Pilihan menggunakan Pancaksara sebagai pencerita LKH lakukan
agar semua kisah yang akan ia sampaikan tidak hanya tergambarkan dari
sudut pandang yang subjektif dari tokoh utamanya saja. Misalnya, jika LKH
menggunakan sudut pandang pertama pelaku pertamanya Gajah Mada, maka
pembaca akan disuguhkan sebuah sajian kisah dari pikiran Gajah Mada saja,
sedangkan yang diinginkan oleh pengarang adalah menyajikan gambaran
kisah yang utuh kepada pembaca agar tidak dipengaruhi subjektivitas dari
manapun. Hal ini dipandang sangat perlu diperhatikan lebih mendalam oleh
pengarangnya mengingat novel yang ia karang adalah sebuah kisah yang
berlatarbelakang sejarah yang pada adegan tertentu harus sangat hati-hati
menulisnya karena jika tidak akan menimbulkan sentimen pada hal-hal
tertentu, seperti yang ada dalam seri Gajah Mada: Perang Bubat.
Juga, alasan mengapa LKH memilih menuliskan cerita ini lewat
penuturan seorang Pancaksara adalah karena ia dalang sekaligus penulis
Kitab Negarakertagama, sebuah kitab yang berisikan tentang kehidupan
kerajaan Majapahit dari sisi istananya. Dengan begitu, LKH menempatkan
novelnya kali ini seolah-olah seluruh hasil pengamatan Pancaksara pada
zaman dahulu untuk kemudian ditulisnya dalam Negarakertagama. Lewat
cara inilah nilai historis yang ditampilkan oleh novel ini lebih kental,
mendukung latar waktu dan tempat yang digunakan pengarang.
Pancaksara memulainya dengan mengulang kisah wafatnya Raden
Wijaya, raja pertama Majapahit. Bukti kutipannya adalah sebagai berikut:
Ada banyak hal yang dicatat Pancaksara, banyak
sekali.Kesedihan kali ini bagai pengulangan peristiwa sembilan belas
tahun yang lalu, yang ditulisnya berdasar kisah yang dituturkan
ayahnya, Samenaka, karena peristiwa itu terjadi Pancaksara masih
belum bisa dibilang dewasa.9
9Ibid., h. 3.

52
Lewat kutipan tersebut pembaca bisa mengetahui bahwa apa yang
tengah dilakukan oleh Pancaksara adalah sebuah lemparan kenangan ke
masa lalu sedangkan ia berada di waktu sekarang, saat kabar tentang
Jayanegara masih simpang siur. Pancaksara dalam cerita ini disebut sebagai
orang ketiga dan sudut pandang yang digunakan LKH adalah maha tahu.
Selain itu, di beberapa adegan, cerita ini mengambil pola cerita berbingkai.
3. Latar
Novel pentalogi seri kedua ini mengambil latar waktu abad XIV-XV
masehi. Dengan begitu, baik dari segi latar tempat yang digunakan
disesuaikan dengan latar waktu yang digunakan. Penggunaan latar ini
berkaitan erat dengan muatan sejarah yang LKH ambil sebagai tema.
3.1. Latar Tempat
Latar tempat yang ia gunakan secara umum adalah di sebuah
wilayah Jawa Timur yang bernama Trowulan, yang sekarang lebih
dikenal dengan nama Mojokerto. Beberapa adegan di kisah ini
mengambil latar di wilayah Jawa Timur lainnya seperti Ujung Galuh
yang sekarang bernama Surabaya, Padas Payung, dan Karang Watu.
Penggunaan wilayah-wilayah yang sekarang tercangkup dalam daerah
Jawa Timur ini dikarenakan pusat kebudayaan dan kerajaan Majapahit
pada zaman itu terletak di wilayah timur Pulau Jawa dan saat itu
Majapahit dihadapkan pada masa peralihan kekuasaan setelah wafatnya
Sang Prabu dan siapa penggantinya. Juga, pada abad empat belas,
Majapahit disibukkan dengan usaha memadamkan makar yang kerap
terjadi di masa Jayanegara dan juga sedang tidak melancarkan ekspansi
ke daerah mana pun.

53
Selain wilayah-wilayah sekitar Jawa Timur, novel ini juga
mengambil beberapa latar tempat yang berada di dalam dan sekitar
istana Majapahit.
3.1.1. Istana Sekar Kedaton Dyah Wiyat
Bukti kutipan:
Hanya berdua di dalam bilik dibantu Dyah Menur,
Maharajasa berdandan menyamarkan diri.10
3.1.2. Istana Sekar Kedaton Kiri
Bukti Kutipan:
Istana yang kini menjadi kediaman
Tribuanatunggadewi Jayawisnuwardhani atau Sri
Gitarja tak kalah megah dari istana utama.11
3.1.3. Antawulan
Bukti Kutipan:
Tua, muda, laki-laki, dan perempuan terpanggil
menjadikan makam Antawulan tumplek blek berjejal-
jejal seperti tidak memberi ruang yang cukup.12
3.1.4. Alun-alun Istana Majapahit
Bukti Kutipan:
Bergetar alun-alun itu karena Patih Daha Gajah Mada
berbicara langsung pada pokok permasalahan.13
3.1.5. Balai Prajurit
Bukti Kutipan:
10
Ibid., h. 472. 11
Ibid., h. 227. 12
Ibid., h. 356. 13
Ibid., h. 20.

54
Balai Prajurit mendadak dibersihkan dan dengan
mendadak dipersiapkan untuk sebuah acara
penghormatan menggunakan tata cara keprajuritan.14
3.1.5. Bale Shakuntala
Bukti Kutipan:
Adakah ruangnya yang murung atau para ratu sedang
murung menyebabkan ruang Bale Shakuntala tampak
berbeda dari biasanya, terlihat ikut suram.15
3.1.6. Padas Payung
Bukti Kutipan:
Padas Payung, dinamai demikian karena tebing yang
memayungi jalan.16
3.1.7. Karang Watu
Bukti Kutipan:
Tebing bebatuan Karang Watu menjulang tinggi dan
sangat terjal.17
3.2. Latar Waktu
Untuk mendukung dan memperkuat penceritaan, waktu yang
digunakan pun juga diperhatikan sedemikian rupa oleh penulis.
Disesuaikan dengan masalah yang diangkat, siapa yang harus dijadikan
penguasa Majapahit, novel ini menggunakan latar waktu tahun 1328,
tahun di mana Majapahit sempat diguncang oleh kematian rajanya dan
puncak kepemimpinan diambil alih oleh ratu kembar setelah
sebelumnya dipimpin oleh seorang biksuni, yakni Gayatri.
14
Ibid., h. 130. 15
Ibid., h. 383. 16
Ibid., h. 345. 17
Ibid., h. 447.

55
LKH menceritakan semua permasalahan mulai dari matinya
Jayanegara di tangan Ra Tanca, terbunuhnya beberapa pendukung
Raden Kudamerta satu per satu oleh Rangsang Kumuda, terbongkarnya
rahasia Kudamerta, pemberontakan di Karang Watu, hingga
terbongkarnya semua permasalahan ini hanya dalam hitungan hari. Hal
ini dibuat untuklebih menonjolkan sisi cekatan Gajah Mada beserta
pasukan Bhayangkaranya yang terkenal sigap.
3.3. Latar Suasana
Latar suasana digunakan oleh penulis untuk mengaduk emosi
pembaca dan untuk membuat pembaca lebih percaya bahwa kejadian ini
mengambarkan suasana Majapahit pada masa tersebut yang dipenuhi
kekacauan.
3.3.1. Kalut
Hal ini dibuktikan oleh kutipan di bawah ini:
Akan tetapi, jerit itu hanya menggema dalam
hati.Dyah Menur tidak mungkin berteriak atau
memanggil namanya, tidak mungkin berlari
menghambur mendekat, bahkan tidak mungkin lagi
berharap Raden Kudamerta tetap suaminya.18
3.3.2. Sedih
Hal ini dibuktikan oleh kutipan di bawah ini:
Bukan atas nama kematian kakaknya, Sri Jayanegara,
tetapi atas nama kemelut yang bersumber dari hatinya
sendiri, Dyah Wiyat menangis. Semua orangmengira
ia menangisi kakaknya, padahal tangisnya bersumber
dari alasan lain.19
18
Ibid., h. 368. 19
Ibid., h. 157.

56
3.3.3. Tegang
Hal ini dibuktikan oleh kutipan di bawah ini:
Wajah Gagak Bongol dan Gajah Enggon menegang.20
3.3.4. Haru
Hal ini dibuktikan oleh kutipan di bawah ini:
Dyah Menur memandang Dyah Wiyat dengan tatapan
mata berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak menyangka
Dyah Wiyat akan mampu bersikap seperti itu. Dugaan
dan penilaian yang terbentuk seketika ambruk. Sekar
Kedaton ternyata tidak seburuk yang ia sangka.
Dengan lengan bajunya, Dyah Menur membasuh air
matanya.21
3.3.5. Kecewa
Hal ini dibuktikan oleh kutipan di bawah ini:
“…. Bila perbuatan Paman terbongkar, Paman yang
harus menanggung semua akibatnya sendiri.Jangan
seret aku.”
Pakering Suramurda tidak menjawab, namun menelan
kata-kata keponakannya yang tearasa amat pahit di
tenggorokan.22
3.3.6. Semangat
Hal ini dibuktikan oleh kutipan di bawah ini:
“Baiklah,” ucap Ra Kembar. “Aku sangat menghargai
keterangan yang kamu jual kepadaku. Sebagaimana
saranmu, aku akan bertindak cepat. Akan aku kumpulkan
teman-temanku. Cukup hanya dengan mereka dan para anak
buahku, tempat yang kausebut itu akan bosah-baseh. Tak
perlu menunggu besok, malam ini juga akan kugempur
mereka yang berani coba-coba berniat makar itu. Akan
20
Ibid., h. 94. 21
Ibid., h. 505. 22
Ibid., h. 281.

57
kulihat bagaimana raut Gajah Mada setelah melihat sepak
terjangku”.23
4. Tokoh
Tokoh-tokoh yang digunakan oleh LKH tidak lain adalah tokoh-
tokoh yang sebagian memang pelaku sejarah Majapahit. Para tokoh fakta
sejarah tersebut ialah Jayanegara, keempat Ibu Ratu, kedua Sekar Kedaton,
suami para Sekar Kedaton, Arya Tadah selaku patih kerajaan Majapahit,
Prapanca atau Pancaksara, Gajah Mada, Ra Tanca, Ra Kembar, Gajah
Enggon, Nambi, Ranggalawe, para Darmaputra Winehsuka, dan Mahapati.
Semua ini LKH cantumkan tanpa mengubah nama asli. Alasannya adalah
bahwa ini sebuah novel yang mengambil fakta sebagai jalan cerita yang
untuk kemudian penulis bumbui dengan fiksi di setiap sisinya dan ingin
memberi efek nyata bagi para pembacanya.
Masih membahas tentang nama yang digunakan LKH, yang perlu
digarisbawahi adalah tidak semua tokoh yang dihadirkan dalam novel ini,
betapapun pentingnya peran tokoh itu, merupakan tokoh nyata yang ada
dalam catatan sejarah. Para tokoh fiktif tersebut adalah para anggota pasukan
Bhayangkara yang dalam novel ini sangat dielu-elukan, yakni Gagak
Bongol, Mahisa Kingkin, Macan Liwung, Riung Samudra, Wraha Kunjana,
Klabang Gendis, Lembang Laut, Arya Surapati, Kinasten, dan Dlapa Welah.
Jika diperhatikan, nama-nama yang digunakan pada tokoh-tokoh prajurit
tersebut adalah nama binatang yang sesuai dengan zaman tersebut, yakni
menggunakan nama binatang untuk menamai manusia. Penamaan manusia
dengan nama hewan ini membuktikan bahwa pada zaman dahulu, hewan
sangat dihormati. Hal ini dikarenakan hewan-hewan yang digunakan
23
Ibid., h. 377.

58
Sebagai nama manusia itu adalah hewan-hewan yang dianggap istimewa,
seperti lembu atau sapi menjadi tunggangan dewa dalam agama hindu.24
4.1. Tokoh Menurut Fungsinya
4.1.1. Utama: Gajah Mada
4.1.2. Figuran:Ibu Ratu Pradnya Paramita, Ibu Ratu Tribhuaneswari, Ibu
Ratu Narendraduhita, Arya Tadah, pasangan Gemuk Trutung,
Bramantya, Karpa, Murti, Banjar, Wilang, Dwarastha, Prabarasmi,
Sang Prajaka, Senopati Suryo Manduro, Senopati Panji Manduro,
para lurah pengikut Pakering Sumamurda, Rubaya, Arya Surapati,
Kinasten, dan Ki Sambi.
4.2. Tokoh Menurut Konflik yang Dibangun
4.2.1. Protagonis
Tokoh dalam novel ini yang termasuk ke dalam tokoh protagonis
adalah Gajah Mada.
4.2.2. Antagonis
Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam tokoh antagonis dalam
novel ini adalah Rangsang Kumuda, Pakering Suramurda, Nyai Ra
Tanca, Ra Kembar, dan Pradabhasu.
4.2.3. Tritagonis
Di dalam novel ini, yang termasuk ke dalam tokoh tritagonis
adalah Gayatri, Sri Gitarja, Dyah Wiyat, Raden Cakradara, Raden
Kudamerta, Gagak Bongol, Gajah Enggon, Macan Liwung,
24
Yusandi, Makna Nama Satwa pada Orang Tempo Doeloe,
http://www.wacananusantara.org/makna-nama-satwa-pada-orang-tempo-doeloe/. Diunduh pada
Kamis, 22 Januari 2015 pukul 17.35 WIB.

59
Jayabaya, dan Riung Samudra adalah tokoh-tokoh yang tergolong
ke dalam tokoh tritagonis dalam novel ini.
Hal yang menarik dari penggambaran tokoh menurut konflik
yang dibangun oleh tiap tokoh yang terlibat di sini adalah pada
tokoh antagonis yang terdiri dari lima tokoh, yakni Rangsang
Kumuda, Pakering Suramurda, Nyai Ra Tanca, Ra Kembar, dan
Pradabhasu. Kelimanya memiliki tujuan dan dasar pemikiran yang
bertolak belakang dan berusaha mencegah Gajah Mada untuk
melakukan usahanya tersebut. Namun, kelimanya memiliki motif
yang berbeda antara satu dengan yang lain.
4.3. Tokoh Menurut Wataknya
4.3.1. Bulat
Dalam novel sejarah ini, yang tergolong ke dalam tokoh bulat
adalah Ibu Ratu Gayatri, Dyah Menur, dan Dyah Wiyat.
4.3.2. Datar
Tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam tokoh datar adalah Raden
Kudamerta dan Raden Cakradara.
4.4. Ulasan Tokoh-Tokoh Dalam Novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara Karya
Langit Kresna Hariadi.
4.4.1. Gajah Mada
Mendengar nama Gajah Mada adalah sebuah jaminan untuk bayangan
kekuatan negara dan kebesaran wibawa yang dimiliki oleh seorang tokoh.
Tokoh yang satu inilah yang mampu mempersatukan Nusantara untuk
pertama kalinya. Tidak hanya itu, ia adalah seseorang yang pendapatnya
selalu dipertimbangkan oleh raja–raja yang pernah menjadikan dirinya patih
ataupun orang kepercayaan. Bukanlah tanpa alasan menjadikan Gajah Mada
sebagai orang kepercayaan.

60
Awalnya, pemuda yang berbadan kekar penuh otot-otot ini25
hanyalah
seorang prajurit dengan pangkat bekel. Bekel dalam KBBI berarti pamong
desa pada zaman dahulu (setingkat di bawah lurah), pengurus sawah milik
bangsawan pada saat raja-raja masih memerintah pulau Jawa. Namun, jika
dikaitkan dengan posisinya sebagai salah satu prajurit dari kesatuan
Bhayangkara, maka bekel di sini memiliki makna sebagai kepala pasukan
pengawal raja masa Majapahit. Kariernya dimulai saat kerajaannya diguncang
prahara oleh rombongan Ra Kuti yang melakukan makar dan membuatnya
harus pontang-panting menyelamatkan Jayanegara ke Badender. Di sanalah
pengabdiannya sangat tinggi dan dinilai oleh para keluarga kerajaan sebagai
seorang prajurit yang mengabdi tanpa pamrih. Oleh pihak kerajaan, ia
dianugerahi jabatan sebagai patih yang mendampingi Sri Gitarja mengurus
daerah Kahuripan dan tidak lama setelah itu ia juga ditugasi untuk menjadi
patih di Daha menemani Dyah Wiyat.
Diceritakan dalam novel ini, Gajah Mada merupakan seorang prajurit
gagah perkasa yang tidak ada tandingannya, baik dari segi fisik maupun cara
berpikirnya. Ia adalah seorang revolusioner di masanya. Ia mampu berpikir
jauh ke depan tanpa ada seorang pun yang tahu apa yang akan
direncanakannya sebelumnya. Matanya yang tajam menandakan bahwa
pikirannya sangat brilian dan cemerlang.26
Pemuda yang tanpa pamrih
mengabdikan dirinya untuk negara ini adalah seorang nasionalis terpuji, sama
dengan Pradhabasu yang tetap berbuat yang terbaik semampunya meskipun di
masa silam negaranya telah mengecewakannya.
Kembali ke Gajah Mada, prajurit ini memiliki kemantapan hati yang
kuat. Cara berbicaranya yang selalu to the point menjadi ciri khas yang
membuat ia dimaklumi oleh para keluarga kerajaan. Hal ini disebabkan
25
Ibid, h. 38 26
Diceritakan pada seri novel selanjutnya bahwa kekuasaan yang ia miliki bahkan melebihi
kekuasaan yang dimiliki oleh rajanya. Hal ini tercermin pada tragedi berdarah, perang Bubat, titik
kemunduran kejayaan Gajah Mada.

61
banyaknya jasa kepada negara yang ia sumbangkan dengan cuma-cuma dan
tentunya semua ucapannya masuk akal dan selalu menjadi solusi di kala
kemelut datang tanpa sebuah pemecahan.
Pun saat para Ibu Ratu sedang berunding untuk memutuskan siapa yang
pantas menggantikan Jayanegara, ia memaksa masuk untuk memberikan
pendapatnya dan dengan nada yang sangat percaya diri ia mengatakan, “Aku
wajib memberikan sumbang saranku, Paman.”27
. Ia patut mengajukan
permintaan untuk bisa hadir dalam rapat terbatas tersebut karena ia merasa
bahwa apapun yang akan terjadi di kerajaan tercintanya itu pada akhirnya
akan menjadi tanggung jawab berat pada dirinya.
“Dulu ketika makar yang dilakukan Ra Kuti, suaraku amat
didengar.Manakala urusannya ada hubungan dengan
perebutan kekuasaan, suaraku amat didengar. Dan
sekarang, di luar sana titik api dalam bara sekam itu
kembali menyala, bau perebutan kekuasaan dimulai lagi.
Adakah paman masih akan menghalangi aku menghadap
Para Ratu untuk menyampaikan pendapatku? Selama ini
tugasku hanya sebagai pemadam kebakaran, orang lain
yang bermain api tapi akulah yang bertugas memadamkan
kebakaran yang terjadi. Tak bisakah kali ini dibalik,
suaraku didengar sebelum kebakaran yang sebenarnya
terjadi?”28
Keluhan Gajah Mada tersebut memberi tahu pembaca bahwa dia adalah
seorang sosok yang dipercaya untuk memadamkan semua kekisruhan ataupun
kekacauan dan selalu saja apa yang ia padamkan adalah sesuatu yang belum
mampu dicegah dan beruntungnya mampu dihadapi dan ditumpasnya dengan
kecerdasan strategi yang digunakannya. Dengan pengalamannya yang telah
berkali-kali berhasil menuntaskan kekacauan di kerajaannya, ia merasa bahwa
untuk kali ini ia wajib diikutsertakan dalam diskusi siapa pengganti raja yang
telah mangkat tersebut. Hal ini dikarenakan ia merasakan ada sesuatu yang
27
Hariadi, Op. Cit., h. 70. 28
Ibid, h. 71

62
buruk akan terjadi setelah wafatnya raja mereka dan dibuktikannya dengan
ditemukannya pembunuhan di lingkungan istana setelah Jayanegara wafat. Ia
mencurigai berbarengannya kematian tersebut.
Peristiwa ini membuktikan bahwa pengaruh dan wibawa yang dimiliki
oleh Gajah Mada sangat besar hingga Arya Tadah, patih Majapahit, pun
tunduk dan ikut memberikan kekuasaan penuh terhadap Gajah Mada untuk
menyelesaikan semua permasalahan yang menimpa Majapahit sepeninggal
rajanya. Namun, posisi Gajah Mada laiknya seorang mandor yang hanya
memberikan arahan dan perintah serta tak luput dari penilaiannya yang
merendahkan orang. Memang, setelah mendapat samir dan lencana dari Ratu
sementara dan Patih Majapahit, secara langsung ia tak ubah laiknya Gayatri
dan Arya Tadah yang tiap titahnya harus dipatuhi. Namun yang terjadi adalah
ketika semuanya sudah terselesaikan, tercipta sebuah pandangan subjektif
bahwa yang berhasil menyelesaikannya adalah anak buahnya. Seperti halnya
kasus pembunuhan yang terjadi setelah Jayanegara wafat, ia hanya berprolog
dan menyerahkan semua tugas kepada Gajah Enggonuntuk membongkar
kasus tewasnya Panji Wiradapa.
“Aku serahkan penelusurannya padamu,” jawab Gajah
Mada. “Berpikirlah dengan rasa penasaran, Gajah Enggon.
Bahwa pada malam ini Tuanku Baginda Jayanegara tewas
terbunuh, ternyata pada malam yang sama, di dalam
lingkungan istana, terjadi sebuah pembunuhan yang lain.
Seseorang mati melalui pembunuhan pula. Masalahnya
yang mati adalah Ki Panji Wiradapa yang jejak jati dirinya
baru kita temukan belum sebulan yang lalu. Kesamaan
hari kematian itu, adakah hanya sebuah kebetulan atau ada
kaitannya, apabila kecurigaan itu bisa mengganggu para
Tuan Putri Ratu dalam sidang menentukan siapa yang
bakal ditunjuk menjadi raja menggantikan Tuanku
Baginda. Jangan sampai para Tuan Putri Ratu mengambil
pilihan yang salah. Sekali lagi, bukan anak-anaknya, yang

63
layak dipersoalkan, namun para calon suami mereka yang
harus dipelototi dengan teliti.”29
Sisi keras lain yang dimiliki oleh Gajah Mada adalah ia kerap kali
meremehkan bawahannya. Hal ini sering terjadi saat bawahannya tidak
memberikan jawaban sesuai harapannya dan atau ketika pola pikir
bawahannya tidak seperti dirinya sehingga ia harus menjabarkan maksud yang
ia inginkan agar bisa dipahami oleh bawahannya. Seperti yang ia lakukan
kepada Wraha Kunjana, seorang prajurit dengan pangkat paling rendah di
pasukan Majapahit.30
Ini menandakan betapa Gajah Mada merasa bahwa
dirinya lebih superior dari lainnya, dengan bukti tambahan ia merasa perlu
didengarkan pendapatnya saat sidang para Ibu Ratu. Sikap dan sifatnya yang
sombong ini disebabkan karena ia sadar betapa berpotensi dirinya serta
memang terbukti berhasil mengatasi semua permasalahan yang menimpa
kerajaannya. Tidak hanya kepada prajurit dengan pangkat yang paling rendah,
sikap meremehkan juga ia tunjukkan kepada Gajah Enggon, pimpinan
Bayangkara.31
4.4.2. Rangsang Kumuda
Rangsang Kumuda adalah nama lain dari Panji Wiradapa alias Ki
Brama Ratbumi Rajasa. Ia adalah seorang kaki tangan dari seorang
pengkhianat negara yang paling berbahaya selama kepemimpinan Jayanegara,
yakni Ramapati atau Mahapati. Orang ini memiliki hati yang sangat culas,
sama dengan pimpinannya. Ketika Mahapati dihukum mati oleh Jayanegara,
ia menghilang tanpa jejak.
“… kelak apabila semua mimpi telah tergapai, aku tidak
akan pernah melupakanmu. Apabila aku menjadi seorang
29
Ibid, h. 93-94 30
Ibid, h. 90 31
Ibid., h. 94.

64
patih dan itu merupakan batu lompatanku untuk bisa
menjadi seorang raja, akan aku bawa kau untuk selalu
berada di belakangku. Kau akan kuberi wilayah sehingga
kau bisa menjadi raja kecil di tempat itu.”32
Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa jika ia menjadi patih di
Wilwatikta, ia akan menggulingkan rajanya, yakni Raden Kudamerta, untuk
kemudian ia yang menduduki dampar itu. Hal yang sama bukan tidak
mungkin akan dilakukannya jika Mahapati atau Ramapati berhasil menjadi
penguasa Majapahit. Hal ini bisa dilihat dari melenyapnya sosok Ratbumi saat
pimpinannya dihukum mati. Jika ia adalah seorang abdi yang setia dan tidak
memiliki ambisi pribadi yang sama dengan Mahapati, ia akan berbelapati atas
matinya Mahapati di tangan Majapahit.
Panji Wiradapa yang kerap dipanggil dengan sebutan paman oleh Raden
Kudamerta juga tidak segan membunuh orang-orang yang ikut membantunya
mendapatkan takhta. Ia membunuh Rubaya, seorang kaki tangan yang sangat
ia andalkan untuk mencelakai Raden Kudamerta dengan tujuan menghasut
Raden Cakradara. Alasannya adalah jika Rubaya sampai tertangkap hidup-
hidup oleh Majapahit, identitas yang selama ini iasembunyikan akan
terungkap. Semua orang yang ia libatkan dalam rangkaian pembunuhan ini
akan ia lenyapkan demi menjaga siapa dirinya yang sesungguhnya. Untuk
menjaga rahasia ini tetap terjaga, ia telah membunuh tiga orang yang telah
membantunya. Ketiga orang itu ialah Lembang Laut, Arya Surapati, dan
Rubaya.
Kekejaman yang ia miliki tidak hanya berhenti pada orang-orang yang
secara tidak langsung membawanya ke puncak impian, tetapi juga kepada
lawannya, yaitu Pakering Suramurda. Paman kandung Raden Cakradara itu ia
bunuh dengan menancapkan anak panah tepat di dadanya saat ia akan
32
Ibid., h. 112.

65
membuka rahasia siapa orang yang bertanggung jawab atas matinya semua
pendukung Raden Kudamerta.
4.4.3. Pakering Suramurda
Pakering Suramurda adalah sesosok lelaki setengah baya yang memiliki
keinginan yang sama dengan Rangsang Kumuda. Jika Rangsang Kumuda
yang juga bernama Panji Wiradapa ini ingin kekuasaan sebagai raja diemban
oleh Raden Kudamerta, maka Pakering Suramurda ingin takhta kekuasaan
tertinggi jatuh kepada keponakan kandungnya, Raden Cakradara.
Pakering Suramurda tidaklah secermat Rangsang Kumuda dalam
menyiapkan strateginya. Itu karena ia memang yakin bahwa tahkta akan jatuh
ke tangan kemenakannya. Segala rencana jahat yang ia siapkan hanya untuk
berjaga-jaga bila kemungkinan terburuk terjadi.
Selain itu, dalam hal kecermatan dalam bertindak, tingkat kewaspadaan
dan tingkat penalaran akibat darisemua yang ia lakukan masih jauh di bawah
Rangsang Kumuda. Ia merencanakan tidak akan segan-segan menghabisi
nyawa pendukung bahkan nyawa Raden Kudamerta sekalipun. Hal ini
tentunya akan membuat seluruh mata istana tertuju pada Cakradara.
Permainan licik yang dilakoni pamannya itu langsung membuat Raden
Cakradara kecewa.
Jika dibandingkan dengan Rangsang Kumuda, apa yang dilakukan oleh
Pakering Suramurda untuk mendudukkan kemenakannya di kursi raja dapat
dipahami sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh orangtua untuk anaknya,
untuk kebahagiaan anaknya, bukan atas dasar nama ambisi pribadi. Orangtua
manapun akan melakukan hal terbaik dan sesulit apa pun untuk mendudukkan
anaknya di tempat yang terhormat.

66
4.4.4. Ra Kembar
Sebagai salah satu dari kelompok yang menentang kekuasaan raja, ia
pun memiliki bibit-bibit pemberontakan dalam dirinya meski kadarnya tidak
menggelegak seperti para Rakrian lainnya. Ia hanya berambisi mengalahkan
posisi serta peranan Gajah Mada dalam kerajaan. Dalam novel ini pula
diceritakan bahwa Ra Kembar meragukan kesetiaan Gajah Mada dalam hal
loyalitasnya terhadap negara. Anggapan tersebut dibuktikan pada kutipan d
bawah ini:
“Gajah Mada bisanya hanya menyalahkan orang lain,”
kata hati Ra Kembar. “Saat Ra Tanca membunuh Sang
Prabu di biliknya, bukankah ia berada di ruangan itu. Ia
yang mengawasi Ra Tanca memberikan pengobatan.
Artinya, ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan
rajanya, mengapa orang lain yang tidak bersalah harus
menanggung akibatnya. Lucu Gajah Mada.”33
Ra Kembar adalah representasi seorang prajurit yang haus pujian serta
jabatan. Ia ingin dihargai dan dihormati sebagaimana yang ia mimpikan, yakni
sebagai pembesar negara, bukan sebagai prajurit dengan pangkat rendah
seperti lurah. Apa pun yang ia lakukan adalah untuk mendapatkan pujian,
jabatan serta memulihkan nama baiknya.
Ra Kembar adalah salah satu dari Darmaputra, sama seperti Ra Kuti, Ra
Tanca, Ra Wedeng, Ra Banyak, Ra Yuyu, dan Ra Pangsa yang melakukan
makar pada 1319. Saat itu, Ra Kembar sedang ditugaskan ke luar kota
sehingga ia tidak ikut serta dalam pemberontakan yang menewaskan semua
anggota Rakrian kecuali Ra Tanca yang memilih bertobat. Dengan matinya
semua Rakrian yang ada tidak membuat orang lain menganggap bahwa Ra
Kembar tidak ada sangkutan apapun dan dinilai bersih dari segala macam
perbuatan buruk yang dilakukan oleh Rakrian lainnya. Ia tetap saja teman
pemberontak yang juga memiliki sifat dan sikap tidak jauh dari Rakrian
33
Ibid., h. 135.

67
lainnya meskipun memang ia tidak pernah terlibat langsung dalam
pemberontakan tersebut. Hal inilah yang membuatnya selalu dianggap remeh
oleh orang lain, selain karena ia memang memiliki perangai buruk.
“Aku mengenal dengan baik siapa kamu, Adi Kembar,”
kata Singa Darba. “Aku tahu ada yang kausembunyikan.
Omong kosong soal telik sandi ceritamu itu. Jangan kau
anggap seolah aku tidak mengenalmu.”34
Kutipan di atas merupakan salah satu pandangan orang lain yang
berseberangan dengan Ra Kembar. Bahkan, orang yang berada dalam satu
jalan dengannya, Nyai Ra Tanca, meremehkan kemampuan Ra Kembar. Hal
tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:
“… Sungguh, yang tidak aku mengerti, mengapa Gajah
Mada mengirim orang yang tidak memadai. Menugasi
Rakrian Kembar menyerbu Karang Watu, apa yang bisa
dilakukan Ra Kembar?”35
Semua anggapan remeh dan sebelah mata itulah yang membuat Ra
Kembar rendah diri dan mengincar sebuah jabatan agar nama baiknya kembali
dihargai oleh orang lain. Namun, usaha untuk mendapatkan nama baik tidak
disertai dengan perhitungan yang cermat selayaknya seorang prajurit yang
seharusnya terbiasa untuk berpikir jauh ke depan. Ra Kembar melewati satu
fase berpikir, yakni ia langsung memikirkan hasil indah yang akan ia
songsong jika hasil kerjanya membuahkan hasil sebaik yang ia angankan. Ia
terbuai dengan hasil yang akan ia dapatkan, yakni mendapat pujian dari para
Ibu Ratu dan kenaikan jabatan. Tanpa pikir panjang, ia mengajak kawan lurah
sesamanya untuk melancarkan serbuan tersebut tanpa terlebih dahulu
mempelajari berapa banyak kekuatan musuh dan medan yang akan dia hadapi.
Semua sifat buruk yang ia miliki diperparah dengan sikap pengecutnya yang
34
Ibid., h. 441. 35
Ibid., h. 454.

68
ia tunjukkan secara nyata kepada anak buahnya. Adegan tersebut terekam
pada kutipan di bawah ini:
Ra Kembar kebingungan.Nyalinya entah lenyap ke mana.
“Sembunyi,” perintah Ra Kembar kepada anak
buahnya.36
Sesaat sebelum Ra Kembar menyuruh anak buahnya bersembunyi, ia
diperintahkan oleh Lembu Pulung untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah
Bhayangkara lainnya setengah selesaikan bersama atasannya, Haryo Teleng
dan Panji Suryo Manduro. Namun, ia malah menjatuhkan perintah kepada
anak buahnya untuk bersembunyi. Sikap kepengecutan itulah yang
membuatnya kelak di kemudian hari tak berani menampakkan wajahnya di
hadapan Gajah Mada saat Rangsang Kumuda tertangkap.
Di sisi lain, di balik semua sikap dan sifat buruk yang dimilikinya,
tetaplah ia seorang prajurit yang menyadari bahwa semua perbuatannya itu
salah dan ia menyesalinya. Ia kecewa dengan dirinya sendiri yang tidak
berpikir panjang dalam ambisinya untuk mengalahkan Gajah Mada.
4.4.5. Pradhabasu
Pradhabasu adalah seorang mantan prajurit Bhayangkara yang sangat
lihai dalam hal telik sandi. Ia juga prajurit yang dekat dan dipercaya oleh
Gajah Mada. Pun ketika ia sudah tidak lagi berada dalam lingkungan istana
karena mengundurkan diri dari pasukan Bhayangkara atas nama balas dendam
dan rasa sakit terhadap putusan Jayanegara, ia tetap menjadi orang
kepercayaan Gajah Mada dengan cara tetap memberikan laporan mengenai
kehidupan dan keadaan di luar istana.
Tokoh ini menjadi salah satu tokoh antagonis dalam novel ini. Namun,
terdapat perbedaan antara Pradhabasu dengan tokoh antagonis lainnya.
36
Ibid., h. 465.

69
Kutipan dialog Gajah Mada di bawah ini mendorong Pradhabasu mengambil
sikap tersebut.
“… Apa yang sebaiknya aku lakukan terhadap perempuan
itu? Aku ingin ia pergi sejauh-jauhnya dari Raden
Kudamerta dan jangan pernah muncul lagi. Aku tidak
ingin ketenangan rumah tangga Rajadewi Maharajasa
terganggu.”37
Pernyataan yang dilontarkan oleh Gajah Mada itulah yang membuatnya
kali ini harus mengambil sikap berseberangan dengan mantan bekel ini. Gajah
Mada berpendapat bahwa kehadiran istri pertama Raden Kudamerta hanya
akan menjadikan malapetaka selanjutnya. Untuk itulah Gajah Mada menyuruh
Pradhabasu menyingkirkan kehadiran Dyah Menur. Kekhawatiran Gajah
Mada diperkuat sebuah peristiwa yakni ketika Dyah Wyat mendapatkan
sebuah kiriman berupa sekeranjang buah mangga yang di dalamnya
disembunyikan tiga ekor ular yang mematikan dari seorang wanita yang
menyamar menjadi lelaki. Kecurigaan Dyah Wyat dan Patih Daha pun
langsung menuju ke istri pertama Raden Kudamerta.
Namun, Pradhabasu memiliki pandangan lain mengenai hal itu. Dengan
membunuh Dyah Menur, masalah perebutan takhta kelak tidak akan
terselesaikan begitu saja. Memang benar jika Dyah Menur lenyap maka tidak
ada penghalang atau perusak keturunan wangsa Rajasa sebagai pemegang trah
kekuasaan. Namun, matinya Dyah Menur dalam rangka menjaga takhta akan
berdampak pada hal lain. Raden Kudamerta bisa saja tidak terima tindakan
Gajah Mada melenyapkan istri yang sangat dicintainya itu lalu menyimpan
dendam dan menuntut balas. Jika benar, maka pertumpahan darah tidak akan
pernah terselesaikan seperti tragedi kerajaan Singasari. Selain itu, alasan lain
mengapa ia tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gajah Mada adalah
37
Ibid., h. 366.

70
karena ia tahu betapa sakitnya kehilangan orang yang disayangi dan tidak
bersalah atas situasi yang terjadi.
Pradhabasu merasa tidak perlu melakukan perintah yang ditugaskan
kepada dirinya karena ia tahu jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut kecil
ini. Suatu hari nanti, ia akan menikahi wanita beranak satu itu sebagai kedok
untuk melindungi orang yang tidak bersalah serta memberikan kasih sayang
seorang ibu bagi kemenakannya yang cacat, Prajaka.38
4.4.6. Gayatri
Gayatri adalah seorang bangsawan wanita (anak raja dan istri raja) yang
tentunya sejak kecil bergelimang harta. Menjelang usia tuanya, ia bertekad
mengabdikan sisa hidupnya menjadi seorang biksuni. Menjadi seorang
biksuni tentunya harus siap melepas semua kehidupan duniawinya termasuk
harta, jabatan, dan segala apapun yang berkaitan dengan duniawi dan ia siap
dengan keputusannya. Membabat habis rambut hitam panjangnya hingga tak
bersisa adalah salah satu langkah yang ia siapkan untuk menjadi seorang
biksuni seutuhnya. Semua jalan pikiran dan emosi pun sudah ia tata
sedemikian rupa menyerupai para biksuni lainnya, yakni memandang semua
yang terjadi pada hidup ini sudah digariskan oleh takdir dan tidak terlalu larut
pada perasaan macam apa pun.
4.4.7. Dyah Wiyat
Dyah Wiyat atau Rajadewi Maharajasa adalah anak bungsu Gayatri
dengan Raden Wijaya. Ia memiliki kemauan yang keras, namun seketika
kemauannya mampu berubah karena hal-hal mendasar yang akan menyangkut
harga dirinya. Awalnya ia tidak mengincar kedudukan sebagai ratu karena ia
mafhum bila Sri Gitarja sebagai anak pertama yang akan diutamakan menjadi
38
Lihat Gajah Mada seri keempat

71
seorang ratu betapapun dirinya lebih berpotensi ketimbang kakaknya itu.
Ketika ia tahu bahwa suaminya ternyata memiliki istri lain dan ia tahu ia
dinikahi hanya untuk dijadikan alat mencapai kekuasaan oleh suaminya, ia
malah bertekad akan menjadi ratu untuk menunjukkan kepada suami dan para
pendukungnya bahwa ia mampu menjadi ratu tunggal tanpa sedikitpun
memberi ruang kepada suaminya untuk menumpang kejayaan. Dalam
pandangan Raden Kudamerta dan para pendukungnya, dengan menikahi
seorang calon ratu, maka dengan sendirinya suami tersebut akan menjadi raja
sedangkan kekuatan raja berada jauh di atas ratu atau dengan kata lain
kedudukan ratu tak ubah laiknya seorang permaisuri.39
Namun, dengan
menjadi ratu Majapahit, ia akan bertindak selaku Ratu Shima yang mampu
berdiri seorang diri tanpa seorang pendamping. Ia akan menjadi ratu yang
tegas dan tidak akan membagi kekuasaannya dengan siapapun termasuk
suaminya sendiri.
Hal yang perlu dicermati di sini adalah ambisi Dyah Wiyat menjadi ratu
memang didasari oleh rasa kecewanya karena diremehkan dan dilecehkan
oleh suaminya dengan menempatkannya menjadi istri kedua. Namun, Dyah
Wiyat bukanlah seorang tuan putri yang tidak mampu berdiri sendiri dan
menunjukkan kemampuan dirinya. Ia yakin dapat menjadi ratu hebat karena ia
sadar dengan kemampuannya yang berada di atas kakaknya. Juga ia mampu
berdiri sendiri dan bertindak tegas ketimbang kakaknya yang kurang mandiri.
Berbicara mengenai tingginya tingkat ketergantungan Sri Gitarja, ini juga
yang menjadi pokok pertimbangan Dyah Wiyat. Jika Sri Gitarja yang menjadi
ratu, maka ditakutkan beban dan tampuk kekuasaan akan diserahkan ke
suaminya dan dengan segera para pendukung Cakradara akan meraja di istana.
Hal yang tidak baik bagi para pendukung Kudamerta.
39
Terdapat perbedaan pengertian yang mendasar tentang arti kata ratu dengan permaisuri.
Ratu menurut KBBI tahun 2008 edisi keempat halaman 1147 berarti raja perempuan
Permaisuri menurut KBBI tahun 2008 edisi keempat halaman 1060 berarti istri raja

72
Dengan alasan semacam itulah, ia mengubah pendiriannya untuk menjadi
ratu.
Juga, keputusannya menerima Dyah Menur hidup seatap dengannya.
Jauh di lubuk hatinya, ia tidak menginginkan suaminya memiliki istri lain
selain dirinya meskipun ia tidak mencintai Kudamerta. Namun, ia begitu tahu
persis rasanya menjadi orang yang terpisah dari orang yang dicintai karena
keadaan. Ia memilih menerima Dyah Menur mendampingi Kumaderta di
istana tanpa syarat apa pun dan tanpa sedikit pun rasa takut pada takhta, kasih
sayang, dan cinta suaminya. Sama seperti Pradhabasu, ia tidak ingin
dilingkupi oleh lingkaran dendam dalam hidupnya.
4.4.8. Raden Kudamerta
Raden Kudamerta atau Abiseka Sri Wijaya Rajasa Sang Apanji
Wahninghyun alias Bre Wengker Wijata Rajasa Hyang Parameswara adalah
seorang bangsawan yang mewarisi wilayah Pamotan. Ia adalah seorang
pemuda yang gagah perkasa, tampan, dan pandai dalam adu berlari. Lelaki
yang juga suami dari Dyah Menur dan telah menjadi seorang ayah dari
seorang anak lelaki ini sebenarnya tidak menginginkan takhta Majapahit
sebagaimana yang sangat diinginkan oleh pendukungnya. Tak ada sedikitpun
keinginan untuk menjadi orang nomor satu di kerajaan besar tersebut.
Baginya, yang terpenting adalah keutuhan rumah tangganya dengan Dyah
Menur, istri yang sangat ia cintai, yang hancur lebur karena impian dari
pendukungnya itu.
Raden Kudamerta dalam hal ini telah secara langsung menjadi alat bagi
Ratbumi, seorang tangan kanan Mahapati yang dihukum mati oleh Jayanegara
karena telah berusaha merebut takhta dari pemiliknya yang sah. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya, yang memiliki ambisi untuk menjadi seorang
raja adalah Panji Wiradapa alias Rangsang Kumuda. Salah satu cara agar
impiannya berhasil adalah dengan memisahkan pasangan suami istri tersebut

73
untuk melanggengkan pernikahan yang terjalin antara Dyah Wiyat dengan
Raden Kudamerta.
“Aku minta maaf, Dyah Wiyat. Aku tak berniat
menyembunyikan hal itu. Aku bahkan ingin meluruskan
hal ini sejak awal, tetapi aku tidak punya pilihan,” jawab
Raden Kudamerta.40
Hal yang perlu diperhatikan dalam kutipan di atas adalah pernyataan
Raden Kudamerta, “tetapi aku tak punya pilihan lain”. Di sini dapat dilihat
bahwa sebenarnya Kudamerta adalah seorang lelaki yang berada di bawah
tekanan sehingga ia tak punya kuasa untuk menolaknya. Keadaan ini
diperparah oleh ketidakmampuannya menyatakan sikap secara jantan untuk
memilih nasibnya sendiri sepahit apapun hasilnya. Ia bisa saja menolak
perjodohan tersebut dan menyelamatkan perkawinan pertamanya apapun
rintangannya. Memang benar ia tidak silau oleh kekuasaan yang sebentar lagi
mungkin akan digenggamnya, tetap saja ia tak punya kekuatan hati untuk
memberontak sesuatu yang salah disekitarnya. Jelas ia tahu apa yang
direncanakan oleh pendukungnya, Panji Wiradapa, namun ia dengan sengaja
juga membiarkan dirinya masuk ke dalam lingkaran tersebut yang bisa jadi
akan menempatkan dirinya sebagai tersangka.
Bukti kuat untuk menunjukkan bahwa ia seorang lelaki pengecut adalah
ketika ia ditanya oleh Gayatri mengenai keadaannya yang telah beristri
sebelum dinikahkan oleh anak bungsunya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan
di bawah ini:
“Hamba belum pernah mengawini siapa pun Tuan Putri,”
jawab Kudamerta dengan suara amat tegas.41
40
Ibid., h. 206. 41
Ibid., h. 498.

74
5. Gaya Bahasa
5.1. Gaya bahasa
Bukan tanpa alasan LKH banyak menggunakan gaya bahasa. Jika
diperhatikan, dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa personifikasi.
Penggunaan gaya bahasa perbandingan yang satu ini banyak dipakai pada
bagian narasi, bukan pada bagian dialog tokoh. Alasannya adalah tokoh-tokoh
yang bermain dalam novel ini bukanlah para tokoh yang senang pada gaya
bicara yang indah dan berbunga-bunga. Latar tempat dan sosial dalam novel
ini sangat menuntut kelugasan, kejelasan, serta keefektifan tiap kalimat yang
diucapkan oleh semua tokoh. Gaya bahasa yang berbunga-bunga penuh
pengandaian atau penuh pembandingan dengan hal lain dalam tiap ucapannya
tidaklah tepat digunakan mengingat hampir semua yang berperan di dalam
novel ini adalah para tokoh militer dan pejabat negara, termasuk kedua Sekar
Kedaton.
Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para tokoh dalam novel ini adalah
kalimat efektif. Tidak ada multitafsir dalam tiap dialognya. Bayangkan jika
dialog yang diucapkan oleh Gajah Mada, misalnya, mengandung makna yang
multitafsir. Bisa jadi semua perintah-perintah yang diucapkan oleh Patih Daha
itu akan diterjemahkan berbeda-beda oleh bawahannya. Kalau pun ada, gaya
bahasa yang digunakan LKH dalam dialog-dialog para tokohnya hanyalah
gaya bahasa retoris dan antonomasia saja. Retoris bisa digunakan dalam
dialog sebagai penekanan maksud si pembicara kepada lawan bicaranya,
seperti pada kalimat, “Rupanya benar peringatan yang kauberikan, Gajah
Mada?” ucap Gayatri.42
Konteks kalimat retoris ini diucapkan oleh Gayatri
setelah sebelumnya Gajah Mada memberikan peringatan kepada ratu
sementara Majapahit itu untuk tidak memberikan sambutan saat pembakaran
jenazah Jayanegara karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan benar
42
Ibid., h. 167.

75
adanya. Kudamerta menjadi sasaran bidik pisau terbang oleh Rubaya. Maksud
kalimat retoris ini adalah membenarkan peringatan Gajah Mada sekaligus
berterima kasih telah diperingatkan.
Juga, dalam dialog banyak terdapat gaya bahasa antonomasia yang
umumnya digunakan saat seseorang menghadap keluarga raja, seperti yang
terdapat dalam kalimat, “Sembah dan bakti hamba, Tuan Putri Biksuni,”
jawab Pradhabasu.43
Kalimat ini digunakan saat seseorang yang derajatnya
lebih rendah berbicara dengan sang Ratu. Alih-alih menyebut nama asli sang
ratu, Ratu Gayatri, Pradhabasu memanggilnya dengan sapaan lain. Gaya
bahasa antonomasia yang juga terdapat pada narasi ini digunakan oleh LKH
sebagai variasi yang bertujuan untuk menambah wawasan pembaca juga
meminimalisir kebosanan yang kerap dialami pembaca.
5.2. Diksi
LKH yang juga berdarah Jawa banyak menggunakan campur kode baik dalam
narasi maupun dialog. Hal ini disebabkan oleh latar tempat yang digunakan
pengarang adalah sebuah kerajaan Majapahit yang kita tahu berpusat di wilayah Jawa
Timur. Penggunaan bahasa Jawa Kuno dalam novel ini untuk mendukung latar waktu
yang digunakan, yakni pada zaman Majapahit. Namun, pembaca tidak akan
dipusingkan dengan istilah-istilah jawa yang digunakan, terlebih pembaca di luar
suku jawa karena LKH memberikan arti kata dari bahasa Jawa itu di dalam catatan
kaki (daftar diksi dalam bahasa Jawa terlampir).
43
Ibid., h. 168.

76
6. Alur
Secara umum, novel ini menggunakan alur maju. LKH, lewat Pancaksara
sebagai penceritanya memulai kisah ini pada situasi menegangkan saat
Jayanegara diracun Ra Tanca. Adapun skema alur dari novel ini adalah sebagai
berikut:
6.1. Pengenalan
Kisah ini dimulai dengan cerita bahwa sang raja Majapahit
kedua, Jayanegara sakit. Dikabarkan bahwa ia menderita sakit yang
terlampau parah. Ada yang mengatakan hanya sakit bisul dan
sebagainya. Intinya bukan jenis penyakit yang membahayakan jiwa sang
Prabu.
Untuk menyembuhkan penyakit Kalagemet itu, pihak kerajaan
memanggil Ra Tanca, seorang pemberontak yang pernah melakukan
makar bersama para rakrian lainnya, untuk mengobati sang raja karena
keahliannya di bidang pengobatan.
Kematian Jayanegara dengan tiba-tiba dan tidak meninggalkan
pewaris takhta kecuali dua orang saudari tirinya itu kontan
menimbulkan pertanyaan mendasar, siapa yang akan menjadi
penggantinya. Di belakang kedua Sekar Kedaton terdapat calon suami
masing-masing yang tentunya diboncengi oleh pendukungnya yang haus
kekuasaan dan saling menempatkan Raden Cakradara dan Raden
Kudamerta di dampar kekuasaan.
6.2. Konflik
Ketegangan kisah ini diawali dengan terbunuhnya Jayanegara
oleh Ra Tanca menggunakan racun sekali teguk. Selama ini Jayanegara
bagai memiliki banyak nyawa karena telah berhasil selamat dari
berbagai upaya makar, seperti Makar Ra Kuti, Makar Nambi, dan

77
Mahapati. Namun, kali ini hanya sekali teguk, Ra Tanca berhasil
menuntaskan dendam lama Ra Kuti bahkan di jarak terdekat dengan
Gajah Mada sekali pun. Pembalasan dendam itu tentu harus dibayar
dengan harga setimpal, yaitu nyawanya sendiri.
Pertanyaan tersebut disusul oleh sebuah kenyataan telak, bahwa
para pendukung Raden Kudamerta satu persatu dibasmi oleh pihak yang
belum dikenal hingga akhirnya Raden Kudamerta sendiri menjadi titik
sasaran selanjutnya. Semua pembunuhan dan percobaan pembunuhan
terhadap suami Dyah Wiyat itu kontan saja menempatkan Raden
Cakradara sebagai tertuduh tunggal. Seperti yang telah diketahui, Raden
Cakradara merupakan saingan berat bagi Raden Kudamerta.
6.3. Klimaks
Puncak kekacauan kisah ini adalah ketika senjata tajam berani
menyentuh anggota keluarga raja secara terang-terangan di depan
umum. Adalah Raden Kudamerta yang terkena lemparan pisau dari
jarak jauh yang dilemparkan oleh Rubaya atas suruhan Rangsang
Kumuda. Dada Raden Kudamerta berdarah dan beruntung tidak sampai
merenggut nyawanya. Hal ini tentu saja merupakan percobaan
pembunuhan setelah sebelumnya banyak pendukung Kudamerta yang
berjatuhan nyawanya.
Pembunuhan demi pembunuhan yang terjadi atas para
pendukung Raden Kudamerta mengantarkan Gajah Mada berhadapan
langsung dengan Rangsang Kumuda, otak di balik semua pembunuhan
dan usaha penjarahan takhta ini. Rangsang Kumuda yang disinyalir
sebagai paman Raden Cakradara atau Pakering Suramurda ini awalnya
sedang mencegat seorang wanita yang tak lain adalah istri pertama
Raden Kudamerta yang hendak melarikan diri ke kotaraja di sebuah
ladang jagung. Kalau sampai wanita itu sampai di kotaraja, maka semua

78
usahanya sia-sia. Namun, informasi itu langsung didengar oleh Gajah
Mada. Oleh karena sebuah kesalahan kecil, suara kentut anak buah
Rangsang Kumuda, terjadi pertempuran tak terelakkan. Dalam
pertempuran itu Rangsang Kumuda berhasil lolos setelah sebelumnya
dengan sukses membuat pingsan pimpinan Bhayangkara, Gajah Enggon.
6.4. Leraian
Ketegangan cerita ini sedikit menurun kadarnya saat Pakering
Suramurda yang dicurigai oleh Gajah Mada sebagai dalang semua
kerusuhan di lingkungan istana ini terbunuh. Pakering Suramurda yang
tak lain adalah paman kandung dari Raden Cakradara ini terbunuh oleh
panahan seseorang yang tak diketahui jati dirinya ketika sedang
melakukan perbincangan dengan kemenakannya.
Gajah Mada yang sementara menggantikan posisi Gajah Enggon
mendapat surat kaleng dari seseorang berjubah putih dan berkuda putih
dengan nama samaran Bagaskara Manjer Kawuryan. Dalam surat itu, si
misterius memberitahu bahwa di Padas Payung akan terjadi pertemuan
antara Raden Cakradara dengan Pakering Suramurda.
Lewat pertemuan itu, Gajah Mada dan Raden Kudamerta yang
begitu kecewa sejak percobaan pembunuhan terhadap dirinya dan
beberapa pendukungnya itu menemui sedikit titik terang. Raden
Cakradara tidak terlibat dalam pembunuhan itu dan ia sendiri menentang
tindakan keji tanpa perhitungan yang dilakukan pamannya. Namun
ternyata, pamannya mengaku bahwa semua pembunuhan yang terjadi itu
bukanlah prakarsanya. Tentu saja Cakradara tidak percaya dan berniat
membunuhnya ketika harga dirinya diinjak-injak oleh paman
kandungnya itu. Namun, niat Cakradara tidak terwujud karena
pamannya dibunuh terlebih dahulu oleh seseorang tak dikenal dengan
memanah tepat di jantungnya.

79
6.5. Penyelesaian
Gajah Mada menganggap Rangsang Kumuda telah mati karena
dia tak lain adalah Pakering Suramurda. Namun, sebuah percobaan
pembunuhan terhadap Dyah Menur dipasar, membuat Gajah Mada harus
terbelalak. Pradhabasu dan Bagaskara Manjer Kawuryan berhasil
membekuk pelaku percobaan pembunuhan itu dan menghadapkannya di
depan Gajah Mada. Tak disangka oleh siapa pun, Rangsang Kumuda,
otak semua pembunuhan terhadap pendukung Raden Kudamerta dan
percobaan pembunuhan terhadap Raden Kudamerta itu adalah Panji
Wiradapa alias Ratbumi, tangan kanan Mahapati. Tentu saja Raden
Kudamerta sangat terkejut karena beberapa hari yang lalu, ia mendapati
tubuh pamannya itu hangus dibakar orang lain.
Ternyata, semua ini adalah intrik untuk menjatuhkan nama baik
Raden Cakradara dengan cara memfitnahnya dan usaha Rangsang
Kumuda berhasil membuat Gajah Mada berpikir ke arah sana. Hal ini
dibuktikan ketika Gajah Mada mendatangi suami Sri Gitarja untuk
diinterogasi.
Selain alur utama dalam novel ini, terdapat juga tiga alur
bawahan lain yang turut menyemarakkan cerita ini. Ada beberapa
sekuen yang saling berhubungan dengan tali simpul lain.
a. Alur Utama
Alur utama yang disajikan LKH ini bercerita tentang perebutan
kekuasaan yang dilakukan oleh Panji Wiradapa. Panji Wiradapa yang
kemudian berganti nama menjadi Rangsang Kumuda ini adalah seorang
penjahat besar yang sempat membuat onar di Majapahit dengan kasus
yang sama. Kini ia kembali lagi dengan nama baru untuk merebut takhta
Majapahit dan menjadi raja di Wilwatikta lewat tangan Raden
Kudamerta.

80
Berikut disajikan skema alur utama yang secara garis besar
menggunakan alur maju.
1. Pengenalan: Jayanegara sakit
1.1. Ra Tanca diminta untuk mengobati Jayanegara yang sedang sakit.
1.2. Alih-alih membuat racikan obat untuk sang raja, Ra Tanca malah
meracik racun.
1.3. Jayanegara meminum racun buatan Ra Tanca yang disangkanya obat.
2. Konflik: Jayanegara terbunuh
2.1. Ra Tanca dibunuh oleh Gajah Mada setelah kedapatan meracun raja.
2.2. Pihak istana bingung siapa yang akan naik menjadi raja.
2.3. Panji Wiradapa menghasut Raden Kudamerta agar mau mengusahakan
takhta kerajaan bisa jatuh ke tangannya. Di saat yang sama, Pakering
Suramurda juga menyiapkan Raden Cakradara untuk menjadi raja
karena raden inilah yang memiliki peluang besar menjadi raja dengan
menikahi anak pertama mendiang Raden Wijaya.
2.4. Rangsang Kumuda membunuh seorang prajurit Raden Kudamerta dan
membunuh seorang Bhayangkara untuk memulai aksinya.
2.5. Pakering Suramurda atau Panji Wiradapa “membunuh” dirinya sendiri
untuk memulai fitnahnya kepada Raden Cakradara.
3. Klimaks: Dada Raden Kudamerta dilempar pisau oleh Rubaya
3.1. Rangsang Kumuda menyandera istri pertama Raden Kudamerta
3.2. Terjadi kontak fisik antara pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh
Gajah Mada dengan pasukan Rangsang Kumuda secara tidak senagaja.
3.3. Gajah Enggon, yang mendampingi Gajah Mada saat penyerangan
terkena lemparan batu dari Rangsang Kumuda dan akhirnya pingsan
berkepanjangan.
4. Antiklimaks: Pakering Suramurda terbunuh
4.1. Gajah Mada mengira bhwa Rangsang Kumuda adalah Pakering
Suramurda yang terbunuh itu.

81
4.2. Gajah Enggon yang telah sadar dari pingsannya membantu Pradhabasu
membongkar semua kekacauan ini.
5. Penyelesaian: Rangsang Kumuda berhasil diringkus oleh Pradhabasu
dan Gajah Enggon.
Novel ini tidak hanya memiliki alur utama yang berkisah tentang
pengungkapan pembunuhan yang dilakukan oleh Rangsang Kumuda,
tapi juga berisikan tentang kisah-kisah yang berada di luar jalur
perebutan takhta sama sekali. Dalam novel setebal 506 halaman ini, titik
skema tiap alurnya saling bertemu satu sama lain.
Alur bawahan yang pertama adalah kisah cinta segitiga antara
Raden Kudamerta dengan kedua istrinya, yakni Dyah Wiyat dengan
Dyah Menur. Alur bawahan kedua adalah kisah perseteruan antara
Gagak Bongol dengan Pradhabasu. Terakhir, alur bawahan tentang
kecemburuan seorang prajurit yang bernama Ra Kembar terhadap Gajah
Mada.
Ketiga cerita yang berhubungan langsung ini akan mempengaruhi
jalannya cerita utama bila ketiganya dihilangkan begitu saja. Namun,
cerita ini akan bermuara pada tahap penyelesaian yang sama atau
dengan kata lain, ketiga cerita sampingan ini akan terselesaikan seiring
dengan selesainya cerita utama novel ini.
Alur bawahan antara Raden Kudamerta dengan kedua istrinya
1. Pengenalan: Dyah Wiyat dan Kudamerta tidak berbahagia dengan
pernikahan yang mereka jalani.
1.1. Kudamerta dipergoki oleh Gajah Mada yang sedang melakukan
penelusuran tentang kira-kira siapa yang membunuh Panji Wiradapa
ketika ia baru pulang mencari istri pertamanya, Dyah Menur.

82
1.2. Setelah menjelaskan apa hubungan yang terjadi antara dirinya dengan
Panji Wiradapa, terpaksa ia juga harus mengakui bahwa ini telah
memiliki istri sebelum dinikahkan dengan Dyah Wiyat.
2. Konflik: Dyah Wiyat tahu bahwa suaminya telah beristri sebelum
mereka menikah.
2.1. Dyah Wiyat marah besar setelah tahu bahwa ia dimadu.
2.2. Dyah Wiyat yang kesal terhadap suaminya memutuskan mengajukan
diri kepada Gayetri untuk menjadi raja Majapahit.
2.3. Dyah Wiyat bertambah kesal dan cemburu ketika ia menerima kiriman
ular yang dapat membunuhnya dan mengira kiriman tersebut berasal
dari istri pertama Kudamerta. Padahal, ular itu kiriman dari istri Ra
Tanca yang cemburu terhadap dirinya.
2.4. Dyah Menur yang dilindungi keberadaannya oleh Pradhabasu dititipkan
kepada seorang emban di istana Dyah Wiyat. Maka jadilah istri pertama
Kudamerta itu menyamar menjadi seeorang emban di sana dengan
mengunakan nama samaran Sekar Tanjung.
2.5. Dyah Wiyat menyukai Sekar Tanjung.
3. Klimaks:Kudamerta menentukan sikap dengan berkata bahwa ia belum
pernah menikah sebelumnya.
3.1. Dyah Wiyat kaget mendengar pernyataan itu.
3.2. Dyah Menur yang tahu sikap macam apa yang diambil suaminya
memutuskan untuk pergi dari istana dan melupakannya.
3.3. Dyah Wiyat tahu jati diri emban yang dia sukai itu.
3.4. Setelah mengetahui sifat baik yang dimiliki Dyah Menur, Dyah Wiyat
memutuskan untuk menerima madunya tersebut dalam istana.
4. Antiklimaks: Dyah Wiyat menahan Dyah Menur pergi dari istana.
4.1. Dyah Wiyat mengatakan bahwa ia tidak keberatan berbagi suami
dengan Menur.

83
4.2. Dyah Menur terharu atas sikap Wiyat.
4.3. Dyah Menur tetap pada pendiriannya.
5. Penyelesaian: Dyah Menur memutuskan untuk pergi meninggalkan
istana bersama Pradhabasu.
Alur utama dengan alur bawahan yang pertama ini bertemu di titik
sekuen saat Gajah Mada melakukan interogasi kepada Kudamerta
tentang pembunuhan Panji Wiradapa. Dalam alur utama, terdapat
sekuen yang menceritakan Gajah Mada mulai mengadakan interogasi
terhadap Kudamerta untuk mengetahui simpul hubungan antara suami
Dyah Wyat itu dengan Panji Wiradapa juga untuk mengetahui siapa di
balik penyerangan terhadap Raden Kudamerta.
Pertemuan kedua alur ini juga terjadi pada titik sekuen ketika Gajah
Enggon berhasil mengungkap siapa sebenarnya Rangsang Kumuda.
Setelah Kudamerta dibuat terkejut dengan kenyataan bahwa biang
keladi semua kekacauan di Majapahit setelah matinya Jayanegara adalah
Panji Wiradapa, ia dibuat kaget dengan pertanyaan yang dilontarkan
oleh Gayatri mengenai isu pernikahannya sebelum menikah dengan
Dyah Wiyat. Dengan terungkapnya siapa sebenarnya Rangsang
Kumuda, selesai pula drama cinta segitiga Raden Kudamerta.
Alur bawahan antara Gagak Bongol dengan Pradhabasu
1. Pengenalan: Pradhabasu menolak tawaran Gayatri untuk kembali ke
pasukan Bhayangkara.
1.1. Pradhabasu tidak bisa melupakan rasa sakit hatinya kepada Gagak
Bongol.
1.2. Kesalahan Gagak Bongol telah menyebabkan perkembangan mental
Prajaka, keponakan Pradhabasu tidak normal.
1.3. Gagak Bongol meminta diadili kembali karena merasa bersalah.

84
2. Konflik: Pradhabasu meminta Gagak Bongol mengasuh Prajaka sebagai
tuntutannya.
2.1. Gagak Bongol terkejut dengan tuntutan tersebut.
2.2. Prajaka diajak masuk ke ruangan oleh Pradhabasu.
2.3. Seluruh orang di ruangan itu tahu keadaan Prajaka yang sebenarnya.
2.4. Gagak Bongol menyetujui tuntutan tersebut.
3. Klimaks: Pradhabasu langsung meninggalkan Prajaka di tangan Gagak
Bongol.
3.1. Pradhabasu melanjutkan tugasnya untuk mengungkap semua kekacauan
di istana saat itu.
3.2. Pradhabasu merindukan Sang Prajaka saat melihat kedekatan antara
Gagak Bongol dengan keponakannya itu.
3.3. Pradhabasu telah menyelesaikan tugasnya.
4. Antiklimaks: Pradhabasu mengambil kembali hak asuh Prajaka dan
pergi dari istana bersama Dyah Menur.
4.1. Gagak Bongol merasa kehilangan Prajaka.
5. Penyelesaian: Pradhabasu telah memaafkan Gagak Bongol.
Pertemuan alur utama dengan alur bawahan kedua ini terjadi pada
titik klimaks di alur utama yang menceritakan tentang upaya
pembunuhan terhadap Raden Kudamerta. Jadi, dengan kata lain, sekuen
awal menuju skema pengenalan di alur bawahan ini merupakan klimaks
bagi alur utama kisahan itu. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa
betapa plot yang dibangun oleh LKH sangat kompleks sehingga antara
sekuen satu dengan sekuen lainnya, bahkan antara sekuen dengan
tahapan di alur lain saling berkaitan.
Tidak hanya itu, tahapan antiklimaks pada alur bawahan kedua ini
beriringan dengan tahap penyelesaian pada alur bawahan yang pertama,

85
yakni ketika Dyah Menur memutuskan pergi dari istana bersama dengan
Pradhabasu.
Alur bawahan ketiga tentang kecemburuan Ra Kembar
1. Pengenalan: Ra Kembar merasa Gajah Mada terlalu cepat menyalahkan
orang lain.
1.1. Ra Kembar yang juga kawan dari Ra Tanca memendam kecemburuan
kepada Gajah Mada.
1.2. Kembar ingin menyaingi Gajah Mada.
2. Konflik: Ra Kembar mendapat informasi bahwa di Karang Watu
terdapat rencana makar.
2.1. Ra Kembar merasa inilah waktu yang tepat untuk menyaingi Gajah
Mada.
2.2. Ra Kembar mengumpulkan pasukan.
2.3. Ra Kembar mengajak Ajar Langse dan Singa Darba untuk berkomplot.
2.4. Singa Darba menolak ikut dan Ajar Langse yang setuju bergabung
berusaha membunuh Gajah Enggon untuk memuluskan niat Ra Kembar
mencapai tujuannya.
3. Klimaks: Ra Kembar menyerang Karang Watu tanpa ada izin dari
atasannya.
3.1. Ra Kembar terbuai dengan khayalan kemenangan yang akan diraihnya.
3.2. Ra Kembar kurang perhitungan.
4. Antiklimaks: Pasukan Ra Kembar tertangkap oleh pasukan makar.
4.1. Ra Kembar ditertawakan oleh Panji Rukmamurti, pimpinan makar itu.
4.2. Panji Rukmamurti menyadarkan bahwa Ra Kembar bukanlah tandingan
memadai bagi Gajah Mada.
5. Penyelesaian:Ra Kembar mengakui kekalahannya.

86
Pada alur bawahan ketiga ini, tidak terjadi pertemuan dengan alur
lain seperti yang terjadi pada alur-alur lainnya. Bahkan, yang terjadi
pada alur bawahan ketiga ini hanyalah persinggungan dengan alur
utama. Sebagai contoh kasus, sekuen pertama pada alur ini
bersinggungan dengan kejadian Jayanegara mati yang merupakan
konflik dalam alur utama. Juga, sekuen ketujuh di alur ini
bersinggungan dengan sekuen yang menceritakan pingsannya Gajah
Enggon di alur utama. Hal ini bisa terjadi karena cerita pada alur
bawahan ini tidak berkaitan erat dengan alur bawahan lainnya sehingga
apabila alur tentang kecemburuan Ra Kembar terhadap Gajah Mada ini
dihilangkan begitu saja, tidak akan mempengaruhi jalan cerita di alur
utama. Berbeda sekali dengan kedua alur bawahan lainnya yang menjadi
sebab akibat pada alur utama.
Meskipun hadirnya alur tentang Ra kembar ini tidak begitu penting,
lewat Ra Kembarlah kita bisa mengetahui bahwa tidak semua prajurit
memiliki kekaguman terhadap Gajah Mada. Ra Kembar pulalah yang
mengantarkan pembaca kepada sebuah pendapat beberapa sejarawan
yang mengatakan bahwa sebenarnya Gajah Madalah yang
merencanakan kematian Jayanegara (lihat analisis intrinsik bagian
penokohan). Secara implisit, LKH menempatkan Ra Kembar sebagai
alat bagi pengarang untuk mengantarkan sudut pandang sejarawan.
Ketiga alur bawahan ini saling bertemu, baik dengan alur bawahan
lainnya maupun dengan alur utama (meskipun yang tejadi pada alur
bawahan yang ketiga hanyalah sebuah persinggungan). Skema-skema
alur, baik alur utama maupun alur bawahan, saling terkait meskipun
keempatnya memiliki sajian alurnya masing-masing. Menariknya,
meskipun ketiga alur bawahan dimulai dari titik skema alur, ketiganya
mengakhiri ceritanya tepat pada titik penyelesesaian alur utama.

87
Bahkan, titik penyelesaian alur bawahan kisah cinta segitiga Raden
Kudamerta dan alur bawahan Pradhabasu berhenti pada titik yang sama.
Meskipun keempat alur yang ada dalam novel ini menceritakan hal
yang berbeda, pada kenyataannya keempatnya disatukan dalam satu
tema besar, yakni perebutan kekuasaan. Pada alur bawahan pertama,
masalah rumah tangga Raden Kudamerta dengan kedua istrinya dipicu
oleh keserakahan Rangsang Kumuda untuk mendapatkan takhta. Demi
tujuan itulah, ikatan pernikahan yang seharusnya dijalani dengan syahdu
dan menjadi sebuah fase kehidupan yang membahagiakan berubah
menjadi neraka. Pelecehan terhadap anak raja pun tak terhidarkan, Dyah
Wiyat ditempatkan menjadi istri kedua.
Hal yang sama juga terjadi pada kedua alur bawahan lainnya. Alur
bawahan yang menceritakan tentang Pradhabasu dengan Gagak Bongol
juga dibangun atas dasar tema besar ini. Keduanya dipertemukan pada
saat genting, yakni Raden Kudamerta diserang dengan pisau lempar
yang pelempar pisau tersebut diringkus oleh Pradhabasu. Dari peristiwa
itulah, kedua sahabat yang pernah terluka karena masa lalu akhirnya
mengungkapkan perasaan masing-masing.
Alur bawahan terakhir yang agak berbeda dari lainnya. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya, hadir atau tidaknya alur ini tidak
berpengaruh terhadap jalannya ketiga alur lainnya. Hanya saja, tema
besar perebutan kekuasaan disampaikan pengarang dengan cara lain
pada alur ini. Dalam novel diceritakan bahwa Ra Kembar sangat ingin
menjadi patih Majapahit sedangkan posisi tersebut sudah direncanakan
akan diduduki oleh Gajah Mada. Untuk keperluan itulah, Ra Kembar
memutuskan untuk menyerbu pemberontakan di Karang Watu meskipun
tanpa memperhitungkan akibatnya. Keinginannya untuk menjadi patih
itulah yang menyebabkannya menjadi prajurit yang gelap mata dan tidak
sadar akan kemampuan dirinya.

88
7. Amanat
Pesan fundamental yang ingin disampaikan oleh LKH adalah jangan sampai
kekuasaan, yang ternyata menyimpan banyak beban, menggelapkan mata hati.
Tak pandang kawan, saudara, bahkan lawan, orang yang sudah mabuk oleh
kekuasaan akan mampu melakukan apapun untuk mendapatkan kekuasaan itu.
Hal ini disimbolkan dengan baik oleh dua orang di balik masing-masing suami
sekar kedaton, Panji Wiradapa dan Pakering Suramurda. Keduanya adalah
interpretasi dari banyak golongan atau pihak yang menganggap kedudukan dan
harta adalah segalanya. Mereka menghalalkan segala cara bahkan menghilangkan
nyawa orang adalah jalan tercepat untuk menuju takhta.
Orang-orang yang haus kekuasaan harusnya bisa berpikir bahwa semakin
tinggi jabatan yang dipegang akan semakin besar pula amanatnya, bukan hanya
sekedar takhta, harta, dan kehormatan saja yang akan diterima. Hanya orang-
orang yang memiliki kecakapan luar biasa yang mampu mengemban tugas
sebagai pemimpin. Gayatri, seorang biksuni yang memiliki ketajaman hati dan
mampu memimpin negara pun sebenarnya enggan menjadi penguasa karena ia
tahu pasti risiko serta tanggungan berat yang mutlak menjadi milik sang
penguasa.
Lebih dari itu, ketegangan antarelite politik selalu saja menimbulkan korban.
Korban tidak hanya timbul dari kalangan mereka, tetapi juga dari rakyat biaya
yang tidak tahu menahu soal politik. Dalam novel ini, yang menjadi korban tidak
langsung dari politik adalah anak dan istri pertama Raden Kudamerta. Keduanya
dijadikan sandera oleh Rangsang Kumuda agar Raden Kudamerta dapat dengan
mudah menjadi raja Majapahit.
Lebih jauh lagi, jangan takut untuk mengambil sikap sepahit apapun
risikonya. Hal ini dicerminkan oleh Raden Kudamerta yang terlalu takut
mengambil sikap saat ia tahu dirinya akan dijodohkan dengan Sekar Kedaton.
Kalau saja ia dulu berani menolak perjodohan itu, ia tak akan kehilangan istri dan
anak yang sangat ia cintai. Namun, di saat-saat genting yang akan menentukan

89
arah hidup Dyah Menur, Dyah Wiyat, dan dirinya sendiri, ia mampu bersikap. Ia
memilih hidup sebagai suami Sekar Kedaton dengan banyak pertimbangan.

90
C. Analisis Penggunaan Sarana Retorika dalam Alur
1. Analisis Penggunaan Sarana Retorika Alur Utama
Dalam sebuah novel yang memiliki jumlah halaman yang cukup banyak, dapat
dipastikan akan selalu terdapat lebih dari satu alur. Namun, yang paling diutamakan
dalam sebuah cerita adalah alur utama atau kernel. Kernel inilah yang akan membawa
pembaca kepada tema dan amanat utama yang ingin disampaikan pengarang. Di sisi
lain, kehadiran alur bawahan atau satelit hanya digunakan untuk menambah variasi
cerita saja. Tentunya, dalam sebuah penyajian hal penting dengan hal yang biasa saja
tidak akan sama. Hal ini dikarenakan agar pembaca dapat menyerap maknanya
dengan lebih mudah.
1.1. Pengenalan
Berita itu masih simpang siur karena belum ada keterangan
resmi yang diberikan pihak istana. Semua masih kabur. Kawula
yang berkerumun di alun-alun, mereka yang berteduh di bawah
rindangnya pohon bramastana, pohon tanjung, dan kesara yang
berjajar di sepanjang jalan, atau yang sambil duduk di sudut alun-
alun sibuk menduga dan dengan sabar tetap menunggu bagaimana
kabar terakhir raja mereka.
Awalnya tersebar berita Kalagemet Sri Jayanegara jatuh sakit,
dengan jenis sakit yang tidak luar biasa. Kasak-kusuk yang
berkembang, sakit yang diderita Jayanegara hanya berupa bisul.
Namun, bisul itu mengeram di pantat Sang Prabu sehingga sangat
menganggu duduk dan tidurnya.1
1Langit Kresna Hariadi, Gajah Mada: Takhta dan Angkara, (Solo: Tiga Serangkai,
2012), h. 8-9.

91
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Namun, bisul itu mengeram di pantat Sang Prabu sehingga
sangat mengganggu duduk dan tidurnya.
Antonomasia
2 Namun, bisul itu mengeram di pantat Sang Prabu sehingga
sangat mengganggu duduk dan tidurnya.
Personifikasi
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Berita itu masing simpang siur karena belum ada keterangan
resmi yang diberikan istana.
Kendur
2 Awalnya tersebar berita Kalagemet Sri Jayanegara jatuh sakit,
dengan jenis sakit yang tidak luar biasa.
Klimaks
3
Kasak-kusuk yang berkembang, sakit yang diderita
Jayanegara hanya berupa bisul.
4 Namun, bisul itu mengeram di pantat Sang Prabu sehingga
sangat menganggu duduk dan tidurnya.
1.2. Konflik
Perhatian segenap yang hadir di ruangan itu segera beralih
kepada Jayanegara. Racun yang diminum mulai menjalar. Gajah
Mada layak merasa cemas karena ia mengenal dengan baik siapa
Rakrian Tanca, bagaimana kemampuan yang dimiliki tabib berusia
amat muda itu. Rakrian Tanca gemar bermain-main dengan racun
paling mematikan, racun warangan yang dibalurkan ke keris dan
ujung tombak maupun trisula, yang setiap goresan dijamin akan
menjadi pembuka pintu gerbang kematian. Ra Tanca juga gemar
bermain-main dengan racun berbagai jenis ular mematikan, mulai
dari jenis bandotan sampai weling. Ra Tanca sendiri kebal terhadap
racun-racun itu karena selalu menelan empedunya, sebaliknya tidak
dengan Jayanegara.

92
Racun yang diminumkan kepada Raja Majapahit itu tentu
merupakan jaminan, korban tak mungkin selamat. Namun, Gajah
Mada tak mau menyerah. Meski tak seperti Ra Tanca yang amat
menguasai ilmu pegobatan, walau sedikit Gajah Mada memahami
bagian-bagian paling sederhana, seperti tindakan apa yang harus
dilakukan untuk menawarkan racun yang terlanjur masuk ke tubuh.
Perintah diberikan kepada seorang prajurit untuk segera mencari
kelapa muda dari jenis degan ijo yang diyakini mampu
menawarkan berbagai jenis racun dengan menyerapnya.
Mayat Ra Tanca yang digotong itulah yang dengan segera
mengagetkan para kawula yang melakukan pepe di alun-alun.
Sejak petang hingga petang ratusan orang berkumpul, bersama-
sama mendoakan agar raja muda anak Raden Wijaya itu segera
sembuh. Akan tetapi, yang tidak terduga terjadi. Arah angin
mendadak berubah.
“Ada apa? Apa yang terjadi?” tanya seorang prajurit yang belum
mengetahui duduk persoalannya.
“Ra Tanca diminta mengobati Baginda, tetapi Ra Tanca malah
meracun Sang Prabu,” jawab prajurit yang lain.
“Ha?” beberapa prajurit yang menggerombol terkejut.
Mayat Ra Tanca yang digotong keluar memang menimbulkan
kecemasan, yang tak ubahnya penyakit lalu menular, menular, dan
menular, menulari siapa saja, menular dari prajurit ke prajurit,
menular ke para abdi dalem istana, menular ke beberapa orang
yang bergerombol tak jauh dari Purawaktra dan dengan segera
berubah menjadi ledakan yang mata menggelisahkan siapa pun.
Berita mengejutkan itu dengan segera menjalar ke sudut-sudut
kotaraja. Nyaris semua kawula yang tinggal di balik dinding batas
kotaraja terhenyak. Kawula yang tinggal di luar dinding batas
kotaraja ada juga yang mnedengar berita itu.2
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Racun yang diminum mulai menjalar. Personifikasi
2 Ra Tanca gemar bermain-main dengan racun paling
mematikan,
Metafora
2Ibid., h. 11-12.

93
3 Racun warangan yang dibalurkan ke keris dan ujung tombak
maupun trisula,
Metonimia
4 Yang setiap goresan dijamin akan menjadi pembuka pintu
gerbang kematian.
Personifikasi
5 Racun yang diminumkan kepada Raja Majapahit itu tentu
merupakan jaminan,
Antonomasia
6 Korban tak mungkin selamat. Pleonasme
7 Arah angin mendadak berubah. Metafora
8 Tanya seorang prajurit yang belum mengetahui duduk
persoalannya.
Pleonasme
9 Ra Tanca diminta mengobati Baginda, tetapi Ra Tanca malah
meracuni Sang Prabu.
Antonomasia
10 Berita mengejutkan itu dengan segera menjalar ke sudut-sudut
kotaraja.
Personifikasi
11 Berita mengejutkan itu dengan segera menjalar ke sudut-sudut
kotaraja.
Pars pro toto
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Mayat Ra Tanca yang digotong keluar memang menimbulkan
kecemasan, yang tak ubahnya penyakit lalu menular, menular
dan menular, menulari siapa saja, menular dari prajurit ke
prajurit, menular ke para abdi dalem istana, menular ke
beberapa orang yang bergerombol tak jauh dari Purawaktra
dan dengan segera berubah menjadi ledakan yang mata
menggelisahkan siapa pun.
Epizeuksis

94
2 Gajah Mada layak merasa cemas karena ia mengenal dengan
baik siapa Rakrian Tanca.
Kendur
3 Ra Tanca sendiri kebal terhadap racun-racun itu karena selalu
menelan empedunya.
Kendur
4 Meski tak seperti Ra Tanca yang amat menguasai ilmu
pengobatan, walau sedikit Gajah Mada memahami bagian-
bagian paling sederhana, seperti tindakan apa yang harus
dilakukan untuk menawarkan racun yang terlanjur masuk ke
tubuh.
Periodik
5 Sejak petang hingga petang ratusan orang berkumpul,
bersama-sama mendoakan agar raja muda anak Raden Wijaya
itu segera sembuh.
Periodik
1.3. Sekuen Klimaks
Mengombak wajah Raden Kudamerta memerhatikan mayat
yang masih bisa dikenalinya dari sisa pakaian dan pahatan timang
yang dikenakan orang yang tubuhnya terbakar hangus. Mayat itu
juga bisa dikenali dari terompah kaki yang melekat. Raden
Kudamerta yang tangannya menggenggam terasa dingin, namun
panas di dadanya apabila menyambar daun-daun kering maka akan
terbakar hangus daun-daun kering itu. Andai telur mentah berada di
dalam genggaman tangannya maka akan matang mengeras telur itu.
“Siapa yang melakukan perbuatan ini, Paman Panji
Wiradapa?” gumamnya. Isi dadanya membuncah menggelegak dan
amat butuh penyaluran.
Namun, Panji Wiradapa telah terlanjur beku menjadi mayat.
Panji Wiradapa tak mungkin menjawab pertanyaan itu. Sekujur
tubuhnya yang menjadi sumber bau daging terbakar merangsang
keinginan ingin muntah.
Raden Kudamerta Breng Pamotan yang baru saja mendapat
anugerah gelar Bre Wengker Wijaya Rajasa Hyang Parameswara
mengedarkan pandangan matanya ke arah semua orang yang
menggerombol melingkar mengelilingi mayat pamannya, seolah
bertanya apa yang telah terjadi. Perapian yang porak-poranda dan
keadaan mayat yang hangus dengan lugas bercerita betapa kejam

95
orang yang melakukan pembunuhan itu. Panji Wiradapa dilempar
ke dalam api yang berkobar dalam keadaan masih hidup. Panji
Wiradapa yang meronta kesakitan menyebabkan perapian porak-
poranda. Api benar-benar telah menghanguskan tubuhnya
menyebabkan seorang prajurit benar-benar muntah. Raden
Kudamerta melirik prajurit itu yang dengan segera bergegas
menjauh.3
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Mengombak wajah Raden Kudamerta memerhatikan mayat
yang masih bisa dikenalinya dari sisa pakaian dan pahatan
timang yang dikenakan orang yang tubuhnya terbakar
hangus.
Hiperbola
2 Raden Kudamerta yang tangannya menggenggam terasa
dingin, namun panas di dadanya apabila menyambar daun-
daun kering maka akan terbakar hangus daun-daun kering
itu.
Hiperbola
3 Raden Kudamerta yang tangannya menggenggam terasa
dingin, namun panas di dadanya apabila menyambar daun-
daun kering maka akan terbakar hangus daun-daun kering
itu.
Paradoks
4 Andai telur mentah berada di dalam genggaman tangannya
maka akan matang mengeras telur itu.
Hiperbola
5 Isi dadanya membuncah menggelegak dan amat butuh
penyaluran.
Hiperbola
6 Namun, Panji Wiradapa telah terlanjur beku menjadi mayat. Metafora
7 Namun, Panji Wiradapa telah terlanjur beku menjadi mayat. Pleonasme
8 Raden Kudamerta Breng Pamotan yang baru saja mendapat Simile
3Ibid., h. 85-86

96
anugerah gelar Bre Wengker Wijaya Rajasa Hyang
Parameswara mengedarkan pandangan matanya ke arah
semua orang yang menggerombol melingkar mengelilingi
mayat pamannya, seolah bertanya apa yang telah terjadi.
9 Perapian yang porak-poranda dan keadaan mayat yang
hangus dengan lugas bercerita betapa kejam orang yang
melakukan pembunuhan itu.
Personifikasi
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Mengombak wajah Raden Kudamerta memerhatikan mayat
yang masih bisa dikenalinya dari sisa pakaian dan pahatan
timang yang dikenakan orang yang tubuhnya terbakar
hangus.
Inversi
1.4.Klimaks
Pada saat yang demikian itulah, Rubaya merasa telah tiba
waktunya. Rubaya beringsut dengan tidak menyolok untuk
mencapai jarak yang cukup dengan sasarannya. Sebagaimana
perintah yang diterima dari Rangsang Kumuda, ia harus bisa
menenggelamkan pisau terbangnya ke dada Raden Kudamerta. Di
latihan yang dilakukannya tiap hari, Rubaya tak pernah meleset.
Apabila dada yang dijadikan sasaran maka dadanya pasti kena.
Demikian pula apabila tenggorokan yang dijadikan sasaran maka
tenggorokannya pasti bisa digapai. Namun, untuk memastikan
sasaran kali ini tidak akan meleset Rubaya merasa perlu bergerak
lebih dekat.
“Aku lempar pisauku dan secepatnya aku membuat kekacauan
supaya bisa lolos dari tempat ini,” kata hati Rubaya atas nama
rencana yang akan dilakukan.
Macan Liwung yang bertanggung jawab atas keselamatan
Raden Kudamerta dan istrinya mulai merasakan bau bahaya yang
akan mendekat. Karenanya Bhayangkara Macan Liwung berada

97
pada puncak kewaspadaannya. Demikian pula dengan Gajah
Geneng, matanya melotot nyaris sejengkal. Pesan yang diberikan
Gajah Mada yang disalurkan melalui Senopati Gajah Enggon
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Akan tetapi, rupanya ada pihak yang ikut bermain-main pula.
Pihak yang merasa harus bertindak atas nama panggilan jiwa.
Dengan penampilan yang sederhana, orang itu tak ubahnya orang
kebanyakan. Padahal, ia mempunyai peran dan jasa yang besar
ketika Majapahit diguncang huru-hara sembilan tahun yang silam.
Orang yang amat terluka hatinya itu memilih mengundurkan diri
dari kehidupan pengamanan istana. Di sebuah rumah sederhana di
luar dinding kotaraja ia bertani. Kini, karena sebuah alasan
menyebabkan orang itu harus ikut campur. Dengan tak menarik
perhatian, orang itu terus berjalan yang ada kalanya harus melawan
arus.
Pusat perhatian tertuju pada api yang makin berkobar dan kian
menjadi, melalap tubuh Sri Jayanegara. Ledakan-ledakan terjadi
karena di antara kayu yang digunakan terdapat ruas bambu kering.
Panas menyebabkan udara dalam batang bambu mekar yang ketika
makin memuai berkesanggupan memecahkan batang bambu itu
dengan ledakan yang cukup keras. Manakala ledakan keras itu
pertama kali terjadi memang mengagetkan siapa pun, namun
ledakan-ledakan berikutnya justru ditunggu-tunggu kehadirannya.
Saat semua perhatian sedang terpusat macam itulah Rubaya
merasa telah tiba waktunya. Dengan memutar pergelangan
tangannya, pisau yang semula tersimpan di balik lengan bajunya
melorot turun dengan gagang menempatkan diri di telapak tangan.
Rubaya mencari kesempatan. Dan, saat ledakan batang bambu yang
terbakar terulang kembali, dengan perhitungan cermat ia
mempersiapkan diri mengayunkan pisaunya.
Dengan ayunan kuat ia melempar. Namun, pada saat yang
bersamaan, orang tak dikenal, orang yang merasa terpanggil
hatinya karena kata hati nurani, orang itu yang terus menempel
segera melompat dan menerjang. Dengan hantaman tangannya ia
berusaha mencegah ayunan pisau, tetapi orang itu sedikit terlambat.
Pisau itu telah terlanjur melesat.
Raden Kudamerta yang menjadi sasaran bidik terhenyak
manakala merasakan sakit yang datang dengan tiba-tiba. Perih yang
bukan kepalang terasa di dada kirinya, yang ketika dengan cermat
ia perhatikan berasal dari sebilah pisau yang tertancap di dadanya.
Terduduk Raden Kudamerta menahan nyeri, menyebabkan
Dyah Wiyat terkejut dan mendekapnya dengan segala
kebingungan. Dengan trengginas Macan Liwung yang merasa

98
kecolongan mencari-cari dari mana asal pisau yang melesat itu.
Bhayangkara Macan Liwung segera meloncat ke sumber
kegaduhan yang terjadi di arah kanan.4
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Sebagaimana perintah yang diterima dari Rangsang
Kumuda, ia harus bisa menenggelamkan pisau terbangnya
ke dada Raden Kudamerta.
Paradoks
2 Macan Liwung yang bertanggung jawab atas keselamatan
Raden Kudamerta dan istrinya mulai merasakan bau bahaya
yang akan mendekat.
Metafora
3 Demikian pula dengan Gajah Geneng, matanya melotot
nyaris sejengkal.
Hiperbola
4 Akan tetapi, rupanya ada pihak yang ikut bermain-main
pula.
Eufimisme
5 Orang yang amat terluka hatinya itu memilih mengundurkan
diri dari kehidupan pengaman istana.
Hiperbola
6 Orang yang amat terluka hatinya itu memilih mengundurkan
diri dari kehidupan pengaman istana.
Eufimisme
7 Pusat perhatian tertuju pada api yang makin berkobar dan
kian menjadi, melalap tubuh Sri Jayanegara.
Personifikasi
8 Perih yang bukan kepalang terasa di dada kirinya, yang
ketika dengan cermat ia perhatikan berasal dari sebilah pisau
yang tertancap di dadanya.
Hiperbola
4Ibid., h. 158-159.

99
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Pada saat yang demikian itulah, Rubaya merasa telah tiba
waktunya.
Periodik
2 Rubaya beringsut dengan tidak menyolok untuk mencapai
jarak yang cukup dengan sasarannya.
Kendur
3 Sebagaimana perintah yang diterima dari Rangsang
Kumuda, ia harus bisa menenggelamkan pisau terbangnya
ke dada Raden Kudamerta.
Periodik
4 Di latihan yang dilakukannya tiap hari, Rubaya tak pernah
meleset.
Periodik
5 Apabila dada yang dijadikan sasaran maka dadanya pasti
kena.
Periodik
6 Demikian pula apabila tenggorokan yang dijadikan sasaran
maka tenggorokannya pasti bisa digapai.
Periodik
7 Namun, untuk memastikan sasaran kali ini tidak akan
meleset Rubaya merasa pelu bergerak lebih dekat.
Periodik
8 Padahal, ia mempunyai peran dan jasa yang besar ketika
Majapahit diguncang huru-hara sembilan tahun yang silam.
Berimbang
9 Dengan tak menarik perhatian, orang itu terus berjalan yang
ada kalanya harus melawan arus.
Periodik
10 Ledakan-ledakan terjadi karena di antara kayu yang
digunakan terdapat ruas bambu kering.
Kendur
11 Manakala ledakan keras itu pertama kali terjadi memang
mengagetkan siapa pun, namun ledakan-ledakan berikutnya
justru ditunggu-tunggu kehadirannya.
Berimbang
12 Saat semua perhatian sedang terpusat macam itulah Rubaya Periodik

100
merasa telah tiba waktunya.
13 Dengan memutar pergelangan tangannya, pisau yang
semula tersimpan di balik lengan bajunya melorot turun
dengan gagang menempatkan diri di telapak tangan.
Periodik
14 Dan, saat ledakan batang bambu yang terbakar terulang
kembali, dengan perhitungan cermat ia mempersiapkan diri
mengayunkan pisaunya.
Periodik
15 Dengan hantaman tangannya ia berusaha mencegah ayunan
pisau, tetapi orang itu sedikit terlambat. Pisau itu telah
terlanjur melesat.
Berimbang
16 Raden Kudamerta yang menjadi sasaran bidik terhenyak
manakala merasakan sakit yang datang dengan tiba-tiba.
Kendur
17 Perih yang bukan kepalang terasa di dada kirinya, yang
ketika dengan cermat ia perhatikan berasal dari sebilah
pisau yang tertancap di dadanya.
Periodik
18 Terduduk Raden Kudamerta menahan nyeri, menyebabkan
Dyah Wiyat terkejut dan mendekapnya dengan segala
kebingungan.
Invers
19 Terduduk Raden Kudamerta menahan nyeri, menyebabkan
Dyah Wiyat terkejut dan mendekapnya dengan segala
kebingungan.
Berimbang
20 Dengan ayunan kuat ia melempar. Periodik
1.5. Sekuen Leraian
“Silakan bertanya, aku akan menjawab sejauh yang aku tahu.”
Gajah Mada dan Gajah Enggon saling melirik.
“Sejak kapan Raden berhubungan dengan Brama Ratbumi?’
amat langsung Gajah Mada menohok dengan pertanyaannya.

101
Dengan cermat dan saksama Gajah Mada berusaha menebak
perubahan wajah Raden Kudamerta. Gajah Mada berharap
pertanyaan itu akan menyebabkan menantu Ratu Gayatri itu
terkejut dan langsung berubah pucat. Akan tetapi, keinginan Patih
Daha itu tidak menjadi kenyataan. Raden Kudamerta memang
kaget, tetapi perubahan raut wajah mewakili rasa herannya karena
nama itu belum pernah dikenalnya.
“Siapa?” balas Raden Kudamerta.
“Brama Ratbumi, Raden,” Gajah Enggon membantu
memberinya tekanan.
“Kalian pikir aku mengenal nama itu?” balas Raden
Kudamerta. “Aku tidak tahu siapa nama yang kalian maksud.”
Gajah Mada menarik kesimpulan, agaknya Raden Kudamerta
tidak mengenal nama Brama Ratbumi Rajasa. Bila yang diajukan
adalah nama lain yang digunakan Ratbumi, mungkin Raden
Kudamerta langsung mengerti siapa yang dimaksud.
“Kalian datang menemuiku untuk menanyakan nama yang
belum aku kenal. Siapa Brama Ratbumi?”
“Brama Ratbumi Rajasa adalah nama lain dari orang yang
amat Raden kenal. Ia mempunyai nama lain Panji Wiradapa,”
Gajah Mada mempertegas.
Kali ini Raden Kudamerta benar-benar kaget. Perubahan raut
mukanya terlihat jelas kalau ia terkejut. Tentu nama Panji
Wiradapa dikenalnya dengan baik. Kematian Panji Wiradapa itu
bahkan memunculkan dendam yang tidak tahu ke mana ia harus
menyalurkan. Belum lagi satu masalah itu terurai, tiba-tiba Gajah
Mada datang dengan membawa keterangan yang belum dipahami
sepenuhnya. Orang yang ditempatkannya sebagai paman itu
ternyata memiliki nama Brama Ratbumi.
“Paman Panji menyembunyikan mana itu?” Raden Kudamerta
bertanya.
“Ya, nama aslinya Brama Ratbumi,” jawab Gajah Mada.
Raden Kudamerta merasa membutuhkan waktu beberapa saat
lamanya untuk memahami kenyataan yang mengagetkan itu.
“Lalu, apa pula yang disembunyikan Paman Panji di balik
nama itu?” tambah Raden Kudamerta.
“Jadi, Raden Kudamerta belum pernah mendengarnya?” Gajah
Mada kembali menegas.
Raden Kudamerta menggeleng pendek, namun tegas.
“Raden masih ingat sepak terjang Mahapati?“
“Ramapati atau Mahapati, semua orang tak mungkin
melupakan. Ia mengadu domba mulai dari Tuban hingga
Lumajang, menjadi penyebab jatuhnya korban Ranggalawe, Sora

102
sampai Nambi. Mulut Mahapati sangat beracun. Itu yang aku ingat
dari sosok Mahapati. Sedemikian parah racunnya sampai
berkemampuan menimbulkan perang,“ jawab Raden Kudamerta.
Sebenarnya layak apabila Raden Kudamera tidak pernah
mendengar sepak terjang Mahapati atau Ramapati karena Raden
Kudamerta datang ke Majapahit belum terlalu lama sementara
perang yang terjadi antara Majapahit dengan Lumajang sudah
berjalan lama. Bahkan, telah berada di wilayah belasan tahun yang
lalu. Akan tetapi, ternyata Raden Kudamerta memiliki pemahaman
yang baik terhadap peristiwa itu. Maka terasa sangat aneh bila
Raden Kudamerta tidak sadar sedang berimpitan pada jarak yang
amat dekat dengan salah satu pelaku yang mendorong terjadinya
perang antara Majapahit dan Lumajang itu. Demikian dekatnya
karena Panji Wirapada adalah Ratbumi.
“Apa kaitan Mahapati dengan Ratbumi?” Raden Kudameta
menekan.
“Panji Wiradapa adalah Brama Ratbumi, sedang Brama
Ratbumi adalah tangan kanan Mahapati, orang kedua setelah
Mahapati atau Ramapati yang paling dicari karena sepak terjangnya
yang tak bisa diampuni,” Gajah Enggon menjawab.5
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Akan tetapi, keinginan Patih Daha itu tidak menjadi
kenyataan.
Antonomasia
2 “Kalian pikir aku mengenal nama itu?” balas Raden
Kudamerta.
Retoris
3 Mulut Mahapati sangat beracun. Metafora
5Ibid., h. 255-257.

103
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Raden Kudamerta memang kaget, tetapi perubahan raut
wajah mewakili rasa herannya karena nama itu belum
pernah dikenalnya.
Berimbang
2 Bila yang diajukan adalah nama lain yang digunakan
Ratbumi, mungkin Raden Kudamerta langsung mengerti
siapa yang dimaksud.
Periodik
3 Belum lagi satu masalah itu terurai, tiba-tiba Gajah Mada
datang dengan membawa keterangan yang belum dipahami
sepenuhnya.
Periodik
4 “Ramapati atau Mahapati, semua orang tak mungkin
melupakan.
Klimaks
5 Ia mengadu domba mulai dari Tuban hingga Lumajang,
menjadi penyebab jatuhnya korban Ranggalawe, Sora
sampai Nambi.
6 Mulut Mahapati sangat beracun.
7 Itu yang aku ingat dari sosok Mahapati.
8 Sedemikian parah racunnya sampai berkemampuan
menimbulkan perang,“ jawab Raden Kudamerta.
9 “Panji Wiradapa adalah Brama Ratbumi, sedang Brama
Ratbumi adalah tangan kanan Mahapati, orang kedua
setelah Mahapati atau Ramapati yang paling dicari karena
sepak terjangnya yang tak bisa diampuni,” Gajah Enggon
menjawab.
Berimbang

104
1.6. Leraian
“Kamu sudah tua, Ki Pakering,” kata Gajah Mada datar.
“Pikirkan dahulu sebelum memutuskan melarikan diri. Bertanyalah
kepada nafasmu, apakah masih punya kemampuan untuk
mendukung niatmu.”
Apa yang dikatakan Gajah Mada benar, Pakering Suramurda
tak mungkin bisa meloloskan diri. Menyerah mungkin pilihan
terpahit yang harus diambil ketika tidak punya pilihan lain, atau
jika pilihan lain itu ada adalah menelan pilis racun warangan yang
disimpan diikat pinggang. Satu butir pilis berisi warangan itu
ditelan maka akan membebaskannya dari Gajah Mada. Akan tetapi,
dengan pasti mengantarkan dirinya ke pintu gerbang kematian.
Namun, Pakering Suramurda tak perlu mengambil pilihan itu.
Suramurda tiba-tiba terhenyak dan sedikit terlambat menyadari apa
yang menimpanya. Ketika tangan Pakering Suramura meraba
dadanya, ada gagang anak panah menancap tepat di belahan
dadanya.6
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Bertanyalah kepada nafasmu, apakah masih punya
kemampuan untuk mendukung niatmu.”
Retoris
2 Bertanyalah kepada nafasmu, apakah masih punya
kemampuan untuk mendukung niatmu.”
Personifikasi
3 Bertanyalah kepada nafasmu, apakah masih punya
kemampuan untuk mendukung niatmu.”
Sinisme
4 Menyerah mungkin pilihan terpahit yang harus diambil. Hiperbola
5 Satu butir pilis berisi warangan itu ditelan maka akan
membebaskannya dari Gajah Mada.
Personifikasi
6 Akan tetapi, dengan pasti mengantarkan dirinya ke pintu
gerbang kematian.
Personifikasi
7 Ketika tangan Pakering Suramurda meraba dadanya, ada Perifrasis
6Ibid., h. 443.

105
gagang anak panah menancap tepat di belahan dadanya.
8 Akan tetapi, dengan pasti mengantarkan dirinya ke pintu
gerbang kematian.
Perifrasis
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 “Pikirkan dahulu sebelum memutuskan melarikan diri.” Kendur
2 Apa yang dikatakan Gajah Mada benar, Pakering
Suramurda tak mungkin bisa meloloskan diri.
Berimbang
3 Menyerah mungkin pilihan terpahit yang harus diambil
ketika tidak punya pilihan lain.
Kendur
Berimbang
4 Menyerah mungkin pilihan terpahit yang harus diambil
ketika tidak punya pilihan lain, atau jika pilihan lain itu ada
adalah menelan pilis racun warangan yang disimpan di ikat
pinggang.
5 Ketika tangan Pakering Suramurda meraba dadanya, ada
gagang anak panah menancap tepat di belahan dadanya.
Periodik
1.7. Penyelesaian
Gajah Enggon menyembah.
“Hamba, Tuan Putri,” jawab Gajah Enggon. “Orang ini
menggunakan nama Panji Wiradapa yang bukan nama sebenarnya.
Karena di balik nama Panji Wiradapa ada nama Brama Ratbumi
yang lenyap lebih dari sepuluh tahun bersamaan sejak Mahapati
dihukum mati. Panji Wiradapa juga menggunakan nama lain
Rangsang Kumuda. Ini orangnya, dalang semua kekacauan itu.”
Meski merupakan jawaban, namun jawaban itu masih
menyisakan pertanyaan yang sulit untuk dipahami.
“Jika Panji Wiradapa adalah pendukung Raden Kudamerta,”
kali ini Mapatih Arya Tadah yang bangkit memecah keheningan,
“mengapa ia mematikan diri sendiri, mengapa ia membunuhi

106
pendukung Raden Kudamerta, bahkan merencanakan membunuh
Raden Kudamerta melalui lemparan pisau itu.”
Pertanyaan Mahapatih Mangkubumi Arya Tadah itulah
sebenarnya yang akan dilontarkan Raden Kudamerta. Sungguh ulah
pamannya itu tak bisa dinalar dan sulit diterima akal. Raden
Kudamerta meraba dada kirinya yang masih terasa nyeri.
“Kenapa, Paman?” Raden Kudamerta menekan. “Kenapa
Paman melakukan semua itu? Kenapa paman bahkan
merencanakan pembunuhan atas diriku? Untuk apa Paman
melakukan semua itu?”
Panji Wiradapa tidak menjawab dan tidak berniat menjawab.
Adalah Raden Cakradara yang berdiri bersebelahan dengan isrinya
merasa ulu hatinya nyeri sekali. Kini terbukti bukan pamannya
yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan itu. Meski
Pakering Suramurda memang menyimpan rencana jahat, agaknya
semua rencana itu belum sempat dilaksanakan. Nasib buruk justru
menimpa Pakering Suramurda, malam sebelumnya ia mati dihajar
anak panah. Siapa orang yang melepas anak panah it?
Sangat terganggu oleh pertanyaan itu, Raden Cakradara
melepas genggaman tangan istrinya dan bergerak ke depan untuk
bisa melihat lebih dekat wujud penjahat yang merupakan tangan
kanan Ramapati itu.
“Kau bisa menjelaskan, Gajah Enggon?” tanya Gajah Mada.
“Kuwakili Panji Wiradapa untuk menjawab pertanyaan itu,”
Gajah Enggon menjawab. “Apa yang dilakukan Panji Wiradapa
adalah sebuah fitnah untuk merusak nama Raden Cakradara. Satu
per satu orang-orang Raden Kudamerta dibunuh. Orang pertama
yang dimatikan adalah dirinya sendiri. Panji Wiradapa mati adalah
rekayasa dengan mengorbankan orng lain. Orang itu didandani
tidak ubahnya Panji Wiradapa, lalu dibunuh. Disusul oleh kematian
berikutnya dan berikutnya yang semua adalah orang-orang Raden
Kudamerta. Dengan pembunuhan-pembunuhan itu maka semua
orang akan mengarahkan pandangan ke Raden Cakradara, orang ini
berharap terbuka peluang bagi Raden Kudamerta menjadi raja, ia
berharap ia yang akan duduk di dampar kepatihan.”
Raden Kudamerta merasa dadanya sesak, sementara Raden
Cakradara merasa ulu hatinya makin perih. Menjadi korban fitnah
sungguh menyakitkan.
“Tetapi, kenapa Paman Panji Wiradapa berencana
membunuhku?” Raden Kudamerta bertanya langsung kepada Panji
Wiradapa dengan amat kecewa.

107
Pertanyaan itu rupanya mengusik Panji Wiradapa. Orang itu
berusaha bangkit untuk memberikan jawaban. Gajah Mada
menolong Panji Wiradapa untuk berdiri.
“Aku tidak menyuruh Rubaya untuk membunuhmu, Raden,”
jawabnya. “Aku yakin Rubaya mampu melukaimu tanpa
membunuhmu. Tugas itu yang aku berikan kepada Rubaya. Rubaya
mempunyai kemampuan bidik yang luar biasa. Jika aku minta
untuk hanya melukai dan jangan sampai mengenai jantung, itulah
yang dilakukan. Ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik,
hanya sayang ia tertangkap. Agar Rubaya tak banyak bicara,
kubunuh dia.”
Raden Kudamerta remuk. Kegilaan Panji Wiradapa ternyata
bergerak terlalu jauh. Sebaliknya, betapa mendidih isi dada Raden
Cakradara. Dengan napas tersengal Raden Cakradara menempatkan
diri berdiri di depan Panji Wiradapa.
“Dan, kaukah yang semalam membunuh Paman Pakering
Suramurda?”
Pembunuhan yang terjadi atas Pakering Suramurda di Padas
Payung memang membuat Gajah Mada bertanya-tanya, siapa
pelakunya. Gajah Mada ikut menunggu lelaki tua itu menjawab.
Panji Wiradapa tiba-tiba tertawa terkekeh.
“Apa beda antara aku, Panji Wiradapa, dengan Pakering
Suramurda, Raden?” jawab Panji Wiradapa. “Di belakang Raden
Kudamerta ada aku yang berusaha keras menempatkan Raden
Kudamerta untuk mencapai gegayuhannya. Lalu, di belakangmu
ada Pakering Suramurda yang menyimpan cita-cita yang sama
seperti aku. Apa akan kausembunyikan rencana-rencana pamanmu
seolah tak pernah terjadi?”
Raden Cakradara terhenyak. Apa yang disampaikan Panji
Wiradapa itu benar adanya dan tidak mungkin dibantah. Semalam
di Padas Payung, Gajah Mada bahkan telah menyadap pembicaraan
antara dirinya dengan pamannya dengan utuh dan langsung. Patih
Daha telah tahu semuanya.7
7Ibid., h. 49-493.

108
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 “Hamba, Tuan Putri.” Antonomasia
2 “….. Dalang semua kekacauan itu.” Metafora
3 Kali ini Mapatih Arya Tadah yang bangkit memecah
keheningan
Hiperbola
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Meski merupakan jawaban, namun jawaban itu masih
menyisakan pertanyaan yang sulit untuk dipahami.
Periodik
2 “Mengapa ia mematikan diri sendiri, mengapa ia
membunuhi pendukung Raden Kudamerta, bahkan
merencanakan membunuh Raden Kudamerta melalui
lemparan pisau itu.”
Klimaks
3 Jika aku minta untuk hanya melukai dan jangan sampai
mengenai jantung, itulah yang dilakukan.
Periodik
4 Meski Pakering Suramurda memang menyimpan rencana
jahat, agaknya semua rencana itu belum sempat
dilaksanakan.
Periodik
5 Nasib buruk justru menimpa Pakering Suramurda, malam
sebelumnya ia mati dihajar anak panah.
Berimbang
6 Apa yang dilakukan Panji Wiradapa adalah sebuah fitnah
untuk merusak nama Raden Cakradara.
Klimaks
7 Satu per satu oang-orang Raden Kudamerta dibunuh.
8 Orang pertama yang dimatikan adalah dirinya sendiri.
Panji Wiradapa mati adalah rekayasa dengan

109
mengorbankan orang lain.
9 Orang itu didandani tidak ubahnya Panji Wiradapa, lalu
dibunuh.
10 Disusul oleh kematian berikutnya dan berikutnya yang
semua adalah orang-orang Raden Kudamerta.
11 Dengan pembunuhan-pembunuhan itu maka semua orang
akan mengarahkan pandangan ke Raden Cakradara, orang
ini berharap terbuka peluang bagi Raden Kudamerta
menjadi raja, ia berharap ia yang akan duduk di dampar
kepatihan.”
12
Raden Kudamerta merasa dadanya sesak, sementara
Raden Cakradara merasa ulu hatinya makin perih.
Berimbang
13 Ia telah melaksanakan tugasnya dengan baik, hanya
sayang ia tertangkap.
Berimbang
14 “Agar Rubaya tak banyak bicara, kubunuh dia.” Periodik
15 Semalam di Padas Payung, Gajah Mada bahkan telah
menyadap pembicaraan antara dirinya dengan pamannya
dengan utuh dan langsung.
Periodik
Dari pendataan retorika tekstual berupa gaya bahasa dan struktur
kalimat yang ditemukan pada alur utama novel Gajah Mada; Takhta dan
Angkara karya Langit Kresna Hariadi dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Tahap Pengenalan
a. Gaya bahasa : 2 kali
b. Struktur Kalimat : 4 kali
Total : 6 kali penggunaan retorika tektual
2. Tahap Konflik

110
a. Gaya bahasa : 11 kali
b. Struktur Kalimat : 5 kali
Total :16 kali penggunaan retorika tekstual
3. Sekuen Klimaks
a. Gaya bahasa : 9 kali
b. Struktur Kalimat : 1 kali
Total : 10 kali penggunaan retorika tekstual
4. Klimaks
a. Gaya bahasa : 8 kali
b. Struktur kalimat : 20 kali
Total : 28 kali penggunaan retorika tekstual
5. Sekuen Leraian
a. Gaya bahasa : 3 kali
b. Struktur Kalimat : 9 kali
Total : 12 kali penggunaan retorika tekstual
6. Leraian
a. Gaya bahasa : 8 kali
b. Struktur Kalimat : 5 kali
Total : 13 kali penggunaan retorika tekstual
7. Penyelesaian
a. Gaya bahasa : 3 kali
b. Kalimat : 15 kali
Total : 18 kali penggunaan retorika tekstual
Dari perolehan data tersebut dapat diketahui bahwa adegan yang
menggunakan sarana retorika tekstual terbanyak adalah adegan klimaks,
yakni sebesar 28 kali. Lalu disusul oleh adegan penyelesaian dan terbanyak
ketiga adalah bagian konflik.

111
Seringnya pengarang menggunakan sarana retorika tekstual dalam
adegan ini menunjukkan bahwa adegan klimaks dalam novel ini
membutuhkan gaya penceritaan yang harus berbeda dengan gaya penceritaan
pada adegan lainnya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan klimaks
merupakan adegan terpenting dalam sebuah kisahan. Seperti yang telah
diketahui bersama, klimaks merupakan titik didih atau titik rumitan yang
ditunggu pembaca lebih dari sekedar menunggu adegan penyelesaian.
Banyak kisahan yang tidak memiliki penyelesaian atau alur yang
menggantung. Hal ini tidak menganggu pembaca, bahkan dengan tidak
hadirnya adegan itu sebuah karya dinilai semakin bagus karena berhasil
membuat pembaca mengembangkan imajinasinya senidri untuk
menghadirkan adegan penyelesaian yang pastinya akan berbeda dengan
pembaca lainnya. Keranekaragaman adegan penyelesaian inilah yang secara
tidak langsung menempatkan pembaca ke dalam sebuah bagian dalam karya
yang tidak bisa dilepaskan, memikirkan bagaimana akhir cerita tersebut.
Namun, bayangkan bila sebuah kisahan tidak memiliki adegan
klimaks. Kisahan tersebut tentu hanya akan diawali oleh adegan pengenalan
dan diakhiri oleh adegan konflik. Tidak ada adegan leraian juga adegan
penyelesaian karena memang tidak ada yang bisa diselesaikan. Tidak ada
kisahan yang tidak memiliki klimaks. Sesederhana apapun kisahan tersebut,
pasti di dalamnya terdapat klimaks sebagai sesuatu yang harus diselesaikan.
Hal ini dikarenakan dengan utuhnya tahapan alur dalam sebuah kisah,
amanat akan dapat diambil oleh pembaca.
Berbicara masalah amanat, tidak hanya cukup pada lengkap atau
tidaknya tahapan alur, tetapi juga akan pada permasalahan bagaimana
adegan-adegan itu disampaikan oleh pengarang dengan tidak mengurangi
maknanya sedikitpun. Proses penulisan inilah yang harus mendapatkan
perhatian lebih dari pengarangnya karena tiap tahap harusnya ditulis dengan
gaya bahasa yang sesuai, khususnya klimaks.

112
Penulisan adegan klimaks memerlukan banyak keterampilan agar
apa yang ingin disampaikan oleh pengarang bisa dengan mudah dimengerti
oleh pembaca. Jika pada tahap klimaks ini pembaca kehilangan ide atau
tidak bisa menangkap peristiwa apa yang sebenarnya sedang terjadi, maka
pembaca tidak akan bisa menikmati lagi adegan-adegan selanjutnya.
Dalam novel yang berlatarbelakangkan sejarah ini, LKH dengan apik
mengemas klimaks dengan cara menggunakan 28 kali sarana retoika tekstual
yang terdiri atas 8 kali penggunaan gaya bahasa dan 20 kali penggunaan
struktur kalimat yang berbeda-beda.
Gaya bahasa yang digunakan dalam tahap ini adalah gaya bahasa
kiasan yang terdiri atas gaya bahasa metafora, personifikasi dan gaya bahasa
retoris yang terdiri atas gaya bahasa hiperbola, eufimisme, dan paradoks.
LKH mencampurkan penggunaan kedua jenis gaya bahasa ini tentu dengan
alasan. Penggunaan dua gaya bahasa dari jenis kiasan dimaksudkan untuk
membantu pemahaman pembaca terhadap peristiwa yang digambarkan
pengarang. Hal ini dilakukan mengingat peristiwa yang dihadirkan ini
bukanlah sebuah pemandangan yang biasa dilihat pembaca di zaman
sekarang. Personifikasi digunakan untuk menceritakan peristiwa pembakaran
mayat Jayanegara. Tentunya pembakaran jenazah seorang raja berbeda
dengan pembakaran jenazah yang kerap disebut ngaben yang ada di Bali.
dengan bantuan personifikasi inilah, pembaca dapat membayangkan bahwa
peristiwa pembakaran jenazah itu menggunakan api yang cukup besar
melebihi api yang biasa digunakan untuk upacara ngaben pada umumnya.
Juga, penggunakan gaya bahasa metafora dalam konteks cerita kesiagaan
Macan Liwung sebagai pengawal Raden Kudamerta dan Dyah Wiyat
membantu pembaca membayangkan betapa siaganya sikap dan tindakan
prajurit tersebut. Bayangan kesigapan dan kesiagaan Macan Liwung
tentunya akan berbeda dengan membayangkan Paspampres yang juga
bertugas mengawal keluarga presiden. Semua penggunaan gaya bahasa ini

113
dimaksudkan untuk membantu pembaca membayangkan gambaran umum
mengingat latar belakang novel ini adalah sejarah kerajaan Majapahit yang
masih jauh dari kata modern. Efek penyimpangan makna yang terdapat
dalam gaya bahasa kiasan ini tidak untuk mengaburkan apa yang ingin
dimaksud pengarang, tetapi justru membantu pembaca memahami apa yang
sebenarnya terjadi karena tanpa menggunakan gaya bahasa, cerita yang akan
disampaikan akan terkesan bertele-tele dan berpotensi menimbulkan
kebosanan saat membaca.
Begitu pula penggunaan gaya bahasa lain yang berasal dari jenis
retoris. Gaya bahasa jenis ini digunakan dalam beberapa kalimat dalam
adegan ini untuk menghasilkan efek yang berbeda bila dibandingkan dengan
menggunakan konstruksi biasa. Seperti penggunaan hiperbola dalam konteks
cerita kesiagaan Gajah Geneng yang digambarkan dengan mata yang nyaris
melotot sejengkal. Dari kalimat tersebut penggunaan frasa melotot sejengkal
memberikan efek pemahaman, Gajah Geneng berada pada kondisi kesiagaan
tertinggi dan semua yang ada dalam tempat itu tidak akan luput dari
penglihatannya. Efek yang dihasilkan tidak akan sama bila hanya
menggunakan kalimat biasa, seperti Gajah Geneng sedang sangat siaga. Inti
yang hendak disampaikan memang sama, namun, penggambaran dan kesan
yang dihasilkan dari kedua kalimat tersebut akan jauh berbeda.
Pada intinya, penggunaan kedua jenis gaya bahasa ini ditujukan
untuk menghasilkan efek dan kesan mendalam terhadap peristiwa ini.
Dengan kesan mendalam yang didapatkan pembaca, mereka dengan mudah
menyerap dan mengikuti adegan selanjutnya. Hal yang sama juga terjadi
pada penggunaan struktur kalimat yang beraneka ragam dalam adegan ini.
Tercatat sebanyak lima struktur kalimat yang digunakan LKH dalam
adegan ini. Kelima struktur kalimat tersebut ialah kalimat periodik, kendur,
inversi, kalimat majemuk setara berlawanan biasa, dan kalimat majemuk

114
bertingkat. Tujuan utama digunakannya kelima jenis kalimat dalam tahap ini
adalah untuk mempertahankan konsentrasi pembaca.
Kalimat inversi digunakan dalam salah satu kalimat pada adegan ini
sebagai upaya menyegarkan pembaca. Peletakkan fungsi predikat yang
mendahului subjek dapat menghilangkan kejenuhan pembaca setelah
membaca struktur kalimat yang hampir senada sebelumnya.
Kalimat periodik ini bertujuan untuk membuat pembaca penasaran
dengan peristiwa yang terjadi. Dengan diletakkannya anak kalimat di awal
kalimat, mampu membuat pembaca penasaran tentang apa yang sebentar lagi
akan terjadi. Begitu pula dengan penggunaan kalimat kendur, meskipun
tidak bertujuan untuk menghadirkan efek ketegangan dan penasaran, kalimat
jenis ini bertujuan untuk membuat pembaca mudah menangkap apa yang
dimaksud pengarang karena bila kalimat ini ditulis dengan konstruksi
periodik, makna yang ingin disampaikan tidak akan tersampaikan dengan
utuh mengingat informasi yang dikandungi oleh kalimat kendur ini cukup
penting bila dibandingkan dengan info dalam kalimat periodik.
Kekayaan penggunaan retorika tekstual yang digunakan untuk
menceritakan adegan klimaks ini sangat membantu pembaca dalam
memahami kisah yang disampaikan. Dengan banyaknya sarana retorika yang
digunakan dalam tahapan ini, pembaca akan merasakan banyak emosi di
dalamnya.
2. Analisa Penggunaan Sarana Retorika Tekstual Alur Tambahan Pertama
Meskipun novel yang mengambil latar belakang sejarah harus mengikuti pakem-
pakem sejarah yang sudah ada, tetap saja masih memberikan celah kepada pengarang
untuk mengembangkan imajinasinya. Begitu pun yang terjadi pada novel sejarah
Gajah Mada; Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi ini. Dalam novel ini,
terdapat tiga alur bawahan yang semuanya rekaan pengarang. Ketiga alur tambahan

115
ini ditujukan untuk membuat pembaca merasakan ketegangan lain selain pada alur
utama dan juga memberikan sedikit ruang untuk bernafas setelah mengikuti alur
utama. Namun, alur bawahan yang disajikan pengarang juga tak kalah esensinya bila
dibandingkan dengan alur utama. Tetap ada pelajaran yang dapat diambil oleh
pembaca.
Seperti halnya alur bawahan pertama yang menceritakan tentang cinta segitiga
antara Raden Kudamerta dengan kedua istrinya ini. Meskipun ini bukanlah inti cerita
dari novel sejarah ini, tetap saja penyajiannya tidak kalah menarik dari penyajian alur
utama.
1.1. Pengenalan
Dyah Wiyat kaget ketika tangan emban tua itu menyentuh
lengannya. Seketika lenyap terampas segenap lamunannya. Dyah
Wiyat merasa kakinya sangat ringan dan melayang ketika emban
tua itu membawanya melangkah. Bayangan wajah Raden
Kudamerta dan Raden Cakradara bergoyang ketika Dyah Wiyat
melintasinya, tanah tempat kakinya berpijak bergelombang tidak
rata. Emban tua itu terkejut ketika Dyah Wiyat sedikit terhuyung,
tetapi dengan segera menguasai diri.
Apa yang terjadi tidak luput dari pandangan para Ibu Ratu dan
memaksa Ratu Biksuni Gayatri mencuatkan sebelah alisnya,
bahkan Gajah Mada dan Mahapatih Arya Tadah mampu
menangkap kejadian itu dan memerhatikan lebih cermat. Raden
Cakradara yang juga melihat itu berusaha tidak menelusuri lebih
jauh, sementara Raden Kudamerta kebetulan sedang menunduk
lebih jauh sehingga tidak melihat apa yang terjadi. Para Ratu
memerhatikan sikap Dyah Wiyat dengan lebih cermat dan memang
terlihat perbedaan yang tegas antara kakak dan adiknya itu. Sri
Gitarja menampakkan rasa gembiranya dengan jelas, rasa
bahagianya terbaca dengan sangat lugas. Sebaliknya, Dyah Wiyat
berbalikan dengan sikap kakaknya.
Manakala sungkem itu dilakukan di hadapan Ibu Ratu
Tribhuaneswari, Dyah Wiyat tidak mengeluarkan secuil pun kata-
kata, juga tak ada basah air mata. Gadis itu hanya menunduk dan
dengan sangat santun merapatkan dua telapak tangannya dalam

116
sikap menyembah. Ibu Tribhuaneswari meraih dan memeluknya,
diciumnya kening Sekar Kedaton itu.
“Jalanilah hidupmu,” kata Ibu Ratu tertua. “Jadilah seorang
ratu yang baik untuk rumah tanggamu, semoga Hyang Widdi
memberimu keturunan yang berbakti dan berguna untuk negeri
ini.”
Dyah Wiyat nyaris tidak mengangguk.
“Terima kasih Ibu Ratu,” jawabnya lirih, nyaris tanpa tenaga.
Emban tua yang bertugas menuntun Dyah Wiyat menjalani
acara itu merasa heran. Namun, disimpannya rasa penasaran itu
dalam hati. Bahwa dalam dada Dyah Wiyat sedang ada gumpalan
sesak yang membuncah menggelegak makin terbaca dari sikap
Dyah Wiyat yang hanya diam tak berbicara apa-apa manakala
melakukan sungkem di hadapan Ibu Ratu Narendraduhita dan Ibu
Ratu Pradnya Paramita. Dari raut mukanya terbaca jelas, Dyah
Wiyat sangat tidak senang menjalani perkawinan itu.
Raut muka Dyah Wiyat juga tidak luput dari perhatian Ibu
Ratu Biksuni Rajapatni Gayatri. Bagaimanapun juga ratu termuda
janda mendiang Raden Wijaya itu adalah perempuan yang
melahirkannya, memberikan air susu, melengkapi rasa kasih
sayang yang dilimpahkannya, yang merasa cemas ketika anak itu
sakit dan selalu berharap semoga ketika dewasa kelak akan
menemukan kebahagiaannya. Sebagai ibu, dengan sendirinya Ratu
Gayatri amat mengenali bahasa wajah ataupun bahasa sikap
anaknya. Raut muka Dyah Wiyat yang pucat dan terbebani
merupakan isyarat anaknya sedang menyimpan gumpalan masalah,
hal yang tidak akan luput dari perhatiannya.
Namun, Dyah Wiyat Rajadewi Maharajasa memang tidak
punya pilihan lain dan sebagian diantaranya memang merupakan
kesalahannya sendiri. Mestinya Dyah Wiyat menolak ketika ikatan
perjodohan itu dulu dirancang. Buah dari sikapnya yang demikian
itu kini harus dipetik, perkawinan itu harus dijalani sampai tuntas.
Walau kakinya bagai kehilangan tenaga untuk menopang tegak
tubuhnya, walau mulutnya terkunci kehilangan kekuatan untuk
bicara mengucapkan ikrarnya, Dyah Wiyat tidak mempunyai
pilihan lain selain kecuali harus menerima apa yang disodorkannya
itu.8
8 Ibid., h. 102-103.

117
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Seketika lenyap terampas segenap lamunannya. Pleonasme
2 Dyah Wiyat merasa kakinya sangat ringan dan melayang
ketika emban tua itu membawanya melangkah.
Pleonasme
3 Bayangan wajah Raden Kudamerta dan Raden Cakradara
bergoyang ketika Dyah Wiyat melintasinya, tanah tempat
kakinya berpijak bergelombang tidak rata.
Pleonasme
4
Para Ratu memerhatikan sikap Dyah Wiyat dengan lebih
cermat dan memang terlihat perbedaan yang tegas antara
kakak dan adiknya itu
Antomonasia
5 Sri Gitarja menampakkan rasa gembiranya dengan jelas,
rasa bahagianya terbaca dengan sangat lugas.
Tautologi
6 Manakala sungkem itu dilakukan di hadapan Ibu Ratu
Tribhuaneswari, Dyah Wiyat tidak mengeluarkan secuil
pun kata-kata, juga tak ada basah air mata.
Perifrasis
7 Ibu Tribhuaneswari meraih dan memeluknya, diciumnya
kening Sekar Kedaton itu.
Antonomasia
8 “Jadilah seorang ratu yang baik untuk rumah tanggamu” Metafora
9 “Semoga Hyang Widdi memberimu keturunan yang
berbakti dan berguna untuk negeri ini.”
Antonomasia
10 Bahwa dalam dada Dyah Wiyat sedang ada gumpalan
sesak yang membuncah menggelegak makin terbaca dari
sikap Dyah Wiyat yang hanya diam tak berbicara apa-apa
manakala melakukan sungkem di hadapan Ibu Ratu
Narendraduhita dan Ibu Ratu Pradnya Paramita.
Hiperbola

118
11 Bahwa dalam dada Dyah Wiyat sedang ada gumpalan
sesak yang membuncah menggelegak makin terbaca dari
sikap Dyah Wiyat yang hanya diam tak berbicara apa-apa
manakala melakukan sungkem di hadapan Ibu Ratu
Narendraduhita dan Ibu Ratu Pradnya Paramita.
Pleonasme
12 Raut muka Dyah Wiyat yang pucat dan terbebani
merupakan isyarat anaknya sedang menyimpan gumpalan
masalah, hal yang tidak akan luput dari perhatiaannya.
Hiperbola
13 Buah dari sikapnya yang demikian itu kini harus dipetik,
perkawinan itu harus dijalani sampai tuntas.
Metafora
14 Walau kakinya bagai kehilangan tenaga untuk menopang
tegak tubuhnya,
Simile
15 Walau kakinya bagai kehilangan tenaga untuk menopang
tegak tubuhnya, walau mulutnya terkunci kehilangan
kekuatan untuk bicara mengucapkan ikrarnya, Dyah
Wiyat tidak mempunyai pilihan lain selain kecuali harus
menerima apa yang disodorkannya itu.
Perifrasis
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Apa yang terjadi tidak luput dari pandangan para Ibu Ratu
dan memaksa Ratu Biksuni Gayatri mencuatkan sebelah
alisnya, bahkan Gajah Mada dan Mahapatih Arya Tadah
mampu menangkap kejadian itu dan memerhatikan lebih
cermat.
Berimbang
2 Raden Cakradara yang juga melihat itu berusaha tidak
menelusuri lebih jauh, sementara Raden Kudamerta
Berimbang

119
kebetulan sedang menunduk lebih jauh sehingga tidak
melihat apa yang terjadi.
3 Manakala sungkem itu dilakukan di hadapan Ibu Ratu
Tribhuaneswari, Dyah Wiyat tidak mengeluarkan secuil
pun kata-kata, juga tak ada basah air mata.
Periodik
4 Dari raut mukanya terbaca jelas, Dyah Wiyat sangat tidak
senang menjalani perkawinan itu.
Periodik
5 Bagaimanapun juga ratu termuda janda mendiang Raden
Wijaya itu adalah perempuan yang melahirkannya,
memberikan air susu, melengkapi rasa kasih sayang yang
dilimpahkannya, yang merasa cemas ketika anak itu sakit
dan selalu berharap semoga ketika dewasa kelak akan
menemukan kebahagiaannya.
Berimbang
6 Buah dari sikapnya yang demikian itu kini harus dipetik,
perkawinan itu harus dijalani sampai tuntas.
Paralelisme
7 Walau kakinya bagai kehilangan tenaga untuk menopang
tegak tubuhnya, walau mulutnya terkunci kehilangan
kekuatan untuk bicara mengucapkan ikrarnya, Dyah
Wiyat tidak mempunyai pilihan lain selain kecuali harus
menerima apa yang disodorkannya itu.
Anafora
1.2.Konflik
“Boleh tahu siapa nama istrimu itu, Kakang?” tanya Dyah
Wiyat.
Raden Kudamerta sungguh bingung, tak tahu bagaimana cara
menjawab.
“Atau, akan kausembunyikan istrimu itu selamanya dariku?”
Raden Kudamerta menyeringai. Darah yang keluar dari
lukanya itu menyebabkan pakaian yang dikenakannya menjadi
merah, padahal lembaran kain yang dikenakan berwarna putih.
Akan tetapi, Dyah Wiyat tak merasa iba. Dyah Wiyat tidak merasa

120
terpanggil untuk segera memberikan pertolongan. Rahasia yang
disembunyikan laki-laki itu, rahasia yang kini bukan rahasia lagi,
bahwa ia telah beristri saat mengawininya, sungguh merupakan
pelecehan yang tak terampunkan.
“Aku anak raja,” kata Dyah Wiyat. “Aku bahkan bisa menjadi
ratu di negeri yang besar ini, yang kebesarannya jauh melebihi
kebesaran Pamotan. Aku bisa seperti Ratu Shima yang sanggup
memenggal tangan adiknya yang bersalah. Aku juga bisa
menjatuhkan hukuman mati kepada suamiku sendiri. Aku anak
raja. Aku dikawini oleh seorang lelaki yang telah beristri. Adakah
pelecehan yang melebihi seperti yang aku alami kali ini, Raden
Kudamerta?”
“Aku minta maaf, Dyah Wiyat. Aku tak berniat
menyembunyikan hal itu. Aku bahkan ingin meluruskan
perkawinan ini sejak awal, tetapi aku tak punya pilihan lain,” jawab
Raden Kudamerta.
“Siapa nama perempuan itu?” Dyah Wiyat mengejar.
“Dyah Menur Hardiningsih,” jawab Raden Kudamerta.
Dyah Wiyat Rajadewi Maharajasa memejamkan mata untuk
menghayati lebih cermat warna perasaan macam apa yang sedang
ia rasakan. Sungguh sama sekali tak ada perasaan marah sebagai
bias rasa cemburu. Yang ada hanya perasaan tersinggung karena
dikawini oleh orang yang menyembunyikan belang karena ternyata
memiliki istri bahkan seorang anak.
Amat sinis senyum yang mencuat di bibir Dyah Wiyat,
menempatkan Raden Kudamerta mengalami kebingungan tak
mampu menerjemahkan apa artinya. Dyah Wiyat yang kembali
menengadah mengarahkan pandangan matanya pada bintang di
sudut langit yang memiliki warna kemerahan. Betapa gelisah Dyah
Wiyat karena tak berhasil menemukannya meski mencari-cari di
mana bintang itu berada. Padahal, ia telah terlanjur beranggapan
bintang itu peralihan roh Ra Tanca.
Dyah Wiyat membalikkan tubuh dan dengan langkah perlahan
naik ke undak-undakan yang membawanya ke ruang tengah
istananya. Langkah yang semula perlahan itu berubah menjadi
bergegas. Dengan mata yakin Dyah Wiyat meninggalkan Raden
Kudamerta termangu sendiri di halaman. Raden Kudamerta jatuh
terduduk. Ia tak lagi peduli andaikata rahasia yang terbongkar itu
akan membawanya ke gantungan. Ia juga tak peduli meski dari
lukanya darah mengalir deras.9
9Ibid., h. 266-267.

121
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 “Atau, akan kausembunyikan istrimu itu selamanya
dariku?”
Retoris
2 Aku anak raja. Sinisme
3 Aku dikawini oleh seorang lelaki yang telah beristri.
4 Adakah pelecehan yang melebihi seperti yang aku
alami kali ini, Raden Kudamerta?”
Retoris
5 Ia tak lagi peduli andaikata rahasia yang terbongkar itu
akan membawanya ke gantungan.
Metafora
6 Ia juga tak peduli meski dari lukanya darah mengalir
deras.
Hiperbola
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Rahasia yang disembunyikan laki-laki itu, rahasia yang
kini bukan rahasia lagi, bahwa ia telah beristri saat
mengawininya, sungguh merupakan pelecehan yang tak
terampunkan.
Antitesis
2 Yang ada hanya perasaan tersinggung karena dikawini
oleh orang yang menyembunyikan belang karena
ternyata memiliki istri bahkan seorang anak.
Kendur
3 Ia tak lagi peduli andaikata rahasia yang terbongkar itu
akan membawanya ke gantungan.
Antiklimaks
4 Ia juga tak peduli meski dari lukanya darah mengalir
deras.
5 “Aku anak raja,” kata Dyah Wiyat. Anafora

122
6 “Aku bahkan bisa menjadi ratu di negeri yang besar ini,
yang kebesarannya jauh melebihi kebesaran Pamotan.
7 Aku bisa seperti Ratu Shima yang sanggup memenggal
tangan adiknya yang bersalah.
8 Aku juga bisa menjatuhkan hukuman mati kepada
suamiku sendiri.
9 Aku anak raja.
10 Aku dikawini oleh seorang lelaki yang telah beristri.
1.3.Sekuen Klimaks
Akan tetapi ternyata masih belum bagi Ibu Ratu yang
terganggu dengan pertanyaan yang mengganjal hatinya. Persoalan
itu telah menjadi desas-desus pembicaraan orang. Mumpung rakyat
banyak sedang berkumpul di Balai Prajurit, Ratu Gayatri
memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan pertanyaan.
Ratu Gayatri Rajapatni menyebar pandangan matanya
menyapu wajah semua orang yang hadir di pendapa dan halaman
Balai Prajurit. Semua orang terpancing rasa ingin tahunya,
persoalan apa kira-kira yang akan disampaikan Ratu Gayatri.
Setelah menjelajah semua wajah, perhatian Ratu ternyata hinggap
di wajah Raden Kudamerta.
“Raden Kudamerta,” kata Gayatri. “Mumpung rakyat banyak
saat ini sedang berkumpul dan untuk meredam jangan sampai
muncul desas-desus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, aku
ingin bertanya kepadamu, Raden, apakah benar ketika kukawinkan
kau dengan Dyah Wiyat, kau telah beristri, yang demikian telah
kautempatkan Sekar Kedaton sebagai istri kedua?”
Pertanyaan yang diajukan dengan tidak terduga-duga itu
menyebabkan Raden Kudamerta pucat pasi. Raden Kudameta yang
gugup menyempatkan memejamkan mata untuk meredam gejolak
yang terpancing mendadak itu. Pertanyaan itu tidak hanya
mengagetkan Raden Kudamerta, semua yang hadir di Balai Prajurit
tanpa terkecuali terkejut. Mereka yang sudah mendengar desas-

123
desus terpancing rasa ingin tahunya apalagi mereka yang baru
mendengar tak kalah kaget.10
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Akan tetapi ternyata masih belum bagi Ibu Ratu yang
terganggu dengan pertanyaan yang mengganjal hatinya.
Antonomasia
2 Ratu Gayatri Rajapatni menyebar pandangan matanya
menyapu wajah semua orang yang hadir di pendapa dan
halaman Balai Prajurit
Metafora
3 Setelah menjelajah semua wajah, perhatian Ratu ternyata
hinggap di wajah Raden Kudamerta.
Antonomasia
4 Apakah benar ketika kukawinkan kau dengan Dyah
Wiyat, kau telah beristri, yang demikian telah
kautempatkan Sekar Kedaton sebagai istri kedua?”
Antonomasia
5 Raden Kudameta yang gugup menyempatkan
memejamkan mata untuk meredam gejolak yang
terpancing mendadak itu.
Hiperbola
6 Pertanyaan itu tidak hanya mengagetkan Raden
Kudamerta, semua yang hadir di Balai Prajurit tanpa
terkecuali terkejut.
Pleonasme
B. Struktur Kalimat
10
Ibid., h. 497-498.

124
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Mumpung rakyat banyak sedang berkumpul di Balai
Prajurit, Ratu Gayatri memanfaatkan kesempatan itu
untuk melontarkan pertanyaan.
Periodik
2 Setelah menjelajah semua wajah, perhatian Ratu ternyata
hinggap di wajah Raden Kudamerta.
Periodik
3 “Mumpung rakyat banyak saat ini sedang berkumpul dan
untuk meredam jangan sampai muncul desas-desus yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan, aku ingin bertanya
kepadamu, Raden, apakah benar ketika kukawinkan kau
dengan Dyah Wiyat, kau telah beristri, yang demikian
telah kautempatkan Sekar Kedaton sebagai istri kedua?”
Berimbang
4 Pertanyaan itu tidak hanya mengagetkan Raden
Kudamerta, semua yang hadir di Balai Prajurit tanpa
terkecuali terkejut.
Periodik
1.4. Klimaks
Raden Kudamerta yang gelisah menengadah. Raden
Kudamerta tidak dengan segera menjawab pertanyaan itu. Tidak
bisa dihindari, semua pandangan mata sedang tertujupadanya.
Namun, yang paling menusuk adalah pandangan mata Dyah Wiyat.
Tanpa setahu Raden Kudamerta, Dyah Wiyat ikut menunggu
jawaban apa yang akan diberikannya. Mendadak Dyah Menur
mersa, jawaban itu sungguh sangat penting. Jawaban yang sedang
ditunggu yang nantinya akan menjadi salah satu dari banyak
pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dyah Menur amat
ingin tahu, apakah Raden Kudamerta benar-benar sosok yang layak
dibanggakan atau bukan.
”Hamba belum pernah mengawini siapa pun, Tuan Putri,”
jawab Raden Kudamerta dengan suara amat tegas.

125
Jawaban itu menyentakkan Sekar Kedaton Dyah Wiyat
Rajadewi Maharajasa. Jelas Raden Kudamerta menyampaikan hal
yang sama sekali tidak benar. Gajah Mada juga terkejut karena
Raden Kudamerta memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan
kenyataan.
Namun, rupanya jawaban itu sudah cukup bagi Ibu Ratu yang
tidak merasa perlu mengejar dengan pertanyaan lain. Patih Daha
Gajah Mada yang berpikir keras kemudian tersenyum. Tiba-tiba
saja Gajah Mada sadar bahwa tak penting bagi Ibu Ratu, apakah
Raden Kudamerta berbicara jujur atau tidak. Yang paling penting
rupanya bagaimana Raden Kudamerta bersikap. Dengan jawaban
itu berarti Raden Kudamerta harus menempatkan Maharajasa
sebagai satu-satunya istri, tanpa ada perempuan lain sebagai istri
yang lain. Jika istri pertama itu ada berarti ia harus disingkirkan.11
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Raden Kudamerta yang gelisah menengadah Asonansi
2 Tidak bisa dihindari, semua pandangn mata sedang
tertuju padanya.
Pleonasme
3 Namun, yang paling menusuk adalah pandangan mata
Dyah Wiyat.
Hiperbola
4 Namun, yang paling menusuk adalah pandangan mata
Dyah Wiyat.
Pleonasme
5 ”Hamba belum pernah mengawini siapa pun, Tuan Putri Antonomasia
6 Jawaban itu menyentakkan Sekar Kedaton Dyah Wiyat
Rajadewi Maharajasa
Antonomasia
7 Namun, rupanya jawaban itu sudah cukup bagi Ibu Ratu
yang tidak merasa perlu mengejar dengan pertanyaan
lain.
Antonomasia
11
Ibid., h. 498-499.

126
8 Patih Daha Gajah Mada yang berpikir keras kemudian
tersenyum.
Hiperbola
9 Tiba-tiba saja Gajah Mada sadar bahwa tak penting bagi
Ibu Ratu, apakah Raden Kudamerta berbicara jujur atau
tidak.
Antonomasia
10 Dengan jawaban itu berarti Raden Kudamerta harus
menempatkan Maharajasa sebagai satu-satunya istri,
tanpa ada perempuan lain sebagai istri yang lain.
Antonomasia
11 Dengan jawaban itu berarti Raden Kudamerta harus
menempatkan Maharajasa sebagai satu-satunya istri,
tanpa ada perempuan lain sebagai istri yang lain.
Pleonasme
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Tanpa setahu Raden Kudamerta, Dyah Wiyat ikut
menunggu jawaban apa yang akan diberikannya.
Periodik
2 Mendadak Dyah Menur merasa, jawaban itu sungguh
sangat penting.
Invers
3 Gajah Mada juga terkejut karena Raden Kudamerta
memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan
kenyataan.
Kendur
4 Tiba-tiba saja Gajah Mada sadar bahwa tak penting bagi
Ibu Ratu, apakah Raden Kudamerta berbicara jujur atau
tidak. Yang paling penting rupanya bagaimana Raden
Kudamerta bersikap.
Periodik
5 Jika istri pertama itu ada berarti ia harus disingkirkan. Periodik

127
1.5. Sekuen Leraian
Bagi Dyah Menur Sekar Tanjung, jawaban suaminya telah
membimbingnya ke mana harus melangkah. Setidaknya untuk
waktu yang panjang, Dyah Menur telah berusaha mengendapkan
hati, melihat tak sekadar menggunakan matanya, tetapi juga
mencoba menggunakan cara pandang lain, tentang bagaimana cara
pandang Raden Kudamerta. Menggunakan cara pandang itu, Dyah
Menur merasa amat maklum ketika Raden Kudamerta mengaku
belum beristri.
Dyah Menur Sekar Tanjung telah siap untuk mengalah dan
itulah yang akan dilakukan karena Raden Kudamerta hanya punya
satu pilihan, menempatkan Sekar Kedaton sebagai istrinya.
Artinya, itu sama halnya dengan tak mungkin menempatkan nama
Dyah Menur Sekar Tanjung sebagai istri pertama. Bahkan, Raden
Kudamerta harus menganggap nama Dyah Menur Hardiningsih itu
tidak pernah ada.
Dyah Wiyat yang membalikkan badan kebingungan. Ke mana
pun ia mencari, bayangan Sekar Tanjung tidak ditemukan.12
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Bagi Dyah Menur Sekar Tanjung, jawaban suaminya telah
membimbingnya ke mana harus melangkah.
Personifikasi
2 Setidaknya untuk waktu yang panjang, Dyah Menur telah
berusaha mengendapkan hati,
Metafora
3 Dyah Menur Sekar Tanjung telah siap untuk mengalah
dan itulah yang akan dilakukan karena Raden Kudamerta
hanya punya satu pilihan, menempatkan Sekar Kedaton
sebagai istrinya.
Antonomasia
12
Ibid., h. 498.

128
4 Ke mana pun ia mencari, bayangan Sekar Tanjung tidak
ditemukan.
Totem Proparte
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Bagi Dyah Menur Sekar Tanjung, jawaban suaminya
telah membimbingnya ke mana harus melangkah.
Periodik
2 Setidaknya untuk waktu yang panjang, Dyah Menur telah
berusaha mengendapkan hati, melihat tak sekadar
menggunakan matanya, tetapi juga mencoba
menggunakan cara pandang lain, tentang bagaimana cara
pandang Raden Kudamerta.
Periodik
Berimbang
3 Menggunakan cara pandang itu, Dyah Menur merasa
amat maklum ketika Raden Kudamerta mengaku belum
beristri.
Kendur
4 Dyah Menur Sekar Tanjung telah siap untuk mengalah
dan itulah yang akan dilakukan karena Raden Kudamerta
hanya punya satu pilihan, menempatkan Sekar Kedaton
sebagai istrinya.
Kendur
5 Artinya, itu sama halnya dengan tak mungkin
menempatkan nama Dyah Menur Sekar Tanjung sebagai
istri pertama.
Klimaks
6 Bahkan, Raden Kudamerta harus menganggap nama

129
Dyah Menur Hardiningsih itu tidak pernah ada.
7 Ke mana pun ia mencari, bayangan Sekar Tanjung tidak
ditemukan.
Periodik
1.6. Leraian
“Kamu akan ke mana?” bertanya Dyah Wiyat.
Dyah Menur Sekar Tanjung tidak tahu bagaimana cara
menjawab pertanyaan itu, mulutnya terkunci. Apabila Dyah Menur
mengira Sekar Kedaton akan marah ternyata dugaan itu salah.
Maharajasa mendekat sambil memerhatikan bayi dalam pelukan
Dyah Menur.
“Ini anakmu?”
Dyah Menur mengangguk, “Hamba, Tuan Putri,”
Dyah Wiyat memandang Dyah Menur dan Pradhabasu
bergantian. Perhatian selanjutnya kemudian lebih banyak ditujukan
kepada Dyah Menur. Pradhabasu yang memerhatikan wajah Dyah
Wiyat mampu menandai sikap damai tanpa permusuhan. Meskipun
kini telah mengetahui adanya hubungan khusus antara suaminya
dengan perempuan itu, hal itu tidak menjadi penyebab Sekar
Kedaton murka.
“Mengapa harus pergi?” Dyah Wiyat mengeluh.
Dyah Menur dan Pradhabasu saling pandang. Dyah Menur
masih terbungkam belum bisa memberi jawaban.
“Kembalilah ke istana,” ucap Rajadewi, “Marilah kita hidup
bersama-sama untuk saling melengkapi. Kau mempunyai hak
sebagai istri tua dan aku tidak akan merampas hak yang kaumiliki.”
Dyah Menur memandang Dyah Wiyat dengan tatapan mata
berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak menyangka Dyah Wiyat akan
mampu bersikap seperti itu. Dugaan dan penilaian yang terbentuk
seketika ambruk. Sekar Kedaton ternyata tidak seburuk yang ia
sangka. Dengan lengan bajunya, Dyah Menur membasuh air
matanya.

130
Dyah Wiyat mendekat dan menyentuh tangan Dyah Menur
ketika perempuan itu menitikkan air mata.
“Hamba tidak paham dengan apa yang Tuan Putri katakan,”
ucapnya lirih.
Dyah Wiyat Rajadewi Maharajasa bergegas memeluk. Dyah
Wiyat ternyata mampu menitikkan air mata. Sikap yang tidak
diduga itu menyebabkan Pradhabasu bingung.
“Apa yang aku inginkan sudah jelas, Sekar Tanjung,” kata
Dyah Wiyat. “Aku sama sekali tidak keberatan suamiku memiliki
istri lain selain diriku. Kembalilah ke istana dan marilah untuk
selalu berdekatan denganku.”13
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Mulutnya terkunci. Metafora
2 Apabila Dyah menur mengira Sekar Kedaton akan marah
ternyata dugaan itu salah.
Antonomasia
3 Maharajasa mendekat sambil memerhatikan bayi dalam
pelukan Dyah Menur.
Antonomasia
4 Dyah Menur mengangguk, “Hamba, Tuan Putri,” Antonomasia
5 Pradhabasu yang memerhatikan wajah Dyah Wiyat
mampu menandai sikap damai tanpa permusuhan.
Pleonasme
6 Hal itu tidak menjadi penyebab Sekar Kedaton murka. Antonomasia
7 “Mengapa harus pergi?” Dyah Wiyat mengeluh. Retoris
8 Dyah Menur masih terbungkam belum bisa memberi
jawaban.
Perifrasis
9 Dugaan dan penilaian yang terbentuk seketika
ambruk.
Hiperbola
13
Ibid., h.504-505.

131
10 “Hamba tidak paham dengan apa yang Tuan Putri
katakan,” ucapnya lirih.
Antonomasia
11 Dyah Wiyat ternyata mampu menitikkan air mata. Perifrasis
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Meskipun kini telah mengetahui adanya hubungan
khusus antara suaminya dengan perempuan itu, hal itu
tidak menjadi penyebab Sekar Kedaton murka.
Periodik
2 Dyah Wiyat mendekat dan menyentuh tangan Dyah
Menur ketika perempuan itu menitikkan air mata.
Berimbang
3 Dengan lengan bajunya, Dyah Menur membasuh air
matanya.
Periodik
2.6. Penyelesaian
Tawaran itu sungguh menggoda. Namun, Dyah Menur
bergeming bersikukuh dengan keputusannya.
Adalah Raden Kudamerta yang datang menyusul terheran-
heran melihat dua orang perempuan yang masing-masing adalah
istrinya itu saling berpelukan begitu kuat. Dyah Menur menangis
sesegukan di pelukan Maharajasa yang juga menangis sesegukan.
Dua perempuan itu membutuhkan waktu lebih lama untuk saling
berbagi.
Bagaikan tercekik leher Sri Wijaya Rajasa Sang Panji
Wahyuninghyun. Raden Kudamerta tidak mampu berbicara ketika
melihat dua perempuan itu akhirnya saling melepas pelukan. Meski
Dyah Wiyat Rajadewi Maharajasa telah meminta, Dyah Menur
Hardiningsih memiliki alasan untuk bersikukuh dengan keputusan
yang diambilnya. Dyah Menur sebenarnya punya kesempatan
untuk melihat wajah kekasih hatinya yang dicintai, namun tidak
diraihnya kesempatan itu.
Dyah Menur berbalik dengan memejamkan mata. Dyah Menur
Hardiningsih yang menggendong anaknya dan Pradhabasu yang

132
juga menggendong anaknya, berjalan makin jauh dan makin jauh
ke arah surya di langit barat. Dan sang waktu sebagaimana
kodratnya akan mengantarkan ke mana pun mereka melangkah.
Sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi
masa lalu.14
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Tawaran itu sungguh menggoda. Personifikasi
2 Namun, Dyah Menur bergeming bersikukuh dengan
keputusannya
Pleonasme
3 Dyah Menur menangis sesegukan di pelukan Maharajasa
yang juga menangis sesegukan.
Antonomasia
4 Dan sang waktu sebagaimana kodratnya akan
mengantarkan ke mana pun mereka melangkah.
Personifikasi
5 Sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa
menjadi masa lalu.
Personifikasi
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Gaya bahasa
1 Dyah Menur menangis sesegukan di pelukan Maharajasa
yang juga menangis sesegukan.
Tautotes
2 Raden Kudamerta tidak mampu berbicara ketika melihat
dua perempuan itu akhirnya saling melepas pelukan
Berimbang
3 Meski Dyah Wiyat Rajadewi Maharajasa telah meminta,
Dyah Menur Hardiningsih memiliki alasan untuk
bersikukuh dengan keputusan yang diambilnya.
Periodik
14
Ibid., h. 505-506.

133
4 Dyah Menur sebenarnya punya kesempatan untuk melihat
wajah kekasih hatinya yang dicintai, namun tidak
diraihnya kesempatan itu.
Berimbang
5 Dyah Menur Hardiningsih yang menggendong anaknya
dan Pradhabasu yang juga menggendong anaknya,
berjalan makin jauh dan makin jauh ke arah surya di
langit barat.
Berimbang
Dari hasil pendataan penggunaan sarana retorika berupa gaya bahasa
dan penyiasatan struktur kalimat pada alur bawahan yang menceritakan
tentang kisah segitiga antara Raden Kudamerta dan kedua istrinya ini,
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tahap Pengenalan
a. Gaya bahasa : 15 kali
b. Struktur Kalimat : 7 kali
Total : 22 kali penggunaan retorika tekstual
2. Tahap Konflik
a. Gaya bahasa : 6 kali
b. Struktur Kalimat : 10 kali
Total : 16 kali penggunaan Retorika tekstual
3. Sekuen Klimaks
a. Gaya bahasa : 6 kali
b. Struktur Kalimat : 4 kali
Total : 10 kali penggunaan retorika tekstual
4. Klimaks
a. Gaya bahasa : 11 kali
b. Struktur kalimat : 5 kali

134
Total : 16 kali penggunaan retorika tekstual
5. Sekuen Leraian
a. Gaya bahasa : 4 kali
b. Struktur Kalimat : 7 kali
Total : 11 kali penggunaan retorika tekstual
6. Leraian
a. Gaya bahasa : 11 kali
b. Struktur Kalimat : 3 kali
Total : 14 kali penggunaan retorika tekstual
7. Penyelesaian
a. Gaya bahasa : 5 kali
b. Struktur Kalimat : 5 kali
Total : 10 kali penggunaan retorika tekstual
Dari perolehan di atas dapat diketahui bahwa adegan paling sering
menggunakan sarana retorika dalam penyajiannya adalah adegan perkenalan,
yakni sebanyak 22 kali. Kemudian, urutan kedua pada adegan konflik dan
klimaks yang masing-masing menggunakan sarana retorika tekstual
sebanyak 16 kali dan pada urutan ketiga pada adegan leraian sebanyak 14
kali.
Adegan pengenalan menjadi adegan yang paling sering menggunakan
sarana retorika dalam alur bawahan yang pertama ini. Hal ini menunjukkan
perbedaan kepentingan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Jika
pada alur utama peristiwa yang ingin ditekankan adalah adegan percobaan
pembunuhan terhadap Raden Kudamerta, yang mana ini adalah adegan
klimaks, maka yang ingin ditonjolkan dalam alur bawahan pertama ini
adalah justru pada adegan perkenalannya.
Peristiwa yang diceritakan pada adegan perkenalan adalah ketika
Dyah Wiyat terpaksa menjalani pernikahannya dengan Raden Kudamerta.

135
Hal yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat seringnya penggunaan
sarana retorika dalam adegan ini adalah ingin menunjukkan betapa tokoh
seorang putri kerajaan tidaklah selamanya bisa bahagia dengan
kedudukannya. Masih banyak masyarakat awam yang mengira bahwa
kehidupan sebagai seorang anggota keluarga kerajaan sangat
membahagiakan. Namun, lewat adegan ini, pendapat seperti itu
terbantahkan. Bahwa Dyah Wiyat yang seharusnya bisa mengeluarkan
pendapat sebagai manusia pada umumnya, pada kisah ini terpaksa
mengendapkan isi hatinya karena terganjal status yang disandangnya. Ia tak
mampu mengatakan dengan jujur bahwa ia mencintai Ra Tanca karena tak
mungkin baginya dapat bersanding dengan seorang pengkhianat kerajaan.
Tak juga ia mampu menolak perjodohan itu karena sebagai putri kerajaan ia
tak benarkan untuk berbuat seperti itu.
Dapat dilihat, untuk mengungkapkan apa yang dialami oleh Dyah
Wiyat pada adegan ini, pengarang banyak menggunakan gaya bahasa
penegasan, seperti pleonasme, tautologi, dan perifrasis. Semua gaya bahasa
penegasan ini bertujuan untuk membuat pembaca percaya bahwa Dyah
Wiyat benar-benar tidak menyukai apa yang diperbuat keluarganya terhadap
dirinya. Selain itu, pengarang juga beberapa kali tercatat menggunakan gaya
bahasa hiperbola yang fungsinya untuk memberikan efek luar biasa dahsyat
terhadap suasana yang ingin digambarkan kepada pembaca. Tidak hanya itu,
metafora yang juga hadir mewarnai adegan ini memudahkan pembaca untuk
memaknai peristiwa ini.
Kompleksnya penggunaan sarana retorika pada adegan pengenalan di
alut tambahan ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah
untuk menarik perhatian pembaca yang dari awal membaca novel ini
disuguhkan dengan adegan-adegan pembunuhan dan ketegangan khas
politik. Lewat pengenalan alur ini, pengarang ingin menghadirkan sebuah
kisah yang tak kalah menegangkan, tapi dalam kemasan yang berbeda.

136
Pembaca akan tetap diajak untuk menikmati suasana tegang namun dengan
cerita yang lebih familiar, kisah percintaan. Bila pada alur utama bisa
mengaduk emosi pembaca, maka kisah cinta yang memang tak biasa ini
tentunya juga harus membuat perasaan pembaca hanyut.
Tujuan kedua adalah untuk mengantarkan pembaca kepada adegan-
adegan selanjutnya. Lewat penekanan-penekanan tentang perasaan Dyah
Wiyat, pembaca dibebaskan untuk menerka terlebih dahulu akan seperti
apakah rumah tangga mereka. Rupanya, cara ini cukup berhasil karena pada
adegan konflik, asumsi pembaca tentang keretakan rumah tangga mereka
terbukti karena Raden Kudamerta kedapatan memiliki istri lain dan ia pasrah
bila harus dihukum mati. Pada adegan inilah, pembaca bisa langsung
menebak bahwa rumah tangga mereka akan hancur. Kemudian, pada adegan
klimaks, pembaca akan dikagetkan karena tebakan mereka salah. Klimaks
yang menjadi titik emosi pembaca yang teraduk juga disajikan dengan
sarana retorika yang cukup banyak.
Adegan pengenalan ini disajikan dengan menggunakan tujuh kalimat
berimbang. Penggunaan kalimat berimbang ini secara garis besar berfungsi
untuk menginformasikan kepada pembaca bahwa ada dua hal penting yang
ingin disampaikan oleh pengarang. Ketika membaca kalimat yang disajikan
dengan konstruksi kalimat berimbang, apapun jenis kalimat majemuknya,
pembaca seolah akan dihadapkan pada dua gambaran yang sama-sama
sedang terjadi pada saat yang sama. Efek penggambaran yang seperti itulah
yang akan membuat pembaca merasa seperti masuk ke dalam cerita.
Penggunaan kalimat jenis periodik juga turut memiliki andil yang cukup
besar dalam pembangunan emosi pembaca. Dengan kalimat ini, pembaca
akan merasakan sensasi ketegangan dan penasaran.
Dengan seringnya penggunaan sarana retorika dalam adegan
pengenalan, pembaca merasa nyaman dan tetap terus mengikuti jalannya
cerita alur bawahan ini tanpa melepaskan konsentrasi pada alur utama.

137
3. Analisis Penggunaan Sarana Retorika pada Alur Tambahan Kedua
3.1. Pengenalan
“Pradhabasu,” kata Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri.
“Hamba, Tuan Putri,” jawab Pradhabasu sigap.
“Aku mempunyai sebuah pertanyaan untukmu,” Ibu Ratu
Biksuni berbicara. “Apakah kamu masih akan membiarkan dirimu
terseret ke mata rantai sakit hati dan dendam? Waktu telah lama
berlalu, apakah sebagai ungkapan rasa tidak sependapat kau masih
akan tetap berada di luar sana? Sebagai ganti sementara Anakmas
Sri Jayanegara yang telah kembali ke Swargaloka sebelum nanti
diputuskan siapa raja yang baru, aku ingin menawarkan kepadamu
untuk kembali. Pintu Bhayangkara masih terbuka untukmu.
Bukankah demikian, Gajah Enggon?”
Gajah Enggon yang tidak menduga akan mendapatkan
limpahan pertanyaan yang mendadak berbelok ke dirinya itu segera
merapatkan dua telapak tangannya dalam sikap menyembah.
“Hamba, Tuan Putri,” jawab Gajah Enggon. “Hamba
sependapat dengan Tuan Putri Ratu. Pada saat terakhir walaupun
Adi Pradhabasu berada di luar Bhayangkara, kembali ia telah
membuat jasa. Kalau tidak karena kesigapannya, barangkali pisau
itu telah menancap di bagian yang berbahya di dada Raden
Kudamerta. Mungkin bisa terkena jantungnya. Sebagaimana Tuan
Putri Ratu Rajapatni Biksuni, hamba juga amat berharap Adi
Pradhabasu akan kembali menjadi bagian dari Bhayangkara.”
Senyap merayap. Dalam waktu sedikit lama Bhayangkara
Pradhabasu meletakkan dua telapak tangannya di dada dan dengan
amat perlahan membawanya ke ujung hidung. Dengan segera
Pradhabasu teringat peristiwa sembilan tahun yang lalu, waktu
yang sebenarnya cukup lama, namun serasa terjadi masih kemarin
petang. Apa yang menimpa sahabat kentalnya, yang sangat kental
hubungan persaudaraan itu, tertebas kepalanya oleh fitnah yang
dilakukan Bango Lumayang atau Singa Parepen. Gagak Bongol
yang tidak berpikir ulang setelah melihat remah jagung pakan
burung merpati yang diduga sebagai alat pengirim berita ke
Majapahit langsung menebas kepalanya dari belakang. Apa yang
dilakukan Gagak Bogol itu terjadi tepat di depan matanya.15
15
Ibid., h. 173-174.

138
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 “Pradhabasu,” kata Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. Antonomasia
2 “Hamba, Tuan Putri,” jawab Pradhabasu sigap. Antonomasia
3 “Aku mempunyai sebuah pertanyaan untukmu,” Ibu Ratu
Biksuni berbicara.
Antonomasia
4 “Apakah kamu masih akan membiarkan dirimu terseret
ke mata rantai sakit hati dan dendam?
Perifrasis
5 Waktu telah lama berlalu, apakah sebagai ungkapan rasa
tidak sependapat kau masih akan tetap berada di luar
sana?
Retoris
6 Sebagai ganti sementara Anakmas Sri Jayanegara yang
telah kembali ke Swargaloka sebelum nanti diputuskan
siapa raja yang baru, aku ingin menawarkan kepadamu
untuk kembali.
Metafora
7 Bukankah demikian, Gajah Enggon?” Retoris
8 Gajah Enggon yang tidak menduga akan mendapatkan
limpahan pertanyaan
Hiperbola
9 “Hamba, Tuan Putri,” jawab Gajah Enggon. “Hamba
sependapat dengan Tuan Putri Ratu.
Antonomasia
10 Sebagaimana Tuan Putri Ratu Rajapatni Biksuni, hamba
juga amat berharap Adi Pradhabasu akan kembali
menjadi bagian dari Bhayangkara.”
Antonomasia
11 Senyap merayap. Personifikasi
12 Senyap merayap. Asonansi

139
13 Apa yang menimpa sahabat kentalnya, yang sangat kental
hubungan persaudaraan itu, tertebas kepalanya oleh fitnah
yang dilakukan Bango Lumayang atau Singa Parepen.
Personifikasi
14 Apa yang dilakukan Gagak Bogol itu terjadi tepat di
depan matanya.
Pleonasme
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Sebagai ganti sementara Anakmas Sri Jayanegara yang
telah kembali ke Swargaloka sebelum nanti diputuskan
siapa raja yang baru, aku ingin menawarkan kepadamu
untuk kembali.
Periodik
2 Pada saat terakhir walaupun Adi Pradhabasu berada di
luar Bhayangkara, kembali ia telah membuat jasa.
Periodik
3 Kalau tidak karena kesigapannya, barangkali pisau itu
telah menancap di bagian yang berbahya di dada Raden
Kudamerta.
Periodik
4 Sebagaimana Tuan Putri Ratu Rajapatni Biksuni, hamba
juga amat berharap Adi Pradhabasu akan kembali
menjadi bagian dari Bhayangkara.”
Periodik
3.2. Konflik
“Pradhabasu,” Ratu Gayatri berkata dengan suara lirih.
Pradhabasu sangat sibuk dengan dirinya sendiri. itu sebabnya,
Pradhabasu tidak mendengar panggilan itu. Barulah ketika
Pradhabasu menengadah, ia terkejut melihat pandangan Ratu
Rajapatni Biksuni Gayatri tertuju kepadanya. Tidak hanya
pandangan Ratu Gayatri, tetapi juga pandangan Arya Tadah.

140
Pradhabasu tersadar ada yang terlewat dari perhatiannya. Bergegas
Pradhabasu menyembah.
“Kau telah mendengar apa yang dikatakan Gagak Bongol.”
Pradhabasu masih dalam sikap menyembah dan tidak
menurunkan tangannya.
“Hamba, Tuan Putri,” jawabnya.
“Aku ingin mendengar apa tuntutannmu?” tanya Gayatri.
Pradhabasu membalas tatapan mata Ratu Rajapatni Biksuni
Gayatri dengan tidak berkedip. Pandangan ini kemudian dialihkan
ke permukaan wajah Mapatih Arya Tadah serta dengan perlahan
Pradhabasu mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Mada.
Setelah kembali menyembah, Pradhabasu beringsut agar bisa
bertatapan mata dengan Gagak Bongol. Setelah sekian lama
meninggalkan Bhayangkara, inilah saatnya Pradhabasu berjumpa
kembali dengan Gagak Bongol.
“Katakan apa tuntutanmu, Pradhabasu,” berkata Ratu Gayatri.
“Apabila kau kauwakili anak Mahisa Kingkin, tuntutan apakah
yang kauajukan terhadap kecerobohan Gagak Bongol yang menjadi
penyebab kematian ayahnya?”
Pradhabasu memandang Gagak Bongol. Sebaliknya, Gagak
Bongol tak merasa segan untuk membalas tatapan mata itu. Jauh di
dalam hati Gagak Bongol terpendam kerinduan kepada sahabatnya,
rindu bisa bergaul sebagaimana dulu pernah bersama. Canda dan
gurau itu tak mungkin terjadi karena munculnya ganjalan yang
membelah di antara mereka.
“Mohon izin untuk berbicara blak-blakan, Tuan Putri Ratu,”
kata Pradhabasu.
“Jika itu yang kau kehendaki, kau tidak perlu merasa sungkan!
Dan, sejak awal kau sudah kuminta berbicara blak-blakan,” jawab
Ratu Rajapatni Gayatri dengan suara amat tenang.
Pradhabasu mengangguk.
“Hamba tidak akan menempatkan diri mewakili keponakan
hamba menuntut agar dijatuhkan hukuman kepada Kakang Gagak
Bongol. Apabila bocah itu menuntut balas mungkin hamba yakin
keponakan hamba tak mungkin bisa melakukan. Dalam kesempatan
ini hamba hanya ingin mengajukan permohonan agar Kakang
Gagak Bongol membantu mengasuh bocah itu, syukur-syukur
kalau Kakang Bongol mau mengambilnya sebagai anak. Itu
permohonan hamba.”16
16
Ibid., h. 188-189.

141
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Barulah ketika Pradhabasu menengadah, ia terkejut
melihat pandangan Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tertuju
kepadanya.
Antonomasia
2 “Hamba, Tuan Putri,” jawabnya. Antonomasia
3 Pradhabasu membalas tatapan mata Ratu Rajapatni
Biksuni Gayatri dengan tidak berkedip
Antonomasia
4 Pradhabasu membalas tatapan mata Ratu Rajapatni
Biksuni Gayatri dengan tidak berkedip
Pleonasme
5 Jauh di dalam hati Gagak Bongol terpendam kerinduan
kepada sahabatnya, rindu bisa bergaul sebagaimana dulu
pernah bersama.
Hiperbola
6 Canda dan gurau itu tak mungkin terjadi karena
munculnya ganjalan yang membelah di antara mereka.
Metafora
7 “Mohon izin untuk berbicara blak-blakan, Tuan Putri
Ratu,” kata Pradhabasu.
Antonomasia
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Barulah ketika Pradhabasu menengadah, ia terkejut
melihat pandangan Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tertuju
kepadanya.
Periodik
2 Bergegas Pradhabasu menyembah. Inversi
3 Tidak hanya pandangan Ratu Gayatri, tetapi juga
pandangan Arya Tadah.
Berimbang

142
4 Setelah kembali menyembah, Pradhabasu beringsut agar
bisa bertatapan mata dengan Gagak Bongol.
Periodik
5 Setelah sekian lama meninggalkan Bhayangkara, inilah
saatnya Pradhabasu berjumpa kembali dengan Gagak
Bongol.
Periodik
6 “Apabila kau kauwakili anak Mahisa Kingkin, tuntutan
apakah yang kauajukan terhadap kecerobohan Gagak
Bongol yang menjadi penyebab kematian ayahnya?”
Periodik
7 Canda dan gurau itu tak mungkin terjadi karena
munculnya ganjalan yang membelah di antara mereka.
Kendur
8 “Jika itu yang kau kehendaki, kau tidak perlu merasa
sungkan!
Periodik
9 Apabila bocah itu menuntut balas mungkin hamba yakin
keponakan hamba tak mungkin bisa melakukan.
Periodik
10 Dalam kesempatan ini hamba hanya ingin mengajukan
permohonan agar Kakang Gagak Bongol membantu
mengasuh bocah itu, syukur-syukur kalau Kakang Bongol
mau mengambilnya sebagai anak. Itu permohonan
hamba.”
Berimbang
3.3.Sekuen Klimaks
“Bagaimana, Gagak Bongol? Kalimat balasan macam apa yang
kausiapkan menjawab tuntutan yang diajukan Pradhabasu? Kalau
kau merasa tak mampu, dengan senang hati aku akan mewakilimu
memungut bocah ini sebagai anakku.”
Gugup Gagak Bongol menyembah.
“Hamba, Tuan Putri,” jawab Gagak Bongol. “Apa yang
menjadi permintaan Adi Pradhabasu menurut hamba bukan sebuah
hukuman, tetapi merupakan anugerah tiada tara. Dengan senang
hati hamba akan menganggap Prajaka sebagai anak hamba. Hamba
akan mengasihi Prajaka dengan sepenuh hati.”
“Meski keadaan bocah itu seperti itu?” balas Ratu Gayatri.

143
“Hamba, Tuan Putri,” jawab Gagak Bongol mantap.
Senyum Ratu Gayatri berlepotan teka-teki.
“Mengasuh Sang Prajaka jauh lebih sulit daripada bertarung
melawan musuh, dan Pradhabasu telah berhasil melaksanakan
tugas itu dengan amat baik. Kelak kita akan melihat apakah Gagak
Bongol akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah dan
ibu sekaligus, atau gagal.”
Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tersenyum, dan ia satu-satunya
yang berhasil tersenyum di ruangan itu. Arya Tadah tidak mampu
mengalihkan pandangannya dari wajah Sang Prajaka sambil
berusaha keras menemukan keyakinan, benarkah Gagak Bongol
menganggap hal itu sebagai anugerah. Bukan pekerjaan yang
gampang untuk mengasuh bocah yang memiliki cacat jiwa
semacam itu.
Padahal, Gagak Bongol benar-benar menganggapnya sebagai
anugerah. Sekian tahun Gagak Bonol dibayangi rasa bersalah, kali
ini tiba-tiba mendapat kesempatan untuk menebus kesalahan itu
dengan memungut keturunan Mahisa Kingkin sebagai anak meski
keadaan bocah itu tidak waras, cacat pada jiwanya.
Bhayangkara Gagak Bongol beringsut mendekat dan
memerhatikan keadaan Sang Prajaka dengan lebih cermat. Yang
tampak di matanya tak hanya wujud bocah itu yang memang
menyedihkan, namun lebih jauh terlihat jelas betapa berat beban
yang disangga Pradhabasu dalam mengasuhnya, mengerjakan
sebuah tugas yang mestinya bukan tugasnya karena orang yang
memiliki kewajiban mengerjakan tugas itu telah tumpas dirapas
hidupnya. Gemetar Bhayangkara Gagak Bongol beringsut semakin
mendekat sambil menjulurkan tangannya. Gagak Bongol
bermaksud berakrab-akrab dengan bocah itu. Namun, yang tak
diduga oleh Gagak Bongol adalah apa yang dilakukan Sang
Prajaka, yang tiba-tiba mengayunkan tangannya mencakar
wajahnya. Gagak Bongol terhenyak amat kaget.
“Gila,” Gagak Bongol meletupkan umpatannya dalam hati.
Gajah Mada terkejut. Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri
tersentak, demikian pula dengan Mahapatih Arya Tadah. Senopati
Gajah Enggon terhenyak kaku, terperangah oleh kejadian yang tak
terduga itu. Gagak Bongol yang tidak menyangkahal itu akan
terjadi merasakan perih di kulit wajahnya. Di antara rasa kaget dari
semua yang hadir, hanya Pradhabasu yang tak kaget. Pradhabasu
seorang yang tersenyum, amat lugas senyum ia umbar tanpa
tendheng aling-aling, Pradhabasu yang amat mengenal bagaimana

144
perilaku keponakannya tidak kaget lagi bocah itu sanggup
melakukan hal itu.17
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 ”Kalimat balasan macam apa yang kausiapkan menjawab
tuntutan yang diajukan Pradhabasu?”
Perifrasis
2 “Hamba, Tuan Putri,” jawab Gagak Bongol. Antonomasia
3 “Apa yang menjadi permintaan Adi Pradhabasu menurut
hamba bukan sebuah hukuman, tetapi merupakan
anugerah tiada tara.
Hiperbola
4 ”Hamba akan mengasihi Prajaka dengan sepenuh hati.” Hiperbola
5 “Hamba, Tuan Putri,” jawab Gagak Bongol mantap. Antonomasia
6 Senyum Ratu Gayatri berlepotan teka-teki. Metafora
7 Bukan pekerjaan yang gampang untuk mengasuh bocah
yang memiliki cacat jiwa semacam itu.
Perifrasis
8 Yang tampak di matanya tak hanya wujud bocah itu yang
memang menyedihkan, namun lebih jauh terlihat jelas
betapa berat beban yang disangga Pradhabasu dalam
mengasuhnya.
Hiperbola
9
Pradhabasu seorang yang tersenyum, amat lugas senyum
ia umbar tanpa tendheng aling-aling,
Pleonasme
17
Ibid., h. 193-194.

145
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 “Kalau kau merasa tak mampu, dengan senang hati aku
akan mewakilimu memungut bocah ini sebagai anakku.”
Periodik
2 Dengan senang hati hamba akan menganggap Prajaka
sebagai anak hamba.
Periodik
3 “Apa yang menjadi permintaan Adi Pradhabasu menurut
hamba bukan sebuah hukuman, tetapi merupakan
anugerah tiada tara.”
Berimbang
4 “Mengasuh Sang Prajaka jauh lebih sulit daripada
bertarung melawan musuh dan Pradhabasu telah berhasil
melaksanakan tugas itu dengan amat baik.
Berimbang
5 Kelak kita akan melihat apakah Gagak Bongol akan bisa
melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah dan ibu
sekaligus, atau gagal.”
Berimbang
6 Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tersenyum, dan ia satu-
satunya yang berhasil tersenyum di ruangan itu.
Berimbang
7 Yang tampak di matanya tak hanya wujud bocah itu yang
memang menyedihkan, namun lebih jauh terlihat jelas
betapa berat beban yang disangga Pradhabasu dalam
mengasuhnya,
Berimbang
3.4. Klimaks
“Tuan Putri,” Pradhabasu memecah keheningan sambil
merapatkan masing-masing telapak tangannya dalam sikap
menyembah.
Ratu Rajapatni Biksuni yang kembali duduk memberinya
kesempatan unuk berbicara melalui isyarat tanganya.

146
“Hamba merasa keperluan hamba menghadap kali ini telah
terwadahi. Oleh karena itu hamba mohon izin meninggalkan
pertemuan ini,” berkata Pradhabasu.
Dari tempat duduknya, Patih Daha Gajah Mada merasa desir
tajam merayapi permukaan jantungnya. Patih Daha Gajah Mada
benar-benar tidak mengira Pradhabasu bersungguh-sungguh
dengan niatnya menyerahkan Prajaka kepada Gagak Bongol.
Demikian juga Mahapatih Amangkubumi Arya Tadah, menyimpan
perasaan serupa dengan Gajah Mada. Untuk beberapa saat Ratu
Biksuni Gayatri terdiam tak berbicara. Dengan berpamitan seperti
itu, Pradhabasu benar-benar mengabaikan tawaran yang ia berikan
utnuk kembali bergabung dan mengabdi menjadibagian dari
pasukan yang pernah ditinggalkannya, Bhayangkara.
Di tempat duduknya, Gagak Bongol kebingungan dalam
upayanya menerka, bagaimana warna hati Pradhabasu sebenarnya.
Ketika semua yang hadir di ruangan itu merasa persoalan yang
diajukan Gagak Bongol masih belum tuntas, sikap Ratu Gayatri
takkalah mengagetkan. Ratu Gayatri malah tersenyum dan
mengangguk.
“Silakan, Pradhabasu, aku izinkan kau meninggalkan tempat
ini,” jawab Ratu Gayatri.
Arya Tadah, Patih Daha Gajah Mada, Senopati Gajah Enggon
dan Bhayangkara Gagak Bongol sendiri, semua dilibas pesona sihir
saat sebelum beringsut meninggalkan ruang pertemuan itu
Pradhabasu sempat menyempatkan memeluk Sang Prajaka.
Dipeluknya bocah itu dengan erat, dibusainya kepala Prajaka
dengan penuh penghayatan dan perasaan. Terlihat sangat lugas
betapa sebenarnya Pradabhasu mengalami kesulitan berpisah dari
keponakannya.
Merinding Gajah Mada melihat bocah remaja bernama Prajaka
itu kebingungan dan agaknya dililit cemas yang luar biasa bakal
berpisah dari orang yang selama ini memberikan cinta dan
perlindungan kepadanya.
Akhirnya, Pradhabasu merasa telah tiba wakunya melepas
pelukan Prajaka. Tanpa banyak bicara dan dengan wajah yang
membeku Pradhabasu beringsut mundur menuju pintu. Setelah
menyembah diarahkan kepada Ratu Gayatri, Pradhabasu berdiri
dan membuka pintu. Ketika Pradhabasu telah berada di luar adalah
bersamaan dengan suara meraung yang amat dikenali. Seperti
binatang, Prajakan melolong meneriakkan kecemasannya. Sang
Prajaka yang tiba-tiba mampu berpikir, sebuah pintu yang tebal
yang ia tidak tahu bagaimana cara membukanya.

147
Namun, Pradhabasu memang telah bulat dengan rencana yang
telah dirancang. Untuk sebuah tugas yang ia bebankan di pundak
sendiri, Pradhabasu membutuhkan keleluasaan gerak sambil
memberi pelajaran kepada Gagak Bongol. Menghadapi musuh di
medan pertarungan memang jauh lebih mudah daripada
menghadapi Sang Prajaka. Pradhabasu yakin Gagak Bongol tidak
mampu menghadapi bocah itu.18
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 “Tuan Putri,” Pradhabasu memecah keheningan Antonomasia
2 Pradhabasu memecah keheningan Metafora
3 Dari tempat duduknya, Patih Daha Gajah Mada merasa
desir tajam merayapi permukaan jantungnya.
Personifikasi
4 Dari tempat duduknya, Patih Daha Gajah Mada merasa
desir tajam merayapi permukaan jantungnya.
Hiperbola
5 Untuk beberapa saat Ratu Biksuni Gayatri terdiam tak
berbicara
Pleonasme
6 Dengan berpamitan seperti itu, Pradhabasu benar-benar
mengabaikan tawaran yang ia berikan utnuk kembali
bergabung dan mengabdi menjadi bagian dari pasukan
yang pernah ditinggalkannya, Bhayangkara.
Perifrasis
7 Di tempat duduknya, Gagak Bongol kebingungan dalam
upayanya menerka, bagaimana warna hati Pradhabasu
sebenarnya.
Metafora
8 Arya Tadah, Patih Daha Gajah Mada, Senopati Gajah
Enggon dan Bhayangkara Gagak Bongol sendiri, semua
dilibas pesona sihir saat sebelum beringsut meninggalkan
Hiperbola
18
Ibid., h. 195-197.

148
ruang pertemuan itu Pradhabasu sempat menyempatkan
memeluk Sang Prajaka.
9 Merinding Gajah Mada melihat bocah remaja bernama
Prajaka itu kebingungan agaknya dililit cemas yang luar
biasa bakal berpisah
Personifikasi
10 Merinding Gajah Mada melihat bocah remaja bernama
Prajaka itu kebingungan agaknya dililit cemas yang luar
biasa bakal berpisah
Hiperbola
11 Tanpa banyak bicara dan dengan wajah yang membeku
Pradhabasu beringsut mundur menuju pintu.
Metafora
12 Seperti binatang, Prajakan melolong meneriakkan
kecemasannya.
Simile
13 Namun, Pradhabasu memang telah bulat dengan rencana
yang telah dirancang.
Hiperbola
14 Pradhabasu membutuhkan keleluasaan gerak sambil
memberi pelajaran kepada Gagak Bongol.
Metafora
15 Untuk sebuah tugas yang ia bebankan di pundak sendiri. Pars Prototo
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 “Hamba merasa keperluan hamba menghadap kali ini
telah terwadahi.
Berimbang
2 Oleh karena itu hamba mohon izin meninggalkan
pertemuan ini,”
3 Dari tempat duduknya, Patih Daha Gajah Mada merasa
desir tajam merayapi permukaan jantungnya.
Periodik

149
4 Dengan berpamitan seperti itu, Pradhabasu benar-benar
mengabaikan tawaran yang ia berikan utnuk kembali
bergabung dan mengabdi menjadi bagian dari pasukan
yang pernah ditinggalkannya, Bhayangkara.
Periodik
5 Di tempat duduknya, Gagak Bongol kebingungan dalam
upayanya menerka, bagaimana warna hati Pradhabasu
sebenarnya.
Periodik
6 Ketika semua yang hadir di ruangan itu merasa persoalan
yang diajukan Gagak Bongol masih belum tuntas, sikap
Ratu Gayatri tak kalah mengagetkan.
Periodik
7
Dipeluknya bocah itu dengan erat, dibusainya kepala
Prajaka dengan penuh penghayatan dan perasaan.
Klimaks
8 Terlihat sangat lugas betapa sebenarnya Pradbahasu
mengalami kesulitan berpisah dari keponakannya.
9 Merinding Gajah Mada melihat bocah remaja bernama
Prajaka itu kebingungan
Invers
10 Tanpa banyak bicara dan dengan wajah yang membeku
Pradhabasu beringsut mundur menuju pintu.
Periodik
11 Setelah menyembah diarahkan kepada Ratu Gayatri,
Pradhabasu berdiri dan membuka pintu.
Periodik
12
Ketika Pradhabasu telah berada di luar adalah bersamaan
dengan suara meraung yang amat dikenali. Seperti
binatang, Prajakan melolong meneriakkan kecemasannya.
Periodik
13 Untuk sebuah tugas yang ia bebankan di pundak sendiri,
Pradhabasu membutuhkan keleluasaan gerak sambil
memberi pelajaran kepada Gagak Bongol.
Periodik

150
3.5. Sekuen Leraian
Meski Pradhabasu telah berhadapan dengan Gajah Mada,
perhatian bekas prajurit Bhayangkara itu tertuju ke arah lain. Di
arah yang menjadi perhatiannya, seorang bocah sedang sibuk
dengan dirinya sendiri. Hanya dua hari Pradhabasu berpisah dari
bocah itu, namun rasanya waktu berlalu setahun lamanya. Rasa
kangen membelit hatinya.
“Gagak Bogol berhasil mengendalikannya,” kata Gajah Mada.
Pradhabasu mengangguk.
“Bagaimana rasanya berpisah dari Sang Prajaka dalam dua hari
ini?” tanya Gajah Mada.
Pradhabasu tersenyum lebar, “Seperti setahun lamanya.”19
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Rasa kangen membelit hatinya. Personifikasi
2 Pradhabasu tersenyum lebar, “Seperti setahun lamanya.” Hiperbola
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Meski Pradhabasu telah berhadapan dengan Gajah Mada,
perhatian bekas prajurit Bhayangkara itu tertuju ke arah
lain.
Periodik
2 Hanya dua hari Pradhabasu berpisah dari bocah itu,
namun rasanya waktu berlalu setahun lamanya.
Berimbang
19
Ibid., h. 361.

151
3.6.Leraian
Boleh dikata kepanikan Gagak Bongol dan kepanikan Dyah
Wiyat di siang bolong itu jelas berbeda. Gagak Bongol mencari-
cari dengan mata melotot hampir lepas dari kelopaknya, namun
yang cari tidak ditemukan. Gagak Bongol layak khawatir. Jika
Sang Prajaka sampai hilang, Pradhabasu pasti tidak akan
memaafkannya.
“Kamu lihat Prajaka?” Gagak Bongol bertanya kepada salah
seorang laki-laki yang ikut menyaksika kesibukan yang terjadi di
Balai Prajurit.
Orang itu menggeleng, Gagak Bongol yang panik berlarian
mencari, namun yang dicari lenyap bagai dibawa hantu. Gagak
Bongol berputar-putar sambil menyapu dengan tatapan matanya,
namun Prajaka lenyap. Benar-benar lenyap.
“Ke mana bocah itu? Atau, jangan-jangan ada yang
membawanya pergi dengan diam-diam. Kalau hilang bocah itu,
Pradhabasu benar-benar akan membunuhku.”
Balai Prajurit kembali sepi. Gagak Bongol seharusnya kembali
ke Antawulan untuk memimpin kerja besar yang dipercayakan
kepadanya. Namun, hilangnya bocah lasak Sang Prajaka yang kini
menjadi anak angkatnya menyebabkan Gagak Bongol harus
mendahulukan mencarinya. Beruntunglah Gagak Bongol karena
Senopati Gajah Enggon mendatanginya dengan langkah lebar.
“Kamu kebingungan mencari apa?” tanya Gajah Enggon.
Betapa cemas Gagak Bongol, terbaca dari wajahnya.
“Aku kehilangan Sang Prajaka,” jawabnya.
Melihat Gagak Enggon bingung karena kehilangan tidak
menyebabkan Gajah Enggon ikut bingung. Senyumnya malah
lebar. Gagak Bongol mengerutkan dahi.
“Pradhabasu menitipkan ini untukmu,” kata Gajah Enggon
sambil menyerahkan lembaran rontal yang dipegangnya.
Betapa tegang Gagak Bongol dalam membaca surat itu.20
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Gagak Bongol mencari-cari dengan mata melotot hampir
lepas dari kelopaknya, namun yang cari tidak ditemukan.
Hiperbola
20
Ibid., h. 500-501.

152
2 Gagak Bongol yang panik berlarian mencari, namun yang
dicari lenyap bagai dibawa hantu.
Simile
3
Gagak Bongol berputar-putar sambil menyapu dengan
tatapan matanya, namun Prajaka lenyap.
Metafora
4 Gagak Bongol berputar-putar sambil menyapu dengan
tatapan matanya, namun Prajaka lenyap.
Pleonasme
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Gagak Bongol mencari-cari dengan mata melotot hampir
lepas dari kelopaknya, namun yang cari tidak ditemukan.
Berimbang
2 Jika Sang Prajaka sampai hilang, Pradhabasu pasti tidak
akan memaafkannya.
Periodik
3 Gagak Bongol yang panik berlarian mencari, namun yang
dicari lenyap bagai dibawa hantu.
Berimbang
4 Gagak Bongol berputar-putar sambil menyapu dengan
tatapan matanya, namun Prajaka lenyap.
Berimbang
5 Kalau hilang bocah itu, Pradhabasu benar-benar akan
membunuhku.
Periodik
6 Beruntunglah Gagak Bongol karena Senopati Gajah
Enggon mendatanginya dengan langkah lebar.
Kendur
3.7. Penyelesaian
“Aku sangat berterima kasih telah kaujaga anakku,”
Pradhabasu berkata di dalam suratnya. “Kini tiba saatnya aku
meminta kembali Sang Prajaka. Untuk selanjutnya, mari kita
lupakan apa yang terjadi di masa lalu.”

153
Gagak bongol langsung lunglai. Udara yang dihirup bagai
belum mencukupi paru-parunya.
“Anak itu sudah diserahkan kepadaku dan aku mulai
menyukainya. Mengapa ia meminta kembali?” Gagak Bongol
meledakkan isi dadanya.
Gajah Mada yang mendekat tidak memberikan sumbangan
pendapat apa pun.
“Sudahlah,” kata Senopati Enggon. “Pradhabasu mungkin
hanya sedang memberi pelajaran kepadamu. Jika Pradhabasu
mengambil kembali anaknya, itu karena anak itu memang miliknya
maka wajar kalau ia meminta kembali.”
Gagak Bongol mengalami kesulitan untuk menerima keadaan
itu. Akan tetapi, bila Pradhabasu meminta kembali, mau apa?
Dengan hati yang tak lagi penuh karena sebagian telah berongga,
Gagak Bongol memacu kudanya kembali memimpin kerja besar
pencandian dan pendarmaan Sang Prabu Jayanegara. Kerja besar
yang butuh waktu beberapa hari itu harus dilanjutkan.21
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Udara yang dihirup bagai belum mencukupi paru-
parunya.
Simile
2 “Mengapa ia meminta kembali?” Gagak Bongol
meledakkan isi dadanya
Hiperbola
3 Pradhabasu mungkin hanya sedang memberi pelajaran
kepadamu.
Metafora
21
Ibid., h. 501.

154
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 “Anak itu sudah diserahkan kepadaku dan aku mulai
menyukainya.
Berimbang
2 Jika Pradhabasu mengambil kembali anaknya, itu karena
anak itu memang miliknya maka wajar kalau ia meminta
kembali.
Periodik
3 Dengan hati yang tak lagi penuh karena sebagian telah
berongga, Gagak Bongol memacu kudanya kembali
memimpin kerja besar pencandian dan pendarmaan Sang
Prabu Jayanegara.
Periodik
Dari hasil pendataan penggunaan sarana retorika berupa gaya bahasa
dan penyiasatan struktur kalimat terhadap alur tambahan kedua yang berkisah
tentang perseteruan antara Gagak Bongol dengan Pradhabasu, penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Tahap Pengenalan
a. Gaya bahasa : 14 kali
b. Struktur Kalimat : 4 kali
Total :18 kali penggunaan retorika tekstual
2. Tahap Konflik
a. Gaya bahasa : 7 kali
b. Struktur Kalimat : 10 kali
Total : 17 kali penggunaan retorika tekstual
3. Sekuen Klimaks
a. Gaya bahasa : 9 kali

155
b. Struktur Kalimat : 7 kali
Total : 16 kali penggunaan retorika tekstual
4. Klimaks
a. Gaya bahasa : 15 kali
b. Struktur kalimat : 13 kali
Total : 28 kali penggunaan retorika tekstual
5. Sekuen Leraian
a. Gaya bahasa : 2 kali
b. Struktur Kalimat : 2 kali
Total : 4 kali penggunaan retorika tekstual
6. Leraian
a. Gaya bahasa : 4 kali
b. Struktur Kalimat : 6 kali
Total : 10 kali penggunaan retorika tekstual
7. Penyelesaian
a. Gaya bahasa : 3 kali
b. Struktur Kalimat : 3 kali
Total : 6 kali penggunaan retorika tekstual
Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa tahap yang paling sering
menggunakan sarana retorika dalam penyajiannya terdapat pada tahap klimaks,
yaitu sebanyak dua puluh delapan kali. Hal ini sama dengan apa yang terjadi
pada alur utama pada novel ini yang penggunaan sarana retorika tekstual
terbanyak terletak pada tahap klimaks.
Klimaks pada alur bawahan kedua ini bercerita tentang kebulatan hati
Pradhabasu yang ingin meninggalkan Prajaka di bawah asuhan Gagak Bongol.
Dengan seringnya digunakan sarana retorika dalam novel ini, dapat diketahui
bahwa klimaks dalam alur ini begitu penting untuk menghasilkan efek yang
dramatis. Semua tokoh yang terlibat dalam alur ini tidak menyangka bahwa

156
Pradhabasu yang sangat menyayangi keponakannya itu akan bersungguh-
sungguh menyerahkan hak asuhnya kepada Gagak Bongol yang begitu ia benci.
Suasana kaget dan tidak percaya inilah yang hendak diwujudkan oleh
pengarang dengan seringnya penggunaan sarana retorika dalam penyajiannya.
Untuk mencapai efek tersebut, dalam penyajian tahap ini, pengarang
menggunakan gaya bahasa antonomasia, metafora, personifikasi, hiperbola,
pleonasme, perifrasis, simile dan pars prototo.
Penggunaan gaya bahasa penekanan, seperti pleonasme dan perifrasis,
dimanfaatkan untuk memberikan penekanaan pada makna yang hendak
disampaikan. Kedua gaya bahasa ini digunakan pada kalimat, “Untuk beberapa
saat Ratu Biksuni Gayatri terdiam tak berbicara” (pleonasme) dan “Dengan
berpamitan seperti itu, Pradhabasu benar-benar mengabaikan tawaran yang ia
berikan untuk kembali bergabung dan mengabdi menjadi bagian dari pasukan
yang pernah ditinggalkannya, Bhayangkara. (perifrasis)
Dari kalimat bergaya bahasa pleonasme tersebut, pengarang ingin agar
pembaca benar-benar yakin bahwa Gayatri benar-benar kehilangan kata-kata
untuk membalas pamit Pradhabasu. Begitu pula halnya dengan penggunaan
gaya bahasa perifrasis pada kalimat tersebut. Lewat kalimat ini, pembaca bisa
mendapatkan info bahwa sebelumnya, Pradhabasu pun menjadi prajurit di
Bhayangkara.
Penggunaan gaya bahasa kiasan yang berupa metafora, personifikasi,
simile, dan juga pars prototo juga menambah semarak efek yang dirasakan oleh
pembaca. Lewat gaya bahasa-gaya bahasa inilah, pembaca bisa mendapatkan
gambaran jelas tentang suasana yang disajikan. Dengan begitu, pembaca
dengan mudah memaknai amanat yang hendak disampaikan.
Tidak hanya itu, penggunaan struktur kalimat periodik pada tahap
klimaks ini menambahkan efek tegang dan penasaran sedangkan penggunaan
kalimat berimbang digunakan pengarang untuk membuat pembaca
mendapatkan informasi penting seputar adegan klimaks ini.

157
4. Analisis Penggunaan Sarana Retorika pada Alur Tambahan Ketiga
4.1. Pengenalan
Ucapan Gajah Mada itu disimak dengan mata cermat. Tidak
seorang pun yang menanggapi. Satu-satunya orang yang berbeda
sikap, tetapi hanya menyimpan di dalam hati adalah Ra Kembar.
Ra Kembar meski menyandang gelar Rakrian, ia hanya seorang
lurah yang membawahi sekitar lima puluh prajurit. Ra Kembar
yang berasal dari kesatuan Sapu Bayu tesenyum sinis. Ra Kembar
punya alasan untuk tidak senang kepada Gajah Mada karena ia
bersahabat akrab dengan segenap Dharmaputra Winehsuka.
“Gajah Mada bisanya hanya menyalahkan orang lain,” kata
hati Ra Kembar. “Saat Ra Tanca membunuh Sang Prabu di
biliknya, bukankah ia berada di ruangan itu. Ia yang mengawasi Ra
Tanca melakukan pengobatan. Artinya, ia mestinya bertanggung
jawab terhadap keselamatan rajanya, mengapa orang lain yang
tidak bersalah harus menanggung akibatnya. Lucu Gajah Mada.”
Meski berpendapat demikian, Ra Kembar tidak melontarkan
pendapat itu. Ra Kembar menyimpan pendapat itu dalam hati.22
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Saat Ra Tanca membunuh Sang Prabu di biliknya, Antonomasia
2 Bukankah ia berada di ruangan itu. Retoris
3 Mengapa orang lain yang tidak bersalah harus
menanggung akibatnya.
Retoris
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
22
Ibid., h. 135.

158
1 Satu-satunya orang yang berbeda sikap, tetapi hanya
menyimpan di dalam hati adalah Ra Kembar.
Berimbang
2 Ra Kembar meski menyandang gelar Rakrian, ia hanya
seorang lurah yang membawahi sekitar lima puluh
prajurit.
Berimbang
3 Ra Kembar punya alasan untuk tidak senang kepada
Gajah Mada karera ia bersahabat akrab dengan segenap
Dharmaputra Winehsuka.
Kendur
4 Saat Ra Tanca membunuh Sang Prabu di biliknya,
bukankah ia berada di ruangan itu
Berimbang
5 Meski berpendapat demikian, Ra Kembar tidak
melontarkan pendapat itu
Berimbang
4.2. Konflik
“Ada sebuah kekuatan yang diam-diam mempersiapkan diri
melakukan makar di sebuah tempat bernama Karang Watu. Mereka
membangun kekuatan yang kelak akan digunakan untuk
memberontak. Menurut pembicaraan itu disimpulkan, kekuatan
makar itu ada hubungannya dengan pembunuhan-pembunuhan
yang terjadi kemarin. Kekuatan makar itu menggunakan lambang
buah maja yang dibelit ular, dipimpin oleh seorang pemuda
bernama Raden Panji Rukmamurti. Gajah Mada akan menyerbu
kekuatan itu, tetapi menurutku, kau mempunyai kesempatan untuk
mendahului. Jika kau berhasil mematahkan kekuatan
pemberontakan itu, artinya apa yang kaulakukan menyamai apa
yang dilakukan Gajah Mada ketika meradam Ra kuti. Tak menutup
kemungkinan pangkat dan jabatanmu akan melesat membelah
langit.”
Wajah Ra Kembar sangat berseri-seri. Kesempatan yang
diidam-idamkan kini telah berada di depannya. Tidak ada ruginya
ia menjalin persahabatan dengan Singajaya meskipun ia mata
duitan.
“Karang Watu”? tanya Ra Kembar.
Singajaya mengangguk.

159
“Kautahu tempat itu?” balas Singajaya.
Ra Kembar meliukkan badan, melemaskan otot-otot.
“Ya Sebuah pedukuhan yang terlindung oleh tebing tinggi dan
sungai meliuk. Menurutku sangat masuk akal bila pedukuhan itu
dijadikan tempat kegiatan macam itu. Jika pintunya yang berbentuk
leher angsa dijaga ketat maka tak seorang pun yang akan tahu apa
kegiatan yang terjadi di sana.”
“Rupanya ada ada rencana makar di sana?” gumam Kembar.
“Itulah yang kudengar dari pembicaraan itu.”
“Baiklah,” ucap Ra Kembar. “Aku sangat menghargai
keterangan yang kamu jual kepadaku. Sebagaimana saranmu, aku
akan bertindak cepat. Akan aku kumpulkan teman-temanku. Cukup
hanya dengan mereka dan para anak buahku, tempat yang kausebut
itu akan bosah baseh. Tak perlu menunggu besok, tengah malam
ini juga akan aku gempur mereka yang berani coba-coba berniat
makar itu. Akan kulihat bagaimana raut wajah Gajah Mada setelah
melihat sepak terjangku.”23
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Tak menutup kemungkinan pangkat dan jabatanmu
akan melesat membelah langit.”
Hiperbola
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Menurut pembicaraan itu disimpulkan, kekuatan
makar itu ada hubungannya dengan pembunuhan-
pembunuhan yang terjadi kemarin.
Periodik
2 Gajah Mada akan menyerbu kekuatan itu, tetapi
menurutku, kau mempunyai kesempatan untuk
mendahului.
Berimbang
23
Ibid., h 376-377.

160
3 Jika kau berhasil mematahkan kekuatan pemberontakan
itu, artinya apa yang kaulakukan menyamai apa yang
dilakukan Gajah Mada ketika meradam Ra kuti.
Periodik
4 Jika pintunya yang berbentuk leher angsa dijaga ketat
maka tak seorang pun yang akan tahu apa kegiatan yang
terjadi di sana.
Periodik
5 Sebagaimana saranmu, aku akan bertindak cepat. Periodik
6 Tak perlu menunggu besok, tengah malam ini juga akan
aku gempur mereka yang berani coba-coba berniat
makar itu.
Periodik
7 Akan kulihat bagaimana raut wajah Gajah Mada setelah
melihat sepak terjangku.
Berimbang
4.3. Sekuen Klimaks
“Bagaimana denganmu?” tanya Ra Kembar.
“Aku ikut.”
“Menurutmu, bagaimana kira-kira sikap Singa Darba?” tanya
Ra Kembar.
“Sikapnya sudah jelas,” jawab Ajar Langse.
“Aku menyesal terlalu terbuka dengan menceritakan melalui
cara bagimana aku memperoleh keterangan penting itu. Singa
Darba memang tak mungkin mengadu kepada Gajah Mada, namun
dapat dipastikan ia akan mengadu kepada Senopati Haryo Teleng,
pimpinannya.”
Sebagaimana Ra Kembar, pada dasarnya Ajar Langse juga
jenis prajurit yang kurang perhitungan. Usulannya bahkan bisa tak
masuk akal dan berlebihan.
“Soal Singa Darba serahkan saja kepadaku. Aku akan
berbicara lagi dengannya. Apabila ia berniat mengadu kepada
pimpinannya, aku akan membungkam mulutnya selamanya.
Tenang saja, aku bisa diandalkan untuk pekerjaan macam itu.”
Hening dan senyap mengalirkan udara di Bale Gringsing,
menemani Rakrian Kembar dalam berpikir. Wajah Senopati Gajah

161
Enggon yang pucat seperti orang mati sungguh menarik
perhatiannya, menumbuhkan gagasan bengkok dari benaknya.
“Kalau kelak aku berhasil menapaki pangkat yang lebih tinggi
aku tidak akan melupakannmu. Itu sebabnya, aku berharap kita
selalu bersama. Keadaan apapun kita hadapi bersama tanpa harus
menyimpan rasa takut. Gabungan kekuatan kita pasti bisa dan
mampu dihadapkan dengan Gajah Mada. Kelak pada saatnya
semua orang akan tahu Ra Kembar dan Ajar Langse adalah
prajurit-prajurit yang tak bisa diremehkan. Sungguh tidak pantas
Ra Kembar menduduki jabatan sekarang, pantasnya Ra Kembar
sudah berpangkat senopati. Bahkan, menjadi panglima pun sudah
sangat pantas.”24
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Apabila ia berniat mengadu kepada pimpinannya, aku
akan membungkam mulutnya selamanya.
Perifrasis
2 Hening dan senyap mengalirkan udara di Bale
Gringsing.
Personifikasi
3 Wajah Senopati Gajah Enggon yang pucat seperti orang
mati sungguh menarik perhatiannya
Simile
4 menumbuhkan gagasan bengkok dari benaknya. Metafora
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Singa Darba memang tak mungkin mengadu kepada Berimbang
24
Ibid., h. 414-415.

162
Gajah Mada, namun dapat dipastikan ia akan mengadu
kepada Senopati Haryo Teleng, pimpinannya.
2 Sebagaimana Ra Kembar, pada dasarnya Ajar Langse
juga jenis prajurit yang kurang perhitungan.
Periodik
3 “Kalau kelak aku berhasil menapaki pangkat yang lebih
tinggi aku tidak akan melupakannmu.
Klimaks
4 Itu sebabnya, aku berharap kita selalu bersama.
5 Keadaan apapun kita hadapi bersama tanpa harus
menyimpan rasa takut.
6 Gabungan kekuatan kita pasti bisa dan mampu
dihadapkan dengan Gajah Mada.
7 Kelak pada saatnya semua orang akan tahu Ra Kembar
dan Ajar Langse adalah prajurit-prajurit yang tak bisa
diremehkan.
8 Sungguh tidak pantas Ra Kembar menduduki jabatan
sekarang, pantasnya Ra Kembar sudah berpangkat
senopati.
9 Bahkan, menjadi panglima pun sudah sangat pantas.”
4.5.Klimaks Rakrian Kembar salah besar dalam mengukur kekuatan musuh.
Ra Kembar dengan lima puluh orang anak buahnya memandang ke
seberang sungai tempat Karang Watu berada dengan penuh
perhatian. Dalam siraman cahaya bulan yang mulai memanjat
langit dan cukup untuk melapangkan jarak pandang, dengan pacak
baris penuh keyakinan, Ra Kembar menyiapkan taklimat sebelum
penyerbuan.
Tepat lima puluh orang jumlah prajurit yang mendukung
penyerbuan itu. Tiap sepuluh orang prajurit dengan pangkat
rendahan berada di bawah pimpinan seorang prajurit yang
dituakan, masing-masing adalah Prajurit Bajang Laut, Prajurit

163
Kenayan, Prajurit Sulung Baung, Prajurit Goda Pasa, dan Prajurit
Arya Pamgat Jiwa.
“Kita manfaatkan perahu yang ada untuk menyeberang, begitu
sampai di sana langsung mengendap. Kita serbu mereka dengan
serangan mendadak”
Ra Kembar benar-benar telah mempersiapkan mereka dengan
sebaik-baiknya. Juga membakar semangat melalui menebar janji-
janji, mereka yang berjasa pada negara akan mendapatkan
anugerah pangkat menjadi lurah prajurit semua. Ra Kembar
menjanjikan kepada pendukungnya untuk bersama-sama mukti
wiwaha, tidak sebaiknya hamukti lara lapa terus sepanjang waktu.
“Semua siap?” tanya Ra Kembar tegas.
“Tandya,” jawab para prajurit pendukungnya serentak.
Rakrian Kembar akhirnya memberi isyarat untuk naik ke atas
perahu yang telah tersedia di tempat itu tanpa rasa curiga sedikit
pun, mengapa ada banyak perahu bagai dengan sengaja disiapkan
untuk menyambut kedatangan mereka. Ra Kembar merasa
penyerbuan itu terlalu mudah. Lebar sungai yang setara separuh
lebar Tambak Segaran bisa menyulitkan bagi mereka yang tidak
bisa berenang. Namun, dengan tersedianya perahu-perahu,
penyeberangan ke Karang Watu terasa sangat mudah. Bahkan
untuk membekuk gerombolan para petualang pun sangatlah mudah.
Ra Kembar bahkan sangat tidak sabar untuk bisa sampai ke
seberang. Itulah sebabnya, Ra Kembar menempatkan diri
bergabung dengan perahu paling depan yang bisa diisi oleh sepuluh
orang. Disusul perahu berikutnya yang menampung sejumlah itu
pula. Disusul lagi oleh perahu berikutnya dan perahu berikutnya.25
A. Gaya Bahasa
25
Ibid., h. 449-450.

164
No Kalimat Gaya bahasa
1 Dalam siraman cahaya bulan yang mulai memanjat
langit dan cukup untuk melapangkan jarak pandang,
dengan pacak baris penuh keyakinan, Ra Kembar
menyiapkan taklimat sebelum penyerbuan.
Personifikasi
2 Juga membakar semangat melalui menebar janji-janji,
mereka yang berjasa pada negara akan mendapatkan
anugerah pangkat menjadi lurah prajurit semua.
Hiperbola
3 Bahkan untuk membekuk gerombolan para petualang
pun sangatlah mudah.
Eufimisme
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Dalam siraman cahaya bulan yang mulai memanjat
langit dan cukup untuk melapangkan jarak pandang,
dengan pacak baris penuh keyakinan, Ra Kembar
menyiapkan taklimat sebelum penyerbuan.
Periodik
2 Juga membakar semangat melalui menebar janji-janji,
mereka yang berjasa pada negara akan mendapatkan
anugerah pangkat menjadi lurah prajurit semua.
Periodik
3 Lebar sungai yang setara separuh lebar Tambak Segaran
bisa menyulitkan bagi mereka yang tidak bisa berenang.
Berimbang
4 Namun, dengan tersedianya perahu-perahu,
penyeberangan ke Karang Watu terasa sangat mudah.
5 Disusul perahu berikutnya yang menampung sejumlah
itu pula.
Repetisi

165
6 Disusul lagi oleh perahu berikutnya dan perahu
berikutnya.
7 Ra Kembar dengan lima puluh orang anak buahnya
memandang ke seberang sungai tempat Karang Watu
berada dengan penuh perhatian.
Kendur
8 Kita manfaatkan perahu yang ada untuk menyeberang,
begitu sampai di sana langsung mengendap.
Klimaks
9 Kita serbu mereka dengan serangan mendadak.
10 Ra Kembar menjanjikan kepada pendukungnya untuk
bersama-sama mukti wiwaha, tidak sebaiknya hamukti
lara lapa terus sepanjang waktu.
Berimbang
11 Rakrian Kembar akhirnya memberi isyarat untuk naik ke
atas perahu yang telah tersedia di tempat itu tanpa rasa
curiga sedikit pun, mengapa ada banyak perahu bagai
dengan sengaja disiapkan untuk menyambut kedatangan
mereka.
Periodik
5. Sekuen Leraian
Tak seorang pun dari mereka yang menyadari bahaya sedang
mengintai. Sungai yang dalam mengalir tenang dengan air serasa
tidak bergerak, tetapi di bagian bawah ada arus yang tidak wajar,
itulah arus bawah yang sulit ditebak ke mana geraknya. Apalagi,
yang berada di arus bawah itu bukanlah keadaan yang wajar tentu,
karena ada puluhan orang yang berenang di kedalaman. Mereka
bisa bertahan di bawah air karena menggunakan ruas bambu
seruling untuk bernapas.
Betapa terperanjat Ra Kembar yang hampir sampai di seberang
itu ketika tiba-tba perahu yang ditumpanginya bergoyang dengan
keras. Demikian kuat goyangan itu menyebabkan perahu itu
terbalik dan penumpangya tercebur berhamburan. Tidak bisa
ditolak kemalangan yang datang karena pisau-pisau dari bawah air
menawarkan tikaman yang mematikan.

166
“Gila, apa ini?” Ra Kembar berteriak.
Apa yang terjadi tidak hanya menimpa perahu Ra Kembar,
tetapi juga perahu-perahu di belakangnya yang jungkir balik
menumpahkan semua penumpang. Serangan yang datang dengan
cara tidak terduga-duga itu mengisap habis kekuatan yang dibawa
Ra Kembar. Kekuatan itu yang dipikir cukup untuk menggilas
Karang Watu itu langsung larut memberi warna merah, itulah darah
dari luka-luka. Seorang prajurit mengalami kesulitan luar biasa
setelah tercebur dalam air karena tidak bisa berenang. Air yang
bagai tanpa dasar menyulitkannya, tetapi ayunan pisau yang
menghujam perutnya menyebabkan prajurit itu dengan sekuat
tenaga membayangkan raut wajah adiknya. Adik perempuan satu-
satunya yang sedang sangat membutuhkannya setelah kedua
orangtuanya meninggal. Kecemasan yang luar biasa dihadapi
prajurit itu. Tidak sekedar takut terhadap datangnya kematian,
tetapi lebih karena cemas memikirkan Sri Widati, siapa yang nanti
yang akan melindunginya setelah ia juga pergi untuk selamanya.
“Mati aku, mati aku,” prajurit itu mengalami kesakitan dan
kebingungan luar biasa.26
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Tak seorang pun dari mereka yang menyadari bahaya
sedang mengintai.
Personifikasi
2 Tidak bisa ditolak kemalangan yang datang karena
pisau-pisau dari bawah air menawarkan tikaman yang
mematikan.
Personifikasi
3 Air yang bagai tanpa dasar menyulitkannya Simile
B. Struktur Kalimat
26
Ibid., 450-451.

167
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Sungai yang dalam mengalir tenang dengan air serasa
tidak bergerak, tetapi di bagian bawah ada arus yang
tidak wajar, itulah arus bawah yang sulit ditebak ke
mana geraknya.
Berimbang
2 Mereka bisa bertahan di bawah air karena menggunakan
ruas bambu seruling untuk bernapas.
Kendur
3 Betapa terperanjat Ra Kembar yang hampir sampai di
seberang itu ketika tiba-tiba perahu yang ditumpanginya
bergoyang dengan keras.
Berimbang
4 Seorang prajurit mengalami kesulitan luar biasa setelah
tercebur dalam air karena tidak bisa berenang.
Kendur
5 Air yang bagai tanpa dasar menyulitkannya, tetapi
ayunan pisau yang menghujam perutnya menyebabkan
prajurit itu dengan sekuat tenaga membayangkan raut
wajah adiknya
Berimbang
6 Tidak sekedar takut terhadap datangnya kematian, tetapi
lebih karena cemas memikirkan Sri Widati, siapa yang
nanti yang akan melindunginya setelah ia juga pergi
untuk selamanya.
Berimbang
4.6. Leraian
Namun, tidak ada kalimat yang bisa dituntaskan dalam
teriakkan karena arus bawah menyeretnya untuk masuk ke pintu
gerbang kematian yang terbuka lebar.
Ra Kembar memanfaatkan kesempatan yang dimiliki untuk
melesat berenang sekuat-kuatnya. Namun, Ra Kembar hanya
menahan napas ketika sampai ke seberang disambut ujung tombak
yang terarah ke mukanya. Senyap tanpa ada kegaduhan menjadi

168
pertanda, serangan yang digelar itu langsung selesai. Yang ada
tinggal kegiatan mengikat sisa penyerbu yang menyerah dan
membiarkan mereka yang terajur menjadi mayat ikut hanyut
bersama aliran sungai.
Rakrian Kembar merasa jantungnya akan lepas. Ra Kembar
yang dipaksa meletakkan tangan di atas kepala menyempatkan
memerhatikan bagaimana nasib segenap anak buahnya dan
merenungkan bagaimana cara mempertanggungjawabkan peristiwa
yang terjadi itu di depan Senopati Panji Suryo Manduro, bahkan di
depan Gajah Mada, orang yang tak disukainya itu.
Ra Kembar kembali terjengkang ketika seseorang menendang
dadanya. Apa yang dialami Rakrian Kembar meleset jauh dari apa
yang dibayangkan. Seorang laki-laki dengan wajah dihitamkan
jelaga menggelandangnya, menyebabkan Ra Kembar jatuh bangun.
Ra Kembar melihat tidak hanya dirinya yang mengalami nasib
seperti itu, tetapi sisa-sisa anak buahnya yang selamat. Pertempuran
yang dibayangkan akan berlangsung seru, angan-angan menangkap
pemimpin orang-orang Karang Watu tidak terwujud. Sebaliknya,
dalam kurun waktu yang sangat singkat, Ra Kembar harus
meletakkan tangan di belakang dan diikat menggunakan tali
janget.27
A. Gaya Bahasa
No Kalimat Gaya bahasa
1 Tidak ada kalimat yang bisa dituntaskan dalam
teriakkan karena arus bawah menyeretnya untuk masuk
ke pintu gerbang kematian yang terbuka lebar.
Metafora
2 Senyap tanpa ada kegaduhan menjadi pertanda,
serangan yang digelar itu langsung selesai.
Pleonasme
3 Yang ada tinggal kegiatan mengikat sisa penyerbu yang
menyerah dan membiarkan mereka yang terajur menjadi
mayat ikut hanyut bersama aliran sungai.
Sinisme
4 Rakrian Kembar merasa jantungnya akan lepas. Hiperbola
27
Ibid., h. 451-452.

169
5 Ra Kembar yang dipaksa meletakkan tangan di atas
kepala
Perifrasis
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Ra Kembar memanfaatkan kesempatan yang dimiliki
untuk melesat berenang sekuat-kuatnya.
Berimbang
2 Namun, Ra Kembar hanya menahan napas ketika sampai
ke seberang disambut ujung tombak yang terarah ke
mukanya.
3 Ra Kembar yang dipaksa meletakkan tangan di atas
kepala menyempatkan memerhatikan bagaimana nasib
segenap anak buahnya dan merenungkan bagaimana
cara mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi
itu di depan Senopati Panji Suryo Manduro,
Berimbang
4.7. Penyelesaian
“Ini dia pahlawan yang ditunggu-tunggu kepulangannya itu.”
Rakrian Kembar semula tidak mengenali siapa saja orang-
orang yang berdiri di hadapannya karena semua wajah dihitamkan
menggunakan jelaga. Namun, Kembar masih bisa mengenali
suaranya. Orang yang baru berbicara itu adalah Bhayangkara Riung
Samudra.
“Bagaimana, Ra Kembar? Upayamu menggulung Karang
Watu berhasil?”
Ra Kembar merasa lebih baik bila dikelupas wajahnya.
Setidaknya memang ada penyesalan dalam hatinya, namun apa
mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Apa yang terjadi telah
terlanjur dengan hasil berupa kotoran yang berlepotan di wajahnya.
Akan tetap, orang-orang yang dikenalinya sebagai
Bhayangkara Jayabaya, Riung Samudra, Panjang Sumprit, tidak
memberikan perhatian kepadanya terlalu lama. Bhayangkara
Jayabaya bertindak cekatan denga membebaskan Rakrian Kembar

170
dari ikatan talinya, demikian juga dengan sepuluh anak buahnya
yang tersisa.
“Berapa orang yang kaubawa?” tiba-tiba terdengar bertanya
dari arah belakang.
Ra Kembar berbalik.
“Lima puluh orang,” jawab Ra Kembar dengan lidah kelu.
Sulit membaca bagaimana isi hati di balik wajah Bhayangkara
Lembu Pulung yang telah dihitamkan itu. Lembu Pulung menebar
pandang memerhatikan keadaan dengan saksama, menyusur tebing
tinggi di belakang bangungan induk, menggerataki bangungan
induk berbentuk pendapa dan bangsal panjang yang juga beratap
rumbia. Lembu Pulung akhirnya menjatuhkan pandangan matanya
ke halaman luas yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan apa saja.
Dengan luas dua kali lipat Tambak Segaran atau lebih, Karang
Watu sanggup menampung prajurit sebesar Jalapati sekalipun. Ke
depan Karang Watu bisa menjadi tempat yang berbahaya.
Beruntunglah sepak terjang orang-orang Karang Watu itu keburu
kemanungsan.
“Apa yang kita lakukan sekarang?” tanya Riung Samudra yang
mendekat.
“Kita tinggalkan, pekerjaan sisanya biarlah dituntaskan oleh
Ra Kembar yang akan dibantu Haryo Teleng dan Suryo Manduro,”
Lembu Pulung menjawab.
Jawaban itu mengagetkan Ra Kembar yang makin merasa
tidak nyaman. Ra Kembar membayangkan ke depan akan
mengalami kesulitan besar, tak tahu apa yang harus dilakukan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada
pimpinannya. Melangkah tanpa minta izin pimpinan, hal itu
merupakan kesalahan yang berat, apalagi kini terbukti terlalu
banyak korban jiwa yang jatuh sebagai akibat kecerobohan yang
diperbuatnya. Ke depan pula namanya akan menjadi buah bibir.
Siapa pun akan menertawakannya. Para gadis tak lagi
mengaguminya, mereka akan menjadikannya sebagai bahan
guyonan.28
A. Gaya Bahasa
28
Ibid., h. 462-464.

171
No Kalimat Gaya bahasa
1 “Ini dia pahlawan yang ditunggu-tunggu kepulangannya
itu.”
Sinisme
2 “Bagaimana, Ra Kembar? Upayamu menggulung
Karang Watu berhasil?”
Retoris
3 Ra Kembar merasa lebih baik bila dikelupas wajahnya Metafora
4 Apa yang terjadi telah terlanjur dengan hasil berupa
kotoran yang berlepotan di wajahnya.
Metafora
5 Ke depan pula namanya akan menjadi buah bibir. Metafora
B. Struktur Kalimat
No Kalimat Struktur Kalimat
1 Rakrian Kembar semula tidak mengenali siapa saja
orang-orang yang berdiri di hadapannya karena semua
wajah dihitamkan menggunakan jelaga.
Kendur
2 Namun, Kembar masih bisa mengenali suaranya. Berimbang
3 Lembu Pulung yang telah dihitamkan itu. Lembu Pulung
menebar pandang memerhatikan keadaan dengan
saksama, menyusur tebing tinggi di belakang bangungan
induk, menggerataki bangungan induk berbentuk
pendapa dan bangsal panjang yang juga beratap rumbia.
Paralelisme
Dari hasil pendataan mengenai pemakaian sarana retorika berupa gaya
bahasa dan penyiasatan struktur pada alur ketiga ini, penulis mendapat
kesimpulan seperti di bawah ini:
1. Tahap Pengenalan

172
a. Gaya bahasa : 3 kali
b. Struktur Kalimat : 5 kali
Total : 8 kali penggunaan retorika tektual
2. Tahap Konflik
a. Gaya bahasa : 1 kali
b. Struktur Kalimat : 7 kali
Total : 8 kali penggunaan retorika tekstual
3. Sekuen Klimaks
a. Gaya bahasa : 4 kali
b. Struktur Kalimat : 9 kali
Total : 13 kali penggunaan retorika tekstual
4. Klimaks
a. Gaya bahasa : 3 kali
b. Struktur kalimat : 11 kali
Total : 14 kali penggunaan retorika tekstual
5. Sekuen Leraian
a. Gaya bahasa : 3 kali
b. Struktur Kalimat : 6 kali
Total : 9 kali penggunaan retorika tekstual
6. Leraian
a. Gaya bahasa : 5 kali
b. Struktur Kalimat : 3 kali
Total : 8 kali penggunaan retorika tekstual
7. Penyelesaian
a. Gaya bahasa : 5 kali
b. Kalimat : 3 kali
Total : 8 kali penggunaan retorika tekstual

173
Dari hasil temuan tersebut, dapat diketahui bahwa tahap yang paling
sering menggunakan sarana retorika adalah tahap klimaks, yakni sebanyak 14
kali. Lalu, disusul oleh tahap sekuen pertama yang menggunakan 13 kali sarana
retorika dan tahap sekuen kedua sebanyak 9 kali dalam penyajian adegannya.
Dengan banyaknya sarana retorika yang digunakan dalam tahap
klimaks, terbukti bahwa dalam sebuah cerita adegan yang dipentingkan adalah
tahap klimaks. Dalam tahap ini, pembaca akan merasakan titik puncak dari
emosi yang telah terbangun dari tahap awal. Akan sangat mengecewakan bila
dari awal penceritaan penyajian yang diberikan menggunakan banyak sekali
sarana retorika, tetapi di adegan klimaks, pembaca disuguhi adegan dengan
penyajian yang biasa saja. Tidak ada alasan untuk menyajikan adegan klimaks
dengan cara yang biasa saja karena betapapun menariknya sebuah adegan tapi
tidak disajikan dengan cara yang menarik, pembaca tidak akan mampu
merasakan daya tarik dari adegan tersebut. Malah pembaca tidak akan
menyadari bahwa ia sebenarnya telah membaca adegan klimaks tersebut.
Dengan menggunakan sarana retorika pada tahap klimaks, pembaca
akan semakin dimudahkan untuk memahami maksudnya dan akan pula semakin
teraduk emosinya. Dengan hadirnya perasaan semacam itu, pembaca akan
merasakan kepuasan yang sangat indah bila berhasil menyelesaikan cerita
tersebut.
Juga, dalam tahapan ini, lebih banyak digunakan struktur kalimat
daripada penggunaan gaya bahasa. Penyiasatan struktur dalam tahap ini
digunakan sebanyak 10 kali sedangkan gaya bahasa hanya 3 kali. Hal ini bisa
terjadi karena adegan yang diceritakan ada tahap ini adalah adegan penyerbuan
ala militer yang tentunya harus meminimalisir penggunaan kalimat bergaya
bahasa demi keefektifan penceritaan adegan penyerangan. Namun, untuk
mempertahankan pembaca, pengarang menyajikannya dengan struktur kalimat
periodik yang berfungsi untuk menimbulkan efek tegang dan penasaran,
kalimat berimbang yang bertujuan untuk memberikan banyak info penting dari

174
satu kalimat, gaya bahasa klimaks yang digunakan untuk menghasilkan efek
ketegangan yang memuncak, dan kalimat kendur yang dimanfaatkan pengarang
untuk menyampaikan informasi penting sejak awal pembacaan kalimat.
Bila dicermati lebih dalam, penggunaan sarana retorika dalam tahapan
alur bawahan ketiga ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan pada tahapan alur
utama dan kedua alur bawahan lainnya. Hal ini disebabkan dari tingkat
kepentingan dan juga keterkaitan alur bawahan terhadap alur utama. Pada alur
bawahan pertama dan kedua masih memiliki beberapa keterkaitan terhadap alur
utama. Namun, alur bawahan terakhir ini sama sekali tidak memiliki
keterkaitan dengan alur utama, pun juga dengan kedua alur bawahan lainnya.
Kehadian alur ketiga ini hanya sebagai refleksi terhadap pembaca
mengenai keadaan manusia yang semakin hari semakin melupakan kapasitas
dirinya sendiri. Hal ini dicerminkan dari Ra Kembar yang memiliki sifat
sombong dan juga haus untuk membuktikan diri sendiri tanpa mengukur siapa
lawan dan siapa dirinya sendiri. Lewat alur ini, pengarang memberitahu
pembaca bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan mengedepankan nafsu
tidak akan membuahkan hasil kecuali kegagalan.
Dari hasil pendataan semua alur yang ada dalam novel ini, dapat
diketahui bahwa alur yang paling banyak menggunakan sarana retorika adalah
alur utama sebanyak 103 kali penggunaan. Lalu, posisi kedua ditempati oleh
alur bawahan pertama dan kedua, yakni masing-masing sebanyak sebanyak 99
kali dan di posisi terakhir oleh alur bawahan ketiga menggunakan 68 kali
sarana retorika.
Dengan seringnya pengunaan sarana retorika dalam alur utama dapat
dibuktikan bahwa alur atau cerita yang paling penting dalam sebuah novel
disajikan dengan cara yang paling menarik daripada alur lainnya. Hal ini
dikarenakan ada amanat utama yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat
alur utama tersebut. Dibandingkan ketiga alur bawahan, alur utama ini memiliki

175
tingkat kepentingan yang paling tinggi mengingat yang dikisahkan adalah
upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik.
Nilai moral yang ingin disampaikan lewat alur utama ini adalah sesuatu
yang dilakukan dengan cara yang tidak baik maka akan berdampak buruk
kepada pelakunya. Secara umum, pesan ini begitu sederhana dan terkesan
monoton, tetapi pesan ini sangat berpengaruh dan memiliki keterkaitan yang
erat dengan kehidupan saat ini. Karena terjepit masalah ekonomi yang tak
kunjung menemukan titik solusinya, banyak orang yang rela melakukan apapun
untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Mereka tidak lagi peduli
bagaimana cara mendapatkannya dan apa akibat yang akan diterima karena
dalam benak mereka hanya bagaimana cara memenuhi hawa nafsu saja. Contoh
nyata yang tak bisa dielakkan lagi, kasus korupsi. Dengan seringnya sarana
retorika yang digunakan untuk menyajikan cerita ini, pembaca bisa lebih mudah
menangkap maksud pengarang.
Sama halnya dengan alur bawahan lainnya. Peringkat pertama terdapat
pada alur bawahan kedua yang bercerita tentang Pradhabasu dan Gagak
Bongol. Pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat alur bawahan ini lebih
penting dan mendesak untuk disampaikan. Amanat yang terkandung dalam alur
bawahan kedua adalah maafkanlah kesalahan masa lalu. Dengan apik
pengarang mengemas pesan tersebut sehingga pembaca tidak merasai digurui
oleh pengarang. Hanya terpaut empat angka saja dengan alur utama,
menjadikan alur bawahan ini memiliki nilai tersendiri bagi pembaca. Selain itu,
dalam alur ini, pembaca juga diberitahu pengarang perihal sikap kecintaan
terhadap tanah air. Hal ini tercermin dari apa yang dilakukan oleh Pradhabasu.
Ia menitipkan Prajaka ke Gagak Bongol tidak hanya untuk menimbulkan efek
jera, tetapi juga agar ia bisa bergerak dengan bebas menyelidiki kerusuhan
macam apa yang terjadi di Majapahit.
Setiap alur dalam novel ini memiliki amanat tersendiri yang relevan
dengan kehidupan saat ini. Begitu juga dengan alur bawahan pertama yang

176
menggunakan sarana retorika sebanyak 99 kali. Dengan adanya alur ini,
pembaca tidak melulu disuguhi cerita-cerita kepahlawanan, tetapi juga kisah
percintaan yang tidak lazim khas kerajaan. Bila ketiga alur lainnya berfungsi
untuk memberikan amanat kehidupan kepada pembaca, maka alur ini berfungsi
untuk menghibur pembaca dan sedikit mengendurkan syaraf tegang setelah
berkali-kali dihadapkan oleh adegan-adegan pembunuhan dan lain-lain. Untuk
menyajikan kisah cinta inilah, pengarang menuliskannnya juga dengan
menggunakan cukup banyak sarana retorika yang ampuh untuk membuat
pembaca terperangah dengan sikap Dyah Wiyat yang mampu beralih
sepenuhnya hanya dalam waktu beberapa hari saja. Juga pembaca akan
merasakan betapa ikhlas dan hati seorang Dyah Menur dalam menghadapi
kekandasan rumah tangganya. Pembaca juga bisa merasakan perubahan sikap
dari Raden Kudamerta yang semula adalah lelaki yang tidak bisa mengambil
keputusan, ketika ia dihadapkan oleh sebuah pilihan, ia akhirnya bisa
menjatuhkan pilihan. Semua itu bisa dirasakan oleh pembaca lewat penggunaan
gaya bahasa maupun penyiasatan kalimat. Selain dapat merasakan efek yang
luar biasa, pembaca juga bisa mengambil kesimpulan, bahwa hidup memang
harus berani mengambil keputusan, sepahit apapun akibatnya. Hal ini telah
ditunjukkan oleh Raden Kudamerta. Alur ini menjadi alternatif bagi pembaca
yang kurang menyukai cerita sejarah atau adegan-adegan kekerasan lainnya.
Begitu pula pada alur bawahan yang terakhir. Sedikitnya perolehan
angka penggunaan sarana retorika pada alur ini dikarenakan cerita yang ada
dalam alur bawahan ini sama sekali tidak ada kaitannya denga alur utama
ataupun alur bawahan lannya. Kalau pun alur ini dihilangkan tidak akan
mengubah jalan cerita semua alur yang ada. Namun, dari cerita ini, pengarang
ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang dilakukan hanya demi menuruti hawa
nafsu saja tidak akan membuahkan hasil yang baik. Pesan ini juga diterima
dengan baik oleh pembaca karena penyajian cerita yang tidak menggurui.

177
Terlepas dari amanat yang disampaikan dalam setiap alurnya, Langit
Kresna Hariadi memiliki ciri khas yang ditampilkan dalam setiap kalimat yang
digunakannya. Ciri khas LKH akan lebih terlihat pada bentuk kalimat yang
menggunakan gaya bahasa dan kalimat yang dibangun menggunakan struktur
kalimat yang telah dijelaskan pada kajian teori.
LKH dalam novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara yang terbit pada
tahun 2012 ini banyak menggunakan kalimat kompleks. Seperti yang telah
diketahui, kalimat komplek merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat
setidaknya dua klausa yang digabungkan dengan menggunakan berbagai jenis
konjungsi. Dalam tabel, kalimat kompleks yang digunakan oleh LKH dibangun
dengan menggunakan susunan kalimat periodik, berimbang, hingga kendur.
Ketiga jenis kalimat itu memiliki cara tersendiri untuk menyusunnya.
Penggunakan ketiga jenis kalimat tersebut menandakan mana informasi utama
dalam kalimat tersebut. Selain itu, penggunaan berbagai macam jenis kalimat
dalam novel ini juga berfungsi untuk memberikan variasi kalimat sehingga
pembaca tidak jenuh. Hal ini terlihat dari beberapa kalimat yang menggunakan
jenis kalimat inversi.
LKH juga mampu mengaduk emosi pembaca lewat digunakannya
struktur kalimat klimaks. Kalimat-kalimat yang dibuat untuk menceritakan
sebuah peristiwa itulah yang akan semakin membuat pembaca penasaran dan
ketika sudah sampai pada akhir kalimat, pembaca akan merasakan sebuah
pelepasan emosi yang kerap disebut dengan katarsis. Hal inilah yang akan
membuat pembaca tidak merasa jenuh membaca novel yang berjumlah 508
halaman ini.
Lebih jauh lagi, LKH pun memiliki ciri khas dari penggunaan gaya
bahasa pada novel ini. Gaya bahasa yang paling sering digunakan dalam novel
ini adalah gaya bahasa antonomasia. Seperti yang telah dibuktikan dalam tabel,
penggunaan gaya bahasa antonomasia ini ditujukan untuk memberitahu
pembaca gelar atau nama lain dari anggota keluarga kerajaan Majapahit. Inilah

178
yang menjadi ciri khas karya sastra yang berhaluan sejarah karangan LKH.
Dengan menggunakan gaya bahasa ini, LKH bisa menggunakan lebih dari satu
gelar untuk menyebut satu tokoh dalam peristiwa yang berbeda.
Hal ini bisa ditunjukkan pada penggambaran tokoh Gayatri. Dalam
sebuah adegan yang menggambarkan pernikahan kedua anaknya dengan
menantu pilihan keluarga, tokoh ini dipanggil sebagai Ibu Ratu Biksuni
Rajapatni Gayatri.29
Pada adegan pembakaran jenazah Jayanegara, Gajah Mada
memanggil tokoh ini dengan Tuan Putri Ratu.30
Perbedaan sapaan juga terjadi
saat tokoh ini sedang berbicara dari hati ke hati sebagai sepasang anak dan ibu
dengan Dyah Wiyat, putri bungsunya. Kala itu, Gayatri diberi sapaan Ibu
Ratu.31
Perbedaan tersebut disinyalir terjadi karena perbedaan situasi saat
adegan tersebut terjadi.
Gaya bahasa hiperbola juga turut ambil andil dalam mengisahkan cerita
ini. Gaya bahasa berlebih-lebihan ini bertujuan untuk menghidupkan emosi
pembaca. Dengan gaya bahasa ini, pengarang bisa membuat pembaca
merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh atau membayangkan bagaimana
peristiwa itu terjadi.
Selain antonomasia dan hiperbola, gaya bahasa yang menjadi ciri khas
LKH dalam novel ini adalah metafora. Gaya bahasa kiasan ini membantu
pembaca memiliki gambaran yang tepat mengenai sebuah peristiwa yang
sedang dijelaskan. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah memaknai
peristiwa yang sedang terjadi. Amanat yang hendak disampaikan oleh LKH pun
akan langsung dapat dimengerti oleh pembaca.
Penggunaan gaya bahasa pleonasme pun juga menjadi ciri khas lain dari
novel ini. Lewat penggunaan gaya bahasa ini, LKH bisa menceritakan peristiwa
yang terjadi dengan cara menegaskan, seperti pada kalimat “Panji Wiradapa
29
h. 103. 30
h. 154. 31
h. 242.

179
terlanjur beku menjadi mayat”. Dari kalimat tersebut, pembaca dapat
mengetahui bahwa tokoh tersebut memang sudah mati. Nilai rasa yang
dihadirkan oleh penggunaan gaya bahasa tersebut pun akan sama sekali berbeda
bila seandainya pengarang hanya menuliskannya seperti “Panji Wiradapa mati”.
Sekilas, novel ini terlihat disampaikan dengan menggunakan kalimat-
kalimat yang panjang atau kalimat kompleks. Penggunaan kalimat panjang
tersebut sekilas akan terlihat terlalu bertele-tele. Namun, di balik penggunaan
kalimat jenis itu, LKH ingin benar-benar membuat pembaca bisa menghayati
penggambaran yang sedang dilakukan oleh pengarang lewat kalimat-kalimat
tersebut. LKH tidak hanya ingin pembaca novel ini hanya sekedar mengetahui,
tetapi juga mampu membayangkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Lewat
kalimat-kalimat yang panjang yang juga seringkali berupa pengulangan itulah
LKH membantu pembaca mengikuti alur yang telah disediakan. Hal ini untuk
mengantisipasi hal yang dapat membingungkan pembacanya lantaran ada empat
kisah yang disajikan dalam satu novel.
Ciri lain yang menjadi kekhasan LKH dalam novel ini adalah
penggunaan diksi dalam bahasa Jawa dan bahasa Sanskerta. Hal ini digunakan
untuk mendukung latar tempat dan juga latar waktu yang digunaka dalam novel
Gajah Mada: Takhta dan Angkara. Penggunaan diksi dalam bahasa Jawa yang
memang dikuasai oleh LKH ini akan menambah suasana yang dirasakan oleh
pembaca.
Penggunaan berbagai macam gaya bahasa serta jenis kalimat yang ada
di dalam novel ini bertujuan untuk menghasilkan efek tertentu yang harus
dirasakan oleh pembaca. Efek tertentu itulah yang akan membawa pembaca
kepada sebuah pengalaman masa lalu. Setidaknya, novel ini dapat dijadikan
referensi sejarah dengan cara yang tidak biasa untuk mengetahui kehidupan
masa lalu.

180
C. Ethos, Pathos, dan Logos
Ethos, pathos, dan logos merupakan aspek yang sangat dipentingkan
dalam bidang retorika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ethos
merupakan kredibilitas pengarang, pathos adalah efek yang dirasakan oleh
pembaca setelah membaca tulisan tersebut, dan logos adalah bukti yang dapat
diajukan oleh pengarang agar pembaca bisa mempercayai apa yang
disampaikan olehnya.
Ethos dalam kaitannya dengan novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara
yang terbit pada tahun 2012 ini mengarah ke pengarang novel ini, yakni Langit
Kresna Hariadi. Awalnya, LKH adalah seorang penyiar radio. Cikal bakal novel
ini merupakan naskah yang ia siapkan untuk drama di radio tempat ia bekerja.
Namun, ia mengubahnya dan menjadikannya sebuah naskah novel yang ia
terbitkan di Tiga Serangkai Solo.
LKH sadar bahwa novel yang ia tulis ini merupakan novel yang
berhaluan sejarah. Ia sadar betul dirinya tidak bisa menulis novel ini tanpa riset
dahulu. Hal ini ia pelajari sejak novel Gajah Mada yang pertama menuai kritik
dan protes dari berbagai pihak. Hal ini sampai terjadi karena ia salah
mengatakan latar tempat di mana Jayanegara diselamatkan oleh Bhayangkara.
Sesuai fakta sejarah, tempat Jayanegara diselamatkan oleh Bhayangkara adalah
di Bedander, tetapi di dalam novel ia menulisnya di Kudadu. Tidak hanya
berhenti sampai di situ, sejarah mencatat bahwa ada rentang waktu sebanyak
sembilan tahun antara kematian Jayanegara dengan pemberontakan Ra Kuti.
Namun, LKH justru menuliskan bahwa Jayanegara meninggal bertepatan
dengan meletusnya pemberontakan tersebut. Masih di novel yang sama, LKH
menyebutkan bahwa Lembu Anabrang masih hidup saat pemberontakan Ra
Kuti, padahal fakta sejarah menyatakan bahwa Lembu Anabrang telah mati saat
meredam pemberontakan Ranggalawe di Tuban.32
32
Ibid, h. vii-viii.

181
Hal inilah yang membuat LKH banyak berbenah dalam menggarap
naskah novel selanjutnya. Ia sadar bahwa fakta sejarah yang ia tulis dengan
keliru dalam novelnya dapat mengakibatkan pembohongan sejarah terhadap
publik dan menyesatkan anak bangsa. Oleh karena itu, belajar dari kesalahan
yang telah lalu, sebelum ia meneruskan menggarap lanjutannya, ia melakukan
riset sejarah dengan lebih serius agar kesalahan serupa tidak lagi terjadi pada
novel selanjutnya.
Berbicara mengenai latar belakang, menulis memang merupakan hobi
yang ia jadikan sebagai sandaran hidup. Sejak dulu ia memang menggemari
dunia tulis menulis. Dalam sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Jawa Post, ia
menuturkan bahwa menulis merupakan wadah untuk melampiaskan emosinya.
Ia mengaku bahwa ia adalah seseorang yang mampu berkhayal tinggi bahkan
khayalannya tersebut bisa dikatakan sebagai khayalan yang ekstrem. Namun,
berkat hobi menulisnya itu, ia arahkan khayalannya yang bisa membahayakan
dirinya sendiri ke dalam sebuah karya. Ia mengelola khayalannya tersebut
untuk dijadikan bahan dalam setiap karyanya.
Dari tangan dinginnya, ia telah berhasil menerbitkan banyak cerita yang
memang bercitarasa sejarah. Meskipun ia bukan berasal dari kalangan
sejarawan, demi menciptakan sebuah karya sastra yang dapat
dipertanggungjawabkan keilmiahannya, ia rela melakukan riset yang cukup
mendalam untuk mendapatkan bahan cerita tersebut.
Pathos dalam kaitannya dengan penelitian ini mengacu pada efek apa
yang dirasakan oleh pembaca novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara. Dari
novel ini, selain pembaca bisa mengetahui sedikit banyak tentang sejarah
kerajaan Majapahit, pembaca bisa merasakan efek-efek tertentu yang
membantu penghayatan terhadap novel ini.
Setelah membaca novel ini, pembaca akan merasakan sebuah penekanan
emosi, ketegangan, dan pengenduran urat saraf. Dari efek ini, pembaca bisa
merasakan sebuah emosi yang berkecamuk mengikuti peristiwa yang sedang

182
disuguhkan. Dari efek-efek inilah, pembaca bisa merasa yakin bahwa kejadian
yang ada di dalam novel memang benar adanya. Lebih dari itu, lewat efek-efek
tersebut, secara tidak langsung pembaca bisa mengambil amanat yang hendak
disampaikan oleh LKH. Hal inilah yang menjadikan LKH tidak terkesan
menggurui pembaca atas moral kehidupan yang hendak ia kedepankan.
Selain memainkan emosi pembaca, LKH juga menginginkan agar
pembacanya bisa menangkap informasi dalam tiap kalimat yang digunakannya
untuk menceritakan kisahan ini. Melalui gaya bahasa antonomasia, pembaca
bisa mengetahui nama lain atau gelar anggota kaluarga raja. Hal ini dapat
membantu pembaca memahami silsilah keluarga raja tanpa harus mempelajari
buku sejarah secara langsung. Tidak hanya sebatas informasi mengenai gelar
kerajaan yang digunakan oleh para tokoh kerajaan yang ada dalam novel ini,
LKH juga memberitahu pembaca mengenai beragam jenis racun yang
mematikan dan umum digunakan untuk membunuh manusia pada zaman
tersebut.
Beberapa kalimat dalam novel ini juga bertujuan untuk menguatkan
imajinasi dan penegasan makna yang berhasil didapatkan oleh pembaca ketika
membaca novel ini. Penguatan imajinasi dan penegasan makna dilakukan LKH
untuk menjaga konsentrasi pembaca dalam mengikuti kisah ini. Ketika sudah
memiliki gambaran mengenai adegan yang sedang berlangsung, pembaca akan
mampu mengikuti adegan demi adegan dengan mudah dan tentu saja
merasakan sebuah penekanan emosi dan ketegangan.
LKH dalam novel ini juga berusaha menciptakan nama baik pada tokoh
yang ia ciptakan. Tokoh yang dimaksud ini adalah Pradhabasu. Hal ini ia
lakukan agar pembaca tidak menilai negatif atas apa yang telah dilakukan oleh
tokoh yang satu ini. Dalam novel diceritakan bahwa Pradhabasu melakukan
protes terhadap keputusan Jayanegara yang ia anggap salah dengan cara
memutuskan keluar dari kesatuan Bhayangkara. LKH mengantisipasi pembaca
yang bisa jadi menilai Pradhabasu sebagai tokoh yang tidak setia terhadap

183
kerajaannya dan juga bukan prajurit yang profesional terhadap pekerjaannya
dengan cara menggunakan gaya bahasa eufimisme dalam kalimat yang
menggambarakan Pradhabasu. Kalimat “Orang yang amat terluka hatinya itu
memilih mengundurkan diri dari kehidupan pengamanan istana”
mengindikasikan bahwa kalimat ini mengandung gaya bahasa eufimisme. Frasa
mengundurkan diri dinilai lebih baik ketimbang menggunakan kata keluar.
Kata keluar dinilai memiliki pengertian yang buruk meskipun maknanya sama
saja dengan mengundurkan diri. Tindakan mengundurkan diri masih merupakan
tindakan yang dilakukan dengan kesopanan dan penuh rasa hormat, tapi kata
keluar merupakan tindakan yang mencerminkan sebuah sikap frontal dan tidak
lagi mengidahkan kesopanan. Lagi-lagi untuk menjaga citra baik Pradhabasu,
LKH sengaja menggunakan frasa mengundurkan diri.
Dalam novel ini, LKH tidak hanya lihai menguasai emosi pembaca,
tetapi juga mampu mempengaruhi opini pembaca. Cara yang digunakan oleh
LKH untuk menjalani maksud tersebut adalah dengan mengajukan beberapa
pertanyaan yang sifatnya tidak memerlukan jawaban. Pertanyaan ini
menggunakan gaya bahasa retoris. Dari pertanyaan tersebut, pembaca seolah
“dipaksa” untuk menyetujui apa yang disampaikan LKH lewat dialog yang
diucapkan tokohnya. Kalimat “Adakah pelecehan yang melebihi seperti yang
aku alami kali ini, Raden Kudamerta?” mengindikasikan bahwa Dyah Wiyat
menyadari bahwa ia telah dilecehkan dan pembaca bisa merasakan bahwa harga
diri seorang anak raja yang selama ini kuat dan memiliki pemikiran yang sangat
brilian terinjak-injak oleh bangsawan yang kedudukannya lebih rendah dari
dirinya. Lewat kalimat ini pula, pembaca bisa merasakan betapa kecewanya
tokoh Dyah Wiyat.
LKH sadar bahwa karya miliknya berpotensi besar akan membuat
pembacanya cepat bosan karena jumlah halaman yang cukup tebal yakni 508
halaman. Rasa bosan yang akan mungkin akan timbul di pertengahan jalan
cerita akan membuat pembaca tidak bisa lagi menikmati novel ini secara utuh.

184
Untuk mengantisipasi hal ini, LKH menyajikan kalimatnya dengan susunan
kalimat inversi dan gaya bahasa asonansi. Dengan kedua cara itulah, pembaca
akan merasakan sebuah penyegaran.
Semua efek-efek yang dirasakan oleh pembaca tersebut dihasilkan oleh
penggunaan gaya bahasa dan struktur kalimat yang digunakan LKH dalam
kalimatnya. Mengingat novel ini merupakan novel yang berhaluan sejarah,
maka ada beberapa hal yang bisa dibuktikan dalam bentuk fakta sejarah. Bukti-
bukti tersebut dapat menambah kepercayaan pembaca terhadap novel ini dan
juga terhadap kepiawaian LKH selaku pengarangnya.
Berikut daftar sejarah dalam novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara
karya Langit Kresna Hariadi yang dibuktikan dengan menggunakan buku
sejarah berjudul Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan
Semenanjung Malaysia karya Paul Michel Munoz.
1. Kutipan di dalam novel:
1319, didorong nafsunya untuk menjadi orang paling utama di
Majapahit, Ra Kuti memimpin anak buahnya mengangkat senjata
menyebabkan Raja harus terusir ke Bedander. (Hlm. 7)
Kutipan dalam sumber sejarah:
Setelah pencaplokan kembali ini, kerajaan mengalami sebuah
periode ketenangan sejenak dan digemparkan lagi pada 1319 oleh
pemberontakan istana oleh seorang bangsawan muda bernama Kuti.
Kuti merupakan anak angkat dari Jayanagara; anak-anak angkat
seperti itu dinamakan sebagai dharmaputra dan umumnya
diposisikan sebagai penjaga istana (Panasala) sebagai pasukan elit.
Permasalahan yang dibuat oleh Ra Kuti begitu besar hingga
Raja terpaksa mundur dari Ibukota hanya dikawal oleh 15 orang
yang berada di bawah komandan seorang pejabat bernama
Gajahmada. Jayanagara mengungsi ke Desa Betander (Hlm. 385-
386).

185
Kedua kutipan tersebut menjelaskan pada pembaca bahwa pada tahun
1319 Ra Kuti melakukan pemberontakan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang dipimpin oleh Jayanegara. Kedua kutipan tersebut juga
menginformasikan bahwa akibat pemberontakan tersebut Jayanegara
(Jayanagara) mengungsi ke Desa Bedander yang dalam sumber sejarah
dituliskan Betander. Perbedaan nama desa ini hanya masalah penulisannya saja,
sama seperti penulisan Jayanegara yang di dalam buku sumber sejarah karangan
Paul Michel Munoz ditulis menjadi Jayanagara.
2. Kutipan dalam novel:
“Aku mendengar pertama kali dari Ra Tanca, ia mengeluh
kepadaku karena istrinya diganggu Sang Prabu,” jawab Gajah Mada
dengan cara membelok dan mengagetkan. (Hlm. 7)
Kutipan dalam sumber sejarah:
Salah satu buruan paling favorit dari Jayanagara adalah istri
seorang tabib istana yang bernama Tansha. (Hlm. 389)
Kedua kutipan tersebut menginformasikan kepada pembaca bahwa
Jayanegara memiliki perilaku yang menyimpang, yakni menggoda istri orang
lain. Dalam novel diceritakan bahwa raja kedua Majapahit ini kerap menganggu
Nyai Ra Tanca, istri dari Ra Tanca. Ra Tanca sendiri di dalam novel diceritakan
sebagai seseorang yang paling ahli dalam pengobatan. Hal ini reevan dengan
sumber sejarah. Kutipan dalam buku sejaah tersebut menceritakan bahwa
buruan paling favorit dari Jayanagara adalah istri dari tabib kerajaan, Tansha.
Tansha adalah seorang tabib kerajaan, dalam hal ini Tansha adalah Ra
Tanca yang merupakan seorang ahli ilmu pengobatan. Kesamaan ini tidak
hanya bisa dilihat dari kemiripan nama yang digunakan, tetapi juga jalan cerita
dalam novel dan dalam sumber sejarah. Hal ini akan dijelaskan pada bagian
selanjutnya.

186
Akan tetapi, Ra Tanca, orang yang dianggap paling mumpuni dalam
bidang pengobatan memanfaatkan kesempatan yang diberikan
kepadanya. Oleh sebuah alasan rakrian Tanca sangat membenci
Jayanegara. Maka ketika ia diundang ke istana diminta mengobati Raja,
digunakan kesempatan itu untuk mendendangkan tembang kematian.
Bukan ramuan obat yang diminumkan kepada Sri Jayanegara, tetapi
racun yang amat mematikan. (Hlm. 9)
Kutipan dalam sumber sejarah:
Pada 1328 M, Tansha dipanggil Jayanagara untuk mengoperasi
suatu infeksi yang membengkak. Mengambil posisi Sang Raja yang
sedang lemah, dia membunuhnya dan tak lama kemudian dia pun
dieksekusi. (Hlm. 389)
Kedua kutipan tersebut membuktikan bahwa Tansha dengan Ra Tanca
merupakan tokoh yang sama. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan ejaan. Kesamaan
tokoh tersebut tidak hanya bisa dibuktikan dengan kejadian yang sama, tetapi juga
pada tahun yang ada dalam sumber sejarah yang tercatat sebagai tahun kematian
Jayanegara. Di dalam novel, tahun kematian Kalagemet juga ditulis pada tahun 1328.
3. Kutipan dalam novel:
Kasak-kusuk yang berkembang, sakit yang diderita Jayanegara
hanya berupa bisul. Namun, bisul itu mengeram di pantat Sang Prabu
sehingga sangat mengganggu duduk dan tidurnya.
Rakrian Tanca yang diampuni, Rakrian yang sembilan tahun terakhir
menekuk wajah amat dalam, kepadanya dipercayakan tugas
mengobati Sang Prabu, membebaskannya dari penderitaan yang
mengganggu ketenangan duduknya, membebaskan dari sakit yang
berkepanjangan.

187
4. Kutipan di dalam novel:
Soal Tuanku akan mengawini Tuan Putri?”
Pertanyaan itu menyebabkan Gajah Mada meradang. Ia
tersinggung.
Kalau kamu punya adik, apakah kamu akan mengawini adikmu?
Kalau kamu punya anak, apakah kamu akan mengawini anakmu? Bila
kamu lakukan hal itu maka kamu adalah binatang.”
Dada Gajah Mada sedikit mengombak.
“Sang Prabu itu raja, ia contoh, ia bukan jenis binatang yang tak
bisa membedakan mana saudara yang tidak pantas diinginkan dan mana
yang boleh dan patut,” lanjut Gajah Mada. (Hlm. 38)
Kutipan dalam sumber sejarah:
Menurut epik-epik, Jayanagara telah memiliki segala yang
diinginkannya, namun sayangnya dan memiliki sebuah obsesi
menyimpang terhadap dua saudari perempuannya, Bhre Kahuripan dan
Bhre Gaha, yang merupakan putri Rajapatni Gayatri. (Hlm. 388)
Kedua kutipan tersebut menginformasikan kepada pembaca tentang sisi negatif
Jayanegara lainnya, yakni kehendak untuk menikahi adik tirinya. Namun, di dalam
novel, LKH terkesan memberikan bantahan terhadap hal itu lewat dialog yang
diucapkan Gajah Mada yang berupa pembelaan. Jadi, kutipan dalam novel itu secara
tidak langsung akan mengajak pembaca untuk melakukan pembuktian dengan
menggunakan buku sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan
keilmiahannya.
5. Kutipan dalam novel:
Sembilan tahun yang lalu, ketika terjadi pemberontakan yang
dilakukan oleh Ra Kuti, Gajah Mada masih berpangkat bekel ketika
memimpin pasukan Bhayangkara melakukan penyelamatan atas Sri
Jayanegara melalui pengawalan luar biasa dengan menempuh perjalanan
amat jauh menusuk ke pegunungan Kapur Utara. Karena jasa-jasa yang

188
luar biasa itulah Gajah Mada dibebaskan dari tugas memimpin
Bhayangkara dan kepadanya dianugerahkan jabatan sebagai patih di
Jiwana mendampingi Sri Gitarja sebagai pemangku wilayah Kahuripan.
Terakhir Gajah Mada menduduki jabatan patih di Daha mendampingi
Breh Daha atau Dyah Wiyat yang menjadi pemangku atas wilayah itu.
(Hlm. 16-17)
Kutipan dalam sumber sejarah:
Setelah beberapa hari, Gajahmada kembali ke Trowulan dan dengan
bantuan beberapa pejabat yang setia membentuk serangan balasan. Kuti
terbunuh dalam penyerangan itu. Sebagai hadiahnya, Jayanagara
mengangkat Gajahmada sebagai perdana menteri Kahuripan. Dia berada
dalam posisi ini selama dua tahun dan kemudian dipromosikan ke kota
yang paling prestisius, Daha (Kediri). (Hlm. 386)
Dari kedua kutipan tersebut pembaca dapat mengetahui bahwa Gajah Mada bisa
mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, pimpinan pasukan
Bhayangkara, adalah karena mendapatkan hadiah atas perjuangannya menyelamatkan
Jayanegara dari pemberontakan Ra Kuti. Dalam sumber sejarah disebutkan bahwa
awalnya Gajah Mada menjadi perdana menteri di daerah Kahuripan dan selanjutnya
ditempatkan di Daha. Dalam novel, jabatan yang dimiliki oleh Gajah Mada adalah
seorang patih di kedua tempat tersebut. Bila dilihat dari arti kata patih di dalam KBBI
edisi keempat halaman 1030, patih adalah mangkubumi, sedangkan mangkubumi
memiliki pengertian perdana mentari. Hal ini menunjukkan adanya sebuah kesamaan
jabatan yang dimiliki oleh Gajah Mada semasa pemerintahan Jayanegara.
6. Kutipan dalam novel:
Kepada anakku Sri Gitarja, atas nama negara aku anugerahkan gelar
sebagai Tribhuanatunggadewi Jayawisnuwardhani, sedang kepada
anakku Dyah Wiyat, aku beri gelar Rajadewi Maharajasa. Padamu
Cakradara, mulai saat searang melekat gelar Cakreswara Sri Kerta
Wardhana Prabu Singhasari, sedang padamu Kudamerta Breng
Pamotan, aku anugerahkan abiseka Sri Wijaya Rajasa Sang Apanji

189
Wahninghyun. Gunakan nama itu sesuai tempat dan waktunya,
sedangkan nama gelar yang oleh negara anugerahkan kepadamu adalah
Bre Wengker Wijaya Rajasa Hyang Parameswara. (Hlm. 78)
Kutipan dalam sumber sejarah:
Brhe Kahuripan, Tribhuvana menikah dengan seorang bangsawan
bernama Cakradhara. Setelah pernikahan kerajaan, dia diganti nama
menjadi Kertavardhana dan diposisikan sebagai pangeran Singosari.
Brhe Daha, yang nama personalnya adalah Rajadevi, menikah dengan
Raden Kudamrta, pangeran Wengker, yang diberi gelar Sri Vijayarajasa.
(Hlm. 390)
Informasi yang dapat diambil oleh pembaca dari kedua kutipan tersebut adalah
pernikahan kedua anak Gayatri dengan bangsawan dan juga gelar yang digunakan
oleh anak dan menantu Gayatri setelah menikah. Perbedaan yang terletak pada kedua
kutipan tersebut hanya terletak pada ejaan yang digunakan. Huruf v dalam bahasa
Sanskerta akan berganti mejadi huruf w dalam bahasa Indonesia.
Beberapa kisah dalam novel yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam buku
sejarah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya tersebut menambah
nilai positif pada novel ini dari segi keilmuan. Dengan begitu, pembaca dapat
diyakinkan oleh LKH bahwa kisah ini memang benar terjadi sekalipun imajinasi
pengarangnya sendiri turut mengambil bagian dalam kisahan ini. Adanya beberapa
bukti yang dapat dipertanggungjawabkan seperti ini, pembaca secara tidak langsung
juga dapat menelusuri jejak sejarah kerajaan Majapahit.
Ethos, pathos, dan logos yang mampu ditampilkan dengan baik oleh LKH
merupakan sebuah jaminan yang tidak bisa diragukan lagi kualitas novel ini sebagai
karya sastra yang bercitarasa sejarah.

190
D. Implikasi
Secara umum, teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang muncul
oleh penulis adalah teori gaya bahasa. Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia kelas XII semester ganjil juga terdapat materi gaya bahasa. Namun, materi
yang diajarkan di jenjang tersebut tidak seluas teori yang ada dalam kajian teoretis
bab II skripsi ini.
Materi yang diajarkan pada jenjang ini adalah gaya bahasa dalam pengertian
gaya bahasa. Padahal, dalam pengertian gaya bahasa sangatlah luas, tidak hanya gaya
bahasa saja. Gaya bahasa hanya salah satu dari pembagian gaya bahasa. Dalam materi
ini, guru mengajarkan kepada siswa bahwa gaya bahasa dibedakan menjadi empat
bagian, yakni gaya bahasa perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan.
Pembagian ini mengambil teori yang dikemukakan oleh JS. Badudu. Pembagian ini
berbeda dengan teori yang ada dalam skripsi ini karena penulis berpijak pada teori
yang dikemukakan oleh Gorys Keraf.
Dari pembelajaran gaya bahasa di tingkat ini, siswa bisa memahami
bagaimana cara menandai sebuah kalimat yang disusun dengan gaya bahasa maupun
tidak. Tidak hanya itu, siswa juga dituntut untuk menafsirkan maknanya untuk
kemudian bisa membuatnya sendiri dengan memperhatikan diksi. Penelitian ini juga
bisa digunakan oleh para guru Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai salah satu acuan
belajar bahwa gaya bahasa tidak serta merta gaya bahasa itu sendiri, tetapi gaya
bahasa adalah salah satu bagian dari gaya bahasa.
Dalam pembelajaran ini, guru dapat menggunakan banyak media untuk
mengenalkan gaya bahasa kepada siswa. Guru dapat mengunakan cuplikan teks
cerpen atau novel, puisi, atau bahkan lirik lagu. Dari media-media tersebut, guru bisa
memberikan contoh kepada siswa kalimat yang seperti apa yang mengandung gaya
bahasa. Setelah diberi arahan, siswa dibiarkan menentukan sendiri mana kalimat yang
mengandung gaya bahasa.
Penelitian ini bisa digunakan baik guru maupun siswa sebagai contoh
bagaimana menganalisis kalimat yang terindikasi mengandung gaya bahasa.

191
Keduanya bisa melihat bagaimana cara menganalisis dan cara mengartikan maksud
dari gaya bahasa tersebut. Tidak hanya itu, dari penelitian ini juga bisa ditemukan
efek apa yang sekiranya akan dihasilkan dari penggunaan gaya bahasa tersebut.
Untuk menjembatani perbedaan pembagian jenis gaya bahasa peneliti
mengusulkan pada pembahasan gaya bahasa menggunakan teori Gorys Keraf. Hal
ditujukan untuk memperjelas perbedaan antara gaya bahasa dengan gaya bahasa yang
selama ini sering dianggap sama oleh peserta didik.

192
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penggunaan sarana retorika dalam
novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi paling banyak
digunakan pada tahapan klimaks. Hal ini dikarenakan tahap klimaks merupakan tahap
yang paling penting dalam sebuah cerita untuk menghadirkan emosi bagi para
pembaca. Hasil ini terdapat dalam semua alur kecuali alur bawahan pertama yang
justru terletak pada tahap pengenalan.
Pada alur bawahan pertama justru yang paling banyak mengunakan sarana retorika
adalah tahap pengenalan. Hal ini dilakukan untuk membuat pembaca nyaman dengan
kisah baru yang ceritanya memang agak sedikit melenceng dari tema besar. Alur ini
hadir sebagai cerita romantika di tengah kisah perebutan takhta yang tentunya
melibatkan para punggawa kerajaan yang hanya dititikberatkan pada penceritaan
sekitar perebutan takhta tersebut, seperti peperangan dan pembunuhuan. Rapatnya
adegan klimaks dengan adegan setelahnya juga turut mempengaruhi jumlah sarana
retorika yang digunakan. Hadirnya alur bawahan pertama ini dimaksudkan agar
pembaca tidak melulu disuguhi kisah-kisah yang menegangkan. Diketahuinya tahap
klimaks yang paling banyak menggunakan sarana retorika sudah menjawab
pertanyaan pada rumusan penelitian yang pertama.
Kedua, sarana retorika dalam novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara karya
Langit Kresna Hariadi ini menimbulkan beberapa efek yang dirasakan oleh pembaca.
Efek yang dirasakan oleh pembaca dihasilkan dari bermacam-macam gaya bahasa
dan berbagai jenis struktur kalimat.

193
Efek penguatan imajinasi pembaca tentang sebuah adegan dihadirkan lewat
penggunaan gaya bahasa simile sebanyak 7 kali dan metafora sebanyak 26 kali.
Lewat gaya bahasa inilah, pembaca bisa membayangkan apa yang sedang terjadi pada
saat itu dengan lebih baik sehingga suasana peristiwa tersebut dapat dengan mudah
dihayati.
Efek penekanan emosi pembaca dihadirkan oleh gaya bahasa hiperbola sebanyak
31 kali dan gaya bahasa personifikasi sebanyak 22 kali. Kedua gaya bahasa ini dapat
memberikan keyakinan kepada pembaca terhadap sebuah gambaran situasi atau
adegan yang sedang dikisahkan oleh pengarang.
Pembaca juga akan diajak pengarang untuk merasakan ketegangan pada adegan-
adegan tertentu. Pembaca akan merasakan ketegangan tersebut lewat kalimat-kalimat
yang dibangun menggunakan struktur kalimat periodik dan klimaks. Dalam novel ini,
struktur kalimat jenis ini digunakan sebanyak 70 kali sedangkan struktur kalimat
klimaks digunakan sebanyak 9 kali. Pembaca tidak hanya akan merasakan
ketegangan saja saat membaca kalimat yang dibangun dengan struktur kalimat
periodik ini, tetapi juga akan penasaran tentang apa yang selanjutnya akan terjadi.
Pada kalimat klimaks, pembaca akan merasakan sebuah ketegangan yang disengaja
oleh pengarang dengan cara menyiapkan pembaca menuju ke inti permasalahan yang
memuncak.
Setelah merasakan ketegangan, pembaca juga diajak untuk mengundurkan urat
syarafnya lewat penggunaan penyiasatan struktur kalimat kendur. Jenis kalimat yang
digunakan sebanyak 19 kali ini berfungsi untuk meredakan ketegangan pembaca
sebelum berlanjut pada ketegangan lainnya.
Efek terakhir juga dihadirkan oleh penggunaan sarana retorika dalam novel Gajah
Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi adalah penegasan makna.
Efek ini dapat dicapai dengan mengunakan dua jenis sarana retorika, yakni gaya
bahasa dan penyiasatan struktur kalimat. Untuk sarana retorika penyiasatan struktur,

194
kalimat yang biasa digunakan adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang
diulang lebih dari satu kali. Penyiasatan struktur kalimat yang digunakan pada
keempat alur dalam novel ini adalah anafora, epizeuksis, dan tautotes. Anafora
digunakan sebanyak 2 kali dan kedua struktur kalimat lainnya masing-masing
digunakan sebanyak satu kali.
Efek penegasan yang dihasilkan oleh pemakaian gaya bahasa berbeda dengan
penyiasatan struktur, tidak ada pengulangan dalam kalimat tersebut. Gaya bahasa
yang digunakan untuk menghasilkan efek ini adalah gaya bahasa pleonasme,
tautologi, perifrasis, paradoks, antitesis, dan sinisme. Gaya bahasa pleonasme
digunakan sebanyak 19 kali, gaya bahasa tautologi digunakan sebanyak 1 kali, gaya
bahasa perifrasis digunakan sebanyak 12 kali, paradoks digunakan sebanyak 2 kali,
antitesis digunakan sebanyak 1 kali, dan gaya bahasa sinisme digunakan sebanyak 4
kali.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pengunaan gaya bahasa yang menghasilkan
efek penegasan makna tersebut adalah gaya bahasa-gaya bahasa yang digunakan. Ada
tiga gaya bahasa yang memang tergolong ke dalam gaya bahasa penegasan, yakni
gaya bahasa pleonasme, tautologi, dan paralelisme sedangkan tiga gaya bahasa
lainnya, yakni paradoks, antitesis, dan sinisme tidak termasuk ke dalam gaya bahasa
penegasan. Gaya bahasa paradoks dan antitesis digunakan pengarang untuk
menegaskan makna dengan cara membandingkan satu suasana dengan suasana
lainnya yang bertolak belakang. Dengan begitu, pembaca akan lebih merasa yakin
tentang adegan atau suasana yang sedang dikisahkan. Lain lagi dengan gaya bahasa
sinisme. Gaya bahasa yang biasanya digunakan untuk menyindir seseorang ini oleh
pengarang digunakan untuk menegaskan sebuah adegan seperti yang terlihat pada
adegan Gajah Mada yang menangkap basah Pakering Suramurda yang ingin
melarikan diri. Dari adegan tersebut dapat dilihat bahwa Gajah Mada ingin
menyadarkan Pakering bahwa ia sudah tua dan tidak bisa berlari cepat dengan cara
menyindir.

195
Selain efek yang dihasilkan untuk membangun penghayatan pembaca, ada pula
sarana retorika yang digunakan pengarang untuk memberikan informasi kepada
pembaca. Lewat pengunaan gaya bahasa antonomasia yang digunakan sebanyak 35
kali ini pembaca dapat mengetahui nama lain dari para tokoh yang ada dalam novel
ini. Gaya bahasa ini memberitahu pembaca bahwa nama lain dari Gayatri adalah Ibu
Ratu Biksuni, nama lain dari Jayanegara adalah Kalagemet. Nama lain para tokoh
tersebut adalah sebuah gelar kerajaan berdasarkan kedudukannya dalam sistem
kerajaan.
Selain memberikan informasi seputar nama lain dari para tokoh, dalam novel ini
juga digunakan sarana retorika yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada
pembaca tentang jenis-jenis racun yang sering digunakan dalam tindak pembunuhan.
Informasi tersebut disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa metonimia
sebanyak 1 kali. Dengan digunakannya gaya bahasa ini untuk kepentingan tersebut,
apa yang dikatakan Horatius tentang sifat karya sastra, dulce et utile, memang benar
adanya. Dari novel ini, pembaca tidak hanya disuguhkan nilai moral yang terkandung
dalam amanat dan nilai sejarah yang terkandung dalam alur utama, tetapi juga
pengetahuan tentang beberapa ular yang mengandung racun berbahaya.
Selain info berupa nama lain dari para tokoh, pengarang juga dapat memberikan
dua info sekaligus dengan menggunakan struktur kalimat berimbang sebanyak 49
kali. Dari struktur kalimat ini, pembaca bisa mengetahui dua informasi sekaligus
dalam satu kalimat saja.
Sarana retorika juga digunakan untuk memunculkan nama baik seorang tokoh. Hal
ini terjadi pada tokoh Pradhabasu. Secara umum, tokoh ini digambarkan sebagai
tokoh yang memiliki kecintaan yang tinggi kepada kerajaannya namun ia memilih
keluar dari kesatuan pengamanan kerajaan karena sakit hati. Ia pun belum bisa
melupakan sakit hatinya itu. Untuk menggambarkan bahwa tokoh ini adalah tokoh
yang berjiwa ksatria, pengarang menggambarkan tindakan tokoh ini dengan sedikit

196
diperhalus menggunakan gaya bahasa eufimisme. Gaya bahasa ini digunakan
sebanyak 3 kali.
Efek pemulihan dari kebosanan pembaca juga ditampilkan dalam penggunaan dua
sarana retorika, yakni gaya bahasa asonansi dan penyiasatan struktur kalimat invers.
Pada gaya bahasa asonansi, pembaca akan merasa disegarkan kembali melalui
keindahan bunyi yang tampil sebanyak 2 kali. Memulihkan pembaca dari kebosanan
yang bisa saja terjadi juga dilakukan dengan menggunakan struktur kalimat invers
yang hadir sebanyak 5 kali.
Tidak hanya efek yang dirasakan lewat perasaan saja, pengarang novel ini juga
mampu menggiring opini pembaca atau bahkan menyesatkan pemikiran pembaca
lewat digunakannya sarana retorika berupa gaya bahasa retoris. Lewat pertanyaan-
pertanyaan yang kerap dilontarkan para tokoh dalam novel ini, pemikiran pembaca
diarahkan seperti pemikiran tokoh yang sedang berdialog tersebut. Untuk
mempengaruhi pola pikir pembaca, gaya bahasa retoris ini digunakan sebanyak 9
kali.
Implikasi novel Gajah Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi
dalam pembelajaran sastra adalah peserta didik dapat memahami bahasa dalam unsur
intrinsik sub gaya bahasa yang dikaji tidak hanya berkisar pada gaya bahasa saja,
tetapi juga penyiasatan struktur kalimat. Juga, tidak hanya berhenti pada proses
penentuan sarana-sarana tersebut, peserta didik juga diharapkan mampu menggali
makna yang terkandung pada pemakaian sarana-sarana tersebut serta mencari efek
yang dihasilkan dari penggunaan tersebut.
Nilai tambah penelitian ini bagi pembelajaran gaya bahasa kelas XII adalah
peserta didik dapat mengetahui efek apa saja yang terkandung dari gaya bahasa-gaya
bahasa yang telah mereka pelajari. Dengan begitu,mereka bisa lebih mahir lagi
memaknai maksud dari kalimat yang bergaya bahasa tersebut. Jika hal itu sudah
mereka lakukan, peserta didik akan lebih mendalami lagi unsur intrinsik lainnya

197
karena dalam penelitian ini, unsur intrinsik bagian gaya bahasa ini dikaitkan dengan
unsur intrinsik lainnya.
Sayangnya, dalam praktik pembelajaran di kelas, pembahasan gaya bahasa hanya
membahas tentang pembagian gaya bahasa, yang sama sekali berbeda dengan
pembagian gaya bahasa dalam penelitian ini. Tidak hanya itu, tidak disinggung
sedikit pun tentang efek yang dihasilkan dari gaya bahasa-gaya bahasa tersebut.
Pembelajaran di kelas hanya menitikberatkan pada bagaimana peserta didik tahu apa
yang dimaksud dengan gaya bahasa dan pembagiannya, serta mengetahui kalimat
seperti apa yang mengandung gaya bahasa. Walaupun gaya bahasa termasuk salah
satu materi yang kerap dijadikan soal pada Ujian Nasional, pertanyaan yang keluar
seputar gaya bahasa pun hanya berkisar pada nama gaya bahasa dari larik puisi atau
pun kalimat dalam kutipan cerpen atau novel.
Begitu pun dengan pembagian gaya bahasa yang ada dalam penelitian ini berbeda
dengan materi gaya bahasa pada pembelajaran di sekolah. Meskipun memiliki
pengertian yang sama, tetap saja peserta didik akan mengalami kebingungan jika
mengikuti pembagian gaya bahasa yang ada dalam penelitian ini. Selain itu, peserta
juga akan semakin bingung dengan perbedaan antara majas dengan gaya bahasa
karena selama ini mereka menyamakan antara gaya bahasa dengan majas, padahal
gaya bahasa adalah salah satu bagian dari gaya bahasa. Dari perbedaan tersebut,
peneliti merekomendasikan untuk pembelajaran materi gaya bahasa sebaiknya
menggunakan pembagian gaya bahasa yang dilakukan oleh Gorys Keraf .
A. Saran
Dari hasil penelitian mengenai sarana retorika yang digunakan dalam novel Gajah
Mada: Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi, peneliti menyarankan
beberapa hal berikut:
Untuk para pengarang, demi menghasilkan sebuah karya yang bercita rasa tinggi
agar dapat menarik minat pembaca, disarankan untuk memanfaatkan sarana-sarana

198
retorika semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan, penggunaan gaya bahasa sangat
berpengaruh untuk membentuk sebuah emosi yang dapat membantu pembaca
memahami makna cerita tersebut.
Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk mencoba genre novel sejarah sebagai
alternatif lain dalam menciptakan karya sastra. Hal ini dapat membantu melestarikan
sejarah bangsa. Tentunya, untuk menciptakan sebuah karya sastra yang berhaluan
sejarah diperlukan proses yang lebih lama untuk melakukan riset agar tidak bertolak
belakang antara karya sastra dengan fakta sejarahnya
Bagi para guru matapelajaran Bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan
pengajaran subbahasan gaya bahasa pada materi unsur intrinsik. Pengajaran materi ini
diharapkan tidak hanya pada kisaran memberitahu pembagian, arti, dan bentuk
kalimatnya saja, tetapi juga bagaimana cara menganalisis kalimat bergaya bahasa dan
mencari tahu apa efek yang dihasilkan dari gaya bahasa tersebut. Juga, pendidik
diharapakan mampu mengaitkan gaya bahasa tersebut dengan unsur intrinsik lainnya.

199
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Emsoe dan Apriyanto Ranoedarsono. The Amazing Stories of
Al-Qur’an; Sejarah yang Harus Dibaca. Bandung: Salamadani. 2009.
Adi, Ganug Nugroho. “Langit Kresna Hariadi: Between Fact and Fiction”,
http://www.thejakartapost.com/news/2013/08/15/langit-kresna-hariadi-
between-fact-fiction.html, 22 Agustus 2014.
Arifin, Zaenal dan Amran Tasai. Cermat Berbahasa Indonesia untuk
Perguruan Tinggi. Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa. 1988.
Aziez, Furqonul dan Abdul Hasim. Menganalisis Fiksi; Sebuah Pengantar.
Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
Chaer, Abdul. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses). Jakarta:
Rineka Cipta. 2009.
Connoly, Francis dan Gerald Levin. A Rethoric Case Book. New York:
Harcourt, Brace, & World, Inc. 1969.
Corbett, Edward P.J. The Little Rhetoric. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
1977.
Damayanti, D. Buku Pintar Sastra Indonesia. Yogyakarta: Araska. 2013.
DEPDIKNAS. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama. 2008.
Fauziah, Atik. Kajian Intertekstualitas Novel Gajah Mada Karya Langit
Kresna Hariadi terhadap Kakawin Gajah Mada Gubahan Ida
Cokorda Ngurah. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2007.
Handoyo. Analisis Struktural Novel Gajah Mada : Bergelut dalam Kemelut
Takhta dan Angkara dan Perang Bubat Karya Langit Kresna Hariadi.
Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2009.
Hendrikus, Dori Wuwur. Retorika. Yogyakarta: Kanisisus. 1991.

200
Kennedy, X.J. An Introduction to Fiction. Canada: Little, Brown, and
Company Limited. 1983.
Keraf, Gorys. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama. 2010.
Luxemburg, Jan Van, dkk., Pengantar Ilmu Sastra,Terj. dari Inleiding in de
Literatuurwetenschap oleh Dick Hartono. Jakarta: PT. Gramedia.
1989.
Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
2007.
Moeliono, Anton M. Kembara Bahasa, Kumpulan Karangan Tersebar. C.
Ruddyanto (ed.). Jakarta: PT. Gramedia. 1980.
Muhammad. Metode Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Arr-Russ Media. 2011
Munoz, Paul Michel. Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan
Semenanjung Malaysia. Jogjakarta: Mitra Abadi. 2009.
Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi. Jogjakarta: Gadjah Mada
University Press. Cet. 5. 2005.
Priyatni, Endah Tri. Membaca Sastra dengan Ancangan Literasi Kritis.
Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
Putra, Bayu. “Lebih dekat dengan Langit Kresna Hariadi, Penulis Novel
Sastra Sejarah Nusantara”
http://www.radarlampung.co.id/read/radar/berita-foto/70960-lebih-
dekat-dengan- langit-kresna-hariadi-penulis-novel-sastra-sejarah-
nusantara. 22 Agustus 2014.
Putrayasa, Ida Bagus. Analisis Kalimat; Fungsi, Kategori, dan Peran.
Bandung: PT. Refika Utama. 2007.
Ratna, Nyoman Kutha. Stilistika; Kajian Puitika, Bahasa, Sastra, dan
Budaya. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
Rahmanto, B. Metode Pengajaran Sastra. Jogjakarta: Kanisius. 1988.

201
Rakhmat, Jalaluddin. Retorika Modern; Pendekatan Praktis. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya. 2008
Sudjiman, Panuti. Memahami Cerita Rekaan. Jakarta: Pustaka Jaya. 1988.
Sugono, Dendy. Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama. 2009.
Susanti, Ratna. Ejaan Yang Disempurnakan Terbaru. Klaten: CV. Sahabat.
2012.
Tarigan, Henry Guntur. Pengajaran Gaya Bahasa. Bandung: Angkasa.
1985.
Teeuw, A. Sastra dan Ilmu Sastra; Pengantar Teori Sastra. Jakarta: PT.
Dunia Pustaka Jaya. 1984.
Tuloli, Nani. Teori Fiksi. Gorontalo: BMT “Nurul Jannah”. 2000.
Wikipedia.”Langit Kresna Hariadi”,
http://id.wikipedia.org/wiki/Langit_Kresna_Hariadi. 22 Agustus 2014.
Yusandi. “Makna Nama Satwa pada Orang tempo Doeloe”,
http://www.wacananusantara.org/makna-nama-satwa-pada-orang-
tempo-doeloe/. 22 Januari 2015.
Yustinah dan Ahmad Iskak. Bahasa Indonesia Tataran Unggul kelas XII
SMK. Jakarta: Erlangga. 2008.
Zaidan, Abdul Rozak dkk. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.
2007.

Nama
NIM
Jurusan
Judul
LEMBAR UJI REFERBNSI
Dessy Husnul Qotimah
1 1 10013000028
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Sarana Retorika pada Alur Utama dan Alur Bawahan dalam Novel
Gajah Mada: Takhta dan AngkhraKaryalangit Kresna Hariadi
dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Kelas XII
No Daftar Referensi ParafPen(6-ihbine
1 Abdurrahman, Emsoe dan Apriyanto Ranoedarsono. The
Amazin g St o r i e s o { Al - Qur' an ; S e iar ah y an g Har us D ib a c a.
Bandung: Salamadani. 2009.
2 Arifin, Zaenal dan Amran Tasai. Cermat Berbahasa Indonesia
untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Mediyatama Sarana
Perkasa. 1988.
e An
aJ Aziez, Furqonul dan Abdul Hasim. Menganalisis Fiksi;
Sebuah Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010. C A4 Chaer, Abdul. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan
Proses). Jakarta: Rineka Cipta. 2009. 4 A5 Connoly, Francis dan Gerald Levrn.A Rethoric Case Book.
New York: Harcourt, Brace, & World, Inc. 1969. C 4a-\
6 Corbett, Edward P.J. The Little Rhetoric. Canada: John Wiley
& Sons, Inc. 7977. aA,/l<
7 Damayanti,D. Buku Pintar Sastra Indonesia. Yogyakarta:
Araska. 2013. 4t8 DEPDIKNAS. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama. 2008.

9 Fauziah, Atlk. Kajian Intertekstualitas Novel Gajah Mada
Karya Langit Kresna Horiadi terhadap Kakawin Gajah Mada
Gubahan lda Cokorda Ngurah. Surakarta: Universitas
Sebelas Maret. 2007.
10 Handoyo. Analisis Struktural Novel Gaiah Mada : Bergelut
dalam Kemelut Takhta dan Angkara dan Perang Bubat Karya
Langit Kresna Hariadi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
2009.
11 Hendrikus, Dori Wuwur. Retoriko. Yogyakarta: Kanisisus.
t991. C Aa
t2 Kennedy, X.J. An Introduction to Fiction Canada: Little,
Brown, and Company Limited. 1983. o A13 Keraf, Gorys. Diksi don Gaya llahasa. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama. 2010. aAr\
\4 Luxemburg, Jan Van, dl<k., Pengantar llmu Sastra,Tetj. dari
Inleiding in de Literatuurwetenschap oleh Dick
Hafiono. Jakatia: PT. Gramedia. 1989.
I
qAn
15 Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakatta:Rineka Cipta. 2007. o A
t6 Muhammad. Metode Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Arr-Russ Media.20ll. C A
l7 Munoz, Paul Michel. Kerajaan-Keraiaan Awal Kepulauan
Indonesia dan Semenanjung Malaysia. Jogiakarta: Mitra
Abadi. 2009.( Ar\
18 Nurgiyantoro, Burhan- Teori Pengkajian Fiksi. Jogjakarta:
Gadjah Mada University Press. Cet. 5. 2005. I At9 Priyatni, Endah Tri. Membaca Sastra dengan Ancangan
Literasi Kritis. Jakarta: Bumi Aksara. 2010. 420 Putrayasa, Ida Bagus. Analisis Kalimat; Fungsi, Kategori, dan
(_ 4

Peran. Bandung: PT. Refika Utama. 2001.I
21 Ratna, Nyoman Kutha. Stilistika; Kajian Puitika, Bahasa,
Sastra, dan Budaya. JogSakarta: Pustaka Pelajar. 2009.1d A
22. Rahmanto, B. Metode Pengajarctn Sastra. Jogjakarla:
Kanisius. 1988. 4A23 Moeliono, Anton M. Kembara Bahasa, Kumpulan Karangan
Tersebar. C. Ruddyanto (ed.). Jakarta: PT. Gramedia. 1980. T\r\
24 Sudjiman, Panuti. Memahami Cerita Rekaan. Jakarta: Pustaka
Jaya. 1988. #25 Sugono, Dendy. Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar.
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2009. H26 Susanti, Ratna. Ejaan Yang Disempurnakan Terbaru. Klaten:
CV. Sahabat.2012. J//n
27 Tarigan, Henry Guntur. Pengajaran Gaya Bahasa. Bandung:
Angkasa.1985. s28 Teeuw, A. Sastra dan llmu Sastra; Pengantar Teori Sastra.
Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. 7984. A29 Tuloli, Nani. Teori Fiksl. Gorontalo: BMT "Nutul Jannah".
2000. #30 Yustinah dan Ahmad Iskak. Bahasa Indonesia Tatqran
Unggul kelas XII SMK. Jakarta: Erlangga. 2008. C Ar\31 Zaidan, Abdul Rozak dl<7<. Kamus Istiloh Sastra. Jakarla: Balai
Pustaka, 2007. a AJZ Putra, Bayu. "Lebih dekat dengan Langit Kresna Hariadi,
Penulis Novel Sastra Sejarah Nusantara",
http : //www. radarlampung. co. id/re adh adar lberrta-foto I 7 09 60 -
lebih-dekat-dengan- langit-kresna-hariadi-penulis-novel-
sastra-sej arah-nusantar a, 22 Agustus 20 1 4.

JJ Wikipedia. "Langit Kresna
http : //id.wikipedia. org I wrkilLangit_Kresna_H anadi,
Agustus 2014.
Hariadi",
22C
I
)t(lt\
34 Yusandi. "Makna Nama Satwa pada Orang tempo Doeloe"http ://www.wacananus antar a.or gl makna-nama-satwa-pada-orans- temoo-doeloel . 22 Januari 201 5.
t
35 Adi, Ganug Nugroho. !'Langit Kresna Hariadi: Between Fact
and Fiction",
http : //www.thej akartapo st. com/news/2 0 1 3 /0 8 I 1 5 I langit-
kresna-hariadi-between-fact-fi ction.html, 22 Agustus 20 I 4. $Jakafta,
NrP. 19771030 200801 2009

KEMENTERIAN AGAMAUIN JAKARTAFITKJl. k. H. Juanda No 95 Cigutat 15412 lndoo$ia
FORM (FR)
No Dokumen : FITK-FR-AKD-081
Tgl. Terbit : 1 Maret 2010
No. Revisi: : 01
Hal 1t1
SURAT BIMBINGAN SKRIPSI
Nomor : Un.0 I /F. 1,{KM.01.3 /...........12013Lamp. : -Hal : Bimbingan Skripsi
Nama
NIM
Jurusan
Semester
Judul Skripsi
Tembusan:l. Dekan FITK2. Mahasiswa ybs.
Ciputat, 3 Desember 2013
Kepada Yth.
Ibu Rosida Erowati, M.Hum.Pembimbing SkripsiFakultas Ilmu Tarbiyah dan KeguruanUIN Syarif HidayatullahJakarta.
As s alamu' al aikum w r.w b.
Dengan ini diharapkan kesediaan Saudara untuk menjadi pembimbing l/II(materi/teknis) penulisan skripsi mahasiswa:
Dessy Husnul Qotimah
l I 10013000028
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Tujuh
Retorika dalam Novel Gajah Mada: Bergelut dalam Kemelut
Takhta dan Angkara karya Langit Kresna Hariadi dan Implikasinya dalam pembelajaran
Bahasa dan Sastra Indonesia kelas XII semester I
Judul tersebut telah disetujui oleh Jurusan yang bersangkutan padatanggal 26 November 2013,abstraksiloutline terlampir. Saudara dapat melakukan perubahan redaksional pada judul tersebut.Apabila perubahan substansial dianggap perlu, mohon pembimbing menghubungi Jurusan
terlebih dahulu.Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjangselama 6 (enam) bulan berikutnyatanpa surat perpanjangan.
Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Was s al amu' al aikum wrw b.
a.n. DekanKajul Sastra Indonesia
Dra. yah ZA, M.PdNIP. 1 121997$ 2{nl

Lampiran 1
Sinopsis Novel Gajah Mada; Takhta dan Angkara karya Langit Kresna
Hariadi
Majapahit kembali ditimpa duka lantaran Jayanegara tewas dibunuh oleh
pengkhianat negara, Rakrian Tanca dengan menggunakan racun ular. Kematian
raja kedua di tangan seseorang yang diam-diam dicintai oleh Sekar Kedaton
Dyah Wiyat itu mengantarkan Wilwatikta ke masa perebutan takhta. Dua orang
calon suami Sri Gitarja dan Dyah Wiyat terlibat di dalamnya. Adalah Panji
Wiradapa, orang kepercayaan Raden Kudamerta, menjadi dalang kekacauan
dan pembunuhan orang-orang Kudamerta. Tujuannya adalah menjadikan
Kudamerta orang nomor satu di kerajaan itu dengan cara memfitnah Raden
Cakradara, calon suami Sri Gitarja. Semua usaha itu tak diketahui oleh pihak
istana, pun oleh calon suami Dyah Wiyat, Raden Kudamerta karena Panji
Wiradapa menggunakan nama lain, yakni Rangsang Kumuda.
Korban mati dari pihak Raden Kudamerta pun berjatuhan di tangan
Rangsang Kumuda. Pertama, usaha mematikan dirinya sebagai kamuflase, para
prajurit pengawal Kudamerta hingga Kudamerta sendiri yang menjadi sasaran
bidik pisau lempar yang sengaja didesain hanya untuk melukai. Semua ini
menyudutkan posisi Cakradara yang dianggap menjadi batu sandungan
Kudamerta.
Sebenarnya, baik Kudamerta maupun Cakradara sama sekali tidak
berminat menduduki kursi raja. Namun, orang yang ada di balik mereka itulah
yang menyimpan hasrat seperti itu. Paman Cakradara, Pakering Suramurda
juga memiliki rencana jahat untuk menjadikan kemenakannya itu raja
Majapahit.
Di tengah-tengah kekacauan itu, hadirlah seorang misterius yang mengaku
bernama Bagaskara Manjer Kawuryan. Keruan saja, Gajah Mada yang saat itu
diserahi mandat penuh oleh Gayatri dan Patih Majapahit untuk menyelesaikan

semua masalah ini terkejut. Prajurit pilih tanding itu tahu betul bahwa nama
sandi itu milik Rakrian Tanca yang telah tewas di tangannya tak lama setelah
Jayanegara tewas. Untungnya, sosok misterius yang selalu menggunakan kuda
dan jubah putih itu berada di pihak Gajah Mada. Ia membantu Patih Daha
memecahkan masalah serius ini hingga tuntas.
Lampiran 2
Kartu Data Diksi dalam Bahasa Jawa
No Diksi Arti Hal
1 Gering Sakit, biasanya sebutan ini ditujukan untuk
raja atau kerabat inti
3
2 Rontal Berasal dari dua kata, yaitu ron dan tal yang
berarti daun, merupakan lembaran daunt al
yang digunakan sebagai alat mencatat,
fungsinya sama dengan kertas sekarang
6
3 Pepe Unjuk rasa 6
4 Kumararaja Putra mahkota atau pangeran pati. Putra raja
yang dipastikan akan menggantikan raja
sebelumnya bila berhalangan atau mangkat.
7
5 Nglangut Sedih, menyedihkan 7
6 Tumpes tapis Ditumpas tanpa sisa 8
7 Dampar kencana Kursi emas, tempat duduk raja 8
8 Nawa surya Sembilan tahun matahari 8
9 Bramastana Nama lain pohon beringin 8
10 Bagaskara
Manjer Kawuryan
Matahari terang benderang 10
11 Warangan Arsenikum 10

12 Degan Ijo Kelapa muda hijau yang secara ilmiah
mampu meredam racun yang terlanjur masuk
ke tubuh
11
13 Timpuh Duduk bersimpuh 12
14 Duh Gusti kang
Maha Agung,
mugi paring
kawelasan
dhumateng
sinuwun rajaning
nagari, paringana
panjang
yuswanira,
linuputna saking
dedosan
Ya Tuhan yang Mahabesar, berilah belas asih
kepada raja negeri, berilah panjang usianya,
bebaskan dari dosa-dosa
13
15 Pepesthen Takdir 14
16 Gelung keeling Rambut yang diikat (digelung) melingkar d
atas kepala. Zaman Majapahit lelaki terbiasa
berambut panjang yang digelung di atas
kepala. Sisa kebiasaan ini masih terlihat di
pedesaan pulau Lombok.
14
17 Maru Perempuan lain yang diperistri suami, dimadu 15
18 Tandya Jawaban isyarat atas perintah pada pasukan
yang berarti siap.
17
19 Blandong Orang yang pekerjaannya menebang kayu di
hutan, di zaman modern berarti pencuri kayu.
18
20 Sinuhun Panggilan untuk raja 18

21 Para wadyabala
sumadya, tandya
Pasukan siap, gerak. 19
22 Sesorah Pidato 19
23 Pralaya Kematian 21
24 Cihna Lambang negara 21
25 Gringsing lobhe
lewih laka
Pola gringsing merah 21
26 Makantar-kantar Keadaan ketika lidah api sampai menjilat-jilat 21
27 Sekar Kedaton Kembang istana 24
28 Sabda pandita
ratu
Sabda raja yang bermuatan hukum. 25
29 Cangkring Dahan bambu 27
30 Ameng-ameng
nyawa
Bermain-main dengan nyawa 33
31 Gemah ripah
lohjinawi kerta
tata lan raharja
Hidup makmur aman tentram 34
32 Pralaya Mati terbunuh 37
33 Pahoman Perapian pemujaan 40
34 Pakunjaran Penjara 40
35 Dahana Api 41
36 Ngembat watang Membidik anak panah 43
37 Ilmu kanuragan Ilmu kesaktian atau ilmu bela diri 43
38 Pasewakan Sidang atau pertemuan besar 45
39 Panangkilan Menghadap 45
40 Mandapa Tempat memelihara burung 46

41 Seba Menghadap 46
42 Panangkil Menghadap 48
43 Hanyepuhi Menjadi sesepuh atau yang mengatur 48
44 Sri Naranata Raja 48
45 Punggawa
parentah kraton
Identik dengan pegawai pemerintah atau
pegawai negeri
49
46 Sentanaraja Sanak saudara raja, kerabat istana, nma aini
hingga sekarang masih ada dan berubah
menjad nama sebuah daerah
49
47 Gegayuhan Cita-cita atau impian 52
48 Nggarapsari Menstruasi 53
49 Maleman Pasar malam 57
50 Disuyuti Dihormati (ditakuti banyak orang) 58
51 Pekatik Orang yang pekerjaannya merawat dan
mengurusi orang
58
52 Gamel Orang yang pekerjaannya mengurusi kandang
kuda
58
53 Ngapurancang Sikap hormat dengan kedua tangan saling
menggenggam di perut
58
54 Kewahyon Orang yang memperoleh anugerah wahyu 59
55 Asoka Nama lain bunga kamboja atau bunga yang
ditanam di kuburan
60
56 Kampil Kantung tempat menyimpan uang 61
57 Ular sendok Kobra 61
58 Sepenginang Waktu yang digunakan untuk makan sirih,
maksudnya tidak terlampau lama
62
59 Benik Kancing baju 64

60 Gua garba Rahim atau kandungan 66
61 Brenggala Cermin 69
62 Ngemban Memangku 72
63 Priprayangan Segala makhluk halus 72
64 Timang Pengait ikat pinggang 85
65 Pangrantunan Penantian, alam lain setelah kematian 98
66 Ampak-ampak
pendhut
Barisan kabut tebal 108
67 Kamanungsan Ketahuan jati dirinya 108
68 Hyang Bagaskara Matahari 110
69 Warastra Anak panah 110
70 Golek Boneka 114
71 Panggrahita Ketajaman mata hati atau indera keenam 116
72 Daradasih Salah satu jenis mimpi menurut primbon
Jawa yang berarti mempi menjadi kenyataan
118
73 Plinteng Katapel 131
74 Diradameta,
Cakrabyuha,
Supit Urang
Nama-nama siasat perang berskala besar,
awalanya istilah-istilah perng itu berasal dari
Mahabrata terutama episode Baratayuda
131
75 Pacak baris Berbaris 133
76 Bregada Bisa diidentikkan dengan satuan berkekuatan
satu korps, satu korps sendiri merupakan
gabungan dari divisi-divisi
133
77 Rata Pralaya Kereta kematian atau kereta pengangkut
jenazah
146
78 Gabah den interi Perumpamaan kondisi kacau-balau 160

79 Paring dawuh Berbicara 180
80 Kemaki Umpatan Jawa, tak tahu diri 203
81 Garu Alat untuk meratakan tanah setelah dibajak 204
82 Singkal Alat untuk membajak tanah 204
83 Nyrampang Melempar dengan senjata 205
84 Gung Binatara Raja besar berwibawa 237
85 Kriwikan dadi
grojokan
Peribahasa Jawa, persoalan kecil apabila
dibiarkan bisa membesar dan menyulitkan
249
86 Maruta Angin 286
87 Berbudi bawa
leksana, ambek
adil paramarta
Berbudi luhur dan adil 309
88 Bakiak Sandal kayu 318
89 Nggegirisi Luar biasa 359
90 Laying
kekancingan
Surat keputusan raja 409
91 Tumbak cucukan Peribahasa, tukang mengadu 413
92 Sanggar pamujan Tempat khusus untuk bersemadi 428
93 Doro muluk Nama isyarat kentongan dengan nada tertentu
sebagai tanda keadaan aman
447
94 Tulup Semacam anak panah 462
95 Daksina Selatan 477

Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMK
Kelas/Semester : XII/1
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia dan Sastra
Indonesia
Topik : Gaya Bahasa
Jumlah Pertemuan : 2 x Pertemuan (pertemuan
pertama)
A. Standar Kompetensi
Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara tingkat unggul
B. Kompetensi Dasar
Menyimak untuk memahami secara kreatif teks seni berbahasa dan teks
ilmiah sederhana.
C. Indikator
1. Mampu memahami pengertian gaya bahasa dan pembagiannya dalam
karya sastra
2. Mampu memahami maknanya
3. Mampu membuat sendiri kalimat bergaya bahasa
D. Tujuan
1. Siswa dapat memahami pengertian dan pembagian gaya bahasa
2. Siswa dapat makna gaya bahasa
3. Siswa dapat membuat sendiri kalimat bergaya bahasa

E. Materi Pembelajaran
1. Pengertian gaya bahasa dan pembagiannya. Gaya bahasa terbagi atas
empat bagian, yakni perbandingan, pertentangan, sindiran, dan
penegasan.
2. a. Gaya bahasa perbandingan terdiri atas metafora, personifikasi,
asosiasi, alegori, simbolik, tropen, metonimia, litotes, sinekdoke,
eponim, hiperbola, eufimisme, alusio, antonomasia, dan perifrasis.
b. Gaya bahasa penegasan terdiri atas pleonasme, repetisi, paralelisme,
tautologi, klimaks, antiklimaks, inversi, ellipsis, retoris, koreksio,
asindeton, polisindeton, interupsi, eksklamasio, enumerasio, dan
preterito
c. Gaya bahasa sindiran berupa ironi, sarkasme, dan sinisme.
d. Gaya bahasa pertentangan berupa paradoks, antitesis, kontradiksio
in terminis, dan anakronisme.
F. Metode Pembelajaran
Metode inkuiri, tanya jawab, pemodelan, dan presentasi
G. Alokasi Waktu
2 x 40 menit
H. Kegiatan Pembelajaran
a. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)
1. Guru memberikan salam dan siswa menjawabnya
2. Guru mengabsen siswa dengan urutan acak
3. Guru membacakan materi apa yang akan dipelajari bersama beserta
tujuannya
4. Untuk menarik minat siswa, guru memutarkan lagu yang berjudul
Usah Kau Lara Sendiri yang dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya dan
Katon Bagaskara.
5. Guru memberikan fotokopian teks lagu tersebut

b. Kegiatan Inti (50 menit)
Eksplorasi
1. Siswa dipancing untuk menyebutkan lirik-lirik lagu yang indah
dari lagu itu.
2. Guru menanyakan kepada siswa apa makna lirik itu.
3. Guru menjelaskan apa yang dimaksud dengan gaya bahasa dan
pembagiannya.
Elaborasi
4. Guru menyuruh siswa menentukan majas apa saja yang ada dalam
lagu tersebut.
5. Guru meminta siswa untuk menafsirkan maknanya.
Konfirmasi
6. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang aktif selama
pembelajaran.
7. Guru mempersilakan siswa yang belum mengerti tentang materi ini
untuk bertanya.
8. Guru menjawab pertanyaan siswa yang diajukan oleh siswa yang
belum memahami materi ini.
9. Guru memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yakni siswa
dibagi ke dalam empat kelompok dan tiap kelompok harus mencari
empat pembagian majas dalam beberapa buah lagu.
c. Kegiatan Penutupan (15 menit)
1. Guru bertanya kepada siswa tentang materi apa yang telah
dipelajari hari ini.
2. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini.

3. Guru dan murid menyannyikan lagu yang tadi diputar bersama-
sama.
I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
No Aspek yang
dinilai
Teknik
Penilaian
Waktu
Penilaian
Instrumen
penilaian
Keterangan
1 Cermat Pengamatan
dan
Pengujian
Proses Lembar
Pengamatan
Hasil
pengamatan
sikap akan
menjadi
bahan
pertimbangan
saat rapat
kenaikan
kelas
2 Kritis
3 Demokratis
4 Komunikatif
5 Teliti
6 Keberanian
J. Sumber Belajar
Yustinah dan Ahmad Iskak. Bahasa Indonesia Tataran Unggul Kelas XII
SMK. Jakarta: Erlangga. 2008

K. Media Belajar
1. Lagu Usah Kau Lara Sendiri
2. Teks lirik lagu.
3. In Focus
4. Speaker Active
Mengetahui,
Kepala SMK Farmasi Minasa Mulia Guru Bahasa Indonesia
Muhammad Imron. M.Si. Dessy Husnul Qotimah, S.Pd

Lampiran:
Teks lagu Usah Kau Lara Sendiri
Kulihat mendung membayangi pancaran wajahmu
Tak terbiasa kudapati terdiam mendura
Apa gerangan bergemuruh di ruang beriakmu
Sekilas galau mata ingin berbagi cerita
Kudatang sahabat bagi jiwa saat batin merintih
Usah kau lara sendiri
Masih ada asa tersisa
Letakkanlah tanganmu di atas bahuku
Biar terbagi beban itu
Dan tegar dirimu
Di depan sana cahya kecil tuk memandu
Tak hilang arah kita berjalan menghadapinya
Sekali sempat kau mengeluh kuatkan bertahan
Satu per satu jalinan kawan beranjak menjauh

Biografi Peneliti
Peneliti yang lahir dengan nama lengkap Dessy
Husnul Qotimah, 19 Desember 1992 ini merupakan anak
pertama dari tiga bersaudara pasangan suami istri, Suwarno
dan Suti Astuti. Pendidikan yang pernah ditempuh peneliti
dimulai dari TK Aisiyah Depok, SD Muhammadiyah 03
Depok yang lulus pada tahun 2004, SMPN 98 Jakarta yang
lulus pada tahun 2007, MAN 13 Jakarta yang lulus pada
tahun 2010. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan
studinya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pendidikan
Strata 1 pada jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, sebuah
disiplin ilmu yang sudah sejak dulu ia sukai.
Berbagai kesempatan berkarier di dunia bahasa sudah peneliti rasakan. Peneliti
memulai pengalaman di dunia tulis-menulis dengan menjadi salah satu wartawan Jurnal
Wisudawan, anggota tim penulis Ensiklopedia Pemuka Agama Nusantara (proyek
Departemen Agama RI), hingga menjadi anggota tim penulis Testimoni Penerima
Beasiswa Chinkung pada tahun 2014. Tidak hanya itu, Wakil Ketua Divisi Bahasa dan
Sastra Indonesia HMJ PBSI periode 2013/2014 ini juga pernah menjadi editor lepas di
Mata Pena Writer pada tahun 2013.
Peneliti tidak hanya mengasah kemampuannya pada bidang tulis-menulis, tetapi
juga mengabdikan dirinya pada dunia pendidikan. Debut mengajarnya peneliti mulai sejak
masih duduk di semester tiga dengan menjadi pengajar privat di Lembaga Bimbingan
Belajar A n B Bintaro dan juga tutor Bahasa Indonesia di Lembaga Bimbingan Belajar
BTA 8 Depok. Saat ini, peneliti tercatat sebagai guru bidang studi Bahasa Indonesia di
SMK Farmasi Minasa Mulia Ciputat dan tutor pada matapelajaran yang sama di Lembaga
Bimbingan Belajar Gama Jogja Nusantara Depok, LBB SSC Cipete, dan LBB Privat RFA.
“Hasil selalu berbanding lurus dengan usaha”
Related Documents